Catatan Denny JA: Mengukur Samudra Emosi Manusia
- Penulis : Krista Riyanto
- Selasa, 29 April 2025 06:45 WIB
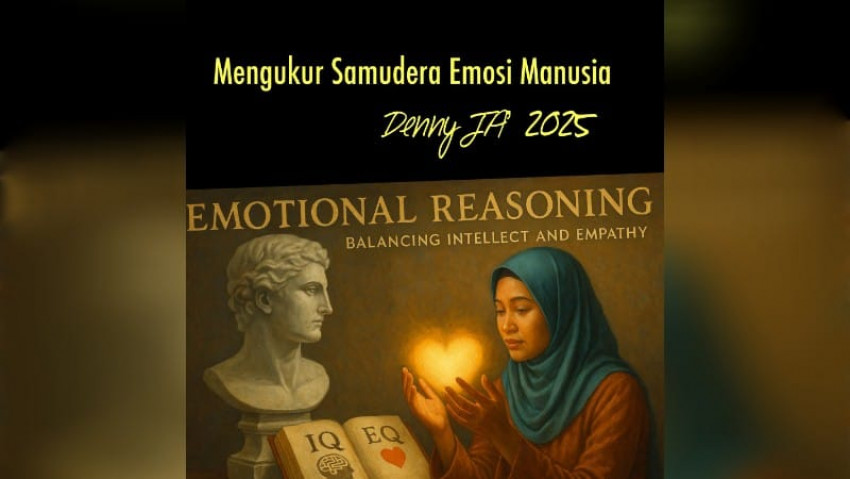
Menyambut Aplikasi Knowing Myself+Healing LSI Denny JA (4)
ORBITINDONESIA.COM - Pada musim gugur tahun 1888, di kota kecil Leipzig, Jerman, langit berwarna kelabu. Seorang mahasiswa muda bernama Anna duduk termenung di depan gedung Universitas, menangis diam-diam.
Ia terperangkap di antara buku-buku tebal tentang logika, reaksi mental, dan perhitungan statistik. Nilai akademiknya tinggi, namun jiwanya terasa hampa.
Baca Juga: Catatan Denny JA: Agama di Era Artificial Intelligence, Antara Identitas Kelompok dan Etika Publik
Di masa itu, psikologi baru lahir sebagai ilmu. Wilhelm Wundt membuka laboratorium pertamanya, membedah pikiran manusia seperti membedah mesin.
Ia mengukur reaksi, menguji ingatan, menghitung ketepatan berpikir. Dunia akademik bersorak; manusia akhirnya bisa dijelaskan dengan angka dan grafik. Namun tak seorang pun bertanya: bagaimana rasanya menjadi manusia yang terluka?
Di tengah gegap gempita nalar, air mata Anna tetap tak terjawab. Sejarah psikologi pun tercatat sebagai kisah awal yang lebih memilih memahami mekanik pikiran, sambil mengabaikan samudera luas yang tersembunyi: emosi manusia.
Baca Juga: Catatan Denny JA: Mengapa Perlu Ikut Merayakan Secara Sosial Hari Besar Agama Lain?
-000-
Kisah Anna di Leipzig, seratus empat puluh tahun silam, terkenang kembali saat saya bersama tim menyusun aplikasi tes psikologi Knowing Myself + Healing dari LSI Denny JA.
Diskusi internal kami mengalir dalam keprihatinan: bagaimana memahami kompleksitas manusia, yang tak hanya berpikir dengan angka, melainkan juga mengalir dalam dunia emosi, luka, dan air mata?
Baca Juga: Catatan Denny JA: Mengetahui dan Memberi Arah Diri Sendiri di Era Artificial Intelligence
Kecerdasan emosional harus hadir dalam aplikasi ini, menjadi bagian penting di antara 13 tes psikologi lainnya. Bahkan lebih dari itu, aplikasi ini harus menyediakan ruang diskusi intens dan personal, sesuai kebutuhan emosi tiap individu yang unik.
Saya kembali menelusuri jejak intelektual di masa silam. Tahun 1905, Alfred Binet di Prancis mengembangkan tes IQ untuk mengukur kecerdasan logis anak-anak.
Dunia pun semakin jatuh cinta pada angka. IQ menjadi paspor menuju sekolah unggulan, karier cemerlang, hidup bermakna. Namun luka batin tetap membusuk dalam keheningan.
Baca Juga: Catatan Denny JA: Mengukur Batin Manusia, Dulu dan Sekarang
Baru pada tahun 1990, di tengah salju kampus New Hampshire, dua profesor muda — Peter Salovey dan John D. Mayer — mengajukan sebuah pertanyaan sunyi yang menggetarkan dunia: bagaimana dengan kecerdasan emosi? Bukankah ia sama vitalnya?
Mereka memperkenalkan konsep Emotional Intelligence: kemampuan untuk menyadari emosi diri sendiri, mengelolanya dengan bijaksana, mengenali emosi orang lain, serta membina hubungan penuh empati.
Dunia pada awalnya tak bergeming. Namun tidak lama kemudian, suara itu menemukan juru bicaranya: Daniel Goleman.
Baca Juga: Catatan Denny JA: Mengukur Kecerdasan dan Potensi Tersembunyi
Melalui bukunya Emotional Intelligence yang terbit pada 1995, Goleman membungkus gagasan itu dalam bahasa yang mampu merobek tembok nalar.
Buku itu meledak laksana meteor. Dunia, untuk pertama kalinya, mulai melihat bahwa kesuksesan hidup bukan hanya soal kepintaran berpikir, tetapi juga kehalusan merasakan.
-000-
Baca Juga: Catatan Denny JA: Mengenang Momen tak Terduga Paus Fransiskus Memberkati Lukisan Saya
Namun, bagaimana mungkin mengukur sesuatu yang sehalus angin dan seintim bisikan jiwa? Mengembangkan tes EQ menjadi tantangan tersendiri.
Salovey dan Mayer akhirnya melahirkan MSCEIT, sebuah instrumen yang mencoba membaca ekspresi emosi dari wajah, menilai ketepatan persepsi dalam situasi sosial, serta mengukur kemampuan mengelola konflik emosional.
Mereka menuntut tiga hal: tes ini harus benar-benar mengukur kecerdasan emosional, bukan sekadar suasana hati belaka.
Ia juga harus mencerminkan kehidupan nyata, bukan eksperimen laboratorium kering. Ia harus pula memiliki norma umum untuk menilai manusia dari berbagai latar belakang.
Seiring berjalannya waktu, lahirlah berbagai tes lain seperti EQ-i dari Reuven Bar-On, yang memperkaya pendekatan ini. Ia menyulam jaringan pemahaman baru tentang dunia emosi.
Dalam keheningan laboratorium, para pionir ini berusaha seperti pelukis yang mencoba membingkai pelangi dalam kanvas kecil: menghadirkan bentuk pada sesuatu yang tak berbentuk.
-000-
Abad ke-21 membuka peta tersembunyi otak manusia melalui kilatan MRI. Antonio Damasio dalam Descartes’ Error memperlihatkan kenyataan pahit: tanpa emosi, manusia tak mampu mengambil keputusan.
Mereka yang kehilangan fungsi emosinya bahkan terjebak sulit bertindak dalam pilihan sederhana, seperti sarapan apa hari ini.
Di saat bersamaan, Martin Seligman memimpin gerakan Positive Psychology. Ia menunjukkan kebahagiaan bukan semata hasil dari prestasi logis.
Ia melainkan buah dari kesadaran diri, hubungan sosial yang bermakna, serta pengelolaan emosi yang sehat.
Dunia korporasi dan pemerintahan pun akhirnya bergerak. Google, Amazon, dan banyak negara maju mulai memasukkan asesmen EQ dalam proses seleksi, promosi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Perlahan, psikologi kembali mendengar jeritan lama Anna di Leipzig: “Aku bukan hanya angka. Aku adalah samudera rasa.”
-000-
Di tengah gelombang besar AI, isolasi sosial, dan kehilangan arah spiritual, LSI Denny JA menghadirkan terobosan: Knowing Myself + Healing.
Program ini menghadirkan Kuis 2 – Emotional Intelligence, yang tidak hanya mengukur kecerdasan emosi, melainkan juga menggabungkannya dengan 12 tes lain sebagai satu kesatuan yang holistik.
LSI Denny JA menambahkan kultur lokal untuk lebih akurat memahami samudera emosi individu.
Di balik gemerlap kesuksesan EQ, para skeptik masih menyisipkan keraguan: apakah pengukuran emosi manusia tak terjebak dalam reduksionisme baru?
Bagaimana dengan kritik bahwa EQ Barat gagal menangkap nuansa lokal seperti "sungkan" atau "hormat kolektif"
Namun, inilah keunggulan Knowing Myself + Healing: algoritmanya menyelaraskan teori Mayer-Goleman dengan kearifan lokal seperti "tepo seliro" Jawa dan "pela gandong" Maluku.
la bukan sekadar terjemahan, melainkan dialog antara sains universal dan denyut nadi kultural. Ini membuktikan samudera emosi manusia memang tak bertepi. Navigasinya harus berpijak pada peta dengan garis pantai kuktur lokal masing-masing.
Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Ini peta yang membimbing manusia melintasi gurun luka batin menuju oase pemulihan, tangan sahabat yang menuntun kita berjalan lebih dalam ke ruang-ruang tersembunyi di dalam jiwa.
Bukan sekadar alat deteksi dini, bukan hanya peta penyembuhan. Program ini menawarkan keajaiban: mendampingi perjalanan batin, menguatkan resiliensi, dan menyalakan lilin-lilin kecil di tengah gelapnya dunia.
-000-
Bayangkan kisah ini. Hendra, seorang manajer muda di Jakarta, dulunya menjadi simbol kegagalan emosional meski berotak cemerlang.
Prestasinya di atas kertas gemilang. Namun dalam kehidupan nyata, ia terperangkap dalam labirin amarah, dendam, dan konflik.
Promosi yang dinantikan jatuh ke tangan orang lain. Dunia yang semula terbuka luas tiba-tiba terasa seperti ruang sempit yang menyesakkan dada.
Dalam keputusasaan, tanpa banyak bicara kepada siapa pun, hanya dari pojok kamarnya, melalui ponsel sederhana, Hendra mengikuti program Knowing Myself + Healing dari LSI Denny JA.
Hasil tes mengguncangnya: IQ-nya tinggi, namun EQ-nya rapuh dan penuh luka. Melalui diskusi online yang disediakan aplikasi itu, Hendra mendapatkan rekomendasi pribadi.
Ia belajar mengenali emosinya tanpa menghakimi. Ia diminta melatih mindfulness, mendengarkan tanpa membela diri, menulis surat untuk dirinya sendiri, dan berdamai dengan bayang-bayang masa kecil.
Ada malam-malam di mana ia menangis tanpa suara. Ada pagi-pagi di mana ia memaksa dirinya tersenyum, sekadar untuk bertahan.
Namun perlahan, perubahan datang. Rekan kerja mulai merasakan keteduhan baru dalam dirinya. Ia menjadi mata air kecil di tengah gurun ego.
Hendra akhirnya dipromosikan — bukan karena ia semakin cepat menghitung, melainkan karena hatinya bertumbuh menjadi pelabuhan yang tenang bagi orang lain.
Di malam syahdu di Bali, menghadap laut yang luas dan tak bertepi, Hendra menulis dalam jurnalnya:
“Kesuksesan bukan tentang berlari lebih cepat dari yang lain. Ia adalah tentang pulang ke rumah batin sendiri, dan memeluknya dengan utuh.”
-000-
Kini, dunia dihuni oleh mesin-mesin yang mampu berpikir lebih cepat dari manusia, dan algoritma yang mencuri perhatian serta emosi kita. Dalam dunia seperti itu, kecerdasan emosional menjadi benteng terakhir kemanusiaan.
IQ mungkin membawa manusia ke Mars, membangun jembatan di atas samudera, dan menciptakan dunia virtual tanpa batas.
Namun EQ — cinta, belas kasih, pengertian — lah yang akan menjaga bumi tetap bernyawa.
Setiap kali kita memilih memahami daripada menghakimi, merangkul daripada menolak, dan mendengarkan suara hati orang lain dengan sungguh-sungguh, kita sedang menyalakan lilin kecil di tengah kegelapan.
Dan mungkin, pada akhirnya, bukan pencapaian megah manusia yang menyelamatkan dunia. Tetapi lilin-lilin kecil itu, emosi yang rapuh, sederhana, dan bercahaya lembut.
Ia yang menjaga dunia tetap manusiawi.***
Jakarta, 29 April 2025
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/16FtJ9stxJ/?mibextid=wwXIfr
