Catatan Denny JA: Mengukur Samudra Emosi Manusia
- Penulis : Krista Riyanto
- Selasa, 29 April 2025 06:45 WIB
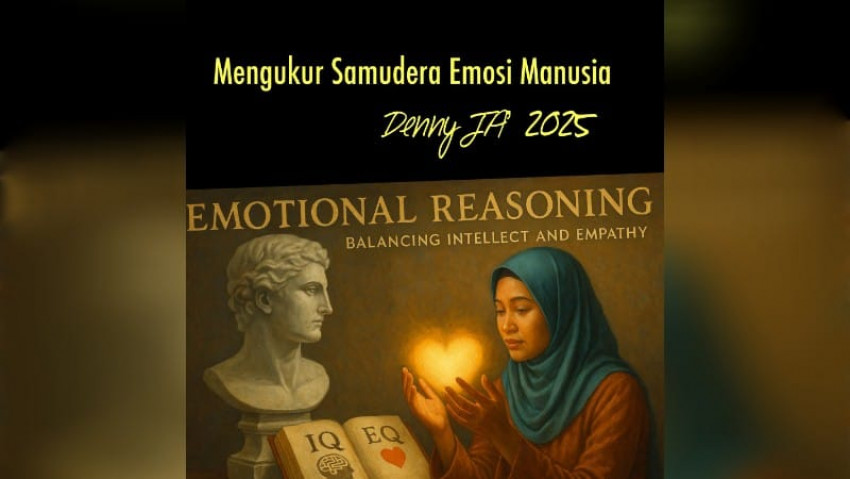
Saya kembali menelusuri jejak intelektual di masa silam. Tahun 1905, Alfred Binet di Prancis mengembangkan tes IQ untuk mengukur kecerdasan logis anak-anak.
Dunia pun semakin jatuh cinta pada angka. IQ menjadi paspor menuju sekolah unggulan, karier cemerlang, hidup bermakna. Namun luka batin tetap membusuk dalam keheningan.
Baru pada tahun 1990, di tengah salju kampus New Hampshire, dua profesor muda — Peter Salovey dan John D. Mayer — mengajukan sebuah pertanyaan sunyi yang menggetarkan dunia: bagaimana dengan kecerdasan emosi? Bukankah ia sama vitalnya?
Baca Juga: Catatan Denny JA: Agama di Era Artificial Intelligence, Antara Identitas Kelompok dan Etika Publik
Mereka memperkenalkan konsep Emotional Intelligence: kemampuan untuk menyadari emosi diri sendiri, mengelolanya dengan bijaksana, mengenali emosi orang lain, serta membina hubungan penuh empati.
Dunia pada awalnya tak bergeming. Namun tidak lama kemudian, suara itu menemukan juru bicaranya: Daniel Goleman.
Melalui bukunya Emotional Intelligence yang terbit pada 1995, Goleman membungkus gagasan itu dalam bahasa yang mampu merobek tembok nalar.
Baca Juga: Catatan Denny JA: Mengapa Perlu Ikut Merayakan Secara Sosial Hari Besar Agama Lain?
Buku itu meledak laksana meteor. Dunia, untuk pertama kalinya, mulai melihat bahwa kesuksesan hidup bukan hanya soal kepintaran berpikir, tetapi juga kehalusan merasakan.
-000-
Namun, bagaimana mungkin mengukur sesuatu yang sehalus angin dan seintim bisikan jiwa? Mengembangkan tes EQ menjadi tantangan tersendiri.
Baca Juga: Catatan Denny JA: Mengetahui dan Memberi Arah Diri Sendiri di Era Artificial Intelligence
Salovey dan Mayer akhirnya melahirkan MSCEIT, sebuah instrumen yang mencoba membaca ekspresi emosi dari wajah, menilai ketepatan persepsi dalam situasi sosial, serta mengukur kemampuan mengelola konflik emosional.
