Catatan Denny JA: Merekam Sejarah Melalui Puisi Esai
- Sabtu, 08 Februari 2025 12:27 WIB
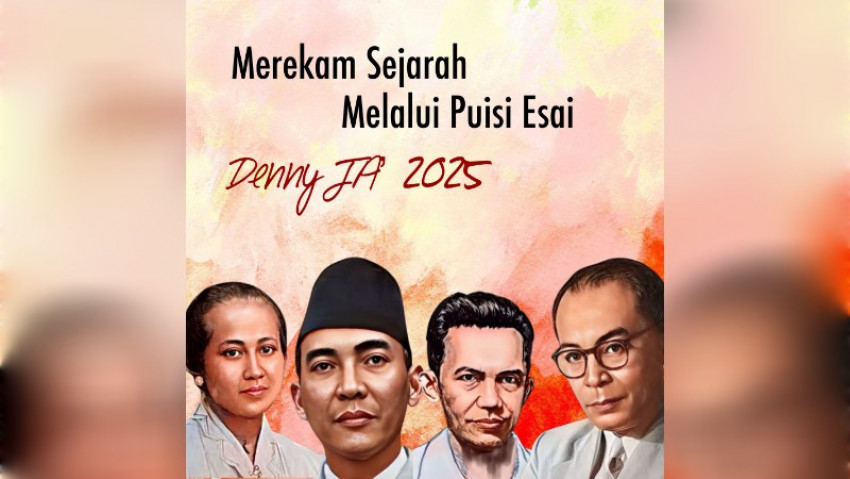
“Mereka yang tidak mengingat masa lalu, akan dikutuk untuk mengulanginya.” (George Santayana)
ORBITINDONESIA.COM - Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah peringatan, cermin yang memantulkan wajah kita hari ini.
Kita mengingat bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk bertanya: Apakah kita telah bergerak maju, atau justru berjalan dalam lingkaran?
Puisi esai adalah cara unik untuk menyelami sejarah. Ia bukan sekadar puisi, tapi menampilkan fakta. Ia bukan sekadar fakta, tetapi juga menghidupkan perasaan yang menyertai setiap peristiwa, dengan tambahan fiksi.1
Ia memberi kita kesempatan bukan hanya untuk membaca sejarah, tetapi untuk merasakannya.
Buku ini adalah dokumentasi ulang kisah 15 tokoh pergerakan Indonesia. Bagaimana suasana batin saat itu, mulai dari berdirinya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, hingga dilema RA Kartini, sang pejuang emansipasi wanita, tetapi akhirnya bersedia menjadi istri keempat seorang bupati.
Bagaimana perasaan HOS Tjokroaminoto ketika muridnya sendiri memecah Serikat Islam menjadi putih versus merah? Malahayati, lebih awal dari perempuan mana pun, memimpin sendiri perang melawan penjajah dengan mengerahkan 2.000 janda.
-000-
Di bawah ini sedikit dianalisis puisi esai atas empat tokoh saja, hanya sebagai percontohan.
Kita bertemu dengan konteks sosial yang melahirkan Mohammad Hatta, Bung Karno, Ki Hajar Dewantara, dan Sutan Sjahrir. Mereka adalah nama-nama besar dalam perjalanan bangsa ini.
Tetapi, di tahun 2025, pertanyaannya bukan hanya tentang siapa mereka, melainkan apakah api perjuangan mereka masih menyala? Ataukah kita hanya hidup dalam bayangan sejarah yang perlahan memudar?
Puisi esai tentang Mohammad Hatta berjudul: Mohammad Hatta dan Korupsi yang Menggila.
Hatta muda datang ke Rotterdam dengan satu keyakinan: bahwa bangsa ini harus bebas, bukan hanya dari penjajahan, tetapi juga dari ketidakadilan yang merayap pelan.
Ia membaca, menulis, dan berdebat, membawa gagasan bahwa pemimpin sejati bukan hanya yang berkuasa, tetapi yang menjaga moralitasnya.
Bukan hanya Indonesia merdeka yang menjadi obsesinya, tapi juga pemimpin yang amanah dan jujur.
Saat itu, Hatta sudah menjadi wakil presiden. Ia akan mengunjungi ibunya. Ia disediakan mobil negara untuk keperluan itu.
Tapi Hatta menolak. Jangan pakai fasilitas negara untuk urusan pribadi.
“Pakai saja mobil teman,” katanya.
Penolakan kecil ini menggambarkan prinsip yang besar. Hatta memahami bahwa korupsi tidak dimulai dengan pencurian dalam jumlah besar, tetapi dengan kebiasaan kecil yang lama-lama dianggap wajar.
Dalam puisi esai, hal di atas diungkapkan melalui bait ini:
Ia tahu, korupsi tak datang dengan gebrakan,
hanya bisikan kecil di awal.
Lalu menjadi kebiasaan,
lalu menjadi sistem,
lalu menjadi bencana.
Dan kini, bencana itu telah datang.
Korupsi bukan lagi perbuatan gelap,
tetapi aturan tak tertulis.
Kejujuran adalah legenda,
diwariskan tanpa pewaris.
Penjara tak lagi menakutkan—
dindingnya bisa dibeli.
Di meja-meja megah, janji berkilau seperti emas,
tapi bayangannya tak berwajah.
Kini, di tahun 2025, batas itu telah lama runtuh. Korupsi bukan lagi sekadar penyimpangan, tetapi telah menjadi sistem yang berjalan dengan rapi.
Jika Hatta bisa melihat kondisi hari ini, apakah ia masih akan percaya pada janji kemerdekaan? Ataukah ia hanya akan diam, karena kecewa terlalu dalam untuk diungkapkan?
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 merosot ke skor 34, menempati peringkat 110 dari 180 negara. Angka ini turun 4 poin dari tahun sebelumnya, sekaligus menjadi skor terendah sejak 2015.
Penurunan ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum, ketidakefektifan regulasi, serta meningkatnya korupsi sistemik di berbagai sektor pemerintahan. Reformasi hukum yang mendalam diperlukan untuk membalikkan tren negatif ini.2
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 tetap berada di skor 34, sama seperti tahun sebelumnya, namun peringkatnya turun ke posisi 115 dari 180 negara.
Selain itu, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 juga mengalami penurunan, dengan skor 3,85 dibandingkan 3,92 pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan meningkatnya korupsi sistemik di berbagai sektor pemerintahan.
Reformasi hukum yang mendalam diperlukan untuk membalikkan tren negatif ini.
-000-
Puisi esai lain yang ada di buku ini soal Bung Karno, berjudul: Marhaen Abad 21.
Ia menanam butir harapan,
tapi yang panen adalah tangan-tangan tak terlihat.
Marhaen, sosok petani kecil yang Bung Karno temui, adalah lambang sebuah ironi. Ia memiliki tanahnya sendiri, tetapi tetap miskin.
Karena nilai lebih dari usahanya tidak menjadi miliknya, tapi “yang panen adalah tangan-tangan tak terlihat.”
Karena kondisi pemiskinan yang melanda rakyat kecil, Bung Karno menggagas sebuah ide besar: bahwa kemerdekaan sejati harus juga berarti kemandirian ekonomi bagi rakyat kecil.
“Untuk siapa keringatku mengalir?”
bisiknya pada batang padi,
yang menunduk diam,
seolah malu untuk menjawab.
Bait ini adalah refleksi dari kenyataan pahit. Seorang petani bekerja keras, tetapi ia tidak merasakan hasilnya. Padi yang ia tanam dijual ke negeri lain, sementara ia sendiri harus membeli beras dengan harga yang kian melambung.
Sudah lebih dari 79 tahun Indonesia merdeka. Gerakan Marhaen sudah didengungkan berulang-ulang. Tapi apa yang terjadi?
Di tahun 2025, negeri ini masih bergantung pada impor. Garam kita asin di laut, tetapi datang ke meja makan dengan bendera asing. Beras tumbuh di tanah ini, tetapi banyak beras negeri lain yang kita makan.
Marhaenisme pernah menjadi api yang membakar semangat rakyat. Tetapi kini, ia hanya menjadi kenangan yang samar, tertelan oleh sistem yang lebih besar dari para petani itu sendiri.
Jika Bung Karno berdiri di tengah pasar hari ini, melihat negeri ini yang kaya akan sawah, tapi tak kunjung swasembada beras, apa yang akan ia katakan?
Data menunjukkan dalam situasi sawah di Indonesia begitu luas, beras masih impor. Pada tahun 2024, Indonesia mengimpor 4,52 juta ton beras, meningkat 47,7 persen dari 2023 yang sebesar 3,06 juta ton, menunjukkan belum tercapainya swasembada beras.3
-000-
Tak hanya soal swasembada pangan, tapi juga ironi di dunia pendidikan. Kita bertemu dengan tokohnya: Ki Hajar Dewantara, yang diekspresikan dalam puisi esai berjudul: Tapi Kecerdasan Kami Tergolong Rendah, Pak Guru.
Sejak kecil, mereka hanya belajar,
menulis lapar, menghitung sunyi.
Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa dengan keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan menuju kemerdekaan sejati. Ia tidak hanya membangun sekolah, tetapi membangun harapan.
Tetapi kini, di tahun 2025, kenyataan yang ada jauh dari idealisme itu.
Kepala sekolah itu berlutut,
jari-jarinya menyentuh tetesan di rumput.
Bukan embun,
bukan air mata.
Ini air kesedihan yang jatuh dari sejarah.
Sejarah meneteskan air mata, bukan karena lupa, tetapi karena kecewa. Pendidikan masih menjadi tembok tinggi bagi banyak anak.
Mereka belajar membaca, tetapi buku yang mereka pegang tidak bisa sepenuhnya dipahami. Satu dari lima anak Indonesia kurang gizi.
Tes matematika, bahasa, dan lainnya, skor anak-anak Indonesia jauh di bawah negara lain.
Pada PISA 2022, skor membaca Indonesia adalah 359, matematika 366, dan sains 383; semuanya di bawah rata-rata global, menandakan mutu pendidikan yang masih rendah.4
-000-
Dalam puisi esai soal Ki Hajar Dewantara, situasi itu diungkapkan dengan cara ini:
Tapi di sore itu, di tahun 2025,
puluhan tahun setelah kematiannya,
seorang kepala sekolah berdiri,
menatap makam Ki Hajar Dewantara.
Ia meratap:
“Kecerdasan bangsa kita sangat rendah.
Stunting mencengkeram satu dari lima anak.”
Mereka memang belajar membaca.
Tapi lidah mereka terjepit oleh piring yang kosong.
Pena bergetar di jari kurus.
Buku terbuka, tapi tak terbaca.
Gizi yang hilang merampas cahaya.
Ia mengadu:
Di negeri lain, ujian adalah tangga.
Tapi di sini, ia menjelma dinding tinggi.
Sejak kecil, mereka hanya belajar,
menulis lapar, menghitung sunyi.
Apakah ini kutukan sejarah,
atau tangan-tangan kami yang gagal menulis takdir?
Jika Ki Hajar bisa berbicara dari makamnya, apakah ia akan menangis? Ataukah ia akan memilih diam, karena luka sejarah terlalu dalam untuk dijahit kembali?
-000-
Kisah tokoh pergerakan dalam buku ini juga ditampilkan dalam sisi tragisnya. Itu tentang salah satu pendiri bangsa, Sutan Sjahrir, dalam puisi esai berjudul: Pejuang Itu Mati dalam Status Tahanan Politik.
Sjahrir membawa gagasan politiknya sendiri. Bahwa Indonesia akan maju jika menerapkan Sosial Demokrasi, dengan mencontoh negara Skandinavia.
Namun gagasannya berbeda keras dengan pandangan Bung Karno yang ingin menerapkan Demokrasi Terpimpin.
Sjahrir percaya sosialisme, tetapi dalam versi gagasan yang tumbuh di Eropa Barat. Ia anti-komunisme yang akan membawa bangsa hancur dalam kediktatoran.
Tetapi gagasannya berbeda dengan Bung Karno, yang saat itu berkuasa. Bung Karno justru merangkul komunisme dalam Gerakan Nasakomnya, karena meyakini bahwa komunisme sebagai partai besar saat itu adalah bagian dari rakyat Indonesia.
Karena alasan yang masih belum sepenuhnya terang, Sjahrir, salah satu pendiri bangsa, dijebloskan ke dalam penjara. Sebuah ironi, sang pejuang ini mati dalam status tahanan politik negerinya sendiri.
Dalam puisi esai, kisahnya diekspresikan dalam aneka bait ini:
Lalu Bagja ingat Sutan Sjahrir,
yang memimpikan Indonesia,
seperti Skandinavia,
sejak dulu,
dulu sekali.
Sjahrir lahir dari sajak yang berbisik,
bukan dari pidato yang mengepalkan tangan.
Ia mencari revolusi yang tak perlu darah,
di halaman-halaman buku, dalam tafsir sunyi sejarah.
Ia membaca sosialisme di bawah lampu Belanda,
bukan dalam ruangan yang berpijar merah.
Di benaknya, keadilan bukan genderang perang,
tetapi sungai yang mengalir tanpa mengguncang tepiannya.
Ia ingin Indonesia berkeringat dalam damai,
bukan membakar rumahnya sendiri,
demi api yang tak bisa dijinakkan.
Memang Sjahrir awalnya memimpin Indonesia sebagai Perdana Menteri. Tapi ia dijatuhkan karena dianggap gagal. Bahkan kemudian ia dituduh berkomplot untuk menjatuhkan pemerintahan resmi.
Lalu datang tuduhan.
Ia yang pernah menjadi tulang punggung republik,
dituduh sebagai bayangan yang berkhianat.
Ia yang hanya memiliki pena dan gagasan,
dituduh menghunus pisau di tengah kegelapan.
Di sebuah pagi yang tak berbunyi,
ia dijemput oleh tangan yang dulu bersalaman.
Bukan oleh penjajah,
tetapi oleh negaranya sendiri.
Bung Karno diam.
Bung Hatta membela,
tapi suaranya kalah oleh keriuhan zaman.
Sejarah menuliskannya di sela-sela,
seperti catatan kaki yang terlupakan.
Di dalam sel yang lebih sempit dari pikirannya,
Sjahrir melihat tubuhnya menipis.
Kakinya tak lagi mampu berlari,
tetapi pikirannya masih terbang lebih tinggi dari temboknya.
Keringatnya mengkristal di udara pengap,
menjadi garam yang tertinggal, saat laut mengering.
Ia mencium bau karat besi,
dan mendengar derit jeruji yang menyanyikan lagu tanpa kata.
Ia sakit, tetapi dokter hanya datang
ketika sakitnya telah menjadi lebih besar dari sel itu sendiri.
Sjahrir wafat dalam status tahanan politik. Tapi gagasan yang diperjuangkannya, negara kesejahteraan model Skandinavia, kini terbukti paling tinggi skor “indeks kebahagian warga negaranya” diukur oleh PBB.
Negara-negara Skandinavia mendominasi peringkat teratas Indeks Kebahagiaan Dunia 2024: Finlandia (skor 7,741), Denmark (7,583), Islandia (7,525), Swedia (7,344), dan Norwegia (7,302).4
-000-
Hatta bermimpi tentang pemerintahan yang bersih, tetapi kita justru tenggelam dalam korupsi yang semakin menggila.
Bung Karno ingin rakyatnya berdaulat, tetapi petani masih menjadi tamu di tanahnya sendiri.
Ki Hajar Dewantara berjuang untuk pendidikan, tetapi anak-anak kita masih berjuang melawan stunting, kurang gizi.
Sjahrir berjuang dengan gagasan, tetapi di negeri ini, gagasan sering kali kalah oleh kekuasaan.
Sejarah bukan hanya milik masa lalu. Ia adalah cermin yang menampilkan wajah kita hari ini. Ia tidak boleh hanya menjadi kenangan yang dibaca di buku, tetapi harus menjadi cahaya yang menuntun kita ke depan.
Tetapi pertanyaannya tetap: Apakah kita masih berjalan di jalur yang mereka rintis? Ataukah kita hanya menjadi saksi bisu dari kemunduran yang mereka coba cegah?
Tak hanya empat tokoh di atas yang dieksplorasi dalam buku puisi esai ini, tetapi juga ada sebelas tokoh pergerakan lainnya.
Puisi esai tak hendak dan jelas dilarang menggantikan reportase sejarah. Tapi puisi esai bisa membantu membuat kisah sejarah ini lebih bernyawa, seperti contoh kisah 15 tokoh pergerakan dalam buku puisi esai ini.
Puisi esai menghidupkan sejarah, membuat tokoh bernapas, merasakan luka, dan berbisik kepada pembaca.
Ia menyalakan emosi, membangun imajinasi, dan menciptakan pengalaman batin yang tak bisa diberikan oleh data kaku.
Namun, puisi esai juga bisa mengaburkan fakta, membiaskan realitas dengan fiksi, dan menanamkan subjektivitas penulis.
Karena itu, untuk akurasi sejarah, kita tetap berpegang pada riset sejarah murni. Ia menawarkan ketelitian, mengandalkan bukti, memverifikasi sumber, dan membangun fondasi kebenaran.
Tetapi sering kali makalah akademik sejarah dingin dan kering, hanya sekadar angka, tanggal, dan peristiwa tanpa jiwa.
Puisi esai merasukkan makna, riset sejarah menjaga keakuratan. Keduanya perlu bersinergi agar sejarah tak sekadar diingat, tetapi dihidupkan dan dipahami dengan jernih.
Dalam puisi esai ada catatan kaki sebagai wakil dari realitas dan fakta yang hendak dipuisikan. Catatan kaki itu adalah ibu kandung yang melahirkan puisi di atasnya. Tak ada puisi esai tanpa catatan kaki, karena catatan kaki itu sumber dari The True Stories.
Tapi catatan kaki: fakta, data dan peristiwa di dunia nyata diolah puisi esai menjadi cerita. Di dalamnya, kata-kata tidak sekadar berbicara, tetapi berdarah, bernapas, dan menyalakan api yang tak hendak padam.”
Jakarta, 8 Februari 2025 ***
CATATAN
(1) Komunitas Puisi Esai tahun 2025 menyelenggarakan Festival Puisi Esai ASEAN ke-4, sudah terbit hampir 200 buku puisi esai, dan sudah disediakan dana abadi untuk Festival Puisi Esai Jakarta serta Puisi Esai Award.
(2) Korupsi di Indonesia memburuk
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun Lagi, Penegakan Hukum Tipikor Perlu Dikaji Ulang?
(3) Indonesia belum swasembada beras
(4) Skor anak-anak didik Indonesia (PISA) termasuk terendah di dunia
Skor Matematika-Membaca Pelajar RI Salah Satu Terendah di Dunia
(5) Indeks kebahagian dunia, negara skandinavia selalu tertinggi
Finland declared happiest country for sixth time in a row - NY Post
