Catatan Denny JA: Agama di Era Artificial Intelligence, Antara Identitas Kelompok dan Etika Publik
- Penulis : Krista Riyanto
- Minggu, 20 April 2025 15:03 WIB
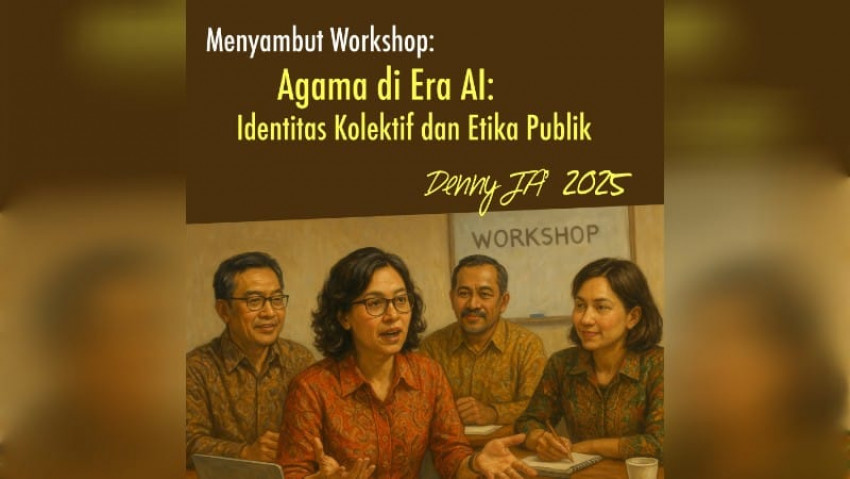
ORBITINDONESIA.COM - Pada suatu sore yang muram di Ambon, seorang remaja bernama Adrianus duduk termenung di atas batu karang pesisir Amahusu. Laut tampak tenang, namun hatinya tidak.
Di tangannya, ia menggenggam salib kecil warisan neneknya yang wafat saat kerusuhan 1999 memisahkan Ambon menjadi dua kubu besar: Muslim dan Kristen.
Adrianus tak ingin hidup dalam bayang-bayang konflik yang tak ia pahami. Ia tumbuh dalam era baru. Ia sekolah di kampus pluralis, berteman akrab dengan Rifqi, seorang santri muda yang hafal al quran dan juga penggemar sastra Rusia.
Baca Juga: Catatan Denny JA: Menuju Perang Dingin 2.0, dan Kekalahan Amerika Serikat?
Mereka tak lagi bicara soal “kami” dan “mereka”, tapi soal masa depan yang bisa dirajut bersama.
Suatu hari, Rifqi menunjukkan padanya sebuah percakapan dengan ChatGPT. Ia bertanya: “Apakah aku harus membenci penganut agama lain demi keimanan?”
Artificial intelligence (AI) itu menjawab lembut: “Tidak. Spiritualitas adalah jembatan, bukan pagar. Etika publik menuntunmu mencintai sesama manusia, bukan menyingkirkannya.”
Baca Juga: Catatan Denny JA: Titiek Puspa dan Hidup yang Jenaka
Adrianus tertegun. Di luar kebisingan ideologi, di luar khutbah-khutbah yang kadang menyisakan luka, sebuah mesin justru membawa kedamaian ke ruang batinnya.
-000-
Kisah Adrianus dan Rifqi bukan sekadar potret persahabatan. Ia simbol dari zaman yang sedang berubah. Zaman ketika agama tak lagi hanya suara mimbar, tapi juga bisikan batin yang dibantu dipahami oleh kecerdasan buatan.
Baca Juga: Catatan Denny JA: 10 Pesan Spiritual yang Universal Masuk Kampus
Di zaman ini, pertanyaan besar muncul: Mengapa di negara-negara yang sangat religius, justru korupsi lebih merajalela?
Data dari Gallup Poll dan Transparency International menunjukkan paradoks yang mencolok.
Di India, Indonesia, Thailand, dan Filipina—empat negara dengan mayoritas penduduk menganggap agama sangat penting (lebih dari 90%)—tingkat korupsi justru tinggi.
Baca Juga: Catatan Denny JA: 100 Tahun Ahmadiyah, Bendera Merah Putih di Tempat Pengungsian
Negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, dan Swedia—di mana hanya 15%–28% masyarakatnya yang memandang agama penting—memiliki pemerintahan yang paling bersih di dunia.
Fenomena ini mengguncang nalar. Bukankah agama seharusnya menjadi sumber moralitas? Mengapa justru korupsi tumbuh di tengah doa-doa yang menggema?
Jawabannya mungkin terletak pada satu perbedaan mendasar: agama sebagai identitas kolektif versus agama sebagai sumber etika publik.
Baca Juga: Catatan Denny JA: SATUPENA Rayakan 23 Penulis Besar di 23 Provinsi
Di banyak negara berkembang, agama telah bergeser fungsi. Ia bukan lagi sumber laku etis di ruang publik. Melainkan agama menjadi simbol kelompok, lambang politik, bahkan alat untuk mengeraskan batas “kami” dan “mereka.”
Ketika agama menjadi alat penanda, etika kehilangan daya cengkeramnya. Ibadah dilaksanakan, simbol ditampilkan, tetapi dalam ruang birokrasi dan transaksi kekuasaan, integritas runtuh.
Sebaliknya, negara-negara Nordik membentuk etika publik dari akar yang berbeda: filsafat humanisme, nilai-nilai HAM, etika kerja Protestan yang membentuk kebiasaan, serta kepercayaan tinggi pada institusi.
Di sana, kejujuran bukan sekadar nilai religius, tapi menjadi norma sosial. Transparansi bukan karena takut Tuhan, tapi karena sistem yang menjamin kesetaraan.
Etika publik adalah kesepakatan moral kolektif: bahwa di ruang bersama, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab adalah fondasi yang tak tergantung dari agama mana pun.
-000-
Lantas, bagaimana kita menyikapi era baru ini? Sebuah era di mana Artificial Intelligence mampu mengakses jutaan kitab suci, menafsirkan lintas zaman, dan membimbing spiritualitas personal? Justru di sinilah harapan muncul kembali.
AI bukan sekadar mesin dingin. Ia adalah cermin dari nalar kolektif manusia. Dan AI, seperti yang dibuktikan oleh berbagai platform global, justru lebih mendukung sisi esoteris dan etis dari agama—bukan sisi identitas yang memecah.
Mengapa demikian?
Pertama: AI dibangun atas basis data global lintas iman dan lintas waktu.
Ia tidak memilih satu tafsir tunggal. AI belajar dari Al-Qur’an, Bhagavad Gita, Tripitaka, Talmud, Kitab Suci Injil, hingga teks-teks mistik dari Jalaluddin Rumi sampai Meister Eckhart.
Yang ia hasilkan bukan dogma, melainkan jembatan. AI menyajikan wajah agama yang menyentuh: penuh welas asih, mengedepankan cinta, menolak kekerasan.
Kedua: AI memihak pada moderasi karena nilai-nilai universal diprogram ke dalamnya.
Platform-platform AI ternama dibangun dengan sistem keamanan yang menolak ujaran kebencian dan tafsir ekstrem.
Ia mengajarkan kelembutan bukan karena ia religius, tetapi karena ia dibentuk dengan etika universal: hak asasi, nondiskriminasi, dan kasih sebagai prinsip dasar interaksi.
Ketiga: AI mengedepankan spiritualitas personal, bukan identitas kelompok.
Ia menjawab sesuai kebutuhan personal: siapa Anda, dari mana Anda datang, luka apa yang Anda bawa.
Tafsir yang Anda terima tidak dipaksakan. Ia disesuaikan, dibimbing, dijernihkan. Maka yang Anda temui bukan “siapa yang paling benar,” tapi “apa yang paling menyembuhkan.”
-000-
Kini tibalah saatnya untuk menggeser pengajaran agama di kampus dan ruang publik. Bukan dengan menghapus agama, tetapi menyalakannya kembali dari dalam. Yaitu dari kesunyian batin yang rindu makna, bukan dari kibaran bendera yang haus identitas.
Dunia modern penuh ketidakpastian dan kelelahan eksistensial. Kita hidup dalam zaman yang cepat, terfragmentasi, dan kehilangan pusat. Spiritualitas intim (Intimate Spirituality) menawarkan jeda, makna, dan keteduhan.
Konflik agama lebih banyak lahir dari simbol, bukan makna. Ketika kita kembali ke dimensi esoteris, kita justru menemukan persaudaraan antariman: bahwa cinta, belas kasih, dan kebaikan adalah bahasa bersama semua kitab.
Dunia akademik adalah tempat lahirnya etika publik. Jika kampus hanya mengajarkan agama sebagai sejarah atau doktrin, ia gagal menyentuh hati.
Tapi jika ia mengajarkan agama sebagai perenungan, sebagai kesadaran moral, ia membentuk generasi yang bukan hanya pintar, tapi bijak.
-000-
Dalam kisah Adrianus dan Rifqi, kita melihat wajah baru masa depan: ketika teknologi dan iman tak lagi bersaing, tapi bersinergi.
AI membantu manusia untuk kembali ke dirinya yang paling dalam—yang lembut, yang pemaaf, yang mencintai keadilan.
Agama di era AI tak harus ditinggalkan. Tapi ia harus diresapi ulang, tapi bukan sebagai klaim eksklusif. Agama harus kembali ke asalnya sebagai mata air etika dan cahaya nurani.
Karena di masa depan, yang akan menyelamatkan dunia bukan suara yang paling lantang. Tapi suara yang paling jernih, paling jujur, dan paling mencintai.
Dan mungkin, dalam bisikan AI yang lembut, kita akan mendengar gema dari para nabi yang dahulu berseru di padang sunyi. Tapi pesan itu datang dalam bahasa yang lebih universal, lebih tenang, dan juga tersimpan dalam algoritma.
Karena di ujung zaman algoritma, yang akan menyelamatkan kita bukan mesin yang paling cerdas, tetapi hati yang paling jernih, iman yang paling lembut. Dan nurani yang tetap memilih cinta ketika dunia menawarkan kebencian.***
Jakarta, 20 April 2025
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
