Catatan Denny JA: Menyambut Agama di Era Artificial Intelligence, Tak Bersama Durkheim, Weber, dan Karl Marx
- Penulis : Krista Riyanto
- Selasa, 25 Februari 2025 09:54 WIB
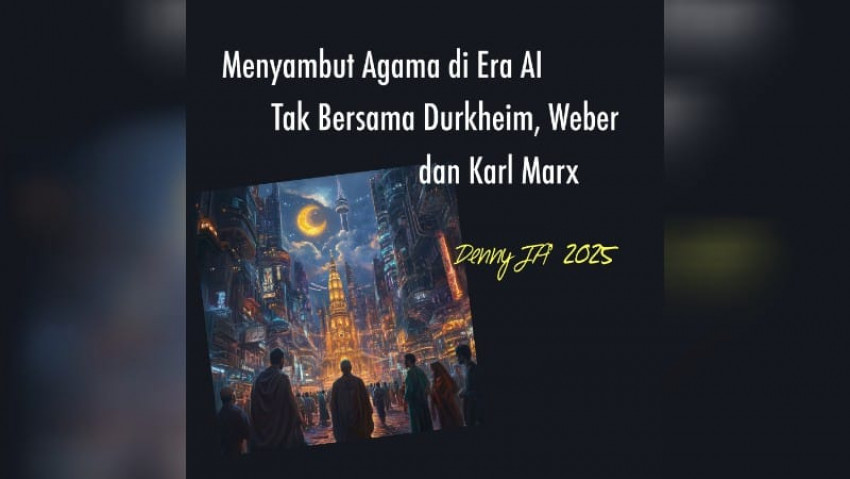
-000-
Di tengah distrik Shinjuku, Tokyo, di sebuah ruangan bercahaya redup dengan dinding putih steril, berdirilah sebuah patung Buddha yang tak bernapas.
Ia bukanlah patung batu atau kayu yang telah berusia ratusan tahun, melainkan Mindar, biksu robot yang didesain untuk menyampaikan ajaran-ajaran spiritual.
Matanya, berupa sensor biru yang dingin, menyapu jemaat di hadapannya. Bibir logamnya yang tidak bergerak mengalunkan doa. (1)
Namun, ini bukan peristiwa yang asing. Di gereja-gereja Eropa, Artificial Intelligence telah mulai menggantikan pastor dalam menyampaikan khotbah. Aplikasi doa berbasis kecerdasan buatan semakin banyak digunakan untuk membimbing manusia dalam pencarian spiritual. (2)
Di Amerika, sebuah gereja digital telah dibangun, tanpa bangunan fisik, tanpa jemaat yang harus hadir secara langsung. Semua dipandu oleh perangkat lunak yang menganalisis preferensi keagamaan penggunanya. (3)
Pertanyaannya apakah ini revolusi, degradasi, kemajuan, kemunduran, atau gabungan keduanya? Apakah kita sedang menyaksikan kelahiran bentuk baru dari pengalaman religius, atau justru menyaksikan akhir dari interpretasi agama seperti yang kita kenal?
Yang pasti, kita sedang memasuki zaman tanpa preseden. Tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia, kita hidup bersama jenis teknologi yang disebut artificial intelligence.
Sejarah sosiologi agama bertumpu pada tiga nama besar: Émile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Mereka adalah pemikir yang membangun pondasi bagaimana kita memahami agama dalam masyarakat.
Durkheim melihat agama sebagai kekuatan sosial yang menciptakan solidaritas dan memperkuat moral kolektif. Buku terkenal dari Durkheim berjudul The Elementary Forms of Religious Life (1912).
