Pemikiran Denny JA Tentang Agama dan Spiritualitas di Era Artificial Intelligence Mulai Diajarkan di Kampus
- Penulis : Krista Riyanto
- Jumat, 14 Februari 2025 21:04 WIB
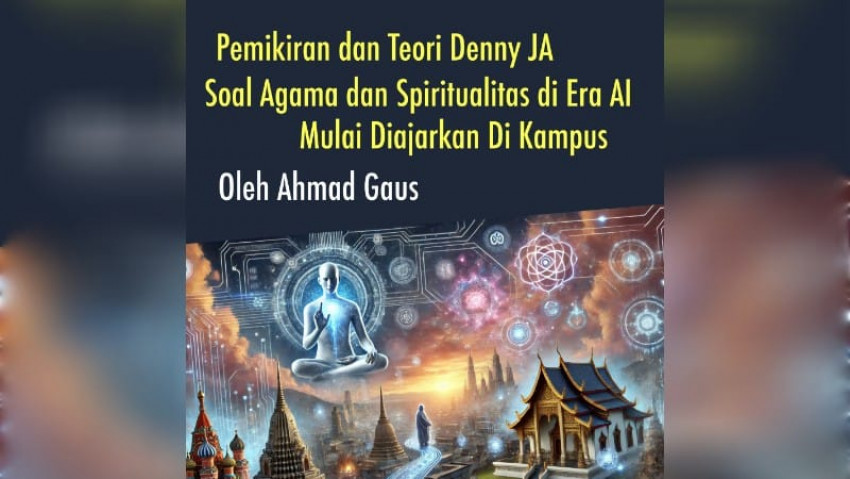
Oleh Ahmad Gaus AF*
ORBITINDONESIA.COM - “Di era artificial intelligence (AI), dalam hitungan detik dan 24 jam sehari, setiap individu dengan mudah mendapat informasi tentang agama, mulai dari sisi historisitasnya, filosofi, dan perbandingan tafsir. Semakin berkembang AI, semakin peran ulama, pendeta, dan biksu menurun.” – Denny JA
Kutipan ini menyoroti bagaimana AI berpotensi menggeser otoritas keagamaan tradisional.
Dulu, ulama, pendeta, dan biksu menjadi penjaga tafsir dan sumber utama pengetahuan agama. Kini, informasi keagamaan tersedia secara instan, dari berbagai perspektif, tanpa batas waktu dan tempat.
AI memungkinkan siapa pun mengakses sejarah agama, tafsir alternatif, hingga kritik terhadap doktrin tanpa perlu lagi perantara otoritas keagamaan.
Hal ini mendemokratisasi pengetahuan, tetapi juga menantang peran pemuka agama. Pemandu agama dan spiritual harus menyesuaikan diri—lebih reflektif daripada dogmatis.
Inilah salah satu dari tujuh prinsip teori Denny JA tentang agama dan spiritualitas di era AI.
Mulai semester genap 2025, teori dan pemikiran agama Denny JA akan diajarkan di berbagai kampus, baik sebagai mata kuliah utuh maupun bagian dari mata kuliah yang sudah ada, di perguruan tinggi negeri dan swasta.
Agama: Dari Dogma ke Evolusi Spiritual
Di sepanjang sejarah, agama bukan sekadar kumpulan dogma atau ritual, tetapi cerminan dari evolusi peradaban manusia. Ia tumbuh, beradaptasi, dan menemukan bentuknya yang baru di setiap zaman.
Dalam era AI, kita menyaksikan pergeseran besar: agama tidak lagi hanya menjadi jawaban atas pertanyaan metafisik, tetapi juga arena refleksi yang terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Denny JA menggagas pemahaman bahwa agama bukan sekadar kebenaran mutlak yang statis, tetapi bertahan karena fungsinya dalam memberikan makna, harapan, dan struktur sosial bagi umat manusia.
Agama bukan hanya iman yang diwariskan, tetapi narasi yang terus ditafsir ulang untuk menjawab tantangan zaman.
Di sinilah spiritualitas baru muncul—bukan sebagai pengganti agama, tetapi sebagai jembatan antara keyakinan lama dan realitas modern.
Esoterika Fellowship Program (EFP), yang dibangun atas pemikiran ini, menjadi ruang akademik untuk menelusuri bagaimana agama, sains, dan filsafat dapat berjalan berdampingan dalam pencarian makna yang lebih luas.
Tujuh Prinsip Denny JA tentang Agama dan Spiritualitas di Era AI
Denny JA mengeksplorasi hal-hal baru yang muncul di era Google dan Artificial Intelligence, yang mengubah cara kita memahami agama.
1. Keyakinan Agama Tidak Berkorelasi dengan Kualitas Kehidupan Bernegara
Negara yang religius tidak otomatis lebih bahagia atau bebas korupsi. Skandinavia, dengan masyarakat sekuler, memiliki indeks kebahagiaan tertinggi di dunia.
Negara-negara skandinavia, seperti Denmark, secara konsisten menempati peringkat teratas dalam Indeks Kebahagiaan Dunia dan Indeks Persepsi Korupsi.
Denmark, misalnya, meraih skor tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi 2023 dengan 90 poin. Negara-negara Nordik juga kuat dalam indikator kebahagiaan seperti PDB per kapita, dukungan sosial, dan harapan hidup sehat.
Ini menunjukkan bahwa agama bukan satu-satunya faktor dalam membangun kehidupan sosial yang baik. Etika, hukum, dan kebijakan publik lebih menentukan kemajuan suatu bangsa.
2. Agama Bertahan Bukan Karena Kebenaran Faktual, tetapi Makna Simbolis
Narasi agama sering bertentangan secara historis, tetapi tetap bertahan karena menawarkan makna mendalam.
Yesus disalib atau tidak, anak yang dikorbankan Ibrahim Ishak atau Ismail, semua berlanjut dalam keyakinan masing-masing.
Agama bertahan bukan karena bukti empiris, tetapi karena fungsinya: memberi harapan, identitas sosial, dan jawaban atas kegelisahan eksistensial manusia.
3. Agama Bukan Lagi Satu-Satunya Panduan Hidup Bahagia dan Bermakna
Dulu, agama adalah satu-satunya pemandu kebahagiaan. Kini, psikologi positif dan ilmu kebahagiaan menawarkan jalan lain.
Hubungan sosial, berpikir positif, mengejar passion, serta kemenangan kecil lebih berperan dalam kesejahteraan manusia.
Agama masih penting, tetapi sains kini menawarkan cara hidup bermakna tanpa harus bergantung pada dogma agama.
4. Era AI Mengubah Peran Otoritas Agama
Dulu, ulama, pendeta, dan biksu memonopoli tafsir agama. Kini, AI dan internet memungkinkan siapa pun mengakses teks suci dari berbagai sudut pandang.
Otoritas keagamaan melemah, karena individu semakin mandiri dalam menafsirkan iman mereka.
Pemuka agama yang bertahan adalah mereka yang beradaptasi, menjadi pembimbing spiritual, bukan sekadar penyampai doktrin.
5. Agama Semakin Menjadi Warisan Kultural Milik Bersama
Hari raya agama kini dirayakan secara sosial oleh semua orang, bukan hanya penganutnya.
Natal di Jepang, idulfitri di Eropa, dan diwali di Amerika menjadi bukti bahwa agama berkembang dari dogma eksklusif menjadi tradisi kultural.
6. Tafsir Agama yang Bertahan adalah yang Selaras dengan Hak Asasi Manusia
Tafsir agama selalu beragam, dari konservatif hingga progresif. Dalam sejarah, tafsir yang selaras dengan hak asasi manusia lebih cenderung bertahan.
Dulu, perbudakan dan diskriminasi berbasis gender didukung tafsir agama, tetapi kini ditolak.
Tafsir agama harus terus berkembang agar tetap relevan dalam masyarakat modern yang menjunjung kesetaraan.
7. Komunitas adalah Kunci Sosialisasi Gagasan Spiritual Baru
Gagasan hanya bertahan jika ada komunitas yang menghidupkannya.
Diperlukan komunitas lintas agama yang merayakan nilai-nilai universal, bukan sekadar dogma eksklusif.
Dengan melihat agama sebagai warisan kultural bersama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih inklusif.
Apakah AI Benar-Benar Akan Mengubah Agama?
Tentu saja, melebih-lebihkan pengaruh AI dalam agama adalah keliru. Agama bukan sekadar teks atau tafsir yang bisa diolah AI.
Agama juga pengalaman batin, komunitas, dan ritual yang hidup dalam manusia. Tidak ada algoritma yang bisa menggantikan doa yang khusyuk, ziarah spiritual, atau hubungan emosional antara pemuka agama dan umatnya.
Namun, AI tetap akan membawa perubahan signifikan. Bukan menggantikan pengalaman religius, tetapi mengubah cara manusia mengakses, memahami, dan mendiskusikan agama.
AI bukan akhir dari agama, melainkan awal dari era baru: spiritualitas yang lebih terbuka, rasional, dan berbasis informasi luas.
Di biara sunyi Tibet, seorang biksu menggunakan AI untuk menganalisis teks-teks kuno, menemukan makna tersembunyi yang hilang berabad-abad.
Kuil Kodaiji di Kyoto, Jepang, memperkenalkan Mindar, robot pendeta berbasis AI, untuk menyampaikan khotbah Buddha. Inisiatif ini bertujuan menarik minat generasi muda terhadap ajaran Buddha.
Tapi teknologi tidak menggantikan doa, tetapi menjadi lentera baru bagi pencarian batin. AI bukan ancaman bagi spiritualitas, melainkan jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam dan universal.
Penutup: Masa Depan Agama di Era AI
Untuk menjembatani agama dan spiritualitas modern, Esoterika Fellowship Program (EFP) dikembangkan sebagai ruang akademik untuk mengeksplorasi bagaimana agama, sains, dan AI dapat saling melengkapi.
Mulai semester ini, program EFP akan berjalan di kampus-kampus mitra, dan terus diperluas ke kampus lain yang berminat menjalin kerja sama.
Jika agama pernah bertahan melewati era cetak, radio, dan internet, bagaimana ia akan berevolusi di era AI?
Mungkinkah keimanan tidak lagi berbasis pada institusi, tetapi pada pengalaman personal yang lebih luas dan interaktif?
Mungkinkah di masa depan, agama bukan hanya tentang Tuhan, tetapi juga tentang pencarian makna dalam data dan algoritma?***
*Ahmad Gaus AF, Ketua Pelaksana Program EFP | Email: gaus.unas@gmail.com
