Resensi Buku Bayangan yang Tumbuh dari Revolusi: Membaca The New Class (1957) Karya Milovan Djilas
- Penulis : Irsyad Mohammad
- Senin, 04 Agustus 2025 16:45 WIB
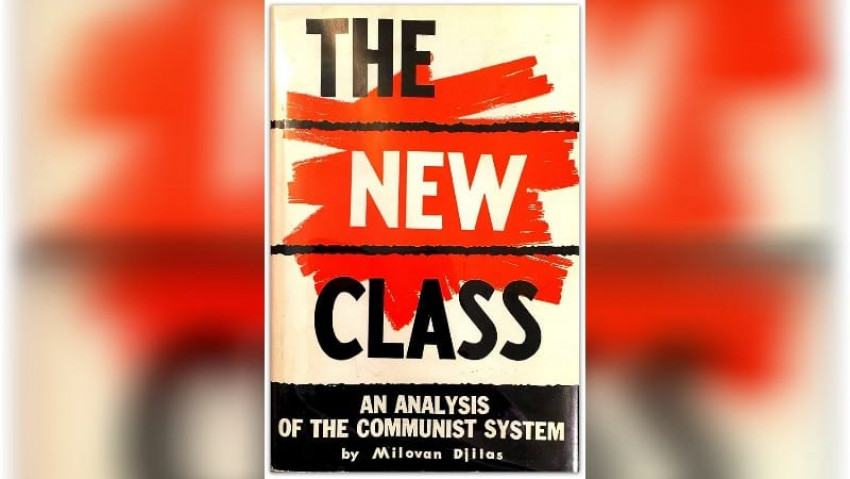
ORBITINDONESIA.COM- The New Class: An Analysis of the Communist System karya Milovan Djilas (1957) bukan sekadar sebuah buku; ia adalah semacam pengakuan berdarah dari dalam jantung kekuasaan, ditulis oleh seseorang yang tak hanya menyaksikan tetapi turut membangun istana ideologis yang kelak ia bongkar sendiri dengan pena. Buku ini adalah salah satu buku yang berpengaruh dalam sejarah Perang Dingin (1947-1991), sebab penulisnya sendiri adalah salah satu Founding Fathers Yugoslavia.
Djilas adalah seorang revolusioner komunis dari Montenegro, ia berjuang bersama Josip Broz Tito dalam Perang Dunia II melawan pendudukan Nazi Jerman, Fasis Italia, serta melawan Chetnik kelompok ekstrimis Serbia, dan rezim Ustaše yang merupakan pemerintahan fasis Kroasia yang menjadi boneka kelompok fasis di Yugoslavia.
Djilas adalah salah seorang Jenderal bintang 3 di Partisan Yugoslavia, ketika Yugoslavia terbentuk ia menjadi ideolog Partai Liga Komunis Yugoslavia. Djilas bersama Edvard Kardelj menjadi ideolog Liga Komunis Yugoslavia. Namun dalam perjalanan sejarahnya Djilas pecah kongsi dengan Tito, hingga ia menulis buku ini yang mengkritik tajam sistem komunisme bukan saja di Yugoslavia namun di seluruh negara komunis.
Baca Juga: Resensi Buku Kebangkitan Syiah: Islam, Konflik, dan Masa Depan
Ironis, ia menjadi lawan ideologi yang ia perjuangkan dan berakhir menjadi tahanan politik. Kendati demikian, Josip Broz Tito menghargainya sebagai mantan kamerad yang pernah berjuang bersama di medan perang, ia tidak membunuhnya ataupun menyiksanya sampai mati. Hal ini yang membedakan Tito dengan diktator komunis lainnya seperti Joseph Stalin.
Revolusi yang Memakan Anaknya Sendiri.
Tak semua pengkhianatan lahir dari niat jahat. Kadang ia tumbuh dari cinta yang terlalu dalam pada sebuah cita-cita yang kemudian retak. Milovan Djilas adalah salah satu dari mereka yang mencintai revolusi, lalu terbangun dari mimpinya saat mendapati bahwa revolusi yang telah diperjuangkannya, dengan darah dan harapan, telah melahirkan anak haram: sebuah kelas penguasa baru yang tak kalah rakus dari tiran yang mereka gulingkan.
Baca Juga: Resensi Buku Age of Empire: 1875–1914: Sihir Kekuasaan dan Darah Koloni
Buku The New Class, diterbitkan pada tahun 1957 di Barat setelah Djilas dijebloskan ke penjara oleh negara komunisnya sendiri, bukan sekadar sebuah karya politik. Ia adalah semacam kitab pertobatan yang getir, ditulis dengan kejernihan yang hanya bisa lahir dari seseorang yang pernah berada di lingkaran terdalam kekuasaan.
Tidak ada teori rumit atau jargon revolusioner yang membingungkan; yang ada hanyalah pengakuan jujur dan brutal bahwa sistem yang dibangun atas nama keadilan justru telah menumbuhkan ketidakadilan jenis baru—lebih rapi, lebih terorganisir, dan lebih sulit dibantah karena dibungkus dalam moralitas ideologi.
Djilas, sebagai mantan pejabat tinggi Partai Komunis Yugoslavia dan salah satu tangan kanan Tito, tidak berbicara dari jarak aman. Ia adalah bagian dari sistem itu sendiri. Ia pernah berdiri di podium revolusi, menyerukan emansipasi dari belenggu kapitalisme, dan mengangkat panji keadilan sosial.
Baca Juga: Resensi Buku Harus Bisa!: Membaca SBY, Mengupas Kekuasaan dengan Senyum dan Strategi
Tapi dalam perjalanannya, ia menyaksikan bagaimana partai yang dulu memperjuangkan kaum tertindas malah berubah menjadi mesin penindas. Ia menyaksikan munculnya “kelas baru”—sebuah kasta birokratik yang mengontrol alat produksi, distribusi, media, pendidikan, dan bahkan moralitas. Mereka tidak disebut borjuasi, tapi fungsi mereka identik: memonopoli kekuasaan dan sumber daya atas nama rakyat.
Tidak Menghapuskan Kelas, Malahan Menciptakan Kelas Baru.
Ada sesuatu yang mengerikan dalam cara Djilas menggambarkan kelas baru ini: mereka bukan predator yang tampak jahat. Mereka tidak hidup seperti raja atau industrialis zaman feodal. Justru karena mereka mengklaim berasal dari rakyat, mereka menyaru dalam bahasa kerakyatan, menutupi dominasi dengan retorika pengorbanan.
Tapi di balik pidato-pidato tentang perjuangan dan kesetaraan, mereka menikmati privilese: rumah dinas, mobil dinas, akses eksklusif ke pendidikan dan kesehatan, bahkan hak untuk menentukan siapa yang layak berbicara dan siapa yang layak dilenyapkan dari sejarah.
Buku ini menggelitik imajinasi kita karena ia tidak berhenti sebagai kritik atas komunisme. Ia bergerak lebih jauh: menjadi cermin untuk segala sistem kekuasaan. Bacalah The New Class hari ini di tengah demokrasi elektoral yang katanya bebas, dan kita akan terkejut betapa familier deskripsi Djilas itu.
Bukankah kita mengenal para elit yang lahir dari “partai rakyat” tapi kemudian hidup dalam pagar tinggi dan tidak bisa lagi mendengar jeritan jalanan? Bukankah jargon tentang “keadilan sosial” sering menjadi mantera yang menghipnosis, tapi melindungi status quo yang tak tersentuh?
Djilas tidak mengusulkan kudeta baru. Ia tidak menyarankan kembalinya kapitalisme atau sistem liberal. Ia bahkan tidak menawarkan cetak biru alternatif. Justru kejujuran inilah yang membuat bukunya terasa otentik dan menyakitkan: ia hanya memotret dengan setia, tanpa perlu menggiring pembaca pada simpulan tertentu.
Ia hanya menunjukkan, bahwa dalam sistem yang mengklaim dirinya sebagai perwujudan tertinggi dari kesetaraan, terdapat struktur yang tidak kasat mata—hierarki yang tidak disebut kelas, tapi berfungsi layaknya kasta yang memutuskan siapa boleh naik, siapa tetap di bawah.
Kekecewaan Djilas atas Ideologi yang Diperjuangkannya dan Keterasingannya Sendiri.
Apa yang paling menghantui dari buku ini adalah narasi tentang keterasingan. Dalam dunia yang dikontrol oleh kelas baru, rakyat tidak hanya kehilangan kekuasaan, tetapi juga kehilangan bahasa untuk menamai penderitaannya. Karena semua dilakukan “atas nama mereka,” maka tidak ada ruang untuk oposisi.
Kritik dianggap sabotase. Keraguan dianggap pengkhianatan. Maka manusia menjadi bisu dalam keterpaksaan. Mereka bekerja untuk negara, tapi negara bukan lagi mereka. Negara adalah wajah kolektif dari para birokrat yang telah menjelma menjadi dewa-dewa kecil, tak terjangkau, tak tergugat.
Kita mungkin mengira bahwa Djilas hanya bicara tentang Yugoslavia atau Stalinisme. Tapi sesungguhnya, ia sedang bicara tentang psikologi kekuasaan itu sendiri: bagaimana idealisme berubah menjadi alat dominasi, bagaimana orang-orang yang dahulu memproklamasikan revolusi perlahan berubah menjadi pelindung status quo, dan bagaimana kekuasaan, jika tak terus diawasi, akan menemukan bentuk baru untuk mempertahankan dirinya, bahkan dalam sistem yang paling revolusioner sekalipun.
Salah satu bagian paling menggetarkan adalah ketika Djilas menyatakan bahwa kelas baru ini tidak akan bisa direformasi dari dalam, karena keberadaan mereka sendiri adalah hasil logis dari struktur sistem. Dengan kata lain, Anda tidak bisa menghapus kasta birokrat tanpa merombak total cara kita memahami kekuasaan dan representasi.
Kritik Djilas bukanlah sekadar koreksi manajerial—ini adalah gugatan moral terhadap seluruh premis sistem satu partai, dan bahkan terhadap ilusi bahwa negara bisa bertindak mewakili “kelas” secara sempurna.
Djilas menulis The New Class dengan ketenangan yang ironis. Tidak ada kemarahan meluap, tidak ada agitasi. Justru dalam ketenangan itu kita merasakan kekuatan kata-katanya. Ia seperti orang yang telah menyaksikan rumahnya sendiri terbakar—bukan oleh musuh, tapi oleh tangan saudaranya sendiri. Ia tidak menjerit. Ia hanya menunjuk ke api dan berkata: “Inilah harga dari kebutaan kita.”
Setelah membaca The New Class, kita tidak bisa lagi melihat konsep revolusi dengan naif. Kita tidak bisa lagi percaya begitu saja bahwa perubahan struktural pasti menghasilkan masyarakat yang adil. Karena sejarah, sebagaimana Djilas tunjukkan, terlalu sering memperlihatkan bahwa struktur baru hanya akan dihuni oleh elite baru yang lebih canggih dalam menyamarkan dominasinya.
Di titik itulah, mungkin, buku ini mencapai kekuatan filosofisnya: sebagai refleksi tentang watak manusia dalam kekuasaan. Betapa mudahnya manusia merasionalisasi dominasi jika ia merasa sedang melayani tujuan mulia. Betapa cepatnya idealisme berubah menjadi justifikasi bagi kenyamanan pribadi.
Penutup
Milovan Djilas dihukum oleh negaranya bukan karena ia mengangkat senjata, tetapi karena ia mengangkat kata-kata. Dan mungkin itulah yang paling ditakuti oleh kelas baru di mana pun mereka berada: seseorang dari dalam, yang menolak berbohong atas nama ideologi, dan memilih membayar harga penuh demi kejujuran.
Kini, lebih dari setengah abad sejak buku ini terbit, kita hidup di era baru. Tapi bayangan kelas baru Djilas masih menghantui dalam bentuk lain: teknokrat, oligark, influencer politik, pejabat meritokratik, dan bahkan dalam organisasi yang katanya nirlaba tapi beroperasi seperti korporasi. Semua mengklaim melayani publik. Tapi siapa yang mengevaluasi mereka? Siapa yang menyuarakan mereka yang tak lagi memiliki suara?
Barangkali, itulah warisan terbesar Djilas: mengingatkan kita bahwa revolusi tanpa pengawasan rakyat akan selalu melahirkan istana baru. Dan istana, betapapun indahnya dibangun atas nama rakyat, akan tetap menjadi istana—yang didiami bukan oleh rakyat, tapi oleh bayangan-bayangan baru kekuasaan.***
