Resensi Buku Age of Empire: 1875–1914: Sihir Kekuasaan dan Darah Koloni
Kita akan membahas sebuah buku monumental dan sangat berpengaruh dalam historiografi dunia, sebuah buku karya sejarawan terkemuka dunia Eric J. Hobsbawm. Ia bukanlah sejarawan sembarangan karena Hobsbawm terkenal sebagai sejarawan marxis dan orang yang menulis sejarah dengan pendekatan marxis. Saking fenomenalnya buku ini sampai dijadikan judul seri game Age of Empires, sebuah game yang sangat terkenal di kalangan pecinta game strategi (Real Time Strategy/RTS).
Seandainya sejarah bisa membisik seperti angin di tengah malam gurun, maka Eric J. Hobsbawm adalah salah satu dari sedikit penulis yang mampu menjadi juru bicara bisikan itu. Dalam Age of Empire: 1875–1914 (1987), buku ketiga dari tetralogi monumentalnya, ia tidak sekadar menyusun peristiwa demi peristiwa, melainkan memanggil kembali roh-roh sejarah yang selama ini tertidur di lorong-lorong museum dan catatan akademik. Ia bukan hanya sejarawan. Ia adalah seorang dukun zaman, penyair kekuasaan, dan pengukir tafsir kolektif.
Pada tataran permukaan, Age of Empire adalah kisah tentang dunia antara dua zaman besar: ketika Eropa sedang berada di puncak kekuasaan globalnya, dan sebelum dunia terjerembab dalam kobaran Perang Dunia I. Tapi di tangan Hobsbawm, kisah ini menjadi jauh lebih dari sekadar narasi geopolitik. Ia berbicara tentang apa artinya menjadi manusia dalam dunia yang sedang berubah cepat: ketika kebudayaan, teknologi, kekuasaan, dan ideologi saling bersilangan dan bertabrakan.
Kapitalisme dan Mesin yang Mengatur Dunia
Sejak awal, Hobsbawm menggambarkan dunia akhir abad ke-19 sebagai dunia yang telah direnggut dari akarnya oleh revolusi industri kedua. Perubahan yang dibawa oleh listrik, kimia, dan mekanisasi bukan hanya menciptakan jenis pekerjaan baru, tetapi juga menciptakan jenis manusia baru. Dunia lama yang bersandar pada komunitas dan ritme alami mulai digantikan oleh waktu pabrik, kecepatan, dan sistem kerja yang menaklukkan tubuh. Ia mengutip angka, memaparkan tren ekonomi, namun tetap menyelipkan kesadaran puitis: bahwa di balik grafik pertumbuhan ekonomi, ada tubuh-tubuh yang kelelahan dan mimpi-mimpi yang tercerabut.
Kapitalisme, dalam narasi ini, bukan semata sistem ekonomi, melainkan cara hidup baru. Hobsbawm menunjukkan bagaimana kapitalisme menyusun kembali kota, memahat ulang keluarga, dan mengatur seksualitas. Ia memahami bahwa ekonomi bukan sekadar soal pasar dan angka, tapi soal bagaimana manusia hidup, mencintai, melahirkan, dan mati. Sejarah sosial dan ekonomi melebur dalam lanskap yang utuh—dari perubahan dalam pola konsumsi hingga lahirnya kelas menengah urban.
Tapi kapitalisme juga menciptakan momoknya sendiri: ketimpangan. Saat segelintir elit hidup dalam dekadensi yang belum pernah ada sebelumnya, mayoritas buruh, petani, dan koloni dijadikan kaki tangga sejarah. Di sinilah Hobsbawm mulai menyusun narasi dialektis khas Marxis—tentang kontradiksi internal yang perlahan membusukkan kemegahan zaman keemasan itu dari dalam.
Imperium Sebagai Imajinasi Politik dan Budaya
Imperium, bagi Hobsbawm, bukanlah struktur kosong. Ia adalah upaya kolektif untuk membenarkan dominasi. Eropa tidak hanya menjajah tanah, tapi juga membangun narasi yang melegitimasi penjajahan. Mereka menciptakan ilmu pengetahuan kolonial, dari etnografi hingga linguistik, dari botani tropis hingga kajian ras, semua untuk menempatkan dunia non-Barat sebagai “yang lain”, yang eksotis, yang harus diselamatkan, dididik, atau dikendalikan.
Yang menarik, Hobsbawm tidak menulis dengan kemarahan—ia menulis dengan semacam ironi tajam, seolah menertawakan kemegahan imperium yang ia tahu akan runtuh. Ia tidak sedang menulis eulogi untuk Barat, melainkan otopsi—menunjukkan bagaimana kegemilangan mereka penuh luka dan darah. Ia bahkan menyuguhkan statistik dan cerita yang kadang saling bertolak belakang, sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sejarah tidak pernah tunggal atau stabil. Setiap kekuasaan yang besar pasti menulis ulang versinya sendiri, tapi Hobsbawm ingin mengungkap yang disembunyikan oleh versi resmi itu.
Lebih dari itu, ia menunjukkan bahwa imperialisme tidak hanya berperan di ranah geopolitik, tetapi juga dalam formasi budaya populer: pameran dunia, novel-novel petualangan kolonial, serta imajinasi visual tentang dunia Timur yang sensual dan “liar”. Sebelum dunia didominasi oleh Marvel dan Netflix, dunia sudah dikuasai oleh narasi kolonial—dalam bentuk Jules Verne, Kipling, atau bahkan sains-voyage.
Kelas, Nasionalisme, dan Ledakan Politik yang Akan Datang
Salah satu kekuatan utama Age of Empire terletak pada cara Hobsbawm membingkai kelas dan nasionalisme secara bersamaan sebagai dua kekuatan besar yang membentuk abad ke-20. Kelas adalah realitas objektif, kata Hobsbawm—ia lahir dari hubungan produksi dan struktur ekonomi. Tapi nasionalisme adalah realitas subjektif, dibangun oleh simbol, bahasa, mitos, dan imajinasi kolektif.
Keduanya, dalam periode ini, saling silang. Di Eropa, kelas buruh mulai menyadari kekuatannya dan membangun serikat, partai politik, bahkan ideologi internasionalisme proletar. Tapi di banyak tempat di dunia kolonial, nasionalisme adalah cara untuk melawan penjajahan, membangun solidaritas berdasarkan identitas etnis atau kebangsaan. Hobsbawm tidak meromantisasi keduanya. Ia menunjukkan bahwa nasionalisme bisa menjadi senjata pembebasan, tapi juga menjadi alat represi dan chauvinisme.
Di sinilah ketajaman analisis Hobsbawm terasa menggigit. Ia paham bahwa sejarah bukan panggung pertunjukan heroisme, melainkan arena perebutan tafsir dan kekuasaan. Nasionalisme yang hari ini diagungkan sebagai wujud cinta tanah air, dalam banyak kasus dulunya hanyalah alat untuk memperkuat negara, membungkam perbedaan, dan memobilisasi rakyat untuk perang.
Ia menuliskan semua ini tanpa menjadi sinis. Justru karena ia begitu percaya pada potensi emansipatoris sejarah, ia sangat kritis terhadap segala bentuk mitos yang membius.
Resonansi di Era Digital dan Neo-Imperium
Apa yang membuat Age of Empire relevan hari ini bukan hanya karena ketepatan historisnya, tetapi karena struktur kekuasaan yang ia bedah masih berulang dalam bentuk-bentuk baru. Hari ini kita tidak lagi hidup dalam dunia imperium formal, tetapi dalam jaringan kekuasaan transnasional: perusahaan teknologi, jaringan militer, sirkuit kapital, dan data. Jika dulu Eropa mengontrol dunia dengan kapal dan senjata, kini imperium bekerja melalui kabel internet, lembaga rating kredit, dan platform media sosial.
Konsep “peta”, “pengetahuan”, dan “kontrol” yang dijelaskan Hobsbawm kini berubah bentuk menjadi big data, surveillance capitalism, dan kecerdasan buatan. Kita hidup dalam dunia pasca-imperial, tetapi dengan logika imperial yang masih hidup dan sehat.
Bahkan ketika kita bicara tentang nasionalisme digital—dari kampanye disinformasi hingga pembentukan identitas kolektif melalui algoritma—kita masih bisa menggunakan kerangka Hobsbawm untuk memahami apa yang sedang terjadi. Maka, membaca Age of Empire hari ini adalah seperti membaca buku sihir kuno yang kebetulan bisa menjelaskan dunia modern secara mengejutkan presisi.
Penutup: Membaca Sejarah untuk Meraba Masa Depan
Eric Hobsbawm menulis sejarah bukan untuk mengagumi masa lalu, tapi untuk memahami dunia yang terus bergerak. Dalam Age of Empire, ia seperti sedang menulis laporan intelijen dari masa lalu kepada generasi yang hidup hari ini. Ia tahu, kekuasaan selalu berubah bentuk, tapi selalu punya wajah yang bisa dikenali: keserakahan, superioritas, dan penindasan.
Namun Hobsbawm juga seorang humanis. Di balik seluruh analisisnya tentang kekuasaan, ia percaya pada kemungkinan perubahan. Ia menaruh harapan pada kelas buruh, pada mereka yang ditindas, pada kebangkitan kesadaran kritis. Mungkin itu sebabnya ia tidak pernah menulis dengan dingin, melainkan dengan nyala yang konsisten: bahwa sejarah adalah medan perjuangan.
Dan mungkin hari ini, ketika kita dikelilingi oleh banjir informasi, pelurusan sejarah, dan propaganda digital, kita lebih butuh Age of Empire daripada sebelumnya. Sebab hanya dengan menelusuri asal usul kekuasaan kita bisa memahami bentuk-bentuk barunya. Dan hanya dengan menggali luka-luka masa lalu kita bisa menyembuhkan dunia yang semakin terpecah.
Hobsbawm menulis sejarah, tapi yang sesungguhnya ia bangun adalah kesadaran. Dan seperti semua kesadaran yang mengganggu kenyamanan, buku ini tidak akan membuatmu nyaman. Tapi ia akan membuatmu bangun.

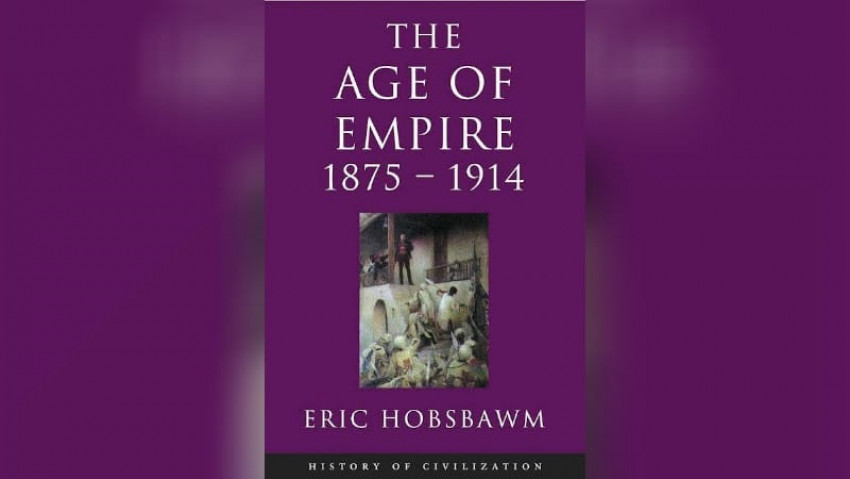







.jpeg)


