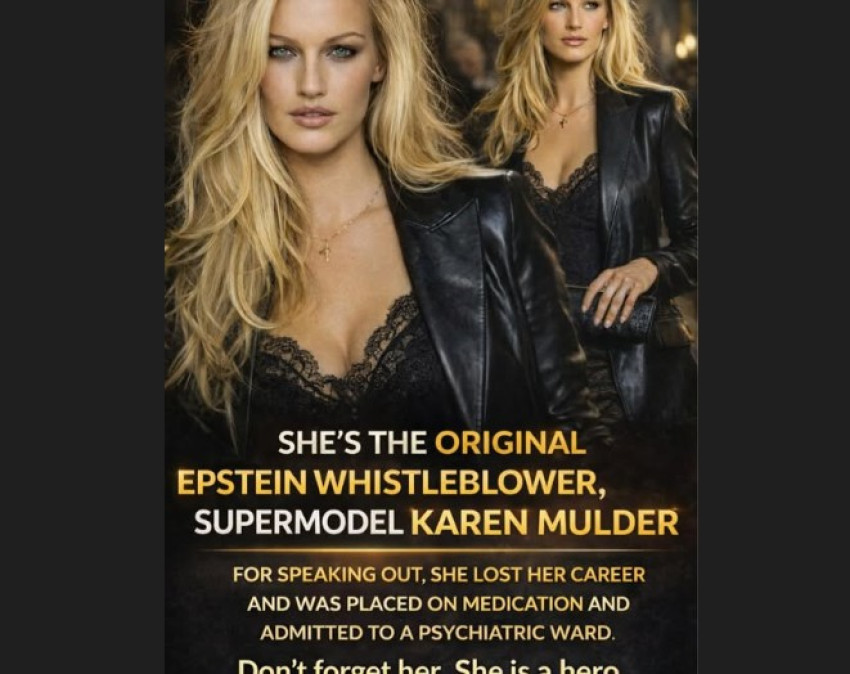Albertus N. Patty: Refleksi Akhir Tahun - Merubuhkan Mentalitas Kolonial
Oleh Albertus N. Patty
ORBITINDONESIA.COM - Di penghujung tahun 2025 ini, saat kaum muda siap menyambutnya dengan pesta, saya teringat pada segelintir kaum muda yang dijeblos dalam penjara. Penyebabnya? Sikap kritis mereka terhadap negara. Daya kritis mereka pun dibungkam. Padahal itulah modal terbesar untuk menjadi bangsa yang maju dan berhasil. Saat suara kritis dibungkam, kemerdekaan menjadi fatamorgana.
Memang, kemerdekaan sebuah bangsa belum selesai saat bendera dikibarkan dan lagu kebangsaan dinyanyikan. Kemerdekaan, menurut Homi K. Bhabha dalam The Location of Culture, adalah proses yang rapuh, selalu berada di antara—di ruang liminal—tempat makna kebebasan terus dinegosiasikan. Di ruang inilah peran kaum muda menjadi penentu: apakah bangsa bergerak ke depan, atau justru mengulang logika lama dengan wajah baru.
Ironi Bangsa
Sejarah Indonesia menunjukkan dengan terang bahwa kemerdekaan lahir dari kaum muda yang tidak patuh secara membuta. Mereka adalah generasi yang berani berpikir, berani mengkritik, dan berani mengambil risiko.
Dalam bahasa Bhabha, mereka menciptakan “third space”, ruang antara, yang memungkinkan lahirnya imajinasi politik baru: Indonesia yang bebas dari kolonialisme, bukan hanya secara administratif dan politik, tetapi, ini yang terpenting, bebas juga secara mental dan kultural.
Namun justru di sinilah ironi bangsa Indonesia hari ini. Negara yang lahir dari keberanian kaum muda kritis kini tampak gelisah menghadapi penguasa bangsa sendiri. Kaum muda yang bersuara dengan data, analisis, dan komitmen kebangsaan tidak diperlakukan sebagai mitra dialog, melainkan sebagai gangguan stabilitas.
Menurut Bhabha, ini adalah gejala klasik negara poskolonial: kekuasaan yang secara formal telah merdeka, tetapi secara simbolik masih mewarisi watak kolonial: takut pada ambiguitas, alergi pada kritik, dan obsesif pada kontrol.
Mentalitas Kolonial
Negara yang dikelola dengan mentalitas kekuasaan ala kolonial ini cenderung merasa terancam oleh mereka yang berada “di antara”: tidak sepenuhnya tunduk, tidak pula sepenuhnya di luar sistem. Kaum muda kritis Indonesia hari ini persis berada di posisi itu.
Mereka tidak anti-negara, tetapi juga tidak mau menjadi alat legitimasi kekuasaan. Mereka mencintai bangsa ini, justru karena itu mereka bersuara. Tetapi dalam logika kekuasaan dengan mentalitas kolonialistik, kritik semacam ini dibaca sebagai pembangkangan.
Penangkapan dan pemenjaraan kaum muda kritis dan punya komitmen kebangsaan dan kemanusiaan, menandai kegagalan negara membaca ruang antara yang dibicarakan Bhabha.
Negara memilih menutup ruang negosiasi makna, dan menggantinya dengan pemaksaan makna tunggal: stabilitas, ketertiban, dan loyalitas tanpa dialog. Inilah momen ketika kemerdekaan berubah menjadi slogan, bukan praktik hidup.
Ironisme ini mengajak kita bertanya dengan jujur: apakah Indonesia sedang membangun masa depan, atau justru sedang membangkitkan kekuasaan kolonialisme masa lalu?
Bangsa yang takut pada daya kritis kaum mudanya sesungguhnya sedang ketakutan pada bayangan kolonial yang belum benar-benar ia kalahkan. Kaum muda yang cerdas dan maju adalah mereka yang mampu bersikap kritis. Tidak ada niat merubuhkan negara. Tujuan mereka adalah merubuhkan mentalitas kolonial oknum penguasa.
Bila negara memiliki komitmen besar terhadap generasi emas maka jalan ke depan bukanlah membungkam sikap kritis kaum muda, melainkan merawat third space—ruang dialog yang mengakui kompleksitas, perbedaan, dan ketegangan. Di sanalah demokrasi bernapas. Di sanalah kaum muda bertumbuh dewasa dan kemerdekaan kita diuji ulang, bukan untuk dilemahkan, tetapi untuk dimatangkan.
Bandung, 30 Desember 2025 ***