Resensi Buku Why Nations Fail (2012) karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson: Analisis Kegagalan Sebuah Negara
- Penulis : Irsyad Mohammad
- Selasa, 05 Agustus 2025 16:14 WIB
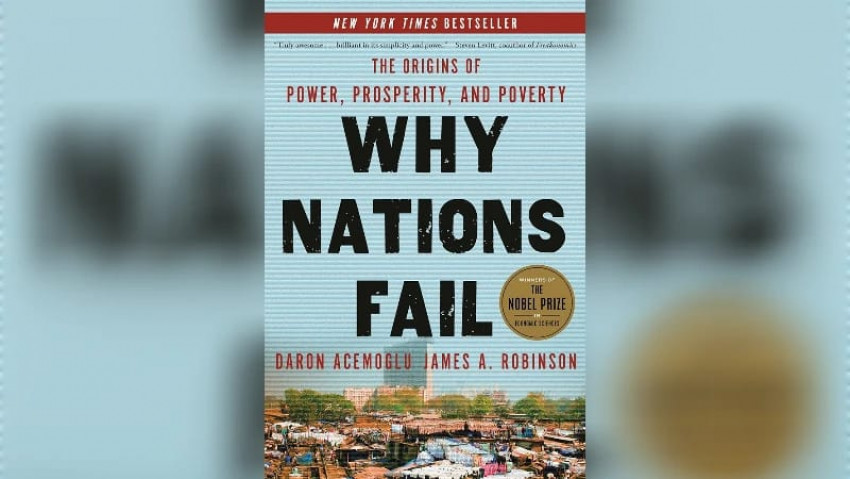
ORBITINDONESIA.COM- Jika Anda pernah bertanya mengapa sebagian negara melesat menjadi pusat kemakmuran sementara yang lain terjebak dalam kemiskinan yang tampak abadi, maka buku best-seller berjudul Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2012) adalah solusinya. Buku ini menawarkan jawabannya dengan ketajaman analisis dan kisah sejarah yang memukau. Lewat perpaduan riset ekonomi, politik, dan sejarah lintas benua, buku ini membongkar mitos-mitos lama tentang peran geografi atau budaya, dan menempatkan institusi politik sebagai kunci nasib bangsa. Dari perbatasan Nogales yang terbelah antara AS dan Meksiko, hingga kisah jatuh-bangunnya negara-negara Afrika, Asia, dan Eropa, pembaca diajak memahami bahwa kemakmuran lahir dari sistem yang inklusif—dan bahwa kemiskinan sering kali bukan takdir, melainkan hasil dari pilihan kekuasaan yang disengaja.
Kemakmuran Bukan Soal Letak, Sumber Daya, atau Budaya
Sejak lama, para ekonom dan sejarawan mencari jawaban mengapa sebagian negara kaya, sementara yang lain tetap miskin. Ada yang menyalahkan letak geografis, ada yang menunjuk rendahnya sumber daya alam, ada pula yang menuduh budaya tertentu kurang mendukung kemajuan. Why Nations Fail hadir untuk membongkar mitos itu dengan tegas.
Daron Acemoglu dan James A. Robinson memulai bukunya dengan serangkaian contoh mencolok: perbatasan Nogales di Amerika Serikat dan Meksiko, Korea Utara dan Korea Selatan, bahkan Botswana dan negara-negara Afrika lain yang memiliki kondisi alam serupa. Mereka menunjukkan bahwa perbedaan nasib bukanlah hasil dari geografi atau etnis, melainkan dari institusi politik dan ekonomi yang dibangun di negara tersebut.
Kuncinya ada pada dua tipe institusi: inklusif dan ekstraktif. Institusi inklusif memberi hak dan peluang luas kepada warga untuk berpartisipasi dalam politik dan ekonomi, menciptakan inovasi, dan mempertahankan hak milik. Institusi ekstraktif, sebaliknya, dikuasai oleh segelintir elite yang menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri, membatasi akses, dan menyingkirkan pesaing. Perbedaan inilah yang menentukan apakah sebuah negara akan tumbuh subur atau terjebak dalam kemiskinan sistemik.
Bagi Acemoglu dan Robinson, kemakmuran bukanlah hadiah alam, melainkan buah dari rekayasa politik. Negara dengan institusi inklusif, seperti Inggris setelah Revolusi Glorious 1688, memiliki fondasi untuk tumbuh. Sementara negara dengan institusi ekstraktif, meski kaya sumber daya seperti Sierra Leone atau Venezuela, justru terjebak dalam “kutukan sumber daya” karena kekayaan itu dipakai untuk memperkuat cengkeraman elite, bukan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Resensi Buku Collapse (2005): How Societies Choose to Fail or Succeed Karya Jared Diamond
Politik adalah Jantung Ekonomi
Buku ini menolak pandangan sempit bahwa ekonomi bisa berkembang hanya dengan kebijakan teknis atau resep pembangunan yang bersifat netral. Acemoglu dan Robinson menunjukkan bahwa di balik setiap kebijakan ekonomi, ada perebutan kekuasaan politik yang menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan.
Mereka memperkenalkan konsep critical junctures—momen sejarah yang membuka peluang perubahan besar, seperti perang, revolusi, atau krisis ekonomi. Negara yang memiliki elite politik mau berbagi kekuasaan biasanya mampu memanfaatkan momen itu untuk membangun institusi inklusif. Namun, di negara dengan elite yang takut kehilangan posisi, momen krisis justru dimanfaatkan untuk memperkuat institusi ekstraktif.
Contohnya, Revolusi Industri hanya mungkin berkembang di Inggris karena ada perlindungan hak paten, kebebasan berusaha, dan sistem hukum yang relatif independen. Sementara di Kekaisaran Austria-Hungaria atau Kekaisaran Ottoman, teknologi baru dihambat karena dianggap mengancam monopoli ekonomi kaum bangsawan.
Inti argumen mereka jelas: ekonomi tidak bisa dipisahkan dari politik. Selama kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir orang, inovasi akan dibatasi, investasi tidak aman, dan peluang ekonomi hanya akan menguntungkan kelompok tertentu. Inilah sebabnya mengapa “reformasi ekonomi” tanpa reformasi politik sering gagal total—karena akar masalahnya tidak disentuh.
Salah satu bagian paling kuat dari Why Nations Fail adalah penjelasan tentang vicious circle—lingkaran setan ekstraksi. Begitu institusi ekstraktif berkuasa, mereka menciptakan aturan yang membuat rakyat sulit melawan dan elite semakin kuat. Kekuasaan ini kemudian digunakan untuk mempertahankan struktur yang ada, menghalangi semua upaya reformasi yang mengancam status quo.
Kita melihat ini di banyak negara yang mencoba “demokratisasi” setelah jatuhnya rezim otoriter, tetapi akhirnya kembali terjebak pada oligarki atau kleptokrasi. Para penulis memberi contoh Republik Demokratik Kongo, di mana warisan eksploitasi kolonial Belgia dilanjutkan oleh elite lokal, dan reformasi hanya menjadi kosmetik.
Namun, buku ini juga menunjukkan virtuous circle—lingkaran kebajikan. Negara yang berhasil membangun institusi inklusif cenderung mempertahankannya karena ada mekanisme check and balance yang kuat, partisipasi luas, dan hukum yang melindungi hak-hak minoritas sekalipun. Amerika Serikat, meski menghadapi tantangan serius, menjadi contoh bahwa institusi inklusif dapat bertahan selama ada perlawanan publik terhadap upaya ekstraksi.
Yang membuat buku ini menggugah adalah pengakuan bahwa perubahan tidak mudah. Institusi inklusif lahir dari konflik, negosiasi, dan kadang revolusi. Dan bahkan setelah lahir, ia selalu terancam. Inklusivitas bukanlah kondisi permanen; ia bisa runtuh bila kekuasaan kembali terkonsentrasi.
Penutup: Belajar dari Peta Sejarah Kekuasaan
Why Nations Fail pada akhirnya bukan hanya buku ekonomi politik, tetapi peta moral tentang kekuasaan. Ia mengajak pembaca melihat sejarah bukan sebagai rentetan kebetulan, melainkan sebagai hasil dari pilihan politik yang disengaja—pilihan untuk berbagi atau mempertahankan kekuasaan.
Pesannya sederhana namun tajam: kemakmuran yang berkelanjutan hanya mungkin tercapai jika kekuasaan politik bersifat inklusif. Begitu kekuasaan itu menyempit dan ekonomi diarahkan untuk melayani segelintir orang, kemiskinan dan stagnasi adalah konsekuensi logisnya.
Buku ini membuat kita waspada terhadap narasi pembangunan yang menjanjikan kemakmuran tanpa demokrasi, atau reformasi ekonomi tanpa reformasi politik. Ia juga menantang pembaca untuk menilai negaranya sendiri: apakah kita sedang membangun lingkaran kebajikan, atau justru terjebak dalam lingkaran setan ekstraksi?
Di luar semua data dan teori, Why Nations Fail adalah peringatan: nasib bangsa bukanlah takdir yang ditulis oleh geografi atau etnis. Ia adalah hasil dari institusi yang kita biarkan tumbuh. Dan institusi, seperti kebun, bisa dipelihara dengan keterbukaan dan partisipasi—atau dibiarkan layu dalam naungan tembok kekuasaan yang terlalu tinggi. Pilihan itu, pada akhirnya, selalu ada di tangan kita.***
