Resensi Buku How Democracies Die (2018) Karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt: Membaca Ulang Demokrasi Kontemporer
- Penulis : Irsyad Mohammad
- Selasa, 05 Agustus 2025 15:42 WIB
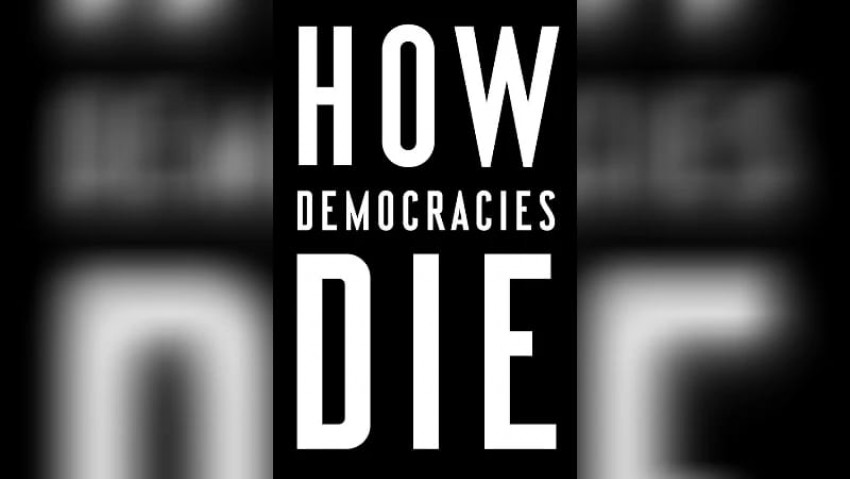
ORBITINDONESIA.COM- Tulisan ini Adalah sebuah resensi buku best-seller di dunia internasional yang menjadi catatan kritis terhadap demokrasi kita hari ini. Buku yang ditulis oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt serta terbit pada 2018 ini mengajak kita untuk merenungi demokrasi kita hari ini. Kedua ilmuwan politik dari Universitas Harvard ini menulis dengan baik sekali, bahkan memberikan komparasi politik atas berbagai pelaksanaan demokrasi di dunia.
Demokrasi Tidak Mati dengan Dentuman, Tapi dengan Tepuk Tangan
Kita sering membayangkan akhir dari sebuah demokrasi sebagai sesuatu yang dramatis—kudeta militer, bentrokan berdarah, atau parade tank di jalanan. Namun Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt mengajak kita membuang imajinasi Hollywood itu. Dalam Why Democracies Die, mereka menunjukkan kenyataan yang lebih sunyi sekaligus lebih mengerikan: demokrasi sering kali mati perlahan, tidak dengan ledakan, melainkan dengan tepuk tangan rakyatnya sendiri. Bukan oleh pemberontak yang datang dari luar, tetapi oleh pemimpin yang lahir dari kotak suara.
Baca Juga: Resensi Buku Age of Empire: 1875–1914: Sihir Kekuasaan dan Darah Koloni
Buku ini membawa kita mengintip lembar-lembar sejarah kontemporer: Hugo Chávez di Venezuela, Viktor Orbán di Hungaria, Recep Tayyip Erdoğan di Turki, bahkan Donald Trump di Amerika Serikat. Mereka tidak pernah tampil sebagai musuh demokrasi. Sebaliknya, mereka membungkus diri sebagai pembaharu yang datang untuk “memurnikan” sistem. Namun, langkah demi langkah, mereka melemahkan institusi, mengganggu independensi pengadilan, mengintimidasi pers, dan membatasi oposisi.
Yang membuat proses ini begitu sulit dideteksi adalah kemampuannya menyaru sebagai reformasi. Rakyat menyambutnya karena percaya inilah jalan menuju demokrasi yang lebih bersih. Padahal, perlahan-lahan, jalan itu mengarah pada demokrasi yang tinggal kulitnya saja. Levitsky dan Ziblatt seperti berkata: “Kita tak akan sadar demokrasi telah mati, sampai kita bangun dan mendapati bahwa semua pintu sudah terkunci dari dalam.”
Norma Tak Tertulis: Tiang Penyangga yang Runtuh Tanpa Suara
Salah satu gagasan paling kuat dari buku ini adalah bahwa demokrasi tidak hanya disangga oleh konstitusi dan hukum tertulis. Ia juga bertumpu pada norma tak tertulis—kontrak sosial yang rapuh—yang mengatur perilaku para politisi. Dua di antaranya menjadi inti pembahasan: mutual toleration (pengakuan bahwa lawan politik adalah rival sah, bukan musuh yang harus dimusnahkan) dan institutional forbearance (kesediaan menahan diri untuk tidak menggunakan semua kekuasaan legal yang dimiliki demi keuntungan jangka pendek).
Ketika norma-norma ini terkikis, demokrasi mulai meranggas dari dalam. Para politisi menggunakan setiap celah hukum untuk menekan lawan. Oposisi tidak lagi dianggap bagian dari demokrasi, melainkan ancaman eksistensial. Setiap tindakan dibenarkan demi “menyelamatkan negara” dari mereka. Dan begitu mutual toleration hilang, semua kompromi menjadi mustahil; yang tersisa hanyalah pertarungan zero-sum.
Levitsky dan Ziblatt menelusuri sejarah Amerika untuk menunjukkan bahwa bahkan negara yang dianggap benteng demokrasi pun tidak kebal dari erosi norma ini. Di masa lalu, politik AS juga pernah diracuni oleh polarisasi ekstrem—dari era Perang Sipil hingga masa segregasi rasial. Bedanya, dulu ada mekanisme informal yang menahan politisi untuk tidak memukul lawan sampai mati secara politik. Kini, mekanisme itu runtuh di tengah arus media partisan, krisis kepercayaan publik, dan strategi politik yang memanfaatkan kemarahan sebagai bahan bakar elektoral.
Baca Juga: Resensi Buku Collapse (2005): How Societies Choose to Fail or Succeed Karya Jared Diamond
Norma ini, kata mereka, runtuh bukan dengan gebrakan, tapi dengan pembiaran. Seperti rayap, ia menggerogoti kayu dari dalam, sampai suatu hari tiang demokrasi ambruk, dan kita baru sadar betapa rapuhnya ia sejak awal.
Kematian Demokrasi Dimulai dari Pilihan Kita Sendiri
Poin paling mengguncang dari Why Democracies Die adalah bahwa keruntuhan demokrasi bukanlah bencana alam; ia adalah hasil dari serangkaian pilihan sadar—baik oleh elite maupun rakyat biasa. Demokrasi bisa mati justru karena rakyat memilih pemimpin yang menggerogotinya, entah karena marah pada sistem lama, tergoda janji perubahan cepat, atau terpesona pada figur yang “berani melawan arus.”
Levitsky dan Ziblatt menggarisbawahi empat tanda bahaya pada politisi yang berpotensi menjadi penggali kubur demokrasi: menolak atau meremehkan aturan main demokrasi, menyangkal legitimasi lawan politik, mendorong atau membenarkan kekerasan, serta menunjukkan kecenderungan membatasi kebebasan sipil. Masalahnya, tanda-tanda ini sering diabaikan saat pemimpin tersebut berada di pihak kita. Kita memberi mereka cek kosong dengan keyakinan bahwa mereka hanya akan menggunakannya melawan “musuh”. Padahal, sekali kekuasaan itu terkonsolidasi, siapa pun bisa menjadi targetnya.
Buku ini tidak berakhir dengan pesimisme mutlak. Ia menawarkan jalan keluar: menghidupkan kembali norma-norma politik, membangun kembali toleransi, dan memperkuat lembaga demokrasi. Namun Levitsky dan Ziblatt realistis: semua itu memerlukan kesadaran kolektif. Demokrasi tidak akan bertahan hanya dengan prosedur pemilu; ia memerlukan budaya politik yang menganggap lawan sebagai bagian dari permainan, bukan ancaman yang harus dilenyapkan.
Mereka menutup dengan peringatan halus: demokrasi mati bukan karena rakyatnya tidak mencintainya, tapi karena mereka membiarkan rasa takut, marah, dan dendam mengambil alih. Dan saat itu terjadi, rakyat justru akan mengantar demokrasi ke kuburnya—dengan tepuk tangan, bukan protes.
Penutup
Pada akhirnya, Why Democracies Die bukan sekadar buku analisis politik; ia adalah cermin yang memantulkan wajah kita sendiri, sebagai warga negara. Levitsky dan Ziblatt memaksa kita untuk melihat bahwa menjaga demokrasi bukan tugas segelintir politisi atau lembaga hukum, tetapi tanggung jawab kolektif yang dimulai dari pilihan sehari-hari: bagaimana kita berbicara tentang lawan politik, bagaimana kita mengonsumsi berita, bagaimana kita merespons janji-janji yang terdengar manis tapi mengandung racun.
Mereka mengingatkan bahwa demokrasi bukan benda mati yang bisa kita simpan di lemari konstitusi; ia adalah makhluk hidup yang harus diberi makan norma, kepercayaan, dan toleransi. Setiap kali kita menutup mata terhadap pelanggaran aturan hanya karena dilakukan oleh pihak yang kita dukung, kita sedang memberi pupuk pada benih otoritarianisme. Setiap kali kita bertepuk tangan untuk kebijakan yang membungkam lawan demi “stabilitas”, kita sedang menggali kubur bagi kebebasan kita sendiri.
Buku ini menutup babnya dengan nada peringatan, tapi juga secercah harapan: bahwa demokrasi bisa diselamatkan, asal kita bersedia mengakui rapuhnya ia dan berhenti menganggapnya sebagai hak bawaan yang tak akan hilang. Karena sejarah sudah terlalu sering membuktikan—ketika rakyat percaya demokrasi akan selalu ada, saat itulah ia paling mudah lenyap. Dan yang paling menyakitkan, kadang ia lenyap bukan karena direbut, tetapi karena kita sendiri yang mengantarkannya pergi.***
