Resensi Buku How Democracies Die (2018) Karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt: Membaca Ulang Demokrasi Kontemporer
- Penulis : Irsyad Mohammad
- Selasa, 05 Agustus 2025 15:42 WIB
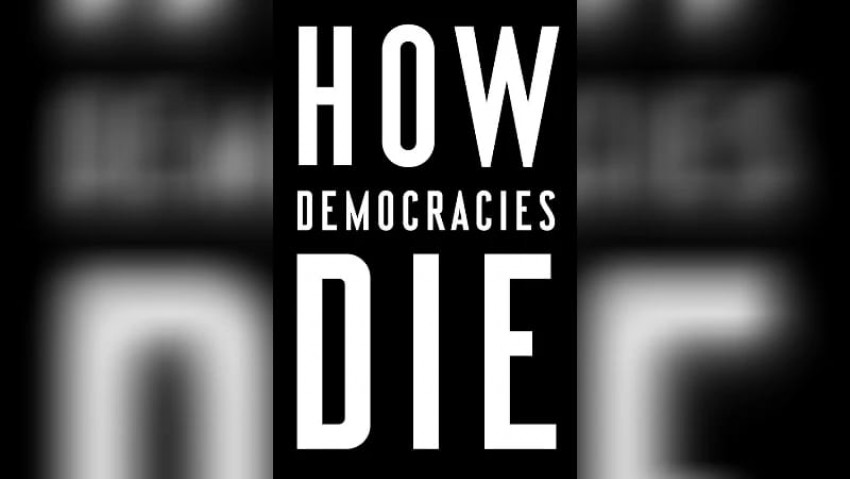
Kematian Demokrasi Dimulai dari Pilihan Kita Sendiri
Poin paling mengguncang dari Why Democracies Die adalah bahwa keruntuhan demokrasi bukanlah bencana alam; ia adalah hasil dari serangkaian pilihan sadar—baik oleh elite maupun rakyat biasa. Demokrasi bisa mati justru karena rakyat memilih pemimpin yang menggerogotinya, entah karena marah pada sistem lama, tergoda janji perubahan cepat, atau terpesona pada figur yang “berani melawan arus.”
Levitsky dan Ziblatt menggarisbawahi empat tanda bahaya pada politisi yang berpotensi menjadi penggali kubur demokrasi: menolak atau meremehkan aturan main demokrasi, menyangkal legitimasi lawan politik, mendorong atau membenarkan kekerasan, serta menunjukkan kecenderungan membatasi kebebasan sipil. Masalahnya, tanda-tanda ini sering diabaikan saat pemimpin tersebut berada di pihak kita. Kita memberi mereka cek kosong dengan keyakinan bahwa mereka hanya akan menggunakannya melawan “musuh”. Padahal, sekali kekuasaan itu terkonsolidasi, siapa pun bisa menjadi targetnya.
Baca Juga: Resensi Buku Age of Empire: 1875–1914: Sihir Kekuasaan dan Darah Koloni
Buku ini tidak berakhir dengan pesimisme mutlak. Ia menawarkan jalan keluar: menghidupkan kembali norma-norma politik, membangun kembali toleransi, dan memperkuat lembaga demokrasi. Namun Levitsky dan Ziblatt realistis: semua itu memerlukan kesadaran kolektif. Demokrasi tidak akan bertahan hanya dengan prosedur pemilu; ia memerlukan budaya politik yang menganggap lawan sebagai bagian dari permainan, bukan ancaman yang harus dilenyapkan.
Mereka menutup dengan peringatan halus: demokrasi mati bukan karena rakyatnya tidak mencintainya, tapi karena mereka membiarkan rasa takut, marah, dan dendam mengambil alih. Dan saat itu terjadi, rakyat justru akan mengantar demokrasi ke kuburnya—dengan tepuk tangan, bukan protes.
Penutup
Pada akhirnya, Why Democracies Die bukan sekadar buku analisis politik; ia adalah cermin yang memantulkan wajah kita sendiri, sebagai warga negara. Levitsky dan Ziblatt memaksa kita untuk melihat bahwa menjaga demokrasi bukan tugas segelintir politisi atau lembaga hukum, tetapi tanggung jawab kolektif yang dimulai dari pilihan sehari-hari: bagaimana kita berbicara tentang lawan politik, bagaimana kita mengonsumsi berita, bagaimana kita merespons janji-janji yang terdengar manis tapi mengandung racun.
Mereka mengingatkan bahwa demokrasi bukan benda mati yang bisa kita simpan di lemari konstitusi; ia adalah makhluk hidup yang harus diberi makan norma, kepercayaan, dan toleransi. Setiap kali kita menutup mata terhadap pelanggaran aturan hanya karena dilakukan oleh pihak yang kita dukung, kita sedang memberi pupuk pada benih otoritarianisme. Setiap kali kita bertepuk tangan untuk kebijakan yang membungkam lawan demi “stabilitas”, kita sedang menggali kubur bagi kebebasan kita sendiri.
Buku ini menutup babnya dengan nada peringatan, tapi juga secercah harapan: bahwa demokrasi bisa diselamatkan, asal kita bersedia mengakui rapuhnya ia dan berhenti menganggapnya sebagai hak bawaan yang tak akan hilang. Karena sejarah sudah terlalu sering membuktikan—ketika rakyat percaya demokrasi akan selalu ada, saat itulah ia paling mudah lenyap. Dan yang paling menyakitkan, kadang ia lenyap bukan karena direbut, tetapi karena kita sendiri yang mengantarkannya pergi.***
Baca Juga: Resensi Buku Collapse (2005): How Societies Choose to Fail or Succeed Karya Jared Diamond
