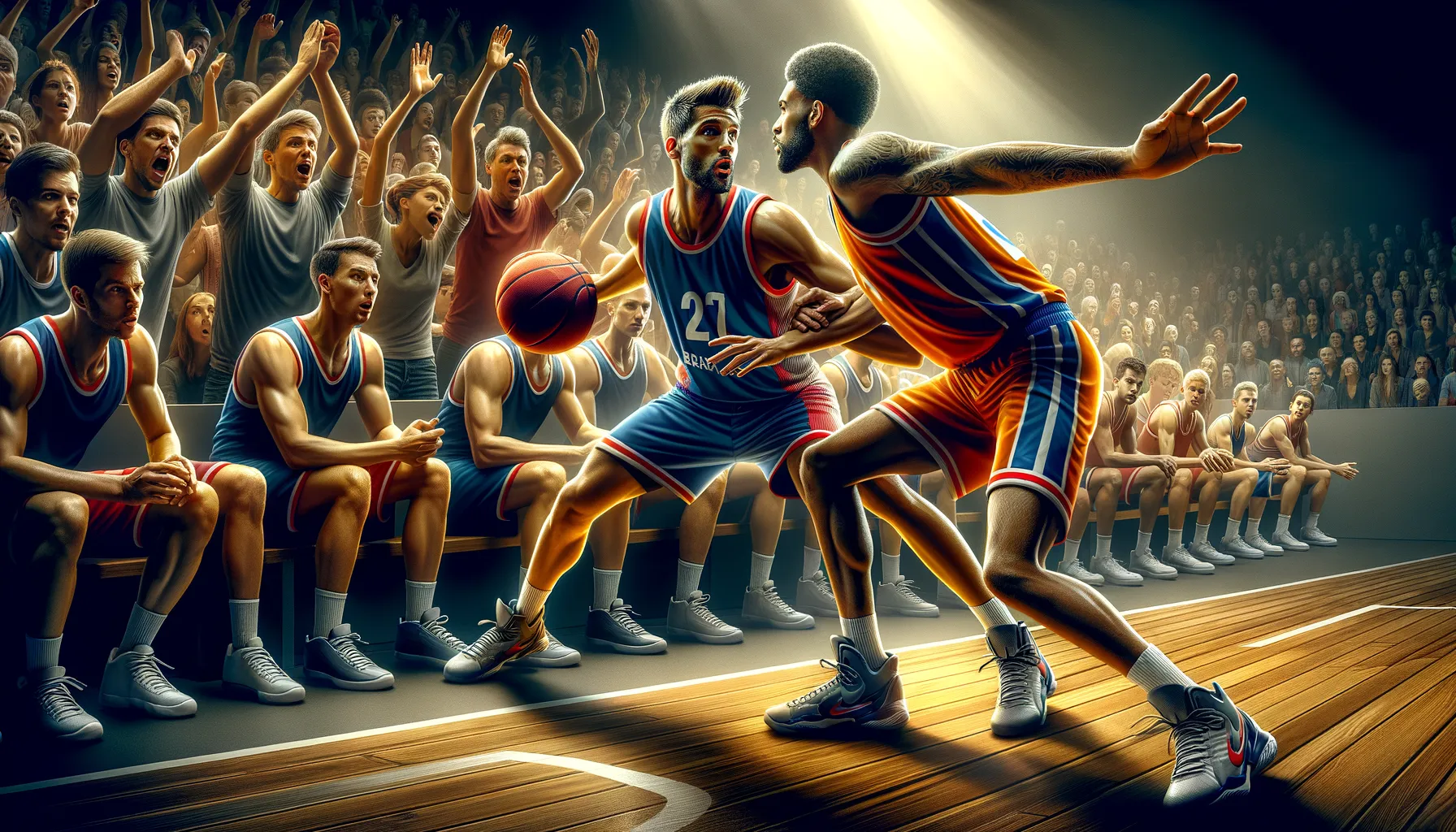Supriyanto Martosuwito: Kereta Cepat dan Kereta Politik
Oleh Supriyanto Martosuwito, wartawan senior
ORBITINDONESIA.COM - Kontroversi Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) kembali memanas. Bukan karena keretanya lambat, tidak nyaman, atau sepi penumpang. Justru sebaliknya — okupansi kereta cepat nyaris penuh setiap hari, terutama di jam sibuk. Catatan KCIC sebanyak 25.316 penumpang tercatat menggunakan Whoosh dalam satu hari - pada 10 Mei 2025 lalu. Ini merupakan angka tertinggi sejak Whoosh dioperasikan secara komersial pada Oktober 2023.
Warga dari Bandung, Padalarang, hingga seantero Jakarta mulai menjadikannya pilihan utama karena waktu tempuh yang hanya 45 menit - sebuah lompatan transportasi yang belum pernah terjadi di sejarah perkeretaapian Indonesia.
Namun perdebatan kini bergeser ke soal lain: kerugian dan utang. Publik disodori angka defisit dan bunga pinjaman, seolah-olah ini tanda kegagalan besar yang mesti ditanggung rakyat.
Pernyataan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak keras penggunaan APBN untuk membayar utang proyek KCJB yang dikelola KCIC - Kereta Cepat Indonesia China - dengan argumen, tanggung jawab penyelesaian utang berada di bawah Danantara sebagai holding BUMN investasi - digoreng habis untuk mengadili penggagasnya, Presiden Jokowi.
Padahal sejak awalnya, Jokowi minta pembangunan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak menggunakan APBN dan diserahkan sepenuhnya kepada BUMN melalui skema “business-to-business”.
Justru Jokowi menolak proposal kontraktor Jepang karena mengharuskan adanya jaminan APBN dari pemerintah Indonesia, sebuah syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah saat itu.
Kini kondisinya dibolak balik - digoreng goreng - karena politik.
DALAM logika transportasi publik, kerugian finansial bukanlah indikator utama. Hampir semua moda transportasi publik dunia beroperasi dengan subsidi, baik terselubung maupun eksplisit.
Transportasi publik jarang menguntungkan secara neraca keuangan.
London Underground membutuhkan subsidi hingga 40% dari biaya operasional. Metro New York menutup hanya sekitar 30–35% biaya dari tarif penumpang. Paris Métro, meski menjadi tulang punggung mobilitas kota, setiap tahun disuntik dana negara demi menjaga tarif tetap terjangkau.
Hanya Jepang dan Singapura yang menjadi pengecualian, itu pun karena operatornya terintegrasi dengan bisnis properti, ritel, dan komersial di sekitar stasiun.
Model seperti itu tidak mungkin langsung diterapkan di Indonesia yang belum memiliki tata ruang sepadat Tokyo atau regulasi lahan seefisien Singapura. Artinya, jika kereta cepat “merugi”, itu bukan anomali — itu norma global.
Justru pertanyaan pentingnya: berapa banyak kerugian sosial yang bisa dihindari karena kehadiran kereta cepat?
Setiap hari, sebelum KCJB beroperasi, jalur tol Jakarta – Bandung menanggung lebih dari 130 ribu kendaraan per arah, dengan waktu tempuh rata-rata 3–4 jam. Biaya kemacetan — bahan bakar, waktu kerja yang hilang, polusi udara, stres berkepanjangan — nilainya jauh melampaui angka di laporan keuangan KCIC.
DARI satu riset Bank Dunia menunjukkan bahwa kemacetan di Jakarta menimbulkan kerugian ekonomi setara 4,5% PDB DKI Jakarta per tahun. Artinya, pemerintah kehilangan lebih banyak dari kemacetan daripada biaya operasional transportasi publik apa pun.
Maka kereta cepat justru menghemat, bukan merugikan, jika dihitung secara sosial dan ekologis.
Yang menjadikan isu ini panas bukanlah angka utangnya, melainkan siapa yang membangunnya. Proyek yang sejak awal dilabeli “proyek Jokowi” telah menjadi sasaran empuk politik.
Sejak penunjukan investor China, pembengkakan biaya, hingga keputusan pemerintah tak menanggung langsung utangnya lewat APBN — semuanya dibingkai dalam nada kecurigaan politik. Padahal, banyak proyek publik besar di era sebelumnya juga tak langsung menguntungkan. Jalan tol trans-Jawa pun awalnya defisit. Bandara Kertajati sempat sepi.
Bendungan besar butuh puluhan tahun untuk menghasilkan manfaat ekonominya. Tetapi tak ada satu pun yang dipersoalkan secara personal terhadap presidennya.
NARASI kerugian kereta cepat adalah contoh klasik bagaimana “politik persepsi” mengalahkan logika ekonomi publik.
Di media sosial, “utang China” diulang-ulang tanpa konteks struktur pinjaman bisnis antar-BUMN. PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China) adalah entitas korporasi, bukan proyek APBN.
Negara memang memiliki saham, tetapi mekanisme keuangannya bersifat investasi, bukan belanja langsung. Pemerintah tetap punya opsi restrukturisasi atau “refinancing”, seperti yang dilakukan banyak negara dalam proyek besar transportasi.
Sayangnya, perdebatan publik di Indonesia jarang menyentuh lapisan yang lebih dalam: apa sebenarnya tujuan strategis dari proyek semacam ini? Kereta cepat bukan sekadar soal Bandung–Jakarta. Ia adalah embrio untuk jaringan baru Pulau Jawa, menghubungkan hingga Surabaya dan berpotensi mengganti pola mobilitas antar-kota yang kini bertumpu pada mobil pribadi dan bus jarak jauh.
Terbukti, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk melanjutkan Kereta Cepat 'Whoosh' hingga ke Surabaya. Perpanjangan rute Kereta Cepat Whoosh ke Surabaya nantinya memberikan dampak cukup besar, mulai dari pemangkasan waktu tempuh dari Jakarta ke Surabaya maupun sebaliknya; meningkatkan efisiensi, dan tentunya dapat saling terintegrasi antar kota di Pulau Jawa.
Jika itu tercapai, manfaat ekonominya akan jauh lebih besar: produktivitas meningkat, urbanisasi terkendali, nilai tanah di sekitar stasiun melonjak, emisi karbon menurun, dan konektivitas antarkota menjadi tulang punggung ekonomi masa depan.
Semua itu adalah “dividen sosial” yang tidak bisa diukur dalam laporan laba rugi tahun berjalan.
Kesalahan terbesar publik — yang juga sering dimanfaatkan oleh elite politik — adalah memperlakukan transportasi publik seperti perusahaan dagang. Kita menilai proyek publik seolah-olah sama seperti toko ritel yang harus untung setiap kuartal. Padahal, bahkan di negara maju, transportasi publik adalah instrumen kesejahteraan sosial.
Ada pepatah dalam perencanaan kota modern: “If you think public transport is expensive, try congestion.”. Jika Anda mengira transportasi publik itu mahal, cobalah hitung kerugian akibat macet. Demikian pula, jika kita mempersoalkan kerugian kereta cepat hari ini, bayangkan berapa besar kerugian produktivitas jika kita tidak pernah membangunnya.
Perdebatan tentang KCJB seharusnya membawa publik pada pemahaman baru bahwa pembangunan transportasi tidak bisa hanya dilihat dari neraca korporasi. Yang lebih penting adalah neraca sosial bangsa: efisiensi waktu, mobilitas manusia, kesempatan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.
Kereta cepat bukan soal Jokowi, bukan pula soal China. Ia adalah simbol bahwa Indonesia akhirnya memasuki tahap di mana waktu warga menjadi sesuatu yang berharga. Dan di tengah hiruk-pikuk politik, itu sebenarnya adalah kemajuan yang pantas dibanggakan. ***