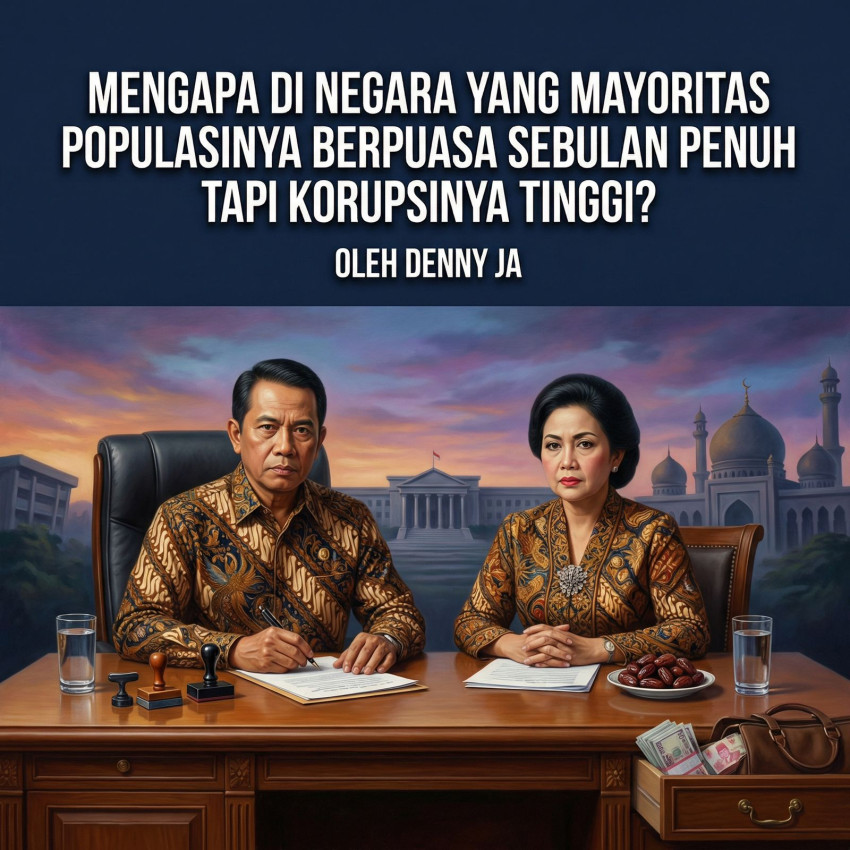Suharto dan Wacana Kepahlawanan: Cerita dan Renungan Seorang Jerman yang Pernah Menjadi Juru Bahasa Resminya
Oleh Berthold Damshäuser*
ORBITINDONESIA.COM - Pada 10 November 2025, Suharto—Presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat dari 1967 hingga 1998—diangkat secara anumerta sebagai Pahlawan Nasional oleh mantan menantunya, Presiden Prabowo Subianto yang kini tengah menjabat. Saya merasa terpanggil untuk menulis mengenai topik ini, namun saya tidak bermaksud mendukung maupun menentang keputusan tersebut. Akan tetapi, saya dengan jujur mengakui bahwa keputusan itu menimbulkan rasa sukacita bagi saya. Perasaan ini berakar pada pengalaman pribadi: saya pernah bertemu langsung dengan Suharto berkali-kali, menghabiskan banyak waktu bersamanya, dan menumbuhkan rasa simpatik terhadapnya.
Bagaimana hal itu terjadi? Pada tahun 1991, saya ditugaskan oleh Kementerian Luar Negeri Jerman untuk bertindak sebagai juru bahasa Suharto selama kunjungan kenegaraan empat hari beliau ke Jerman. Sekali lagi, dan kali ini atas permintaan tegas dari Suharto sendiri, saya kembali ditunjuk sebagai juru bahasa pada kunjungan berikutnya ke Jerman pada tahun 1995. Selain itu, saya juga terlibat dalam kunjungan Kanselir Jerman Kohl ke Indonesia (1991 dan 1995), serta dalam berbagai percakapan telepon antara kedua kepala negara, terutama pada minggu-minggu menjelang pengunduran diri Suharto pada tahun 1998.
Sejak kunjungan kenegaraan pertama Suharto ke Jerman pada tahun 1991, terjalin hubungan yang hangat dan menyenangkan antara beliau dan saya. Saya mengenal Suharto sebagai seorang pria berusia lanjut yang santun dan ramah, dengan aura yang menyenangkan. Sebaliknya, saya tampaknya juga meninggalkan kesan yang baik baginya, dan yang terutama, beliau menaruh kepercayaan kepada saya—mungkin karena percakapan empat mata yang panjang pada hari pertama kunjungannya ke Jerman, ketika beliau menanyakan secara mendalam tentang kehidupan pribadi saya, dan –sepertinya– mencatat secara positif bahwa istri saya, Dian Apsari, berasal dari Jawa. Yang paling penting tentu adalah bahwa saya menegaskan: Indonesia adalah tanah air kedua saya, dan saya akan mendampinginya sebagai juru bahasa seoptimal mungkin, sambil menjaga setiap rahasia dengan setia.
Dengan demikian, kami sangat akrab dan juga bertemu di luar acara-acara resmi. Beliau bahkan mengundang saya ke pelantikan terakhirnya pada Maret 1998 di Jakarta. Beberapa kali saya juga menjadi tamu di rumah pribadinya di Cendana, Jakarta, meskipun hanya untuk pertemuan singkat, terakhir kali pada bulan Juni 1998, setelah beliau mengundurkan diri. Tentang pertemuan terakhir yang tak terlupakan itu, akan saya singgung secara khusus pada bagian akhir esai ini …
Tentu saja, saya telah mempelajari Suharto dan sejarah Indonesia—khususnya periode 1960 hingga 2000—secara mendalam, termasuk dalam kapasitas saya sebagai Indonesianis dan dosen di Universitas Bonn. Saya juga banyak berdiskusi dengan seorang “spesialis Suharto” yang istimewa, yaitu sahabat saya Ramadhan K.H., yang tinggal di Bonn pada tahun 1980-an dan tengah mengerjakan biografi Suharto yang kemudian diterbitkan pada 1989 sebagai otobiografi Suharto berjudul Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tidakan Saya, Otobiografi, seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.. Kang Atun—demikian saya memanggil sahabat saya yang meninggal pada 2006—bukanlah pengagum Suharto, dan penilaiannya terhadap Suharto sangat kritis, namun jauh lebih objektif dan subtil dibandingkan gambaran yang sebagian besar satu sisi dan negatif di media Jerman maupun publikasi Barat lainnya, termasuk karya ilmiah.
Kang Atun juga menyarankan kepada saya untuk mengeditori versi berbahasa Jerman dari otobiografi Suharto, dengan alasan bahwa karya itu merupakan dokumen penting bagi sejarah. Saya mengikuti saran tersebut, dan versi bahasa Jerman dari otobiografi itu terbit pada tahun 1994 dengan judul Soeharto: Gedanken, Worte und Taten. Eine Autobiographie aufgrund von Schilderungen gegenüber G. Dwipayana und Ramadahan K.H.. Kemudian, bersama istri saya, saya juga menerjemahkan buku Suharto Butir-Butir Budaya Jawa. Pituduh dan Wewaler ke dalam bahasa Jerman. (Diterbitkan di Jerman pada tahun 2002 dengan judul: Javanische Weisheit. Pituduh und Wewaler. Spruchdichtung aus Indonesien.)
Terkait pengalaman saya sebagai juru bahasa Suharto, pada tahun 2020 saya diwawancarai oleh Deutsche Welle, platform berita internasional dari Jerman. Dalam wawancara itu, saya tidak hanya menceritakan beberapa anekdot menarik, tetapi juga memberikan penilaian mengenai kiprah dan kepribadian beliau. Bagian yang relevan dari wawancara tersebut saya lampirkan dalam esai ini sebagai tambahan.
Dalam wawancara itu, menurut pandangan saya, tampak dengan jelas pro dan kontra yang juga kini, setelah pengangkatan Suharto sebagai Pahlawan Nasional, mewarnai perdebatan publik. Mungkin juga terlihat kecenderungan saya untuk berusaha memahami Suharto, termasuk membela beliau. Peran sebagai pembela Suharto memang kerap saya ambil, khususnya sebagai dosen di Universitas Bonn dalam beragam diskusi panjang dengan mahasiswa saya. Bahkan dalam mengambil peran itu, saya sering harus membela diri sendiri. Selain kritik pedas—sering kali dari mahasiswa berpandangan kiri—yang menuding Suharto sebagai diktator kejam dan pembantai manusia, saya juga secara pribadi dituduh sebagai “teman seorang pembunuh massal”. Dalam serangan yang begitu berlebihan dan absurd, satu-satunya pilihan hanyalah berdiri sebagai pembela diri dan sekaligus menyoroti sisi-sisi baik, serta jasa-jasa besar Suharto bagi bangsa Indonesia, agar tercermin dengan adil di tengah bayang-bayang kontroversi.
Namun tentu saja, kelemahan, kekhilafan, dan perbuatan salah Suharto tidak bisa diabaikan, terutama dalam konteks pengangkatannya sebagai Pahlawan Nasional. Dari sudut pandang formal, dalam menilai kewajaran pengangkatannya, ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia harus diperhatikan, terutama bagaimana istilah “Pahlawan Nasional” didefinisikan dalam peraturan tersebut.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut, disebutkan: Pahlawan Nasional adalah warga negara Indonesia yang karena keberanian, pengorbanan, dan jasa-jasanya yang luar biasa dapat dijadikan teladan dalam perjuangan menegakkan dan memajukan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan: Berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, tidak pernah menyerah pada musuh, tidak tercela dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya.
Mengenai jasa-jasa luar biasa, terutama terkait keberhasilan pembangunan dan pemeliharaan stabilitas nasional, kemungkinan besar bahkan bagi kebanyakan pihak yang menentang Suharto, tidak ada keraguan. Hal berbeda muncul ketika membahas apakah Suharto dapat dijadikan teladan dalam segala hal—khususnya bagi generasi berikutnya—dan terutama sejauh mana beliau tidak tercela dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya.
Bagaimana menanggapi, misalnya, mereka yang mengkritik keras pengangkatan Suharto sebagai Pahlawan Nasional, apabila mereka menyoroti bahwa Suharto, dalam kasus pembunuhan misterius (Petrus), sebagai Presiden dan wakil tertinggi eksekutif negara, jelas dan terbukti melanggar hukum? Sebab, dalam otobiografinya Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, ia sendiri menyatakan bahwa ia memberikan otorisasi atas operasi Pembunuhan Misterius (Petrus) sebagai bentuk “terapi kejut” untuk menanggulangi kejahatan. Dapatkah seseorang dijadikan teladan jika ia sebagai Presiden pernah melanggar hukum? Seseorang yang mungkin secara pribadi juga turut bertanggung jawab atas tindakan penganiayaan terhadap kaum komunis, para disiden, dan aktivis?
Dalam hal ini, saya pada dasarnya dapat menerima argumentasi Farid Mustofa yang, dalam esainya berjudul “Makna Pahlawan” (Sumber: https://hatipena.com/artikel-opini/makna-pahlawan/), menyatakan: Jika ukuran pahlawan hanya pada jasa, maka banyak yang masuk daftar. Tapi jika ukurannya juga tanggung jawab moral, maka tidak semua jasa bisa lolos. Ada syarat moralnya.
Memang, menurut ukuran moral yang umumnya berlaku pada masa sekarang, kekerasan terhadap lawan politik, perilaku otoriter, dan sebagainya tentu akan dikecam, dan sosok seperti Suharto jelas tidak dianggap layak memperoleh status sebagai pahlawan. Namun, faktanya hingga sekarang banyak tokoh sejarah tetap dihormati oleh bangsanya dan bahkan secara umum sebagai pahlawan atau panutan, meskipun mereka sama sekali tidak memenuhi kriteria moral zaman sekarang. Di antara contohnya yang paling menonjol adalah Iskandar Agung, Jenghis Khan, dan Mao Zedong.
Bahkan di Eropa, di mana para elit politik kerap memuji diri memiliki moralitas yang sangat tinggi dan ingin tampil sebagai teladan bagi seluruh dunia, kaisar abad pertengahan Karolus Magnus (748–814 M) tetap dihormati dan diagungkan. Hal ini terlihat, misalnya, dari penamaan penghargaan Eropa yang paling bergengsi, yaitu the International Charlemagne Prize of Aachen, yang mengambil namanya. Sejak tahun 1950, penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh Eropa yang dianggap berjasa bagi integrasi dan perdamaian (sic!) di Eropa. Tampaknya sepenuhnya diabaikan bahwa Karolus Magnus memimpin peperangan yang sangat brutal, terutama terhadap bangsa Saksonia, yang dalam perjalanannya melibatkan eksekusi massal, pembaptisan paksa, pengusiran, dan tindakan-tindakan yang oleh sebagian sejarawan dewasa ini ditafsirkan sebagai bentuk genosida. Ia memerintah secara absolutis, bertumpu pada kekuatan militer dan legitimasi gereja, sementara kristenisasi paksa merupakan unsur utama pemerintahannya. Dengan demikian, Uni Eropa pada hakikatnya justru memuliakan seseorang yang secara nyata melakukan pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia.
Timbul sebuah pertanyaan yang tak mudah dijawab: moralitas siapa, dan moralitas yang mana yang patut dijadikan acuan? Moral bukanlah hal sederhana; standar moral yang berlaku umum sulit ditetapkan. Friedrich Nietzsche pernah menegaskan: Moral predigen ist leicht, Moral begründen schwer (Menkhotbahkan moral itu gampang, membuktikan kebenaranya sulit). Moral bukanlah hukum alam yang abadi; ia lahir dan tumbuh dari pertemuan kebudayaan, agama, sejarah, struktur kekuasaan, dan pengalaman hidup suatu masyarakat. Sesuatu yang dianggap “baik” pada suatu masa atau dalam satu kebudayaan bisa tampak keliru, bahkan tak bermoral, pada waktu atau budaya lain. Nilai-nilai pun berubah seiring waktu: hal-hal yang dulu dianggap sah —perang, perbudakan, kekuasaan absolut— kini dipandang sebagai sesuatu yang harus dikutuk. Tidak ada “moral yang benar” yang tetap dan pasti. Moral selalu berada dalam proses negosiasi yang tak pernah usai, menyeberang antara kebudayaan, zaman, dan relasi kuasa, menantang kita untuk terus mempertanyakan, menimbang, dan memahami.
Terkait Suharto, pertanyaannya adalah: moral seperti apa yang mengikat dirinya, terutama sebagai pemimpin nasional? Sepertinya ia menempatkan kepentingan mayoritas rakyat sebagai prioritas. Sementara mereka yang dianggap mengancam kepentingan mayoritas, menurut pandangannya, tidak perlu dipedulikan—bahkan, bila perlu, disingkirkan atau dieliminasi. Dalam hal ini, ia menyerupai banyak penguasa masa lalu yang cirinya bertindak tanpa ampun. Lalu, seharusnya kita sampai pada penilaian atau kesimpulan seperti apa saat ini? Bagaimanapun kita menilai, kita tetap harus menyadari bahwa penilaian terhadap tindakan orang lain akan selalu bersifat subjektif. Bahkan dalam upaya mencapai objektivitas, kita senantiasa sulit menemukan jalan keluar dari belantara dialektika.
Tidak dapat dihindari bahwa setiap penilaian selalu berpijak pada pandangan moral kita sendiri. Namun hal itu sepenuhnya sah. Pada dasarnya, di balik setiap upaya menegakkan suatu moral tertentu, tersimpan dorongan yang lebih mendasar: keinginan untuk mewujudkan keadilan. Dorongan moral itu sendiri, pada inti terdalamnya, adalah dorongan untuk menegakkan keadilan.
Adili Suharto! Itu yang menjadi salah satu slogan gerakan Reformasi pada tahun 1998. Dalam hal ini, mengadili tentu saja bukan berarti menghukum atau memvonis, melainkan melakukan tindakan adil terhadap seseorang, atau dalam praktiknya, menjatuhkan putusan atau menilai secara adil terhadap objek tertentu.
Namun, keadilan juga sesuatu yang sulit—setidaknya keadilan duniawi, keadilan yang lahir dari tangan manusia. Keadilan selalu terikat pada keterbatasan kita: keterbatasan pengetahuan, keterbatasan daya tangkap, dan keterbatasan untuk melihat keseluruhan. Manusia tidak pernah sanggup mengetahui sepenuhnya semua fakta, motif, maupun konsekuensi jangka panjang yang relevan. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan bertumpu pada pengetahuan dan nalar—dua hal yang tak pernah mencapai kesempurnaan. Karena itu, banyak filsuf, dari Plato hingga John Rawls, penulis A Theory of Justice (1971), berpendapat bahwa keadilan hanyalah cita-ideal yang dapat didekati, namun tak pernah sepenuhnya diraih. Inilah hakikat keadilan duniawi, keadilan manusiawi, yang selalu menjadi cerminan yang tak pernah utuh dari moral manusia, yang pada dirinya pun kurang memiliki objektivitas dan universalitas.
Akhirnya, yang tersisa bagi kita hanyalah menyerahkan penilaian yang sejati—termasuk terhadap Suharto—kepada Dia yang, menurut keyakinan agama-agama, satu-satunya mampu melakukannya: Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pengadil. Penilaian-Nya, dapat diduga, sejalan dengan inti banyak tradisi teologis: bukan semata-mata hasil tindakan, melainkan—dan terutama—niat serta motif yang melandasinya. Tindakan yang lahir dari altruisme, dari ketulusan niat, dari kepedulian terhadap sesama, akan dinilai berbeda dibanding tindakan yang digerakkan oleh kepentingan diri. Bila motifnya murni, kekeliruan dalam pelaksanaannya dapat diampuni. Suatu perbuatan tampil dalam cahaya niatnya, bukan hanya akibat luarnya. Barangkali di sinilah letak perbedaan mendasar antara keadilan manusia dan keadilan ilahi: manusia menilai apa yang tampak, Tuhan menimbang kedalaman motif dan ketulusan upaya. Faust, drama paling tersohor dari pujangga Jerman Johann Wolfgang von Goethe—yang tokoh utamanya, Faust, telah menanggung banyak dosa—ditutup dalam pengertian yang sama. Kalimat terkenal terakhir yang diucapkan para malaikat berbunyi: Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. (Barang siapa yang senantiasa berusaha dan berjuang, akan kami selamatkan).
Bertitik tolak dari semua itu, dalam kaitan dengan Suharto, timbul pertanyaan yang bagi kita tak terjawab. Apakah Suharto telah berusaha dan berjuang dengan tulus—apakah ia, pada hakikatnya, bertindak atas dasar altruisme dan bukan karena pamrih, secara konkret karena cintanya kepada bangsa Indonesia? Apakah dalam tindakannya yang selalu ia utamakan adalah bangsa itu, yakni kesejahteraan mayoritas besar rakyat dan manusia Indonesia? Tetapi, ya, kita tidak dapat menjawab pertanyaan ini; berbeda dengan Tuhan, kita tidak mampu menembus ke dalam jiwa seseorang.
Pada titik ini, izinkan saya sekali lagi merujuk pada pengalaman pribadi saya bersama Suharto—khususnya percakapan terakhir kami pada bulan Juni 1998 yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk terakhir kalinya saya bertamu ke kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta, dan kami membahas pengunduran dirinya dari jabatan Presiden serta kekecewaan mendalam yang meliputi proses tersebut. Dalam suasana percakapan yang sangat akrab, terlintas di benak saya sebuah pertanyaan yang sebelumnya tak pernah saya berani kemukakan. Saya menanyakan perihal putra-putrinya, termasuk mengapa Pak Harto begitu mendukung mereka meraih posisi tinggi di Indonesia atau dalam ekonomi Indonesia—seraya menyampaikan bahwa langkah itu dapat mencemarkan namanya karena bisa dianggap sebagai nepotisme. Mendengar pertanyaan itu, raut wajahnya seketika membeku, dan ia hanya menjawab singkat: “Mereka pengusaha kok.” Setelah itu, percakapan berjalan tersendat-sendat dan berakhir dalam suasana kelam. Saya pun tak pernah lagi menerima undangan darinya. Tentu saja, pertanyaan semacam itu baginya terasa sangat kurang ajar. Suharto tampaknya memang sosok yang kurang mampu melakukan kritik diri, apalagi menerima kritik dari luar. Boleh jadi ia bahkan meyakini bahwa segala yang ia lakukan adalah benar belaka …
Walaupun hasil akhir pertemuan itu mengecewakan saya, hal itu tidak mengubah rasa simpati saya kepadanya. Simpati ini bahkan begitu besar, sehingga situasi yang pastilah sangat sulit bagi Suharto pada bulan-bulan menjelang pengunduran dirinya—dengan segala demonstrasi yang sarat kebencian terhadapnya—juga membuat saya merasa pilu. Saya pun sangat cemas mengenai ke mana situasi yang tegang pada waktu itu akan berujung. Apakah Suharto akan bersikeras tetap berkuasa? Apakah ia akan mengerahkan militer, yang sebagian besar dukungannya masih bisa ia pastikan? Apakah ia akan mengambil risiko terjadinya perang saudara? Betapa lega saya ketika ia mengundurkan diri dengan cukup cepat. Lengser itu bagi saya merupakan bukti sempurna akan rasa tanggung jawabnya, nasionalismenya, dan kecintaannya kepada bangsa Indonesia. Dengan senang hati saya menyimpulkan bahwa saya ternyata tidak terlalu keliru dalam menilai kepribadian Pak Harto.
Seperti telah saya ungkapkan, saya memahami sepenuhnya alasan mereka yang dengan keras menentang pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Suharto. Namun kepada teman-teman Indonesia—selama mereka bukan korban langsung dari kebijakan Orde Baru—saya anjurkan untuk memandang persoalan gelar kepahlawanan ini dengan santai. Pengangkatan Suharto sebagai Pahlawan Nasional tidak akan benar-benar merugikan bangsa Indonesia; masih banyak persoalan lain yang jauh lebih berat dan mendesak. Saya juga berharap agar teman-teman Indonesia tidak terlalu diliputi rasa kesal ketika jasa seseorang diangkat, sementara kesalahannya seolah tertimbun. Ada sebuah wejangan Jawa yang sarat kebijaksanaan: mikul dhuwur, mendhem jero. Menurut saya, kemampuan untuk memaafkan merupakan salah satu keutamaan luhur manusia Indonesia, sebuah sikap yang sering ditunjukkan bangsa ini—bahkan terhadap Belanda, sang mantan penjajah.
Suharto diangkat sebagai Pahlawan Nasional bersama sembilan tokoh lainnya, termasuk Marsinah, seorang buruh pabrik yang menjadi simbol perjuangan pekerja Indonesia dan yang diculik serta dibunuh pada tahun 1993. Kepahlawanan Marsinah sama sekali tidak diragukan. Bahwa kini Suharto—yang memimpin rezim yang dapat dianggap bertanggung jawab atas kematian buruh perempuan itu—berdiri sebagai Pahlawan Nasional di samping Marsinah sungguh sesuatu yang menarik. Keputusan tersebut dapat dilihat sebagai sinis, tetapi barangkali juga bijaksana, karena mencerminkan keterbukaan besar yang sarat dialektika. Di hadapan kepahlawanan Marsinah, kepahlawanan Suharto tampak memudar. Namun, peran seorang pemberontak dan pejuang melawan kekuasaan memang dalam beberapa hal lebih mudah dibandingkan peran seorang penguasa, yang selama lebih dari tiga dekade memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa, terus bergulat dengan realitas politik, dan terpaksa mengambil keputusan—termasuk yang dianggap keras.
Saya telah menyebutkan di awal bahwa saya merasa sukacita ketika mendengar Suharto diangkat menjadi Pahlawan Nasional. Hal ini terjadi meskipun saya menganggap sebutan “Pahlawan” sudah usang dan atavistis, serta mempertanyakan apakah suatu bangsa benar-benar membutuhkan pahlawan. (Di seluruh dunia hanya ada sangat sedikit negara yang mengenal atau menganugerahkan gelar resmi Pahlawan Nasional. Selain Indonesia, negara-negara tersebut adalah Armenia, Republik Demokratik Kongo, Georgia, Jamaika, Ukraina, dan Rwanda.)
Mengapa saya merasa sukacita? Sebagai seseorang yang teguh percaya kepada Tuhan dan dunia spiritual tempat jiwa-jiwa manusia yang telah meninggal berada, saya dapat membayangkan bahwa jiwa Suharto menyadari bahwa ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh bangsa yang dicintainya—dan bahwa ia bahagia karenanya. Saya, pada gilirannya, bersukacita karena Suharto di dunia roh dapat merasakan kebahagiaan itu.
Bonn, tanggal 19 November 2025
Lampiran
Kutipan dari wawancara Deutsche Welle (DW) dengan Berthold Damshäuser (BD) berjudul Suharto, di Mata Penerjemah Jerman. Mulai dari mie instan, 'benda ajaib' di kamar hotelnya, perasaannya terhadap Habibie, bahkan kengawurannya; apa saja yang diingat Berthold Damshäuser sebagai penerjemah Jerman untuk mantan presiden Suharto?, versi lengkap terakses di: https://www.dw.com/id/suharto-di-mata-penerjemah-jerman/a-53659584
DW: Banyak kritik selama ini atas kepemimpinan Suharto yang dinilai ‘bertangan besi`, bagaimana pandangan terhadapnya di Jerman dan Anda sendiri?
BD: Penilaian di Jerman terhadap Suharto rata-rata negatif, terutama di kalangan saya sendiri, Indonesianis, sangat negatif. Orde Baru disebut diktator militer. Rakyat Indonesia seolah-olah sangat menderita di bawah pemerintahannya, terutama terkait peristiwa 1965 (G30S) dan penumpasan komunisme, soal Timor-Timur dan Aceh. Suharto dinilai sebagai orang yang begitu kejam, tidak menghargai HAM, dan juga sebagai koruptor. Kadang sulit juga bagi saya untuk menyampaikan kepada mahasiswa sebuah gambaran yang lebih objektif. Kalau kita melihat Orde Baru, perkembangan ekonomi cukup positif. Jumlah orang di bawah kemiskinan berkurang dan ada swasembada beras, dan sebagainya. Terutama ada juga stabilitas. Stabilitas baru kita hargai, jika stabilitas terganggu. Stabilitas di Indonesia bisa dibilang stabil dalam tiga dasawarsa. Itu juga sesuatu. Selama 30 tahun, ekstremisme agama tidak kelihatan. Sebernarnya dari berbagai segi, suasana di Indonesia ketika itu jauh lebih menyenangkan.
DW: Sebenarnya apa yang dilakukan Suharto untuk menangkal kelompok ekstremis?
BD: Beberapa tokoh ekstremisme agama kembali ke Indonesia di zaman reformasi. Mungkin mereka tidak pulang jika Suharto masih jadi presiden. Aliran dana dari Timur Tengah untuk mendukung kalangan Islam yang radikal bisa diduga akan dipersulit di bawah Orde Baru. Melihat hubungan antaragama, Orde Baru cukup berhasil. Dan hal itu tidak lepas dari figur Suharto sendiri sebagai orang Jawa yang berkiblat pada budaya priyayi yang diwarnai oleh sinkretisme agama yang toleran dan tidak dogmatis. Suharto sendiri memberi contoh yang baik, sebagai tokoh yang terkenal dekat dengan kebatinan. Dan, dalam hal lain juga kelihatan jenis toleransi yang penting: Dalam kabinet Suharto ada menteri yang "gay", dan semua orang tahu, juga pubklik yang tahu. Sepertinya, itu tidak mungkin lagi terjadidi Indonesia sekarang.
DW: Meski Anda cukup dekat dengan Suharto, pasti ada yang Anda tak setuju dari Suharto, apa sajakah itu?
BD: Cukup dekat dalam arti ada rasa simpati kepadanya sebagai manusia. Dan tentu, banyak sekali yang tidak dapat saya setujui sebagai orang yang besar dalam suasana demokratis, di sebuah negara yang sangat menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk hak individual dan hak politik. Suharto bukan demokrat sejati, ia lebih mirip otokrat yang feodal, ya, sejenis raja Jawa yang modern. Dari segi demokrasi sejati tentu patut ditolak. Tapi, ya, Indonesia punya sejarah budaya yang berbeda, unsur feodal masih kuat. Dan, menurut kesan saya, sang “Raja Jawa” itu seorang nasionalis yang berupaya untuk berbuat yang terbaik bagi bangsanya, atau -paling sedikit- yang dianggapnya sebagai hal terbaik. Termasuk untuk rakyat kecil. Nasib petani banyak ia pikirkan, ia sendiri berasal dari kalangan itu. Dan, Suharto selama masa pemerintahan cukup populer di kalangan rakyat. Hasil pemilihan umum di bawah Orde Baru memungkinkan kesimpulan demikian.
DW: Namun ditengarai ada kecurangan?
BD: Saya kira, sejauh ada permainan curang untuk menghasilkan hasil pemilu yang "baik", pada dasarnya ada kemungkinan rakyat Indonesia untuk tidak memilihnya. Saya kira dalam pemilihan sebebas-bebasnya pun Suharto masih akan didukung oleh mayoritas pada waktu itu, karena mereka merasakan keadaan ekonomi dan lain sebagainya berkembang ke arah positif.
DW: Meski demikian, tetap saja pada tahun 1998 ada desakan untuk mengundurkan diri?
BD: Ya, di tengah krisis ekonomi pada tahun itu, kepercayaan masyarakat kepada Suharto sangat menurun. Tapi, justru dalam keadaan itu ia membuktikan rasa kebangsaan, nasionalismenya. Dalam waktu yang cukup singkat ia bersedia menyerah, mengundurkan diri. Menurut saya, itu bisa dinilai sebagai tindakan yang sangat bertanggung jawab. Bisa saja, ia ngotot, dan berupaya untuk tetap berkuasa. Dukungan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan ABRI, masih ada. Bisa terjadi perang saudara atau paling sedikit kekacauan yang luar biasa. Hal itu tidak diinginkannya. Ia telah bertindak secara arif. Banyak penguasa lain tidak bersikap seperti Suharto pada waktu itu.
DW: Masih adakah yang menjadi tanda tanya Anda atas sosok Suharto?
BD: Ya, ada. Bukan saja tanda tanya tapi sebuah masalah besar. Perihal penumpasan komunisme pada tahun 1965/66. Peristiwa yang mengakibatkan pembunuhan begitu banyak manusia yang tidak bersalah. Saya ingin tahu yang Suharto rasakan saat itu. Sejauh mana ia ketahui secara persis yang sesungguhnya terjadi di seluruh Indonesia. Sejauh mana ia sadari betapa ganas dan kejam kejadian itu. Mengapa ia membiarkan semua itu terjadi selama berbulan-bulan. Ingin bertanya kepadanya: apakah tidak ada jalan lain? Haruskah sebrutal ini? Apakah saat itu ia merasa bahwa bangsa Indonesia sebegitu terancam oleh komunisme/marxisme? Apakah ia sempat merasa bersalah?
DW: Apa pesan Anda pada Suharto, andai saja ia masih hidup?
BD: Mungkin bukan pesan, tapi saran. Ini berkaitan dengan sebuah kesan yang saya peroleh selama berjam-jam menyaksikan Suharto dalam pembicaraan dengan Kanselir Kohl, juga dengan presiden dan menteri-menteri Jerman. Pihak Jerman, terutama Kanselir, banyak bertanya kepada Suharto. Mereka ingin tahu tentang politik di Indonesia, tentang budaya Indonesia, tentang pandangan Pak Harto pribadi. Rasa ingin tahu mereka ternyata besar sekali. Sedangkan Suharto cuma menjawab, tidak tanya balik. Sepertinya tak ada rasa ingin tahu padanya.
Suharto memang bukan cendekiawan dalam arti biasa. Juga tidak pernah menerima pendidikan luas, dia bukan akademisi. Barangkali, satu-satunya keahlian yang sungguh ia mililiki adalah bidang kemiliteran. Sepertinya, ia berada dalam dunia yang relatif “kecil“, dunia budaya Jawa. Dan itu sudah mencukupi baginya. Sesungguhnya, karirnya cukup menakjubkan. Dengan bekal yang minim itu, ia berhasil menjadi pemimpin bangsa yang berhasil. Pasti ia memiliki akal sehat yang istimewa, sanggup menganalisis masukan para ahli, dan mengambil keputusan yang baik.
Nah, saran saya kepadanya akan seperti ini: Coba dong, Pak Harto, tingkatkanlah rasa ingin tahu, berupaya memperluas wawasan. Tentang dunia, juga tentang dunia ide. Bacalah banyak buku, buku sejarah dunia, buku filosofi. Baca juga karya sastra, termasuk karya sastra Indonesia modern.
Saya kan orang sastra, juga berupaya menyebarkan sastra Indonesia melalui terjemahan ke bahasa Jerman. Nah, dulu kepada Suharto saya sarankan untuk mengadakan program resmi bersama pihak Jerman untuk pertukaran budaya, khususnya di bidang sastra dan bahasa. Saya ingat, betapa saya berusaha untuk meyakinkan dia bahwa penyebaran sastra Indonesia modern melalui penerjemahan sangatlah penting. Reaksinya sama sekali tidak membuktikan bahwa ia terkesan oleh ide seperti itu, malah saya punya perasaan bahwa ia kurang memahami poin saya, karena jawabannya yang saya ingat cukup ngawur. Tapi ada asistennya yang mencatat saran saya, dan akhirnya hal itu menjadi topik dalam pembicaraan dengan Kanselir Kohl. Kanselir Jerman mengapresiasinya, dan akhirnya didirikanlah sebuah “Komisi Indonesia-Jerman untuk Bahasa dan Sastra”. Ternyata ada keuntungan khusus menjadi penerjemah Suharto. Tapi, lepas dari itu, saya merasa beruntung sekali berkenalan secara dekat dengan tokoh yang memimpin bangsa Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa.
Berthold Damshäuser, akrab dipanggil “Pak Trum”, lahir pada tahun 1957 di Wanne-Eickel, Jerman. Sejak 1986 hingga 2023, ia mengabdikan dirinya sebagai pengajar bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Bonn. Ia adalah koeditor Orientierungen, jurnal bergengsi yang mengkaji kebudayaan Asia. Damshäuser dikenal luas sebagai penerjemah puisi—mengalihkan karya-karya Jerman ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya—serta beberapa kali dipercaya menjadi penerjemah Presiden Suharto dalam kunjungan kenegaraan. Bersama Agus R. Sarjono, ia menyunting Seri Puisi Jerman yang diterbitkan sejak 2003.
Pada 2010, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menunjuknya sebagai Presidential Friend of Indonesia. Pada 2014 dan 2015, ia diundang menjadi anggota Komite Nasional Indonesia sebagai Tamu Kehormatan Pekan Raya Buku Frankfurt. Esai-esainya dalam bahasa Indonesia telah menghiasi halaman Majalah Tempo, Jurnal Sajak, dan berbagai media terkemuka. Karya-karya tulisnya dihimpun dalam buku Ini dan Itu Indonesia – Pandangan Seorang Jerman. Salah satu karya terbarunya, yaitu buku Eksegesis Pancasila: Membaca Ulang Lima Sila. Amatan Seorang Jerman akan terbit di Indonesia pada akhir tahun 2025. Sejak 2023, ia menjadi anggota Persatuan Penulis Indonesia (SATUPENA) dan menetap di Bonn, Jerman.
Website Berthold Damshäuser di Universitas Bonn:
https://www.ioa.uni-bonn.de/soa/de/pers/personenseiten/berthold-damshaeuser/berthold-damshaeuser ***