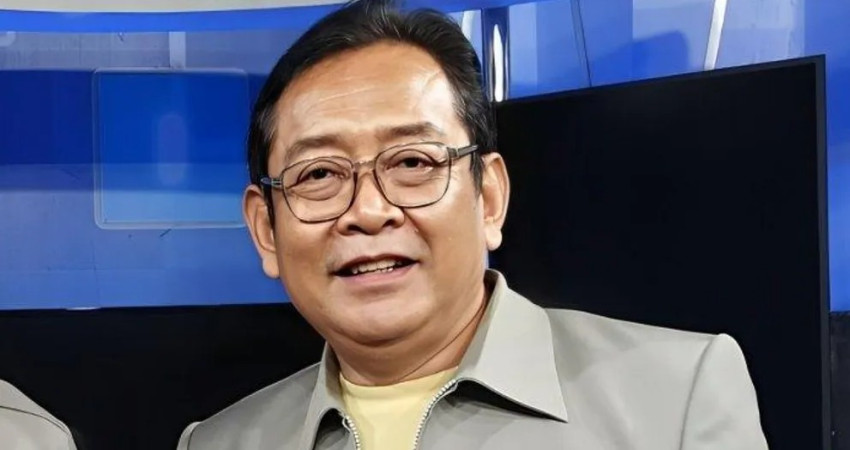Hasil TKA 2025: Darurat Literasi, Darurat Numerasi
Oleh Muhammad Subhan
ORBITINDONESIA.COM - Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 jenjang SMA sederajat yang diumumkan pemerintah pada Selasa, 23 Desember 2025, menyisakan kegelisahan. Bukan kegelisahan kecil, melainkan kegelisahan besar tentang arah pendidikan kita.
Angka-angka yang muncul bukan sekadar statistik, melainkan potret buram kompetensi akademik siswa Indonesia.
Hasilnya sungguh bikin sedih!
Nilai rata-rata Matematika wajib hanya berada di kisaran 36 dari skala 100. Bahasa Inggris lebih memprihatinkan lagi, di angka 24. Sementara Bahasa Indonesia, yang seharusnya menjadi fondasi literasi, hanya mencapai sekitar 55.
Angka-angka ini bukan sekadar rendah, tetapi mengkhawatirkan.
Mengutip Kompas.com edisi Selasa, 23 Desember 2025, Kemendikdasmen merilis nilai rata-rata TKA 2025 jenjang SMA: Bahasa Indonesia wajib (55,38), Matematika wajib (36,10), Bahasa Inggris wajib (24,93), PPKN (60,91), Antropologi (70,43), Projek Kreatif dan Kewirausahaan (56,34), Bahasa Indonesia lanjut (68,02), Matematika lanjut (39,32), Bahasa Inggris lanjut (45,23), Biologi (54,40), Sosiologi (60,07), Ekonomi (31,68), Kimia (34,92), Sejarah (62,72), Fisika (37,65), Geografi (70,36), Bahasa Arab (64,97), Bahasa Jepang (55,21), Bahasa Mandarin (57,60), Bahasa Jerman (36,57), Bahasa Korea (28,55), dan Bahasa Prancis (45,05).
Rendahnya nilai Matematika wajib, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia menunjukkan persoalan serius pada literasi dan numerasi siswa Indonesia.
Meski TKA tidak menentukan kelulusan, hasil ini tetap menjadi cermin kompetensi nasional. Cermin itu memantulkan wajah pendidikan kita yang lelah, timpang, dan belum sepenuhnya pulih.
Hasil TKA seharusnya menjadi dasar refleksi dan perbaikan pembelajaran secara sistemik. Namun, yang tampak justru potret memilukan. Data ini semestinya mendorong evaluasi kebijakan, penguatan pendampingan bagi satuan pendidikan, serta peningkatan kualitas pembelajaran.
Kemendikdasmen di laman resminya menyampaikan dan memastikan pemanfaatan hasil TKA selaras dengan prinsip keadilan dan pemerataan layanan pendidikan. Data hasil TKA menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam memetakan capaian pendidikan antarwilayah serta menyusun kebijakan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.
Pertanyaannya kemudian, sesulit itukah soal-soal TKA? Ataukah kemampuan siswa yang memang belum terbentuk dengan baik?
Ada banyak faktor yang menyebabkan nilai TKA, khususnya Matematika, “jeblok”. Salah satu yang paling menonjol adalah buku ajar dan metode pengajaran yang kurang memotivasi. Pembelajaran masih dominan berorientasi pada hapalan rumus, bukan pemahaman konsep. Siswa mungkin mampu menyelesaikan soal prosedural, tetapi tidak memahami alasan di balik sebuah perhitungan.
Akibatnya, siswa tidak terbiasa berpikir kritis. Pembelajaran berlangsung satu arah: guru menjelaskan, siswa mencatat, lalu mengerjakan latihan tanpa ruang eksplorasi dan diskusi. Penyelesaian soal menjadi otomatis, bukan hasil pemahaman yang kokoh. Ketika TKA menghadirkan soal berbasis pemecahan masalah dan penalaran, siswa pun gagap.
Faktor berikutnya adalah lemahnya budaya numerasi dan kuatnya asumsi bahwa Matematika adalah pelajaran sulit dan menakutkan. Pandangan ini bukan hanya hidup di benak siswa, tetapi juga orang tua, bahkan sebagian pendidik. Akibatnya, siswa sudah menyerah sebelum berjuang. Latihan mandiri minim, kepercayaan diri rendah, dan kesiapan mental saat ujian rapuh.
Ketika soal menuntut interpretasi data dan penerapan konsep dalam konteks kehidupan sehari-hari, siswa tidak memiliki bekal yang cukup.
Pandemi Covid-19 juga meninggalkan dampak panjang. Pembelajaran daring tidak berjalan merata. Banyak sekolah kekurangan fasilitas, akses internet, dan pendampingan. Matematika, yang membutuhkan interaksi intensif dan latihan berkelanjutan, menjadi salah satu mata pelajaran yang paling terdampak.
Di saat yang sama, implementasi kurikulum berbasis kompetensi belum sepenuhnya siap di semua daerah. Guru dituntut beradaptasi cepat, namun pelatihan tidak selalu memadai.
Perlu ditegaskan, nilai rendah tidak identik dengan ketidakmampuan siswa. Pemerintah sendiri menyatakan bahwa penurunan nilai lebih disebabkan metode dan dukungan pembelajaran yang belum optimal. Siswa bisa mulai memperbaiki diri dengan memperkuat pemahaman konsep, mencari pendekatan belajar yang lebih menarik, berlatih soal berbasis penalaran, serta bergabung dengan komunitas belajar.
Potret rendahnya TKA juga sejalan dengan hasil PISA Indonesia yang masih berada di bawah standar internasional, terutama pada numerasi dan sains. Penyebabnya bersifat sistemik: kualitas guru yang belum merata, keterbatasan sarana prasarana, kurikulum yang sering berganti, miskonsepsi konsep dasar, serta rendahnya akses dan minat literasi.
Memang, numerasi bukan sekadar urusan nilai ujian. Ia adalah bekal masa depan. Dunia kerja dan kehidupan modern menuntut kemampuan berpikir logis, memahami data, dan mengolah informasi.
Pemerintah memang berupaya memperbaiki kondisi ini, tetapi perubahan tidak bisa instan. Ia membutuhkan kerja bersama guru, sekolah, siswa, dan orang tua. Tanpa itu, angka-angka TKA hanya akan terus menjadi pengingat pahit tentang pekerjaan rumah pendidikan yang belum selesai.
Harapan ke depan, tentu, tidak berhenti pada membaca angka-angka dan saling menyalahkan. Hasil TKA 2025 semestinya menjadi titik balik untuk membangun pembelajaran yang lebih berpihak pada proses belajar, kontekstual, dan menyentuh nalar serta pengalaman siswa.
Literasi dan numerasi harus dihadirkan sebagai keterampilan hidup, bukan sekadar materi ujian.
Matematika perlu dibumikan dalam persoalan sehari-hari, Bahasa Indonesia dikuatkan sebagai alat berpikir dan bernalar, sementara Bahasa Inggris diposisikan sebagai jendela dunia, bukan momok. Sekolah harus kembali menjadi ruang aman untuk bertanya, mencoba, dan salah, bukan sekadar tempat mengejar angka dan gengsi.
Jika refleksi ini ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konsisten, pendampingan guru yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat, darurat literasi dan numerasi bukan tak mungkin diurai. Pendidikan Indonesia tidak kekurangan anak-anak cerdas, tetapi sering kekurangan sistem yang memberi ruang tumbuh bagi daya pikir dan rasa ingin tahu. TKA seharusnya tidak dikenang sebagai kabar buruk semata, melainkan sebagai alarm keras agar kita berani berbenah, sekarang, bersama-sama, sebelum keterlambatan menjadi kebiasaan.***