Wardah Nuroniyah: Dilema Hukum dan HAM yang Mempersempit Ruang Publik
Oleh Prof. Dr. Wardah Nuroniyah, S.H.I, M.S.I, Wakil Sekretaris Komisi Hukum Dan HAM MUI/Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
ORBITINDONESIA.COM - Di atas kertas, hukum dan hak asasi manusia (HAM) sering diposisikan sebagai dua pilar utama negara demokratis. Hukum berfungsi menciptakan keteraturan, sementara HAM menjadi penanda martabat kemanusiaan.
Namun dalam praktik politik kontemporer, keduanya tidak selalu berjalan beriringan. Bahkan, tidak jarang justru saling bertabrakan. Ketika itu terjadi, ruang publik—tempat warga menyuarakan keadilan dan nalar etik—perlahan menyempit.
Persoalan mendasarnya terletak pada fondasi masing-masing. Hukum, dalam praktik bernegara, kerap berkelindan dengan kekuasaan. Ia lahir dari proses politik, disusun oleh elite, dan ditegakkan oleh institusi yang tidak selalu steril dari kepentingan.
Sementara HAM berpijak pada nilai yang lebih purba dan universal: kemanusiaan itu sendiri. HAM tidak mengenal batas negara, tidak tunduk pada nasionalisme sempit, dan tidak bisa dinegosiasikan oleh kalkulasi elektoral.
Di titik inilah dilema itu bermula. Dan tragisnya, dilema itu terus berkembang, sejalan dengan ambisi kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai instrumen politik.
Ketika Hukum Menjadi Instrumen Kekuasaan
Dalam banyak kasus, hukum tidak lagi berfungsi sebagai penyangga keadilan, melainkan berubah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. Undang-undang disusun bukan untuk melindungi warga, tetapi untuk melanggengkan kepentingan politik tertentu.
Di sinilah hukum berpotensi “dikebiri”: bukan dihapus, melainkan dimanipulasi agar tampak sah secara prosedural, tetapi kehilangan roh etiknya.
Fenomena ini dapat dilihat dalam menguatnya politik dinasti di berbagai negara yang mengaku demokratis.
Demi keberlanjutan kekuasaan “penerus generasi politik”, berbagai aturan yang semula dirancang untuk mencegah konflik kepentingan justru diubah atau dihilangkan. Batas usia, masa jabatan, hingga mekanisme etik dilemahkan melalui rekayasa hukum yang sah secara formal, namun problematis secara moral.
Akibatnya, hukum tidak lagi menjadi wasit netral, melainkan pemain yang ikut bertanding. Ketika itu terjadi, ruang publik menyempit. Kritik dianggap ancaman. Perbedaan pandangan dicurigai sebagai pembangkangan. Dan HAM—yang seharusnya menjadi pagar terakhir—sering kali disisihkan atas nama stabilitas dan nasionalisme.
Di Indonesia, dilema ini menemukan salah satu ekspresinya yang paling kompleks di Papua. Di satu sisi, negara berdiri di atas prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah. Di sisi lain, terdapat laporan berulang mengenai pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, serta pendekatan keamanan yang dominan.
Ketika isu Papua dibingkai semata-mata sebagai persoalan separatisme dan keamanan nasional, dimensi kemanusiaan sering kali terpinggirkan. Suara-suara kritis—baik dari masyarakat sipil, jurnalis, maupun aktivis HAM—kerap dicap sebagai anti-negara.
Dalam situasi seperti ini, hukum lebih sering tampil sebagai alat pengendalian, bukan perlindungan. Padahal, HAM justru menuntut kehadiran negara yang lebih manusiawi: mendengar, mengakui luka sejarah, dan membuka dialog setara. Ketika pendekatan ini kalah oleh logika kekuasaan, ruang publik menyempit, dan konflik berlarut tanpa resolusi bermartabat.
Dilema hukum dan HAM tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga global. Salah satu contoh paling mencolok adalah upaya pengadilan pidana internasional untuk memproses dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Palestina, termasuk tuduhan serius terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Terlepas dari perdebatan hukum dan politik yang menyertainya, satu hal menjadi terang: proses hukum internasional kerap terhambat oleh kekuatan geopolitik. Dukungan Washington terhadap Israel menunjukkan bagaimana hukum internasional tidak selalu berlaku setara. Negara kuat dapat menciptakan kekebalan de facto bagi sekutunya, sementara HAM rakyat sipil—dalam hal ini warga Palestina—menjadi korban yang terus berulang.
Situasi ini memperkuat skeptisisme global: bahwa hukum internasional masih tunduk pada relasi kuasa, bukan sepenuhnya pada keadilan universal. Ketika itu terjadi, ruang publik global pun menyempit. Solidaritas kemanusiaan sering dibungkam oleh narasi keamanan dan aliansi strategis.
Pertanyaannya kemudian: mungkinkah hukum dan HAM dipertemukan dalam ruang publik yang lebih luas dan sehat?
Pengalaman negara-negara Skandinavia memberi secercah harapan. Di sana, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan, tetapi sebagai kontrak sosial yang hidup. Independensi peradilan dijaga ketat. Transparansi menjadi norma, bukan slogan. Lebih penting lagi, HAM tidak diperlakukan sebagai ancaman bagi negara, melainkan sebagai fondasi legitimasi negara itu sendiri.
Di negara-negara tersebut, kritik dianggap bagian dari patriotisme. Media dan masyarakat sipil diberi ruang luas untuk mengawasi kekuasaan. Dengan demikian, hukum dan HAM tidak saling meniadakan, melainkan saling menguatkan.
Menutup Dilema, Membuka Ruang Publik
Dilema hukum dan HAM sesungguhnya bukan takdir. Ia adalah pilihan politik. Ketika hukum dipisahkan dari etika kemanusiaan, ia kehilangan makna. Sebaliknya, HAM tanpa perlindungan hukum akan rapuh dan mudah diinjak.
Tantangan terbesar demokrasi hari ini bukan sekadar menegakkan hukum, tetapi memastikan bahwa hukum tetap berpihak pada kemanusiaan. Ruang publik hanya akan tetap luas jika negara berani menempatkan HAM bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai kompas moral.
Di situlah demokrasi diuji—bukan pada prosedur pemilu semata, tetapi pada keberanian melindungi manusia, bahkan ketika itu tidak menguntungkan kekuasaan.
Dalam tradisi Islam, gagasan tentang hak asasi manusia sesungguhnya bukan barang impor dari modernitas Barat. Ia berakar kuat dalam teks suci dan etika kenabian. Salah satu rujukan paling fundamental adalah Surat Al-Hujurat ayat 13:
“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal (li ta‘ārafū). Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.”
Ayat ini memuat tiga prinsip besar yang relevan dengan wacana HAM kontemporer.
Pertama, kesetaraan asal-usul manusia. Tidak ada hierarki ras, etnis, bangsa, atau kelas sosial. Semua manusia berdiri setara sebagai ciptaan Tuhan.
Kedua, pluralitas sebagai kehendak ilahi, bukan ancaman. Perbedaan bangsa dan suku bukan alasan dominasi, melainkan jalan untuk saling mengenal, memahami, dan membangun koeksistensi.
Ketiga, standar kemuliaan bukan kekuasaan atau identitas, melainkan takwa.
Takwa: Jembatan Moral dan Spiritual
Dalam konteks ini, takwa tidak bisa dipersempit sebagai kesalehan ritual semata. Dalam khazanah Islam klasik, takwa selalu mengandung dimensi moral, sosial, dan spiritual sekaligus. Al-Ghazali memaknai takwa sebagai kesadaran batin yang melahirkan perilaku etis terhadap sesama. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa ketakwaan sejati tercermin dalam keadilan dan penolakan terhadap kezaliman, siapa pun korbannya.
Dengan demikian, takwa bukan sekadar relasi vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi juga relasi horizontal dengan sesama manusia. Di sinilah HAM menemukan pijakan teologisnya. Melanggar hak hidup, martabat, dan kebebasan manusia lain bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan spiritual.
Nabi Muhammad SAW menegaskan hal ini dalam khutbah Wada’ : “Wahai manusia, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci.”
Pernyataan ini, dalam bahasa modern, adalah deklarasi hak hidup, hak kepemilikan, dan hak atas martabat manusia—jauh sebelum lahirnya deklarasi HAM modern.
Masalah muncul ketika hukum dan politik modern melepaskan diri dari fondasi etik ini. Ketika HAM diperlakukan sebagai variabel yang bisa dinegosiasikan demi stabilitas kekuasaan, maka baik nilai Islam maupun prinsip PBB sama-sama dikhianati.
Di sinilah benturan hukum dan HAM menjadi tajam: hukum positif tunduk pada kalkulasi politik, sementara HAM -- baik dalam Islam maupun dalam piagam internasional -- menuntut keberpihakan mutlak pada kemanusiaan.
Jika HAM dipahami sebagai pertemuan antara moral dan spiritual—sebagaimana diajarkan Al-Qur’an -- maka ruang publik seharusnya menjadi ruang etika, bukan sekadar arena kuasa. Negara yang mengaku demokratis dituntut bukan hanya taat prosedur hukum, tetapi juga setia pada nilai kemanusiaan universal.
Di titik inilah hukum, HAM, agama, dan demokrasi seharusnya saling menguatkan. Sebab, seperti pesan Al-Hujurat, manusia diciptakan bukan untuk saling meniadakan, melainkan untuk saling mengenal -- dan dalam pengenalan itu, menjaga martabat sesama sebagai bentuk takwa yang paling nyata.***





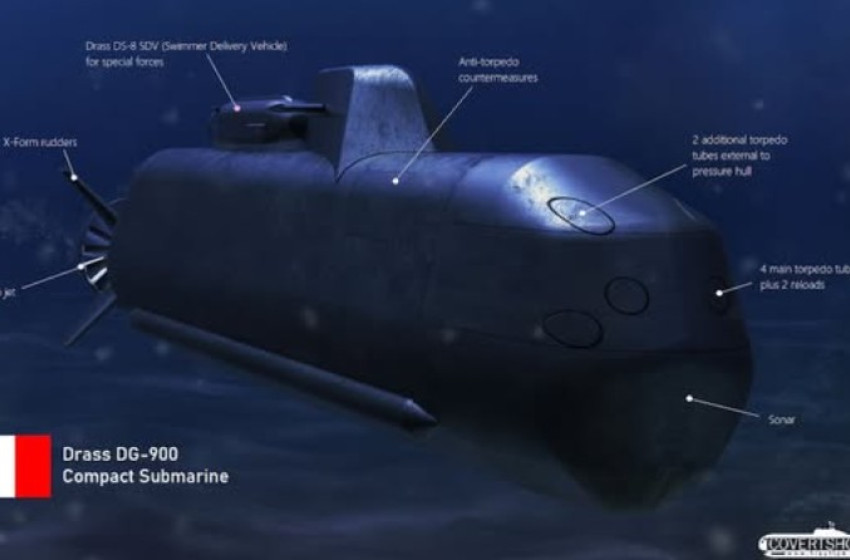



.jpeg)


