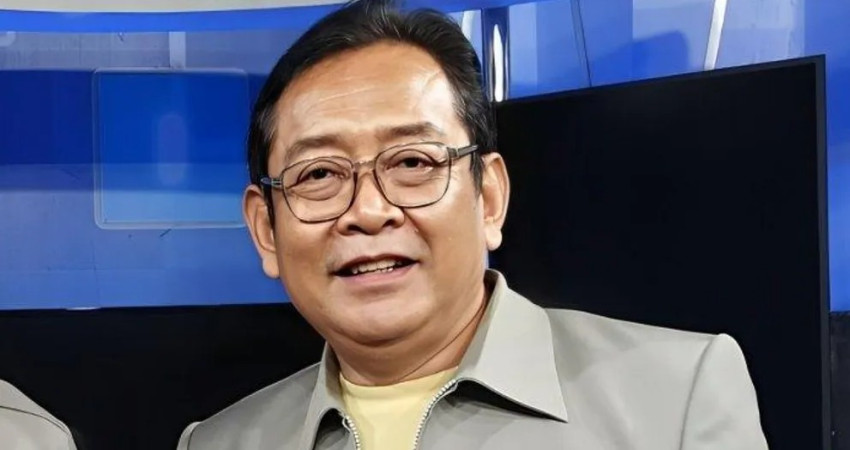Puisi Esai Denny JA: Tiga Prajurit Itu pun Hilang
Sebuah Puisi Esai Tentang Bencana Sumatra dan Problem Ekologis
Oleh Denny JA
ORBITINDONESIA.COM - (Kisah di bawah ini adalah fiksi, tapi diinspirasi oleh gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas membantu bencana Sumatra) (1)
-000-
Nama perempuan itu Ani.
Pagi masih basah oleh embun
ketika kabar itu datang
menjadi paku berkarat
dipalu pelan ke jantung hatinya.
“Suami Ibu
hilang dalam tugas.”
Kata “hilang” jatuh ke lantai,
retaknya merambat ke dinding,
ke kaca foto keluarga
yang tiba-tiba terlalu penuh
oleh orang-orang
yang tak sempat menjadi tua.
-000-
Ani duduk, terpana.
Semalaman ia tak bicara.
Jam dinding berdetak
bagai barisan sepatu
yang salah hitung langkah:
terus maju,
tapi tak pernah sampai ke pintu.
Di meja,
cangkir kopi suaminya
masih menyisakan jejak bibir,
seolah ia hanya keluar sebentar,
bukan ditelan peta bencana.
Ia tentara.
Berangkat bukan untuk perang,
melainkan untuk kemanusiaan.
Namun hujan
tak pernah menandatangani perjanjian.
Dan langit
tak mengenal kata “gencatan”.
-000-
Di Sumatra,
hujan turun sebagai palu raksasa
yang memukul bukit
sampai lupa cara berdiri.
Hutan yang dulu
mengikat tanah dengan doa akar,
sudah lama ditebang.
Di meja rapat dan stempel kantor;
izin-izin tumbuh lebih cepat
daripada pohon belajar teduh.
Maka ketika hujan datang,
bumi kehilangan tangan
untuk memegang dirinya sendiri.
-000-
Hari-hari berlalu
tanpa kabar pasti.
Kata “hilang”
menjadi bayangan
yang tidur di sudut rumah Ani,
menyusup ke piring,
mengintip dari gagang pintu.
Televisi menyala.
Wajah serius, grafik, slogan:
“Pemerintah bekerja.”
Di luar layar,
kata-kata publik mengalir deras:
“pemerintah lambat,
kurang sigap,
tak cukup serius,”
seperti air di atap seng
yang tak tahu
ke mana seharusnya pulang.
“Kurang serius?”
Ani menggigit kata itu
seperti biji pahit yang tak tahu
harus diludahkan ke mana.
Suaminya berangkat dengan tubuh utuh
dan kembali dalam peti yang senyap;
jika itu masih disebut
kurang serius,
apa nama untuk nyawa
yang tak sempat mengetuk
pintu pulangnya sendiri?
-000-
Di medan bencana,
suaminya melawan lumpur
yang bergerak bagai makhluk hidup:
binatang buta
yang menelan nama dan pangkat
dalam satu suap keruh.
Pangkat tak bercahaya di bawah hujan,
nama tak dibedakan oleh arus.
Di hadapan longsor,
manusia dilucuti
hingga tinggal keberanian
yang tak pandai berenang,
namun tetap melompat
demi menarik satu tangan lagi
keluar dari gelap.
-000-
Ketika jasad ditemukan,
Ani terdiam
menjadi tanah
yang baru kehilangan bukit.
Kata “gugur”
diucapkan resmi, rapi,
bagai map yang ditutup pelan
di atas meja upacara.
Di rumah Ani,
kata itu berarti:
tak pulang;
kursi kosong di meja makan;
seragam lipat
yang tak lagi punya bahu.
-000-
Negara berpidato,
bendera dilipat sempurna,
trompet meniup doa hafalan.
Nama suaminya lewat sebentar
di layar berita,
lalu tenggelam
di antara grafik dan iklan deterjen.
Namun duka tak mengenal arsip.
Ia datang tiap malam,
duduk di kursi yang sama,
mengubah suara hujan
menjadi langkah sepatu basah
yang selalu berhenti
tepat di depan pintu
tanpa pernah mengetuk.
-000-
Di luar rumah Ani,
perdebatan tak selesai:
siapa lambat,
siapa lalai,
siapa menandatangani
kontrak yang membuat bukit pincang?
Di gedung tinggi,
slide demi slide berganti;
kurva, anggaran, prosedur;
nama suaminya
mengecil jadi angka kaki halaman.
Sementara itu,
peta digambar ulang
di atas hutan yang belum menua;
akar digadaikan
demi selembar izin baru,
dan bumi diam-diam
menyiapkan hujan berikutnya.
-000-
Tiga prajurit itu pun hilang.
Bukan hanya dari tugas,
melainkan dari masa depan
yang mereka tata pelan
di ujung meja makan:
nama anak,
cicilan rumah,
hari tua di kota kecil
yang mereka kira
tak punya longsor.
Ani berdiri di depan seragam itu,
seperti berdiri di hadapan bumi
yang baru saja kehilangan
cara mencintai manusia.
Ia akhirnya mengerti:
bencana bukan sekadar
hujan yang jatuh
atau tanah yang bergerak,
melainkan jarak yang kita ciptakan
antara hidup
dan bumi yang menghidupi.
Ketika hutan diperlakukan
sebagai angka,
ketika akar ditukar izin,
ketika bukit dinilai
lebih murah dari suara air,
bumi belajar bicara
dengan bahasa yang paling keras.
Maka jika kita ingin
tak lagi menghitung
nama di peti mati,
kita harus belajar
mencintai bumi
bukan setelah ia marah,
melainkan saat ia
masih diam.
Karena hujan
tak pernah berniat membunuh.
Ia hanya datang
mengingatkan:
tanah yang tak kita jaga
akan berhenti
menjaga kita.*
Jakarta, 22 Desember 2025
CATATAN
(1) Tiga prajurit gugur dalam tugas membantu bencana Sumatra
Total 3 Prajurit TNI Gugur Saat Evakuasi Korban Banjir dan Tanah Longsor di Sumbar
-000-
Berbagai puisi esai dan ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/1DfnGPhwB3/?mibextid=wwXIfr