Denny JA: Harga Sosial dari China yang Menumbuhkan Ekonomi di Atas 8 Persen Selama Tiga Dekade, 1979–2010
Belajar dari Model Pembangunan China, Norwegia, Amerika Serikat (4)
Oleh Denny JA
ORBITINDONESIA.COM - Pada suatu sore di awal 2000-an, seorang ibu di desa kecil di sepanjang Sungai Huai membawa ember ke tepi air.
Ia menunggu lama, lalu berhenti. Air sungai berwarna cokelat kehitaman. Busa tipis mengambang di permukaan. Bau kimia menusuk hidung. Ia menutup embernya kembali.
Beberapa kilometer ke hulu, sebuah pabrik kimia baru saja menyelesaikan target produksi bulanannya. Grafik menanjak. Laporan ke pusat memuaskan. Pertumbuhan tercapai.
Namun di hilir, ikan mati mengapung. Anak-anak menderita penyakit kulit. Sawah kehilangan kesuburannya.
Tidak ada pidato yang menghubungkan dua peristiwa ini. Tidak ada laporan resmi yang menyandingkan grafik PDB dengan sungai yang tak lagi layak diminum. Tetapi bagi ibu itu, hubungan sebab-akibat terasa gamblang.
Di sinilah pertanyaan paling sunyi dari keajaiban ekonomi China muncul: siapa yang membayar harga pertumbuhan?
-000-
I. Ketika Angka Naik, Jarak Melebar
Pertumbuhan di atas 8 persen selama puluhan tahun menciptakan kemakmuran yang belum pernah ada dalam sejarah manusia.
Ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Kota-kota menjulang. Infrastruktur membentang jauh melampaui imajinasi generasi sebelumnya.
Namun pertumbuhan cepat jarang datang sendirian. Ia membawa ketimpangan.
Di China, ketimpangan pertama yang mengeras adalah ketimpangan geografis. Pesisir timur melesat jauh ke depan. Pedalaman tertinggal. Shenzhen dan Shanghai menjadi etalase masa depan. Gansu dan Guizhou tetap bergulat dengan masa lalu.
Lalu muncul ketimpangan sosial. Kelas menengah baru tumbuh di kota. Di desa, para lansia tertinggal tanpa jaminan sosial yang memadai. Buruh migran membangun kota-kota modern, tetapi tidak sepenuhnya menjadi warga kota.
Sistem hukou, registrasi penduduk, menjelma tembok tak kasatmata. Ia memisahkan hak dan peluang. Buruh migran bekerja di kota, tetapi akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarganya sering dibatasi.
Cina tidak buta terhadap ketimpangan ini. Namun ia memilih menundanya. Logikanya sederhana:
lebih baik tidak setara tetapi tumbuh, daripada setara dalam kemiskinan.
Pertanyaannya: sampai kapan ketimpangan bisa ditunda tanpa berubah menjadi ledakan?
-000-
II. Lingkungan sebagai Korban Pertama
Jika ketimpangan adalah bayangan sosial pertumbuhan, maka kerusakan lingkungan adalah lukanya yang paling kasatmata.
Langit kelabu Beijing bukan mitos. Sungai tercemar bukan propaganda Barat. Pada puncak industrialisasi, sebagian besar sungai besar China tercemar berat. Udara di kota-kota industri kerap berada pada level berbahaya bagi kesehatan manusia.
Mengapa ini terjadi?
Karena pertumbuhan ekstrem membutuhkan energi murah, produksi masif, dan regulasi longgar. Dalam kompetisi antardaerah, pejabat lokal berlomba menarik investasi. Lingkungan sering menjadi korban yang paling mudah dikorbankan.
Negara pusat mengetahui masalah ini. Namun selama bertahun-tahun, prioritas tetap pada pertumbuhan. Seorang pejabat pernah berkata sinis, “Langit biru tidak bisa dimakan.”
Ungkapan ini merangkum dilema klasik pembangunan: apakah hidup sehat bisa menunggu, sementara kemiskinan menekan dari segala arah?
Cina memilih menunggu. Baru setelah tekanan sosial meningkat, protes lingkungan bermunculan, dan legitimasi mulai terancam, negara berbalik arah. Investasi besar-besaran pada energi terbarukan pun dimulai.
Namun luka lama tidak hilang seketika. Sungai membutuhkan puluhan tahun untuk pulih. Penyakit tidak serta-merta lenyap.
-000-
III. Represi sebagai Harga Stabilitas
Pertumbuhan ekstrem China tidak hanya dibayar dengan lingkungan dan ketimpangan, tetapi juga dengan kebebasan.
Dalam sistem di mana legitimasi politik bertumpu pada kinerja ekonomi, stabilitas menjadi segalanya. Protes yang mengganggu stabilitas diperlakukan sebagai ancaman eksistensial.
Serikat buruh independen dibatasi. Media diawasi. Kritik keras disenyapkan. Negara menjaga satu narasi utama: pertumbuhan adalah proyek nasional, dan proyek nasional tidak boleh diganggu.
Bagi sebagian warga, ini harga yang dapat diterima. Mereka melihat hasil nyata: pekerjaan, rumah, dan masa depan anak-anak.
Bagi yang lain, ini adalah penyangkalan martabat. Mereka bertanya: apa arti kemakmuran jika suara dibungkam?
Dalam filsafat politik, inilah dilema klasik antara keamanan kolektif dan kebebasan individu. China memilih sisi yang tegas.
-000-
IV. Generasi yang Membayar, Generasi yang Menikmati
Salah satu ciri pertumbuhan ekstrem adalah ketidakseimbangan antargenerasi.
Generasi awal reformasi bekerja keras dengan upah rendah dan jaminan minim. Mereka membangun fondasi. Generasi berikutnya menikmati kota modern, pendidikan lebih baik, dan peluang global.
Namun generasi muda hari ini menghadapi tantangan baru: harga rumah yang melambung, kompetisi yang semakin ketat, dan tekanan kerja yang ekstrem. Fenomena lying flat dan involution menjadi ekspresi kelelahan kolektif.
Lying flat adalah pilihan sadar untuk menarik diri dari kompetisi sosial yang ekstrem, menurunkan ambisi, dan hidup minimal sebagai bentuk perlawanan diam terhadap sistem yang melelahkan dan terasa hampa makna.
Involution adalah kondisi ketika upaya, jam kerja, dan kompetisi terus meningkat, tetapi hasil stagnan. Energi kolektif terkuras tanpa kemajuan, memicu frustrasi dan rasa hidup berputar di tempat.
Ironinya, pertumbuhan yang dahulu menjanjikan mobilitas kini terasa seperti jebakan. Tangga sosial makin curam.
China dihadapkan pada pertanyaan moral baru: bagaimana mendistribusikan buah pertumbuhan tanpa mematikan semangat yang dahulu membangunnya?
-000-
Di balik angka pertumbuhan, selalu ada harga yang tak pernah masuk neraca.
Alexandra Harney (2008) menelusuri bagaimana murahnya produksi China kerap lahir bukan dari efisiensi murni, melainkan dari biaya yang dipindahkan dan disembunyikan.
Yang dipindahkan itu nyata. Risiko keselamatan kerja ditanggung buruh. Upah ditekan di bawah martabat hidup layak.
Limbah dilepas ke sungai. Desa-desa dipaksa diam demi memenuhi target produksi. Dunia global menikmati barang yang lebih terjangkau, sementara ongkos sesungguhnya jatuh pada tubuh manusia dan lanskap hidup.
Air berubah warna. Udara memendekkan napas. Tanah kehilangan ingatan kesuburannya.
Dalam logika ini, sungai bukan lagi sekadar aliran kehidupan. Ia menjelma arsip sunyi dosa industri yang tak ingin diakui.
Keunggulan kompetitif tampil sebagai prestasi nasional, padahal ia juga dapat dibaca sebagai mekanisme pelupaan kolektif: melupakan siapa yang menanggung sakit agar grafik tampak sehat dan legitimasi tetap utuh.
Sementara itu, Yuen Yuen Ang (2020) menyorot paradoks yang lebih dalam. Sebuah negara dapat tumbuh cepat sekaligus menanggung korupsi luas, karena tidak semua korupsi bekerja dengan cara yang sama.
Ada korupsi yang merampok dan mematikan. Ada yang melicinkan birokrasi. Ada pula yang menyulut investasi. Masing-masing meninggalkan luka yang berbeda pada jaringan sosial dan kepercayaan publik.
Pertumbuhan tetap bisa berlari, tetapi ia berlari sambil menumpuk utang moral. Ketimpangan mengeras. Kemarahan dipendam.
Legitimasi politik harus terus dibayar dengan kontrol. Dari sini, represi tidak lagi sekadar watak rezim, melainkan mekanisme sistemik untuk menjaga mesin tetap stabil ketika distribusi harapan tidak lagi seimbang.
Dan ketika generasi muda menyadari bahwa tangga sosial semakin curam, bahwa kerja keras tak lagi menjamin mobilitas, lahirlah lying flat.
Ia bukan kemalasan, melainkan duka sosial. Sebuah penarikan diri yang sunyi dari kompetisi yang dirasakan tidak adil. Sebuah cara bertahan ketika masa depan tak lagi menawarkan janji yang masuk akal.
Bayangan Tragedi Tiananmen 1989 membekas dalam ingatan negara: ketika tuntutan partisipasi politik bertemu dengan logika stabilitas, tank menjadi argumen terakhir bahwa pertumbuhan takkan dibiarkan diganggu oleh jalanan.
Perkiraan korban Tiananmen Square bervariasi ratusan hingga ribuan. Tentara menembaki demonstran damai, menangkap massal, menyensor kebenaran, meninggalkan trauma kolektif, dan keheningan negara. Juga luka demokrasi Tiongkok yang tak sembuh sepanjang sejarah.
-000-
V. Negara Menyadari Batas
Memasuki dekade 2010-an, sinyal perubahan kian jelas. Kepemimpinan baru menyadari bahwa pertumbuhan tanpa koreksi dapat berubah menjadi bumerang.
Narasi resmi mulai bergeser:
* dari “pertumbuhan tinggi” ke “pertumbuhan berkualitas”,
* dari ekspansi tanpa batas ke “pembangunan hijau”,
* dari ketimpangan ke “kemakmuran bersama”.
Namun perubahan narasi tidak otomatis menghapus struktur lama. Kepentingan daerah, utang, dan kebiasaan pertumbuhan cepat masih kuat mencengkeram.
Transisi selalu lebih sulit daripada akselerasi.
-000-
VI. Refleksi Filosofis: Apakah Tujuan Menghalalkan Cara?
Di sinilah filsafat hadir, bukan sebagai penghakim, melainkan sebagai cermin.
Apakah mengorbankan lingkungan hari ini demi kesejahteraan esok bisa dibenarkan? Apakah membatasi kebebasan demi stabilitas kolektif sah secara moral?
China menjawab dengan pragmatisme sejarah. Barat sering menjawab dengan prinsip universal. Keduanya menyimpan kontradiksi.
Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa kemajuan tanpa ruang publik berisiko melahirkan alienasi. Sementara pemikir klasik Cina menekankan harmoni dan ketertiban.
China modern berdiri di antara dua warisan ini. Ia tidak sepenuhnya Barat, tidak sepenuhnya tradisional.
-000-
VII. Pelajaran bagi Dunia Berkembang
Esai ini bukan ajakan meniru, melainkan undangan untuk merenung.
Pertumbuhan tinggi memang menggoda. Angka besar memberi legitimasi. Namun biaya yang menyertainya sering tersembunyi, muncul belakangan, dan sulit diperbaiki.
Pelajarannya bukan bahwa pertumbuhan harus dihindari, melainkan bahwa urutan prioritas moral menentukan arah sejarah.
Apa yang ditunda hari ini dapat menjelma krisis esok hari.
Keajaiban ekonomi China adalah kisah terang. Tetapi bayangannya panjang.
Ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan represi bukan kecelakaan. Mereka adalah konsekuensi dari pilihan sadar.
Kini, ketika pertumbuhan melambat, Cina tak lagi bisa menunda pertanyaan moral. Mesin yang dahulu berlari kencang kini harus belajar mengerem.
Dan di situlah bab terakhir menanti. Bab tentang refleksi, koreksi, dan masa depan.*
Jakarta, 6 Januari 2026
REFERENSI
1. The China Price
Pengarang: Alexandra Harney
Penerbit: Penguin Press
Tahun terbit: 2008
2. China’s Gilded Age
Pengarang: Yuen Yuen Ang
Penerbit: Cambridge University Press
Tahun terbit: 2020
-000-
Ratusan esai karya Denny JA tentang filsafat hidup, ekonomi politik, sastra, minyak dan energi, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, psikologi positif, catatan perjalanan, serta ulasan buku, film, dan lagu dapat ditemukan di Facebook: Denny JA’s World.
https://www.facebook.com/share/p/1HVUkmF51u/?mibextid=wwXIfr









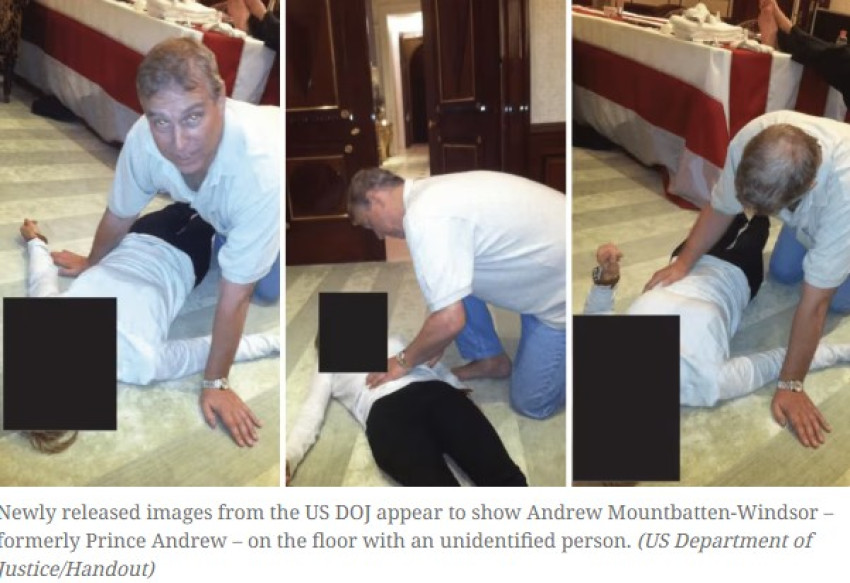
.jpeg)

