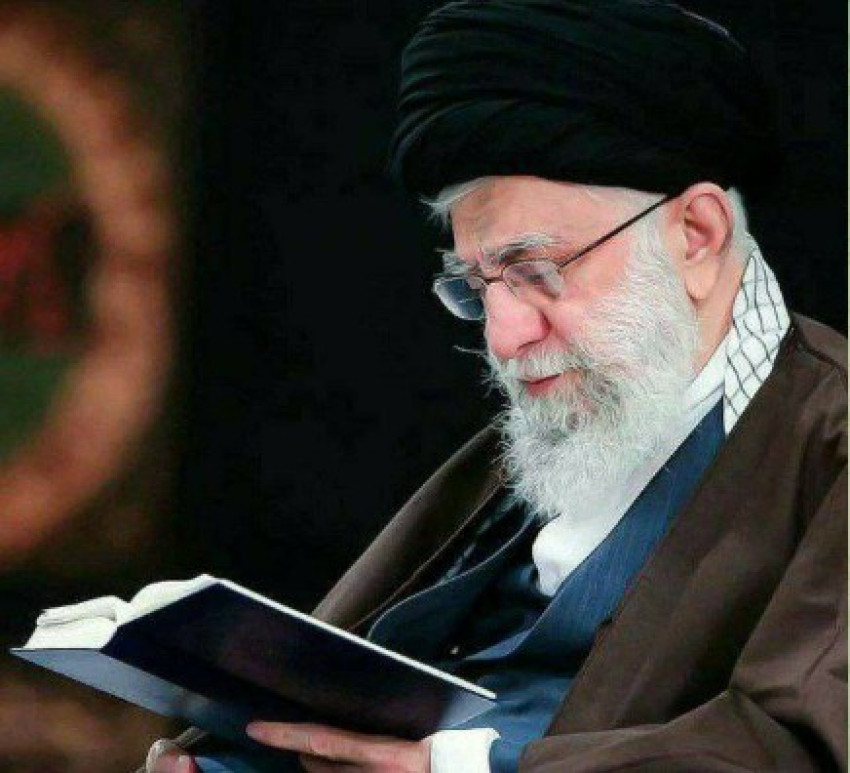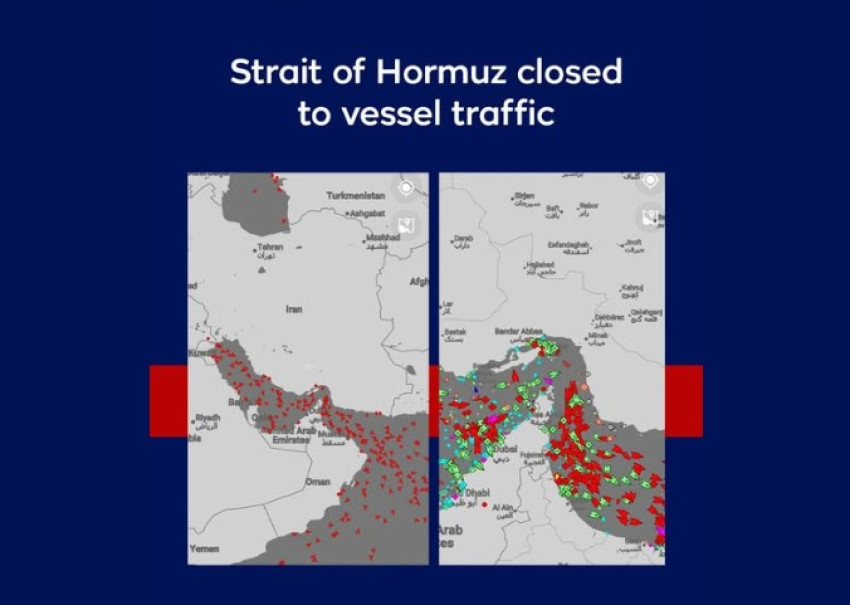Ruang Kelas di Indonesia Bukan Tempat Rekayasa Sosial Zionis
Oleh Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat, kolumnis Middle East Monitor
ORBITINDONESIA.COM - Pemandangan seorang pejabat asing yang membahas cara "mengubah buku teks" di negara berdaulat harus diakui sebagai apa adanya: sebuah penegasan dominasi ideologis.
Pernyataan baru-baru ini yang dikaitkan dengan Rabbi Yehuda Kaploun—seorang pengusaha Miami, pengikut Chabad Hasid, donor kampanye Trump, dan sekarang Utusan Khusus AS untuk Memantau dan Memerangi Antisemitisme—merupakan upaya terang-terangan untuk mengawasi ingatan sejarah di luar perbatasan AS.
Dikonfirmasi oleh suara Senat yang sempit dan partisan dengan hasil 53–43, Kaploun sekarang memegang wewenang duta besar di Departemen Luar Negeri. Dia telah menjelaskan bagaimana dia bermaksud menggunakannya.
Berbicara di Konferensi Jerusalem Post Washington, Kaploun mengidentifikasi Indonesia sebagai target prioritas. “Indonesia memiliki 350 juta Muslim yang tinggal di negara mereka. Bagaimana kita akan mengubah buku-buku pendidikan mereka?” tanyanya, sebelum bersikeras bahwa kurikulum harus dibentuk ulang untuk menentukan “siapa yang harus bertanggung jawab” atas Gaza.
Ini bukan bahasa yang sembarangan. Ini adalah deklarasi niat: untuk merekayasa ulang bagaimana jutaan anak-anak Indonesia memahami kolonialisme, kekerasan, dan penderitaan Palestina—dengan menggunakan kekuatan AS sebagai pengungkit.
Ini tidak ada hubungannya dengan memerangi antisemitisme. Ini sepenuhnya berkaitan dengan kontrol narasi.
Solidaritas Indonesia dengan Palestina tidak didorong oleh kebencian agama, dan bahkan pengawas pro-Israel mengakui hal ini. Ini adalah perpanjangan langsung dari identitas anti-kolonial Indonesia sendiri.
Konstitusi 1945 mewajibkan bangsa untuk menentang kolonialisme "dalam segala bentuknya," sebuah prinsip yang ditempa melalui berabad-abad eksploitasi Belanda dan pendudukan Jepang. Rakyat Indonesia mengenali arsitektur dominasi ketika mereka melihatnya: penyitaan tanah, pemerintahan militer, sistem hukum yang terpisah, dan perlawanan yang dikriminalisasi sebagai teror.
Pengakuan itu tercermin dalam buku teks Indonesia—dan justru itulah yang ingin dihancurkan oleh Israel dan sekutunya.
Menurut surat kabar Indonesia Republika, Israel telah memantau kurikulum Indonesia selama bertahun-tahun melalui lembaga think tank Inggris-Israel IMPACT-se, bekerja sama dengan Yayasan Keluarga Ruderman. Laporan tahun 2023 mereka menganalisis 169 buku teks yang digunakan dalam Jalur Standar Umum Indonesia, yang mencakup sekitar 85 persen siswa di seluruh negeri. Temuan tersebut dengan tegas membantah klaim indoktrinasi anti-Semit.
Referensi terhadap orang Yahudi dalam buku teks pendidikan Islam sebagian besar bersifat netral atau positif. Terorisme secara eksplisit dikutuk. Pluralisme dan keragaman budaya dirayakan. Bias terhadap minoritas agama, etnis, dan ras secara aktif dicegah. Bahkan para peneliti yang terkait dengan Israel ini mengakui bahwa buku teks Indonesia menyajikan pandangan yang seimbang tentang hubungan internasional.
Yang mereka tentang adalah kebenaran politik. Israel digambarkan sebagai penjajah kolonial. Penggusuran Palestina diperlakukan sebagai ketidakadilan yang berkelanjutan. Keberadaan asli orang Yahudi di wilayah tersebut diakui, tetapi praktik negara Zionis dianalisis melalui lensa kolonial yang sama yang diterapkan orang Indonesia pada pemerintahan Belanda dan Jepang. Buku teks bahkan mengakui perkembangan material yang terbatas di bawah kolonialisme—sementara secara tegas menolak dominasi itu sendiri. Kejujuran intelektual inilah yang sekarang dituduhkan.
CEO IMPACT-se, Marcus Sheff, memuji toleransi Indonesia hanya untuk berpendapat bahwa toleransi tersebut harus dipersenjatai untuk "memperbaiki" narasi tentang Israel, sementara Jay Ruderman, anggota dewan IMPACT-se dan presiden Yayasan Keluarga Ruderman, menolak kurikulum Indonesia karena kurangnya sejarah Israel yang "faktual" dan pendidikan Holocaust yang memadai—tuntutan yang pada praktiknya berupaya menormalisasi negara Zionis dengan melemahkan, menggeser, atau menghapus sejarah Palestina.
Kaploun kini telah memberi sinyal bahwa kepatuhan akan ditegakkan melalui tekanan pada pemerintah dan program pendidikan yang didanai PBB, dengan mekanisme "akuntabilitas" bagi mereka yang menolak. Ini bukan diplomasi. Ini adalah paksaan. Pendidikan dipersenjatai untuk menciptakan persetujuan.
Kebejatan proyek ini semakin diperparah oleh waktunya. Saat Israel menghancurkan sekolah dan universitas di Gaza, membunuh para pendidik, dan memusnahkan seluruh generasi siswa Palestina, Washington tidak menunjukkan urgensi yang sebanding untuk melindungi pendidikan Palestina.
Sebaliknya, mereka terpaku pada pendisiplinan kelas-kelas di Indonesia karena menolak untuk menyembunyikan kejahatan Israel. Penghancuran pendidikan di Gaza ditoleransi; penolakan untuk berbohong tentang hal itu di Jakarta tidak.
Pemerintah Indonesia harus merespons dengan sikap menantang, bukan diplomasi. Jakarta harus secara tegas menolak campur tangan asing dalam kurikulumnya, menegaskan komitmen konstitusionalnya terhadap anti-kolonialisme, dan mengungkap kesamaan yang keliru antara menentang antisemitisme dan menegakkan ortodoksi Zionis.
Indonesia dapat memperkuat posisinya dengan memperluas pendidikan anti-rasisme universal—secara eksplisit mengutuk antisemitisme, Islamofobia, dan semua bentuk rasisme—sambil mempertahankan pendirian yang tanpa kompromi terhadap hak-hak Palestina dan hukum internasional.
Posisi Indonesia beresonansi justru karena berprinsip. Semakin banyak orang Indonesia—terutama generasi muda—merangkul visi negara tunggal di Palestina bersejarah, di mana Yahudi dan Palestina hidup setara, bukan sebagai penguasa dan rakyat. Visi ini menolak supremasi etnis, pendudukan permanen, dan hak asasi manusia selektif—logika yang justru ingin dihindari Indonesia.
Yang benar-benar menakutkan mereka yang berusaha menulis ulang buku teks Indonesia bukanlah kebencian, tetapi koherensi. Bukan ketidaktahuan, tetapi ingatan.
Indonesia tidak membutuhkan pengawasan moral dari Washington. Kedaulatan Indonesia perlu dihormati. Keadilan tidak pernah dibangun dengan membungkam pihak yang dijajah—dan Indonesia, yang lahir dari perlawanan, memahami hal itu dengan sangat jelas dan menyakitkan.***