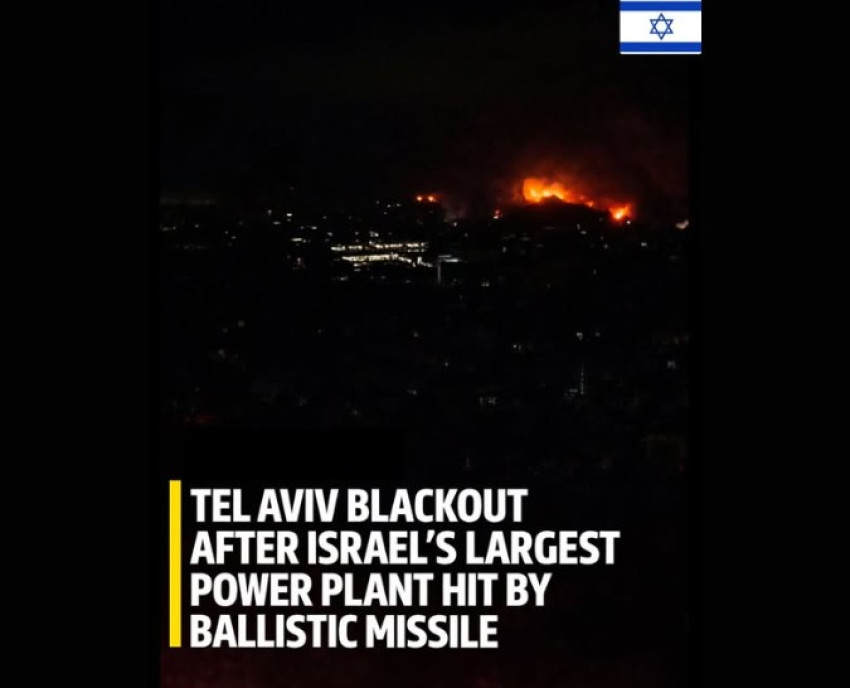Albertus M. Patty: Bencana Ini Diskriminatif
Oleh Albertus M. Patty, kolumnis
ORBITINDONESIA.COM - Bencana kerap disebut sebagai peristiwa alam. Namun, pengalaman kemanusiaan berulang kali memperlihatkan bahwa bencana hampir selalu merupakan hasil perjumpaan antara alam yang rapuh dan kebijakan manusia yang lalai.
Tanah longsor di provinsi Khatlon, Tajikistan, pada awal 2009 memberi pelajaran penting. Desa Baldzhuvan selamat tanpa korban jiwa karena seorang aktivis lokal, Bibi Rahimova, bertahun-tahun membangun kesadaran warganya tentang bahaya hidup di wilayah yang tidak stabil. Keselamatan itu lahir dari pengetahuan, kewaspadaan, dan keberanian untuk mendahului bencana.
Pelajaran ini terasa pahit ketika kita bercermin pada Indonesia. Bertahun-tahun aktivis lingkungan, termasuk dari Greenpeace Indonesia, Forum Hijau Indonesia, dan WALHI, telah mengingatkan negara tentang bahaya eksploitasi tambang dan penghancuran hutan yang melaju nyaris tanpa kendali.
Peringatan yang diberikan dengan data yang lengkap itu sering kali kalah oleh retorika pertumbuhan ekonomi dan janji investasi. Lalu ekologi Sumatera dan Aceh hancur total, lalu banjir bandang datang sebagai kesaksian yang tak terbantahkan: gelondongan kayu hanyut, tanah longsor menelan kampung, dan kehidupan masyarakat runtuh dalam sekejap.
Disaster Apartheid
Yang paling menyayat bukan hanya skala kehancurannya, melainkan watak bencana yang tidak netral. Bencana ini diskriminatif. Ia tidak menghantam semua orang secara setara.
Seorang warga di Tamiang, Aceh, melukiskannya dengan jujur: sementara penguasa dan pengusaha yang merusak hutan dan tanah menikmati guyuran keuntungan di rumah-rumah mewah mereka di Jakarta atau bahkan di luar negeri, rakyat jelata harus menanggung penderitaan yang tak terperi. Rumah, jalan, jembatan, dan jejaring sosial hancur; masa depan menjadi samar. Inilah yang disebut disaster apartheid: bencana yang mengakibatkan penderitaan yang dibagi secara timpang oleh sistem.
Dalam konteks ini, disaster apartheid tidak terutama merujuk pada ketimpangan dalam penanganan pascabencana, melainkan pada ketimpangan sejak awal yaitu ketimpangan kebijakan. Pilihan politik-ekonomi yang memberi karpet merah pada eksploitasi sumber daya alam, disertai pengawasan yang lemah, telah memindahkan risiko ekologis ke pundak masyarakat kecil. Mereka yang paling sedikit menikmati keuntungan justru paling besar menanggung dampak.
Refleksi ini beresonansi dengan pemikiran Vandana Shiva. Dalam bukunya Soil Not Oil, Shiva menegaskan bahwa krisis iklim dan bencana ekologis bukanlah krisis alam semata, melainkan krisis keadilan. Ia menulis, “The climate crisis is not caused by too many people, but by too much greed.”
Kolonialisme Baru
Keserakahan yang dilembagakan melalui kebijakan negara menjadikan tanah dan hutan sekadar komoditas, sementara manusia direduksi menjadi variabel risiko.
Shiva juga mengingatkan bahwa model ekonomi ekstraktif melahirkan kolonialisme bentuk baru, kolonialisme yang tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam. “What we are witnessing is a new form of colonization—of nature, of farmers, and of the poor.”
Dalam konteks Indonesia, kolonialisme ini tampak pada akumulasi keuntungan luar biasa di segelintir tangan, sementara masyarakat lokal kehilangan tanah, air bersih, dan rasa aman.
Ironinya, kebijakan politik-ekonomi yang diklaim membawa kemakmuran justru memperlebar jurang kaya–miskin dan menciptakan ketergantungan ekonomi pada oligarki. Ketika hutan rusak dan tanah kehilangan daya dukungnya, masyarakat bukan hanya kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga kehilangan kedaulatan. Bencana lalu hadir bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai konsekuensi yang dapat diprediksi.
Bukan Takdir
Menyebut bencana sebagai “takdir” dalam situasi seperti ini adalah cara halus untuk menutupi tanggung jawab. Menyebut bencana Sumatera dan Aceh sebagai takdir sama artinya sedang mempersalahkan Allah seolah bencana yang terjadi dirancang oleh Allah. Ini dosa besar!
Sesungguhnya bencana Sumatera dan Aceh adalah cermin dari pilihan-pilihan kolektif elite politik kita. Ia memperlihatkan siapa yang dilindungi oleh kebijakan dan siapa yang dibiarkan rentan. Jika elite politik kita masih abai dan menganggap remeh bencana yang ada, lalu eksploitasi dianggap harga yang wajar demi pertumbuhan, maka disaster apartheid akan terus berulang.
Banjir bandang di Sumatera dan Aceh mengajak kita berhenti melihat bencana semata sebagai peristiwa alam, dan mulai membacanya sebagai peringatan moral.
Negara masih memiliki pilihan: memperbaiki tata kelola, memulihkan hutan dan tanah, serta menempatkan keselamatan rakyat di atas keuntungan jangka pendek. Tanpa perubahan arah itu, bencana akan terus datang, dan datang lagi dengan lebih dahsyat. Dan bencana itu akan kembali diskriminatif karena selalu menimpa mereka yang paling lemah.
Bandung, 20 Desember 2025 ***