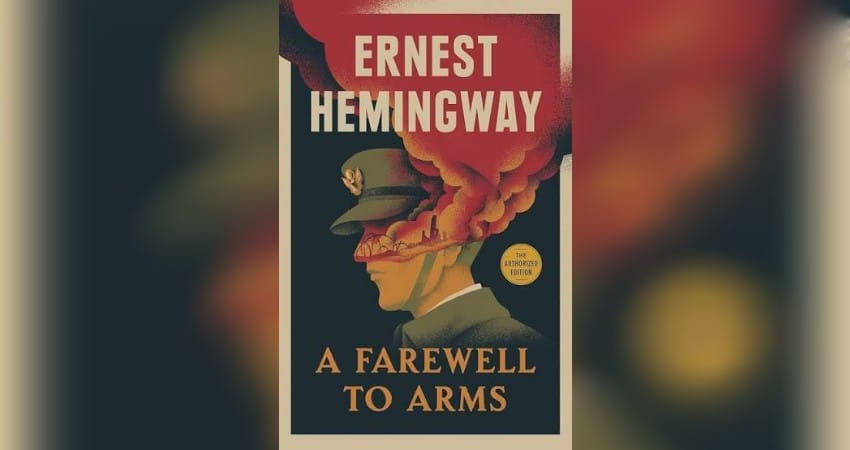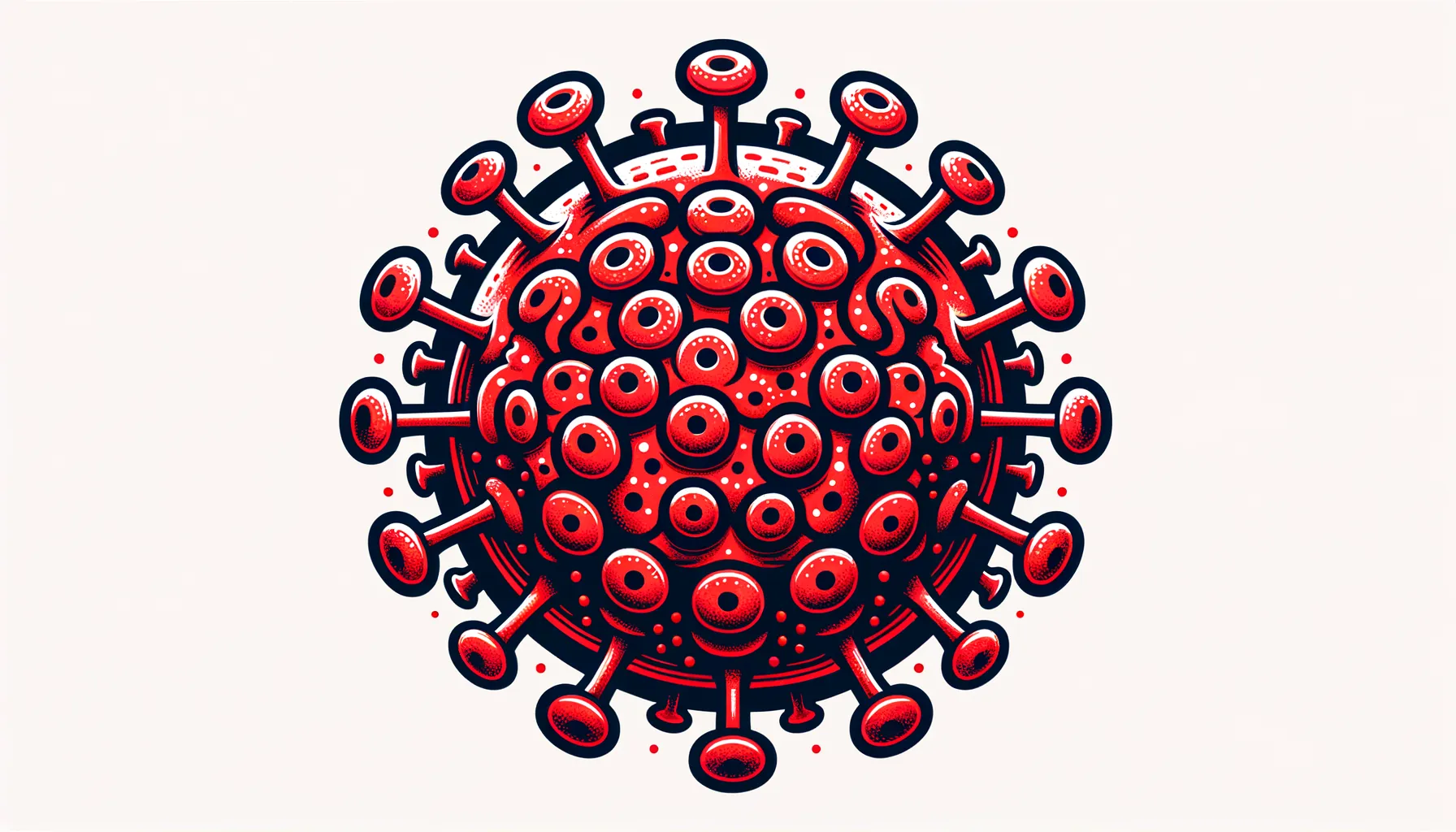Resensi Buku A Farewell to Arms Karya Ernest Hemingway: Cinta, Perang, dan Keputusasaan Manusia Modern
ORBITINDONESIA.COM- Ketika Ernest Hemingway menerbitkan A Farewell to Arms pada 1929, dunia sastra modern tiba-tiba terdiam. Novel ini tidak hanya tentang perang dan cinta, melainkan tentang keterasingan manusia di tengah kehancuran makna.
Hemingway, yang pernah menjadi sopir ambulans Palang Merah di garis depan Italia selama Perang Dunia I, menulis novel ini bukan dari imajinasi, tetapi dari luka batin yang nyata — luka yang diubahnya menjadi gaya prosa paling dingin dan jujur dalam sejarah sastra modern.
Judulnya sendiri, A Farewell to Arms (Perpisahan kepada Senjata), menyiratkan lebih dari sekadar kepergian dari medan perang. Ia adalah perpisahan dari ilusi — tentang cinta, patriotisme, dan bahkan Tuhan.
Novel ini menempatkan pembacanya di tengah absurditas perang, di mana segala nilai runtuh dan satu-satunya hal yang masih mungkin adalah mencintai — meski cinta itu pun akhirnya harus dikorbankan.
Isi dan Alur Cerita: Antara Medan Perang dan Medan Hati
Tokoh utama, Frederic Henry, adalah seorang perwira muda Amerika yang bertugas di korps ambulans tentara Italia selama Perang Dunia I. Ia menjalani hidup dengan dingin, tanpa idealisme, hingga bertemu dengan Catherine Barkley, seorang perawat Inggris yang kehilangan tunangannya dalam perang.
Hubungan mereka dimulai dengan permainan rayuan, tetapi berkembang menjadi pelarian dua jiwa dari absurditas dunia. Ketika medan perang berubah menjadi neraka tanpa makna, cinta menjadi satu-satunya tempat berlindung.
Namun Hemingway menolak romantisasi. Bahkan di saat-saat paling lembut, bayangan perang tetap mengintai. Frederic terluka, kembali ke garis belakang, lalu mendapati kekacauan tentara Italia yang mundur dan membunuh sesama prajuritnya sendiri.
Ia kemudian mendesersi, melarikan diri bersama Catherine ke Swiss — hanya untuk menyaksikan kekasihnya meninggal saat melahirkan anak mereka.
Kematian Catherine adalah puncak absurditas: bahkan cinta yang paling murni pun tak punya tempat di dunia yang telah kehilangan makna. Frederic hanya bisa berjalan keluar dari rumah sakit “dalam hujan”, meninggalkan tubuh Catherine — simbol tragis bahwa manusia modern tidak lagi bisa memeluk apa pun, kecuali kesendiriannya.
Gaya dan Teknik Penulisan: Keheningan sebagai Kejujuran
Hemingway dikenal dengan “Iceberg Theory” — teori gunung es — di mana sebagian besar makna tersembunyi di bawah permukaan narasi. Prosa dalam A Farewell to Arms tampak sederhana, bahkan dingin, tetapi di balik kesederhanaan itu mengalir emosi yang membara dan sunyi yang menakutkan.
Bahasanya pendek, ekonomis, tanpa hiasan. Dialog antar tokoh sering kali datar, tetapi justru di situlah intensitasnya lahir: cinta diungkapkan tanpa kata, penderitaan tanpa air mata, dan kehilangan tanpa ratapan.
Dalam gaya ini, Hemingway tidak menawarkan penghiburan. Ia menulis perang bukan dengan retorika heroik, melainkan dengan lirisisme yang kering dan brutal.
Semua hal — darah, salju, anggur, tubuh manusia — digambarkan tanpa komentar moral, seolah dunia kehilangan narasi etik. Pembaca dibiarkan merasa hampa, dan dari kehampaan itulah muncul makna paling dalam.
Tema dan Makna: Cinta dalam Dunia Tanpa Tuhan
Pertama, Perang sebagai absurditas:
Hemingway tidak menggambarkan perang sebagai medan kehormatan, melainkan teater kebodohan kolektif. Semua orang menderita, mati, atau kehilangan arah tanpa alasan yang masuk akal. Dalam dunia seperti itu, konsep kepahlawanan menjadi parodi, dan manusia hanya bisa bertahan dengan keheningan.
Kedua, Cinta sebagai bentuk pemberontakan:
Hubungan Frederic dan Catherine bukan sekadar kisah asmara, melainkan upaya eksistensial untuk menolak kehancuran. Cinta menjadi semacam agama baru — satu-satunya nilai yang masih bisa dipercayai di tengah kekosongan spiritual. Tetapi bahkan cinta pun akhirnya dikalahkan oleh absurditas dunia, menunjukkan betapa rapuhnya harapan manusia.
Ketiga, Kesunyian dan ketakberdayaan manusia modern:
Setelah Catherine meninggal, Frederic tidak berteriak atau menangis. Ia hanya berjalan sendirian ke luar ruangan. Dalam kesunyian itu, Hemingway menunjukkan puncak keputusasaan manusia modern: kehilangan semu++a sistem makna — agama, negara, cinta — dan dibiarkan menatap kehampaan dengan kepala tegak.
Konteks Historis: Generasi yang Hilang
A Farewell to Arms lahir dari konteks “Lost Generation” — generasi penulis dan pemuda Eropa yang hancur secara moral setelah Perang Dunia I. Hemingway, bersama T.S. Eliot dan F. Scott Fitzgerald, menggambarkan dunia yang tidak lagi memiliki pusat nilai.
Frederic Henry adalah prototipe manusia modern: sinis, pragmatis, dan haus makna, tetapi selalu gagal menemukannya. Dalam dirinya, Hemingway mengabadikan wajah generasi yang kehilangan arah, tetapi tetap hidup dengan keberanian dingin.
Relevansi dan Pembacaan Modern
Lebih dari seabad kemudian, novel ini tetap relevan. Dunia hari ini, dengan perang yang terus berlangsung, kehilangan moral publik, dan pencarian makna pribadi, tidak jauh berbeda dari dunia Frederic Henry.
Bagi pembaca modern, A Farewell to Arms bukan sekadar kisah cinta tragis, tetapi pelajaran tentang kemanusiaan tanpa ilusi — tentang bagaimana mencintai dalam dunia yang tidak menjamin kebahagiaan, dan bagaimana tetap berdiri di tengah kekacauan tanpa alasan untuk berharap.
Penutup: Perpisahan yang Tak Pernah Selesai
A Farewell to Arms adalah novel tentang perpisahan — bukan hanya kepada perang, tetapi kepada harapan, cinta, dan bahkan Tuhan. Dalam setiap halaman, Hemingway seolah berbisik bahwa kehidupan adalah medan perang tanpa kemenangan: yang ada hanya keberanian untuk menatap luka tanpa berpaling.
Gaya prosa Hemingway yang dingin justru menyalakan bara makna paling hangat: bahwa dalam kesunyian dan kehilangan, manusia masih bisa menemukan bentuk keberanian tertinggi — keberanian untuk mencintai meski tahu segalanya akan hilang.
Pada akhirnya, perpisahan dalam novel ini bukanlah akhir, melainkan kondisi abadi manusia: hidup adalah serangkaian perpisahan yang kita hadapi dengan kepala tegak dan hati yang retak.***