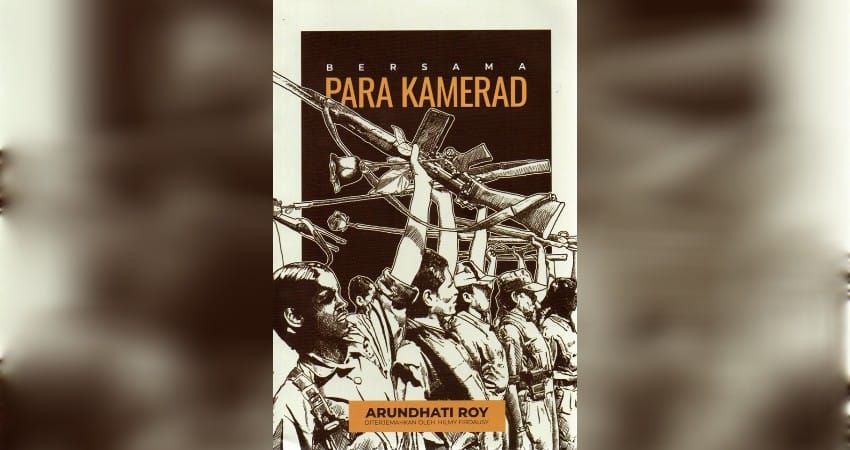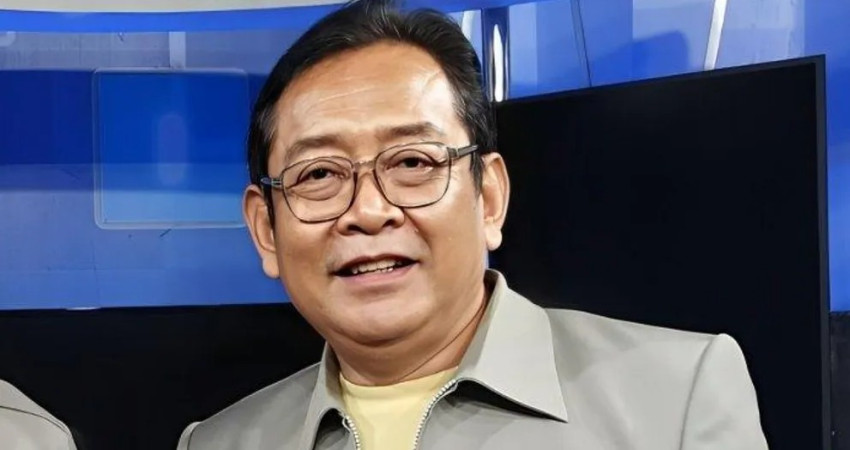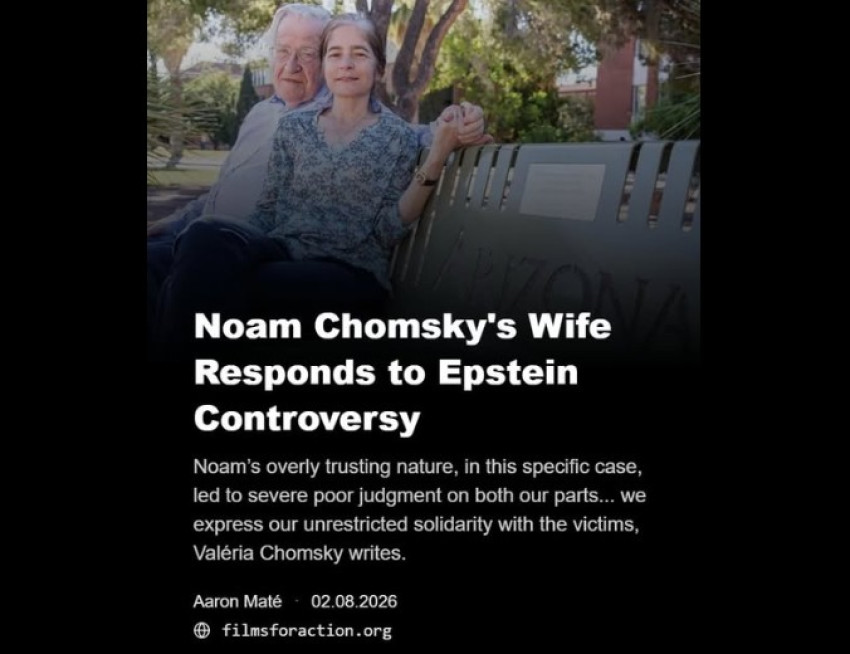Resensi Buku Bersama Para Kamerad: Arundhati Roy dan Lembah Perlawanan
ORBITINDONESIA.COM- Buku Bersama Para Kamerad adalah terjemahan dari esai panjang Arundhati Roy yang berjudul asli Walking with the Comrades, pertama kali diterbitkan pada tahun 2011 oleh Penguin Books India. Dalam versi bahasa Indonesia, buku ini diterbitkan oleh GDN Press dan terbit di Indonesia pada tahun 2022 dengan judul Bersama Para Kamerad.
Buku ini bukan novel, bukan pula laporan jurnalistik biasa, melainkan sebuah elegi politik dan sekaligus puisi perlawanan. Ia ditulis setelah Arundhati Roy — novelis asal India yang memenangkan Booker Prize lewat The God of Small Things (1997).
Arundhati Roy melakukan perjalanan ke dalam hutan Dandakaranya, basis gerilyawan Maois India (disebut juga Naxalite), yang kala itu tengah diperangi oleh negara India melalui operasi militer besar-besaran Operation Green Hunt.
Di sana, Roy tidak sekadar “meliput”, tapi hidup dan berjalan bersama para pemberontak, makan dari panci yang sama, tidur di tanah yang sama, dan menulis dari jarak yang paling berbahaya sekaligus paling manusiawi: jarak yang menyentuh.
Isi dan Struktur Buku: Jurnalisme yang Menjadi Kesaksian
Dalam Bersama Para Kamerad, Roy tidak menulis dengan gaya berita atau laporan investigatif seperti wartawan konvensional. Ia menulis dengan intonasi puitis dan politik yang berpadu, sebuah jurnalisme yang berubah menjadi sastra, dan sastra yang menjadi amunisi moral.
Buku ini terbagi dalam beberapa bagian yang mengikuti struktur perjalanannya ke jantung hutan Bastar di India tengah — wilayah yang menjadi medan perang antara negara dan rakyatnya sendiri.
Roy mendeskripsikan bagaimana hutan-hutan tropis di Chhattisgarh bukan sekadar bentang alam, melainkan ruang hidup jutaan warga suku Adivasi (penduduk asli India) yang diusir dari tanah mereka atas nama “pembangunan”, “keamanan nasional”, dan “kemajuan ekonomi”.
Ia menyingkap wajah kapitalisme neoliberal India yang bertopeng modernisasi, di mana korporasi tambang dan pemerintah bekerja sama untuk menjarah tanah mineral yang dihuni suku-suku kecil tak bersenjata.
Di sinilah Arundhati Roy menemukan paradoks besar abad ke-21: demokrasi elektoral yang tampak indah di kota, tetapi berdarah di hutan.
“Ketika negara menjadi korporasi,” tulisnya, “setiap bentuk perlawanan rakyat disebut terorisme.”
Roy menelusuri realitas itu dengan mata tajam seorang intelektual dan hati lembut seorang penyair. Ia menulis tentang perempuan-perempuan muda yang menjadi kombatan, tentang tawa di tengah peluru, tentang api kecil yang tak padam meski diliputi kabut propaganda dan represi.
Arundhati Roy: Dari Novelis Menjadi Kamerad
Untuk memahami buku ini, kita perlu menempatkan Arundhati Roy bukan hanya sebagai penulis, tetapi sebagai saksi moral zaman. Setelah kesuksesan besar The God of Small Things, Roy memilih jalan yang jarang ditempuh sastrawan besar.
Roy turun ke jalan, menentang globalisasi, kapitalisme, dan nasionalisme agresif India.
Ia menjadi penulis-aktivis yang menulis bukan demi karier, tetapi demi keyakinan. Dalam Bersama Para Kamerad, ia menolak untuk menjadi pengamat yang netral. Ia memihak — pada yang tertindas, pada yang disingkirkan, pada yang disebut “pemberontak” oleh negara.
Sikap ini membuatnya dihujat di tanah airnya, dianggap “pengkhianat bangsa” oleh nasionalis India. Tapi di situlah kekuatan moral Roy berakar: ia lebih memilih dikutuk karena berpihak pada yang benar daripada dipuji karena diam.
Makna Politik dan Filsafat Perlawanan
Di balik kisah perjalanan Roy di hutan-hutan Bastar, tersembunyi sebuah pertanyaan universal tentang makna perlawanan. Apakah kekerasan gerilyawan Maois dapat dibenarkan ketika negara lebih dahulu menindas dengan kekerasan yang lebih besar?
Apakah rakyat yang mempertahankan tanah mereka disebut kriminal hanya karena mereka tidak tunduk pada hukum buatan elit kota?
Roy tidak memberi jawaban pasti. Ia menulis dengan kesadaran tragis: bahwa keadilan tidak selalu lahir dari hukum, dan kemanusiaan tidak selalu berpihak pada yang menang. Ia menulis:
“Ketika negara memerangi rakyatnya sendiri, siapa yang akan menyebut itu perang saudara, dan siapa yang akan menyebut itu pembangunan?”
Dengan demikian, Bersama Para Kamerad bukan sekadar laporan tentang perang di hutan India, melainkan refleksi tentang hubungan antara negara, rakyat, dan kekuasaan global.
Ia mengajak pembaca untuk melihat kembali arti “kemajuan” dalam dunia modern — apakah kemajuan berarti gedung-gedung tinggi dan investasi, ataukah kemampuan manusia untuk hidup berdampingan dengan alam tanpa saling menghancurkan?
Relevansi bagi Dunia Modern
Membaca Bersama Para Kamerad hari ini berarti membaca kembali peta dunia yang sama: di mana rakyat kecil diusir demi proyek tambang, hutan dibakar demi sawit, dan kekuasaan membungkus diri dengan kata “pembangunan”.
Kisah para kamerad di hutan Bastar bisa saja terjadi di Papua, Kalimantan, atau Amazon.
Roy menulis dari India, tapi gema kata-katanya bergema lintas batas bangsa dan bahasa. Ia menunjukkan bahwa imperialisme baru kini tidak lagi datang dari penjajah asing, tapi dari negara sendiri yang menjadi kaki tangan kapital global.
Buku ini, dalam konteks Indonesia, menjadi cermin keras bagi nurani kita: sejauh mana kita berani berjalan bersama kaum kecil, mendengar bahasa mereka, dan memihak tanpa syarat?
Penutup: Jurnalisme yang Menjadi Doa Perlawanan
Bersama Para Kamerad bukan hanya buku tentang perang, melainkan tentang kemuliaan manusia yang bertahan di tengah kehancuran. Ia bukan hanya kesaksian, tapi juga elegi; bukan hanya laporan, tapi juga doa — doa yang lahir dari lumpur, peluh, dan darah.
Arundhati Roy menulis dengan bahasa yang menyala, tapi penuh kasih. Ia menolak menjadi penulis yang netral, sebab di dunia yang tidak adil, netralitas adalah bentuk keberpihakan pada penindas.
Buku ini layak dibaca oleh siapa pun yang ingin memahami wajah lain globalisasi — wajah yang tidak tampak di gedung-gedung pencakar langit, tetapi di mata perempuan desa yang menenteng senapan bambu demi mempertahankan tanahnya.
Pada akhirnya, Bersama Para Kamerad adalah pengingat bahwa kemanusiaan sejati tidak lahir di pusat kekuasaan, melainkan di pinggiran, di antara mereka yang berani melawan dengan keyakinan bahwa dunia yang adil masih mungkin diperjuangkan.***