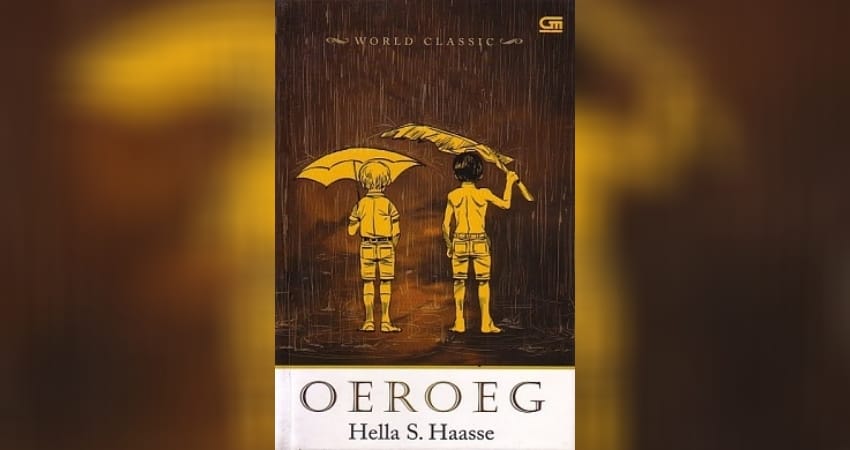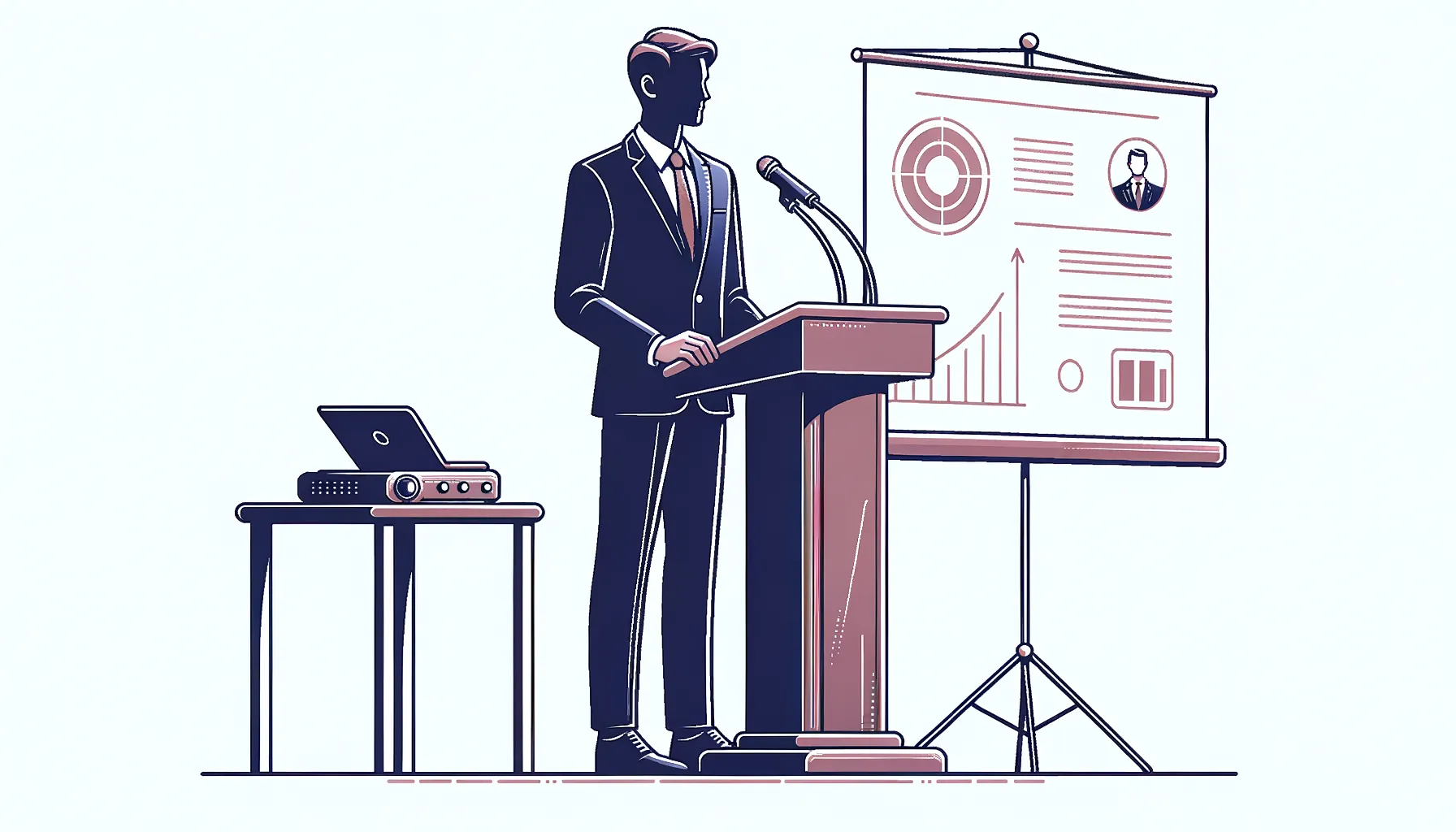Resensi Buku Oeroeg Karya Hellas S. Haasse: Bayangan Persahabatan dan Kolonialisme
ORBITINDONESIA.COM- Novel klasik Belanda yang berjudul Oeroeg, ditulis oleh Hella S. Haasse, seorang novelis besar Belanda yang sering disebut “Grand Old Lady of Dutch Literature." Novel ini menjadi kajian yang menarik bagi siapa pun yang ingin mendalami karya sastra di era seputar perjuangan kemerdekaan Indonesia
Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1948 oleh Uitgeverij Querido, Amsterdam, Belanda. Di Indonesia, novel ini telah diterbitkan dalam terjemahan berbahasa Indonesia dengan judul Oeroeg yang sama. Bahkan novel ini telah diangkat menjadi film layar lebar pada tahun 1993.
Latar Sejarah dan Konteks Penulisan
Hella Haasse menulis Oeroeg segera setelah Perang Dunia II berakhir, dalam masa ketika Belanda baru saja kehilangan Hindia Belanda (Indonesia) yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945.
Di tengah ketegangan politik itu, novel ini menjadi karya yang sangat berani karena berusaha menatap hubungan kolonial secara jujur—tidak dari perspektif nasionalisme sempit, tetapi dari kacamata kemanusiaan dan persahabatan. Yang menariknya yang menulis tentang hal ini adalah orang Belanda sendiri. Hellas S. Haasse tidak sungkan mengkritik keras penjajahan dan kolonialisme negerinya sendiri lewat buku ini.
Haasse sendiri lahir di Batavia (Jakarta) pada tahun 1918 dan menghabiskan masa kecilnya di Hindia Belanda. Maka Oeroeg bukan sekadar fiksi, melainkan juga nostalgia dan refleksi personal atas dunia kolonial yang dikenalnya—dunia yang terbelah antara “Belanda kulit putih” dan “Pribumi yang dijajah."
Novel ini menjadi salah satu karya pertama dari penulis Eropa yang berani mengkritik ketimpangan kolonial dan melihat Indonesia bukan sekadar “latar eksotik”, melainkan tanah dengan martabat dan sejarahnya sendiri.
Ringkasan Cerita: Sahabat yang Terpisah oleh Warna Kulit
Cerita Oeroeg dikisahkan oleh seorang narator “aku” — seorang anak Belanda tanpa nama — yang tumbuh di perkebunan teh di Jawa Barat bersama sahabat masa kecilnya, seorang anak pribumi bernama Oeroeg.
Persahabatan mereka sederhana, polos, dan penuh kehangatan: mereka berenang bersama di danau, menjelajahi hutan, dan berbagi dunia tanpa sadar akan batas sosial yang kelak memisahkan mereka.
Namun seiring mereka tumbuh dewasa, bayang kolonialisme mulai membelah mereka. Si “aku” dikirim ke sekolah Belanda di Eropa, sementara Oeroeg tetap di Hindia, memandang dunia dari sisi yang lain.
Ketika sang narator kembali ke Hindia Belanda sebagai orang dewasa, situasi telah berubah: perang kemerdekaan sedang berkobar, dan Oeroeg telah menjadi bagian dari gerakan perlawanan Indonesia melawan Belanda.
Klimaks cerita terjadi ketika sang narator — kini seorang perwira Belanda — berhadapan dengan sosok Oeroeg yang tidak lagi ia kenal: bukan lagi sahabat masa kecil, melainkan musuh ideologis dalam dua dunia yang saling bertentangan.
Dalam perjumpaan singkat mereka, keduanya menyadari bahwa “jarak antara penjajah dan yang dijajah” bukan sekadar geografis, melainkan batiniah — jarak yang diciptakan oleh sejarah dan identitas.
Tema dan Gagasan Utama
Novel Oeroeg menyoroti konflik identitas dan kehilangan di tengah perubahan sejarah. Hella Haasse menggambarkan betapa rapuhnya hubungan personal ketika dibebani oleh struktur sosial kolonial.
Tema utama novel ini adalah persahabatan yang mustahil bertahan di bawah bayang kekuasaan, serta kesadaran bahwa kasih sayang manusia bisa dikalahkan oleh sistem yang menindas.
Selain itu, novel ini menyinggung tema rasa bersalah kolonial: narator Belanda menyadari bahwa ia dan bangsanya telah lama “hidup di atas tanah orang lain” tanpa memahami penderitaan dan aspirasi rakyat pribumi. Dalam momen-momen kontemplatif, ia mengakuinya dengan getir: “Aku baru sadar bahwa aku tidak pernah benar-benar mengenal Oeroeg.” Kalimat ini adalah inti tragedi kolonial — bahwa penjajah tak pernah sungguh mengenal yang dijajah.
Haasse juga memperlihatkan sisi batin Oeroeg yang ambigu: ia bukan sekadar simbol perlawanan, tetapi juga representasi dari manusia yang mencari jati diri dalam sistem yang merendahkannya.
Dengan begitu, Oeroeg bukan hanya kisah dua sahabat, tapi alegori tentang dua bangsa yang saling berpisah karena sejarah.
Gaya Bahasa dan Struktur
Dengan panjang hanya sekitar 100 halaman, Oeroeg adalah novella yang padat namun sangat liris. Haasse menulis dengan gaya introspektif dan elegan, memadukan lirisisme lanskap tropis dengan refleksi moral yang tajam.
Deskripsi alam Jawa — hutan, perkebunan, dan danau — digambarkan dengan detail penuh nostalgia, namun juga sebagai simbol bagi perubahan: alam tetap indah sementara manusia di dalamnya saling menjauh.
Bahasa Haasse menampilkan nuansa kerinduan, seolah setiap kalimatnya adalah cara untuk “menatap kembali masa kecil yang tak bisa dikembalikan”.
Di sisi lain, novel ini tidak jatuh pada sentimentalitas: ia tetap rasional dan reflektif, menunjukkan kecanggungan orang Belanda menghadapi dekolonisasi.
Penerimaan dan Pengaruh
Sejak terbit, Oeroeg menjadi novel wajib baca di sekolah-sekolah Belanda selama beberapa dekade. Ia menjadi semacam rite of passage bagi generasi Belanda pascakolonial — membantu mereka memahami sejarah kolonial yang selama ini diabaikan.
Novel ini juga telah diadaptasi menjadi film berjudul Oeroeg pada tahun 1993, disutradarai oleh Hans Hylkema.
Bagi pembaca Indonesia, Oeroeg memiliki posisi yang unik. Ia bukan ditulis oleh orang Indonesia, namun berhasil menyampaikan pandangan manusiawi terhadap perjuangan kemerdekaan dan penderitaan rakyat.
Dalam konteks sastra dunia, ia bisa disandingkan dengan Heart of Darkness karya Joseph Conrad atau A Passage to India karya E. M. Forster, tetapi dengan sensitivitas tropis yang lebih lembut dan jujur.
Makna dan Relevansi bagi Pembaca Modern
Kini, lebih dari 75 tahun setelah diterbitkan, Oeroeg masih terasa relevan. Novel ini mengajarkan bahwa dekolonisasi bukan hanya peristiwa politik, tetapi juga penyembuhan psikologis dan spiritual.
Dalam dunia global saat ini, di mana identitas dan warisan kolonial masih menjadi perdebatan, kisah tentang dua sahabat yang dipisahkan oleh warna kulit dan sejarah tetap menggugah hati.
Bagi pembaca Indonesia, Oeroeg menawarkan kesempatan untuk melihat bagaimana seorang penulis Belanda mencoba memahami “kita” — rakyat jajahan — bukan sebagai objek, tetapi sebagai manusia yang setara.
Ini menjadikan Oeroeg bukan sekadar dokumen sejarah sastra kolonial, tetapi juga jembatan empati lintas bangsa.
Penutup: Jejak yang Tak Pernah Hilang
Oeroeg adalah kisah kehilangan — kehilangan sahabat, tanah air, masa kecil, dan rasa tidak bersalah. Ia adalah surat cinta sekaligus surat penyesalan kepada masa lalu kolonial.
Dalam kesunyian akhirnya, narator menyadari bahwa ia “tak lagi punya rumah di mana pun” — tidak di Belanda, tidak pula di Indonesia.
Di situlah tragedi sekaligus keindahan Oeroeg: kisah dua anak manusia yang pernah berbagi dunia yang sama, namun akhirnya berdiri di dua sisi sejarah.***