Catatan Denny JA - Menuju Energi yang Ramah Lingkungan: Point of No Return
Menghadiri Eksibisi dan Konferensi Minyak Internasional ADIPEC, 3–6 November 2025 (3)
Oleh Denny JA
ORBITINDONESIA.COM - Pagi itu, seorang ayah di Jakarta menatap langit kelabu yang menggantung di atas rumahnya. Udara berdebu, sinar matahari tampak kusam seperti disaring kabut asap yang pekat.
Di sampingnya, anak laki-laki berumur sembilan tahun memeluk tas sekolahnya dan bertanya dengan polos, “Ayah, kenapa langit kita tidak biru lagi?”
Pertanyaan sederhana itu menembus jantung kenyataan: bahwa setiap tarikan napas manusia kini membawa jejak dari kecerobohan masa lalu.
Setiap tetes bensin yang terbakar, setiap kilowatt listrik yang dihasilkan dari batu bara, menjadi noda tak kasat mata di paru-paru bumi.
-000-
Sejak revolusi industri di abad ke-18, manusia menemukan cara mengubah batu bara, minyak, dan gas menjadi mesin kemajuan.
Asap pabrik menjadi lambang kejayaan, dan bara api menjadi denyut modernitas. Namun di balik gemerlap itu, bumi mulai memanas, perlahan tapi pasti.
Tahun 1896, ilmuwan Swedia Svante Arrhenius untuk pertama kalinya memperingatkan dunia tentang efek rumah kaca akibat emisi karbon dioksida.
Namun kala itu, dunia masih mabuk akan penemuan mesin uap; peringatan ilmiah dianggap gangguan bagi euforia kemajuan.
Baru pada dekade 1970-an, setelah krisis minyak mengguncang dunia dan foto-foto bumi dari luar angkasa memperlihatkan betapa rapuh planet biru ini, kesadaran baru tumbuh.
Energi yang sama yang menghidupkan dunia juga perlahan membunuhnya. Istilah “energi rendah karbon” lahir dari rahim ketakutan kolektif.
Ini adalah gagasan untuk menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi bersih: matahari, angin, air, panas bumi, dan biomassa.
Konteks sosialnya pun kompleks. Di negara-negara maju, lahir gerakan lingkungan yang menuntut tanggung jawab industri terhadap polusi.
Di dunia berkembang, isu ini bertabrakan dengan kebutuhan ekonomi: bagaimana menyeimbangkan kemakmuran dan keberlanjutan?
-000-
Tahun 1992, di Konferensi Rio de Janeiro, dunia menandatangani United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Inilah tonggak pertama kesadaran global bahwa bumi adalah rumah bersama.
Lalu pada 1997, lahirlah Protokol Kyoto, di mana negara-negara industri berjanji mengurangi emisi mereka.
Namun, janji itu belum cukup. Suhu bumi terus naik, gunung es mencair, dan badai datang lebih sering dari doa.
Barulah pada tahun 2015, dunia mencapai kesepakatan besar: Paris Agreement. Sebanyak 195 negara menyatakan tekad untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2°C dibanding masa praindustri, dengan upaya ideal menahan di 1,5°C.
Di sanalah istilah baru memasuki kamus peradaban: net zero emission. Dunia bersepakat untuk menyeimbangkan karbon yang dilepaskan dengan yang diserap kembali oleh alam agar bumi bisa pulih.
-000-
Namun, di balik diplomasi megah itu, ada perdebatan yang getir. Negara-negara maju diminta bertanggung jawab atas “utang karbon” masa lalu mereka.
Sementara negara berkembang, yang masih berjuang keluar dari kemiskinan, diminta menahan laju pembangunan yang digerakkan energi murah.
Keadilan iklim menjadi isu moral global: apakah dunia siap berbagi tanggung jawab dan teknologi untuk menyelamatkan satu-satunya rumah yang kita miliki bersama?
Dalam konteks inilah, dekarbonisasi menjadi bukan sekadar istilah teknokratik, tapi panggilan spiritual zaman.
Ia adalah upaya radikal membebaskan peradaban dari jerat karbon yang mengikat setiap mesin dan setiap ambisi ekonomi. Ia juga ujian empati manusia terhadap generasi yang belum lahir.
-000-
Pada November 2025 di ADIPEC, Abu Dhabi, diskusi tentang masa depan energi mencapai titik reflektif.
Di jantung industri minyak dunia, para pemimpin global duduk bersama dalam sesi bertajuk “Decarbonisation – Balancing Energy Security, Sustainability, and Affordability.”
Ironinya justru menyentuh: di negeri para produsen minyak, lahir tekad untuk menata ulang arah peradaban energi.
Mereka berbicara bukan hanya tentang efisiensi dan profit, tetapi tentang keseimbangan antara keamanan energi, keberlanjutan ekologis, dan keterjangkauan bagi rakyat.
Karena energi bersih yang mahal bukanlah solusi, melainkan bentuk baru dari ketimpangan.
Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) bahkan berkomitmen menginvestasikan 15 miliar dolar untuk proyek-proyek dekarbonisasi: Carbon Capture and Storage (CCS), elektrifikasi, hidrogen biru, dan kecerdasan buatan untuk efisiensi energi.
Dunia pun melihat arah baru: bahwa bahkan raksasa minyak kini ingin berubah.
-000-
Sementara itu, Indonesia — negeri di garis khatulistiwa dengan kekayaan energi melimpah — perlahan menulis babnya sendiri dalam sejarah rendah karbon.
Komitmen yang pertama kali diumumkan pada Paris Agreement kini diperkuat menjelang COP30 pada 2025: target penurunan emisi absolut pada 2035, dan net zero emission pada 2060, atau lebih awal jika memungkinkan.
Pemerintah tengah menyusun Just Energy Transition Roadmap, memastikan pekerja batu bara tidak kehilangan masa depan. Energi hijau tak boleh menjadi jargon, tapi kesejahteraan nyata bagi rakyat.
Melalui Energy Transition Mechanism, Indonesia menargetkan 72% energi terbarukan pada pertengahan abad.
Namun, sejarah selalu menuntut harga. Transisi ini bukan perjalanan tanpa luka. Akan ada daerah yang kehilangan pekerjaan lama, perusahaan yang harus beradaptasi, dan masyarakat yang menyesuaikan gaya hidup.
Tapi setiap peradaban besar pernah melalui masa krisis untuk mencapai kebijaksanaan.
Kini, di era digital dan kecerdasan buatan, ujian terbesar umat manusia bukan lagi menaklukkan bumi, tetapi memeliharanya.
-000-
Dekarbonisasi adalah refleksi terdalam manusia modern: apakah kita masih sanggup mencintai bumi dengan cara yang tidak merusaknya?
Di balik setiap konferensi, kebijakan, dan investasi, ada ratapan laut yang naik ke daratan, ada doa petani yang gagal panen, dan ada harapan anak-anak yang ingin langitnya kembali biru.
Ketika dunia menggenggam janji-janji dekarbonisasi, kita diundang untuk ikut bertanya: mampukah kita menepatinya?
Mampukah kita membangun dunia yang bukan hanya bebas karbon, tapi juga adil dan manusiawi? Karena sejatinya, dekarbonisasi bukan hanya proyek energi. Ia adalah proyek kemanusiaan.
Dan ketika senja menurun di gurun Abu Dhabi, dengan cahaya oranye yang menyapu menara-menara konferensi, satu pesan menggema di udara.
Masa depan energi tidak boleh lagi hanya tentang kilowatt dan dolar, tetapi tentang kasih sayang antar generasi.
Bayangkan jika ada proyek seperti ini, proyek green hydrogen senilai $2,1 miliar. Ia mengubah air laut menjadi energi bersih.
Inisiatif ini tidak hanya memotong 4,5 juta ton emisi/tahun, tetapi juga melatih 1.200 petani lokal sebagai teknisi energi terbarukan.
Ini bukti nyata bahwa dekarbonisasi harus inklusif dan memberdayakan manusia akar rumput.
Dan dari titik itu, sejarah mungkin akan mencatat: manusia akhirnya belajar untuk tidak hanya hidup di bumi, tetapi hidup bersama dan memelihara bumi.*
Abu Dhabi, 3 November 2025
REFERENSI
1. Daniel Yergin, The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World (Penguin Press, 2011).
2. Vaclav Smil, Energy and Civilization: A History (MIT Press, 2017).
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/1D8C8GrJQM/?mibextid=wwXIfr

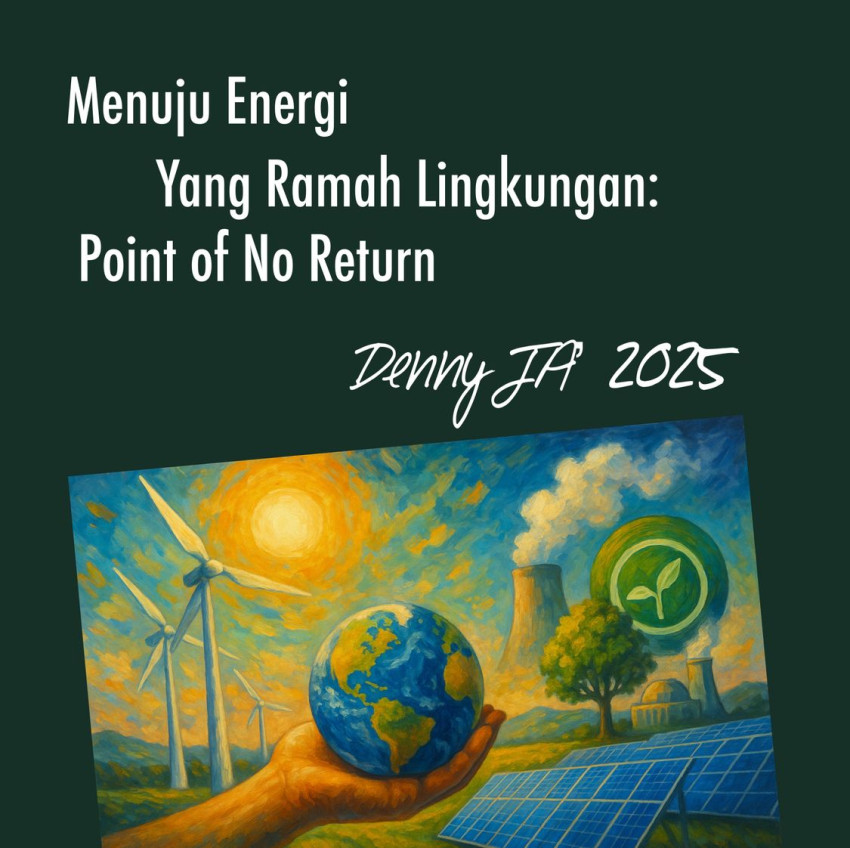
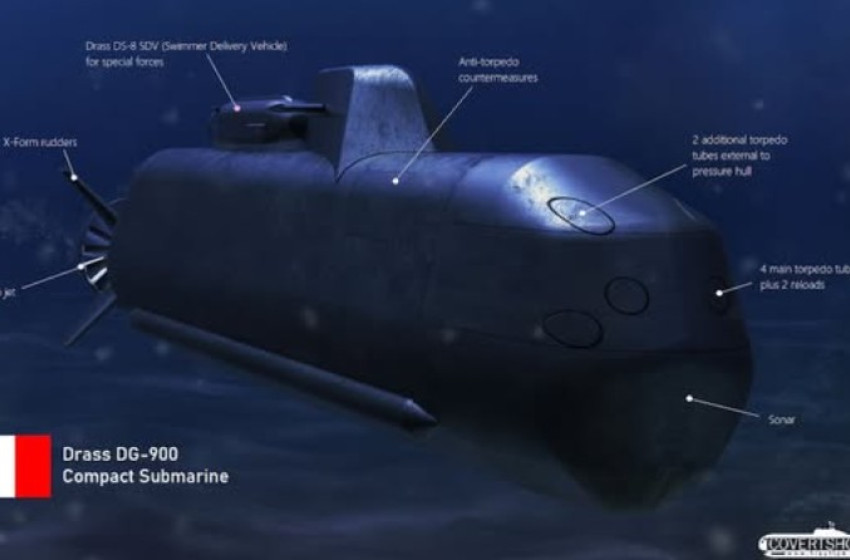



.jpeg)





