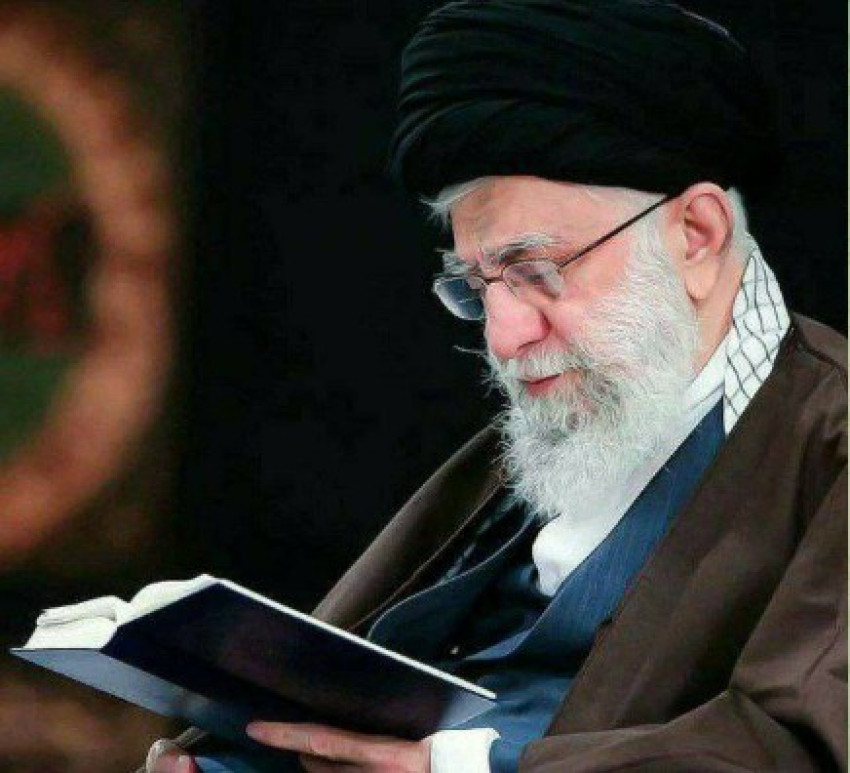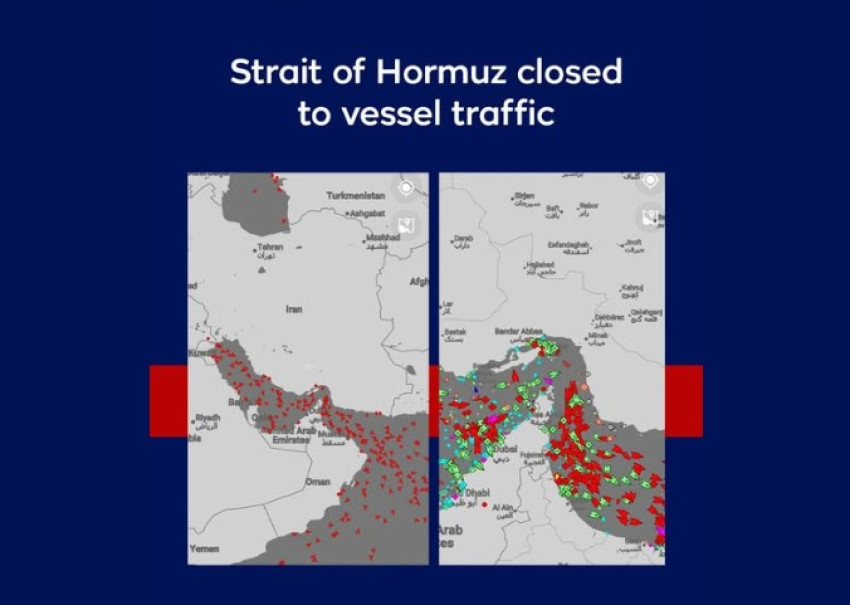Nyoto Santoso: Krisis Iklim Makin Parah, Bumi Makin Menua
Oleh Dr. Ir. Nyoto Santoso, Pengamat Lingkungan IPB University, Bogor
ORBITINDONESIA.COM - Bumi seperti manusia: menua, rapuh, dan kian sering demam. Bedanya, demam bumi bukan sekadar suhu tubuh naik, melainkan suhu planet yang terus meningkat akibat kerakusan manusia membakar fosil, menebang hutan, dan menjarah alam tanpa jeda. Kini, krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan — ia sudah di depan mata.
Bencana iklim datang silih berganti. Banjir besar, kekeringan panjang, badai dahsyat, hingga gelombang panas ekstrem menjadi wajah baru dari “musim” yang kehilangan arah. Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dua pertiga dari semua bencana alam di dunia kini berkaitan langsung dengan perubahan cuaca: kekeringan, banjir, dan badai. Dan dari semua jenis bencana itu, justru bencana cuaca-lah yang paling dipengaruhi aktivitas manusia.
Lihatlah Samudra Pasifik dan Atlantik — dua wilayah yang kini menjadi arena tarung badai tropis. Di Pasifik barat, setiap tahun rata-rata lebih dari 25 topan terbentuk, sementara di Atlantik, badai-badai besar seperti Katrina, Harvey, dan Ian menjadi simbol betapa dahsyatnya amarah alam. Di antara badai itu, kekuatan angin bisa mencapai 119 kilometer per jam atau lebih, melumat kota dan desa dalam hitungan jam.
Hurricane Andrew, yang menghantam Florida pada tahun 1992, masih diingat sebagai badai paling mahal dalam sejarah Amerika Serikat: menelan kerugian hingga 25 miliar dolar AS dan menewaskan 26 orang. Tapi angka itu tampak kecil dibandingkan dengan badai di Bangladesh tahun 1970 yang merenggut nyawa sekitar 300 ribu jiwa.
Para ilmuwan kini sepakat: semakin hangat suhu laut akibat pemanasan global, semakin kuat pula badai yang lahir darinya. Suhu laut yang meningkat menciptakan lebih banyak uap air di atmosfer — bahan bakar utama bagi badai tropis. Maka tak heran bila badai-badai kini tak hanya lebih sering, tapi juga lebih ganas.
Di puncak dunia, di mana salju abadi dulu tak pernah hilang, es kini mencair dengan cepat. Himalaya — atap dunia dan sumber air bagi miliaran manusia di Asia — perlahan kehilangan kemegahannya. Gletser-gletser yang dulu mengilap kini surut, menipis, dan pecah menjadi sungai es yang berlari ke lembah. Akibatnya, jutaan penduduk di India, Nepal, dan Tiongkok menghadapi ancaman krisis air dalam beberapa dekade ke depan.
Di ujung lain planet ini, Kutub Utara pun menjerit. Lapisan es laut di Arktik mencair dua kali lebih cepat dari perkiraan ilmuwan. Satelit NASA menunjukkan bahwa dalam empat dekade terakhir, luas es musim panas di Kutub Utara telah menyusut lebih dari 40 persen. Es yang mencair ini bukan sekadar drama alam, tapi alarm keras bagi peradaban manusia. Karena setiap ton es yang hilang berarti naiknya permukaan laut — mengancam tenggelamnya kota-kota pesisir dari Jakarta hingga Miami.
Ironisnya, manusia sendiri mempercepat bencana yang menimpa dirinya. Bendungan, tanggul, dan kanal dibangun tanpa perhitungan ekologi; rawa dan hutan bakau dikeringkan untuk industri; hutan tropis ditebang demi sawit dan tambang. Padahal, alam punya cara sendiri untuk menahan air, menyimpan karbon, dan menyejukkan udara. Ketika semua itu hilang, air hujan yang dulu terserap kini meluap, menenggelamkan kota.
Sementara di belahan bumi lain, kekeringan menjerat. Gelombang panas ekstrem melanda Eropa dan Amerika setiap musim panas. Sungai-sungai besar seperti Rhine dan Mississippi pernah surut hingga kapal tak bisa berlayar. Di Asia Selatan, ladang-ladang kering kerontang, sawah gagal panen, dan hutan terbakar.
Semua ini saling terhubung: es yang mencair menaikkan laut, laut yang hangat memperkuat badai, badai menghancurkan daratan, dan daratan gundul memperparah banjir. Siklus kehancuran itu kini menjadi wajah baru bumi yang menua.
Bumi tidak marah — ia hanya merespons. Ia menunjukkan gejala sakit dari luka yang manusia ciptakan. Dan gejala itu semakin parah: badai datang lebih sering, hujan tak menentu, musim panas makin panjang, es kutub mencair, permukaan laut naik, dan udara makin pengap.
Para ilmuwan sudah memperingatkan sejak awal abad ini bahwa jika pembakaran bahan bakar fosil tidak dikurangi secara drastis, suhu bumi akan naik di atas ambang aman 1,5°C. Kini kita sudah di ambang itu. Setiap kenaikan sekian derajat berarti bencana baru yang tak terhindarkan.
Bumi menua bukan karena waktu, tapi karena keserakahan manusia. Ia bukan hanya kehilangan keseimbangan ekologis, tapi juga kehilangan rasa hormat dari penghuninya. Bila manusia terus mengabaikan tanda-tanda alam, maka suatu hari nanti, badai terakhir mungkin akan datang — bukan sekadar badai cuaca, tapi badai peradaban.
Krisis iklim bukan lagi isu lingkungan semata. Ia adalah persoalan moral, ekonomi, dan kemanusiaan. Bumi tidak butuh diselamatkan — ia akan bertahan dalam bentuknya sendiri. Yang perlu diselamatkan adalah manusia yang hidup di atasnya. Karena jika bumi benar-benar menua dan runtuh, maka sejarah manusia pun ikut tamat.***