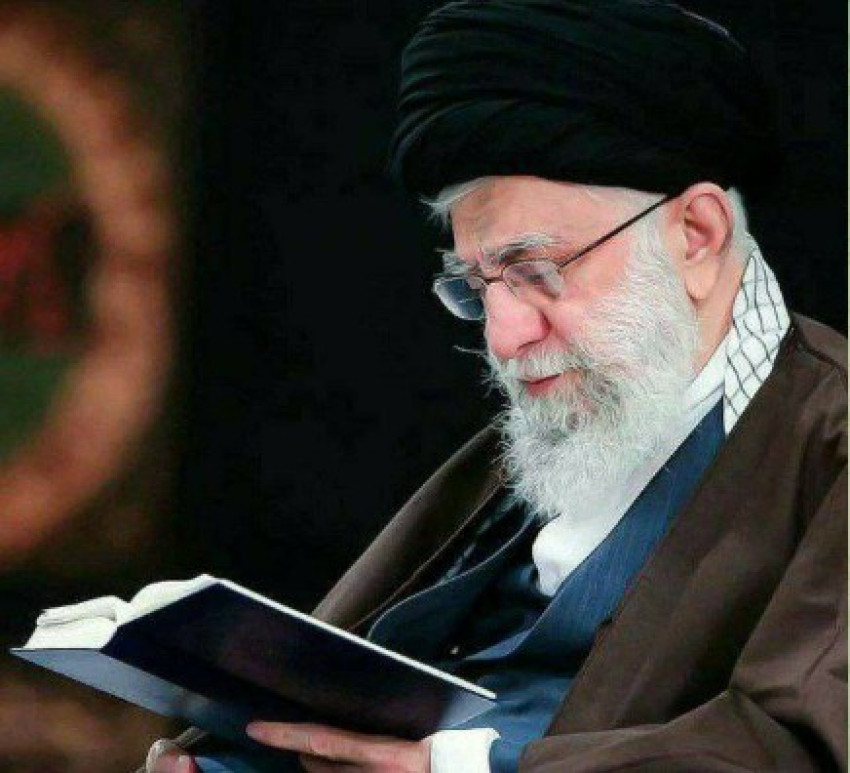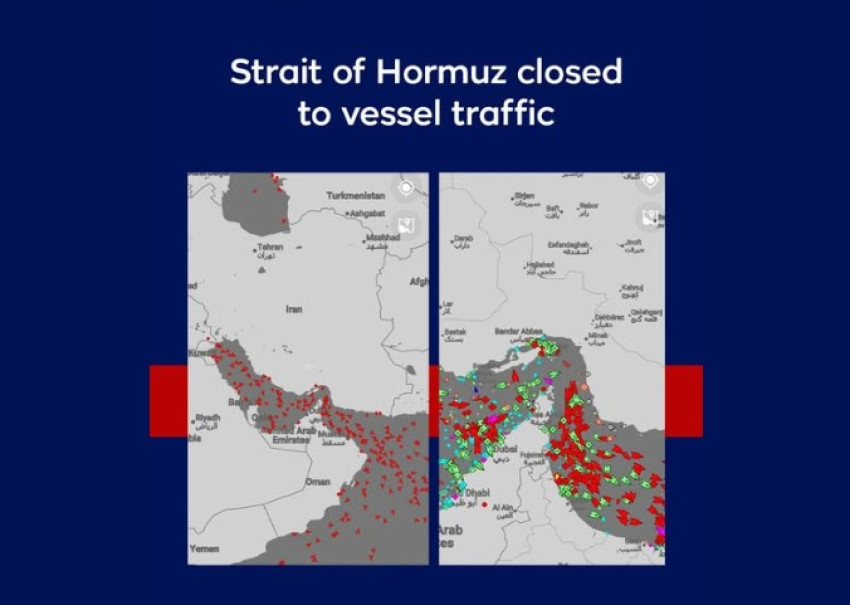Cerpen Iyek Aghnia: Suara Fals dari Tape Recorder Kuno
ORBITINDONESIA.COM - “Saya ingatkan kepadamu. Jangan sekali-kali kamu sampaikan kepada siapa pun—termasuk keluargamu—bahwa akulah yang menerima uang mega proyek itu. Kamu tahu risikonya jika ini tersebar. Kamu bukan hanya kehilangan jabatan. Bukan hanya itu.”
“Siap, Pak. Tapi wartawan itu sudah tahu aliran uangnya menuju Bapak.”
“Kamu selesaikan. Itu tugasmu. Siapa nama wartawan itu?”
“Markudut.”
“Markudut?”
Rekaman percakapan dari tape recorder kuno itu masih terngiang di telinga Markudut. Rekaman puluhan tahun silam, saat ia masih menjalani hari-hari sebagai wartawan lapangan.
Sebagai jurnalis muda pada zamannya, tape recorder kecil itu adalah senjata utama. Setia menemaninya memburu fakta, merekam suara, dan mengunci kebenaran agar tak mudah dipelintir.
Rekaman itu ia peroleh dari seorang pegawai pemerintah yang dituduh korupsi oleh pimpinannya dalam sebuah mega proyek. Padahal, pegawai itu tak pernah menerima sepeser pun. Tak ada satu pun fakta yang mengarah pada keterlibatannya dalam pusaran korupsi tersebut.
Ironisnya, justru ia dilaporkan ke aparat hukum oleh sang Pimpinan Negeri—dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Pimpinan yang dikenal sok alim itu merasa reputasinya ternoda.
Dengan narasi garang yang dimuat berbagai media, Pimpinan Negeri bersumpah siap digantung di pohon nanas jika terbukti menerima aliran komisi. Maklum, daerah itu memang terkenal sebagai penghasil nanas—meski gapura selamat datangnya berornamen buaya.
“Saya dilaporkan ke aparat hukum gara-gara rekaman itu,” adu pegawai tersebut kepada Markudut, saat mereka bertemu di areal persawahan.
“Dituduh mencemarkan nama baik. Padahal itu jelas-jelas suara dia,” keluhnya lirih, penuh kekecewaan.
Siang itu, matahari merayap perlahan ke kaki langit. Keduanya memandang hamparan sawah yang membentang luas.
Di kejauhan, sekumpulan burung terbang meliuk-liuk, lalu menyambar batang-batang padi. Mereka tak mencuri banyak—sekadar mengganjal perut. Setelah kenyang, burung-burung itu terbang tinggi ke angkasa dan baru kembali esok hari.
Tak seperti mereka yang berdasi. Yang mencuri aspal, semen, bantuan sosial, bahkan kubah masjid. Beras untuk orang miskin pun mereka jarah. Mereka mencuri bukan untuk hidup, tapi untuk tujuh turunan.
Dan anehnya, kaum berdasi itu tetap dihormati. Dipuja, diagungkan bak dewa—meski telah divonis koruptor oleh lembaga resmi.
“Itulah kehidupan,” desis Markudut. “Yang benar belum tentu mendapat keadilan.”
Ancaman tak hanya diterima pegawai itu. Markudut pun merasakannya. Namun ia memilih diam. Malu jika mengeluh. Baginya, itu risiko profesi.
“Sebutin saja nominal yang Anda mau. Pimpinan Negeri pasti meluluskannya,” bujuk seorang bawahan.
Markudut hanya tersenyum lebar.
“Apa susahnya menyebutkan angka?” desak si bawahan.
Markudut tertawa. Tawa panjang, membahana.
“Murah sekali nilai saya sebagai jurnalis,” katanya akhirnya. “Hanya dihargai uang segitu? Seumur hidup kepercayaan orang pada saya hilang begitu saja. Saya jadi tikus got. Jadi sampah masyarakat. Jadi bahan cerita sampai mayat saya di kuburan.”
Kata-kata itu menampar wajah si bawahan.
“Mohon, jangan tularkan ilmu tak terhormat itu pada saya,” lanjut Markudut tenang.
“Saya mohon, dengan segala hormat.”
Wajah si bawahan memerah. Ia pergi tanpa pamit, seperti disiram air mendidih.
Sebagai jurnalis muda kala itu, Markudut teringat pesan Pemimpin Redaksinya—seorang wartawan tua yang hidup sederhana, menjaga integritas dengan keras kepala.
“Kamu harus paham,” katanya suatu hari, “pekerjaan ini mulia. Kita penjaga nurani publik. Jangan tergoda harta yang hanya sesaat.”
“Integritas dan kepercayaan tak bisa dibeli uang. Itu yang harus kamu jaga.”
Kata-kata itu menancap di dada Markudut.
Di timur, purnama muncul dengan senyum pucat. Bintang berkelip membentuk galaksi. Harmoni semesta terasa kontras dengan dekadensi moral manusia—yang menuhankan harta, tahta, dan syahwat.
Azan magrib menggema dari surau kecil di kampungnya.
Markudut bergegas. Tanpa sadar, tape recorder kuno itu masih menyala.
“Kamu harus mengatakan saya tidak menerima uang itu.
Kalau kamu bilang sebaliknya, risikonya besar.
Bukan hanya jabatanmu.
Aku akan laporkan kamu ke aparat hukum.
Aku ini pemimpin besar. Dekat rakyat.
Aku tahu keinginan publik—bahkan sebelum mereka menginginkannya.
Kamu paham?”
Suara itu terus bergema. Tanpa malu.
Ketika malu telah mati, dan justru dipamerkan sebagai kebanggaan.
Padahal malu adalah sebagian dari iman.
Toboali, 8 Februari 2026
Iyek Aghnia adalah nama pena Rusmin Sopian, penulis dan pegiat literasi yang tinggal di Toboali, Bangka Selatan. ***