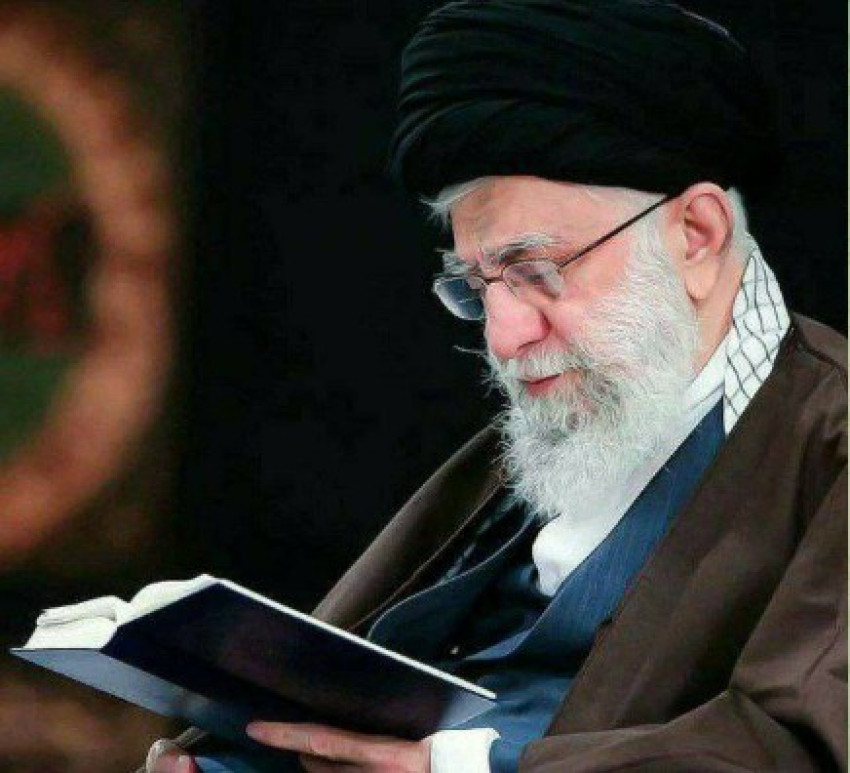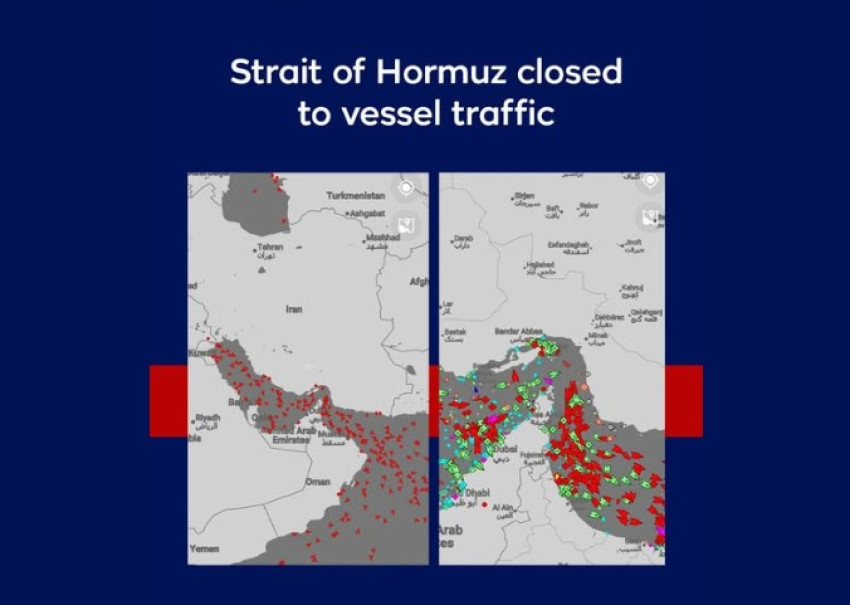Denny JA: Kesaksian Atas Luka Sosial dan Sejarah Melalui Puisi
- Renungan Festival Puisi Esai ASEAN Ke-5 di Sabah, Malaysia, Februari 2026
Oleh Denny JA
ORBITINDONESIA.COM - Ketika saya menerima penghargaan BRICS Award 2025 for Literary Innovation, inilah yang saya sampaikan dalam sambutan.
Saya terjemahkan kembali orasi itu ke dalam bahasa Indonesia agar getar maknanya tetap utuh, dan saya kutipkan isinya agak panjang.
BRICS bukan sekadar aliansi ekonomi. Ia adalah pertemuan peradaban.
Berbagai negara kita memikul kebudayaan yang tua, luka yang dalam, dan harapan yang tangguh.
Terlalu lama narasi global, terutama dalam sastra, dibentuk oleh satu belahan dunia saja. Padahal kemanusiaan tidak bernapas dengan satu paru paru.
Penghargaan Sastra BRICS adalah tindakan penyeimbangan.
Ia menegaskan bahwa Global South bukan catatan kaki dalam sastra dunia, melainkan sumber imajinasi moral, pengalaman hidup, dan pembaruan kreatif.
Dengan semangat itu, saya menerima penghargaan ini dengan kerendahan hati. Bukan hanya untuk diri saya, tetapi untuk para penulis yang berani bereksperimen.
Mereka yang berani melampaui bentuk mapan, menulis dari kenyataan hidup, dan percaya bahwa tantangan sosial baru menuntut bahasa sastra yang baru pula.
-000-
Apa Itu Puisi Esai
Genre yang saya sebut puisi esai lahir dari satu pertanyaan sederhana.
Bagaimana kita menceritakan kebenaran sosial yang tidak sanggup dipikul oleh statistik, namun juga tidak sepenuhnya tertampung oleh puisi liris semata.
Puisi esai memadukan penyelidikan dengan imajinasi. Kasus nyata, penderitaan nyata, dan luka sosial yang nyata diangkat ke dalam martabat sastra.
Di sini fakta diberi napas. Emosi menjadi wawasan moral. Penderitaan tidak dipertontonkan, melainkan dibagikan.
Puisi esai berakar di Indonesia, ya. Namun ia beresonansi di mana pun martabat manusia diuji.
Penghargaan ini memberi isyarat penting bahwa suara yang lahir dari Global South mampu berbicara bermakna kepada dunia.
Dalam tradisi dunia, puisi esai berkelindan dengan arus documentary poetry dan poetry of witness yang digagas Carolyn Forché. Bedanya, versi Indonesia ini menggabungkan riset sosial dengan spiritualitas komunitas, menjembatani etika dan estetika.
Meski hibriditas ini (puisi dan esai) kerap memicu debat, puisi esai justru memperkokoh kesaksian sosial. la memastikan fakta tidak membeku menjadi dogma, melainkan mencair menjadi empati yang terus mengalir di pembuluh darah sejarah kita.
-000-
Mengapa Penghargaan Ini Penting
Sastra dunia hari ini memang masih sangat dibentuk oleh tradisi Barat. Itu adalah fakta sejarah, bukan permusuhan.
Namun sastra menjadi lebih kaya ketika lebih banyak kenyataan diizinkan berdiri sejajar.
Penghargaan Sastra BRICS memperluas lingkar imajinasi. Ia memungkinkan berbagai filsafat tentang hidup, penderitaan, dan harapan berjumpa tanpa hirarki.
Di titik itulah sastra benar benar menjadi global.
Saya teringat masa awal menulis puisi di beranda rumah sederhana di Indonesia.
Dengan lampu temaram dan radio yang bersuara jauh, saya belajar bahwa hidup yang tampak biasa menyimpan kisah luar biasa yang menunggu untuk disuarakan.
Kita menulis agar penderitaan tidak dihapus oleh waktu.
Kita berinovasi agar bahasa tetap mampu menyembuhkan.
Kita bercerita agar tak seorang pun menderita sendirian.
Untuk para penulis muda Global South, kisah kalian tidak terlalu lokal. Ia justru diperlukan.
-000-
Itulah orasi yang saya nyatakan ketika menerima penghargaan sastra BRICS 2025.
Filosofi inilah yang terus berdenyut di Festival Puisi Esai ASEAN Ke-5 di Sabah, Malaysia, Februari 2026. Festival ini bukan sekadar perayaan sastra, melainkan peristiwa kesaksian.
Bertempat di IPG Kampus Kent, Tuaran, lokasi bersejarah bagi tumbuhnya puisi esai di Sabah, festival ini mempertemukan penyair, akademisi, dan pembaca dari berbagai negara ASEAN. Tema besar yang diangkat adalah Puisi Esai dan Kecerdasan Buatan.
Dalam forum diskusi, satu kesepahaman muncul.
Puisi esai adalah genre yang telah hadir, hidup, dan tidak bisa ditolak keberadaannya.
Ia menyuarakan isu kemanusiaan dan berfungsi sebagai diplomasi sastra lintas bangsa.
Kecerdasan buatan dibicarakan sebagai alat bantu, bukan pengganti nurani. Ia membantu riset, visualisasi, dan alih wahana.
Namun suara manusia tetap menjadi pusat.
Atas jasa Datuk Jasni Matlani dan para penggerak di Sabah, festival ini berkibar sebagai bukti bahwa sastra dapat tumbuh dari komunitas, dirawat dengan ketekunan, dan diperluas tanpa kehilangan ruh.
-000-
Salah satu momen yang menyentuh di festival itu adalah pemutaran video AI karya Ririe Aiko, yang mengalihwahanakan puisi esai saya berjudul Bukit Itu Menangis Menimbun Satu Keluarga. Ini puisi renungan Bencana Sumatra tahun lalu, dengan kritik ekologi.
Puisi ini mengisahkan sebuah bukit tua yang dahulu ramah, menjaga desa dengan hutan dan akar yang kuat. Ia hidup berdampingan dengan warga yang menebang dengan hormat dan menanam kembali dengan cinta.
Namun segalanya berubah ketika industri datang membawa mesin besar dan logika laba.
Hutan digunduli tanpa permisi. Akar dicabut tanpa ingatan. Bukit kehilangan penyangga dan perlahan menjadi rapuh. Ketika hujan besar datang, bukit itu runtuh dan menimbun sebuah mobil kecil berisi satu keluarga yang sedang beristirahat. Enam nyawa hilang dalam sunyi.
Puisi ini menolak menyebutnya musibah. Ia menyebutnya cermin.
Bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi kontrak kontrak bisnis yang dahulu ditandatangani tergesa.
Bukan hanya tanah yang longsor, tetapi tanggung jawab yang runtuh.
Dalam visualisasi AI, suara bumi menjadi nyata. Wajah keserakahan tampil tanpa nama. Penonton terdiam, karena yang ditampilkan bukan sekadar tragedi, melainkan keterlibatan kita semua.
-000-
Mengapa Penting bagi Sastra Mendokumentasikan dan Menarasikan Luka Sosial dan Sejarah
Pertama, sastra memberi wajah pada angka.
Statistik mampu menghitung korban, tetapi gagal merasakan kehilangan. Ia berhenti pada jumlah, grafik, dan tabel yang rapi.
Sastra melampaui itu. Ia menghadirkan nama, suara, kenangan, dan keheningan yang tertinggal setelah bencana.
Lewat sastra, kita melihat seorang ibu yang kehilangan anak, seorang ayah yang pulang ke rumah kosong, sebuah desa yang tak lagi sama.
Dengan begitu, korban tidak larut menjadi data. Mereka tetap manusia yang pernah hidup, mencinta, dan berharap.
Kedua, sastra melawan lupa yang dilembagakan.
Sejarah resmi sering ditulis oleh pemenang, oleh kekuasaan, oleh mereka yang selamat dan memiliki suara. Banyak luka sosial yang sengaja dipadatkan, disederhanakan, bahkan dihapus demi stabilitas dan kenyamanan.
Sastra hadir sebagai ruang tanding bagi ingatan yang ditertibkan. Ia memberi tempat bagi suara yang terpinggirkan, bagi kisah yang tidak tercatat dalam arsip negara. Sastra menjaga agar luka tidak disapu ke bawah karpet sejarah sebelum benar benar disembuhkan.
Ketiga, sastra membangun empati lintas waktu dan generasi. Puisi, novel, dan kesaksian sastra memungkinkan penderitaan masa lalu dirasakan kembali oleh mereka yang tidak mengalaminya.
Pembaca muda dapat merasakan ketakutan, kehilangan, dan harapan generasi sebelumnya, bukan sebagai pelajaran kering, melainkan sebagai pengalaman batin.
Di situlah kesadaran moral diwariskan. Bukan lewat ceramah atau slogan, melainkan lewat getaran sunyi yang mengubah cara kita memandang sesama.
Tanpa sastra, sejarah menjadi dingin dan mekanis. Tanpa kesaksian sastra, luka sosial mudah diulang karena tak pernah benar benar dirasakan.
Sastra adalah ingatan hidup yang menolak kekejaman menjadi kebiasaan, dan menolak ketidakadilan menjadi normal.
-000-
Dua buku penting ini bisa dikutip untuk memperkaya pandangan tentang sastra sebagai kesaksian.
Pertama, The Unwomanly Face of War, karya Svetlana Alexievich, 1985.
Buku ini menyusun kesaksian perempuan Soviet yang mengalami Perang Dunia Kedua. Alexievich tidak menulis sejarah perang dari sudut strategi atau kemenangan, melainkan dari dapur, ruang rawat, dan trauma yang sunyi.
Ia menunjukkan bahwa perang bukan hanya peristiwa militer, melainkan kehancuran batin yang panjang. Buku ini mengembalikan kemanusiaan ke dalam sejarah besar yang sering maskulin dan heroik.
Kedua, If This Is a Man, karya Primo Levi, 1947.
Ditulis oleh korban sekaligus penyintas Auschwitz, buku ini adalah kesaksian jujur tentang kehidupan di kamp konsentrasi. Levi menulis dengan bahasa tenang dan presisi moral.
Justru ketenangan itulah yang membuat kekejaman terasa telanjang. Buku ini menjadi tonggak sastra kesaksian karena menunjukkan bahwa mengingat adalah kewajiban etis. Tanpa ingatan, kejahatan berisiko diulang.
-000-
Festival Puisi Esai ASEAN Ke-5 di Sabah mengingatkan kita pada satu hal mendasar. Bahwa sastra bukan pelarian dari dunia, melainkan cara paling jujur untuk menghadapinya.
Di tengah banjir informasi, statistik, dan kecerdasan buatan, manusia tetap membutuhkan cerita untuk memahami dirinya sendiri.
Puisi esai hadir sebagai kesaksian atas luka sosial agar penderitaan tidak dibungkam, agar keadilan tetap dicari, dan agar harapan tidak kehilangan bahasa.
Selama masih ada luka yang belum sembuh, sastra belum selesai bekerja. Dan selama masih ada manusia yang berani bersaksi, puisi akan terus menemukan jalannya.^^^
Jakarta, 8 Februari 2026
Referensi
Alexievich, Svetlana. The Unwomanly Face of War. Progress Publishers, 1985.
Levi, Primo. If This Is a Man. Einaudi, 1947.
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/17uyPFVukJ/?mibextid=wwXIfr