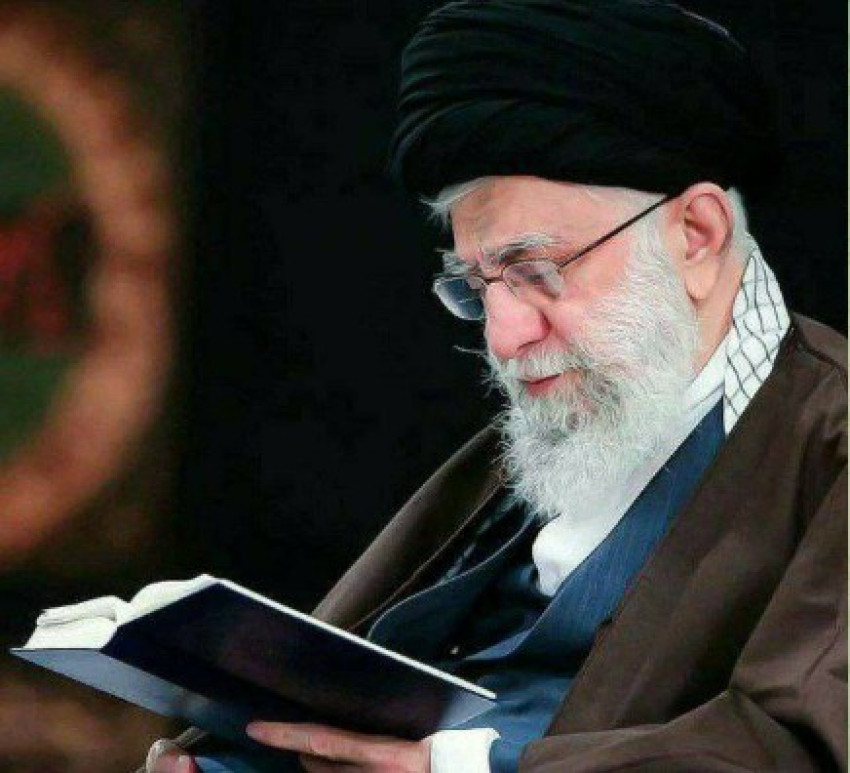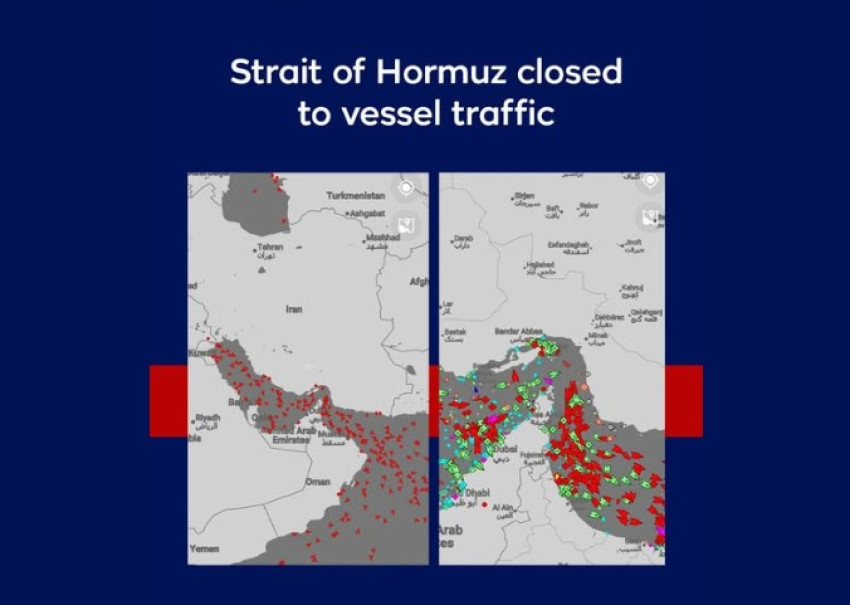Puisi Esai Denny JA: Tinggalkan Ibu, Selamatkan Saja Adikmu
Sebuah Puisi Esai
Oleh Denny JA
ORBITINDONESIA.COM - (Kisah ini diinspirasi oleh Arman dan Keluarganya, yang dua hari hidup di hutan, karena banjir dan longsor melanda Sumatra, lebih dari 1000 nyawa melayang). (1)
-000-
Hujan malam itu
bukan turun.
Ia runtuh.
Langit dilepas dari paku-pakunya,
menimpa bukit, rumah,
dan nama-nama
yang belum selesai saling berpamitan.
Aku berbicara keras pada ibu,
bukan karena aku kuat,
melainkan karena aku panik:
“Mak, di sini bukan tempat aman.”
Kalimat itu pecah
sebelum sempat menjadi nasihat,
sebab tanah di kiri-kanan
sedang belajar bergerak,
dan bumi kehilangan ingatan
tentang cara menopang manusia.
Kami bertiga mengangkat tubuh ibu.
Beratnya bukan daging dan tulang,
melainkan sejarah:
rahim yang dulu melindungiku dari gelap,
kini gemetar
diangkat anaknya
di lorong hutan
yang menyempit
seperti doa terakhir.
Rumah sudah tak bernama.
Ia bukan lagi bangunan,
melainkan kenangan
yang dikunyah lumpur.
Tinggal gereja, mesjid.
Itu pun hanya lehernya tampak,
kepala iman terbenam,
seolah doa pun
kehabisan tanah
untuk berdiri.
Namaku Ahmad.
Aku selamat
karena terlalu sering takut.
Takut meninggalkan rumah.
Takut meninggalkan ibu.
Takut pada malam
yang membuat Tuhan terasa
lebih dekat ke tanah
daripada ke manusia.
Kami terjebak di tengah hutan.
Kiri longsor.
Kanan longsor.
Depan dan belakang sama saja:
semua arah
adalah jatuh.
Kami panik.
Memanggil siapa saja yang punya kuasa:
Tuhan,
juga bupati,
memanggil negara,
memanggil siapa pun
yang masih punya peta
dan rasa tanggung jawab.
“Pak, kami di tengah ini,”
kataku.
Padahal yang kumaksud:
kami di tengah
akibat yang panjang,
akibat dari pohon-pohon
yang ditebang
jauh sebelum hujan datang.
Di sela gemuruh air,
aku teringat hutan-hutan
yang sejak dulu dibabat.
Bukit-bukit yang dulu
berakar kuat
seperti doa nenek moyang,
kini gundul,
licin,
tak lagi punya jari
untuk mencengkeram tanah.
Ketika pohon-pohon tumbang,
tanah kehilangan tulang.
Ketika akar dicabut,
bumi kehilangan urat nadi.
Dan hujan,
yang seharusnya berkah,
berubah menjadi palu,
memukul lereng
hingga tubuh kampung
retak serentak.
Tengah malam,
ibu berbisik:
Ahmad, aku lapar.
Kata itu
lebih dingin
daripada angin gunung.
Adik juga berkata sama.
Dan aku,
anak lelaki yang diajari tabah,
tak punya apa-apa
selain air mata
yang jatuh
tanpa suara.
Gelap begitu rapat
hingga wajah ibu
satu meter dariku
lenyap
seperti masa depan.
Kami hanya berpegangan tangan,
takut tercerai,
takut mati
sendirian.
Api kecil kami nyalakan,
bukan untuk terang,
melainkan untuk percaya
bahwa tubuh ini
belum sepenuhnya kalah.
Ibu berkata,
kita jangan pisah lagi.
Jika dipanggil Tuhan,
biarlah
bersama.
Kalimat itu
lebih berat
daripada bukit
yang runtuh berulang kali
oleh luka lama
yang tak pernah diobati.
Aku turun sendiri.
Bukan karena berani,
tapi karena harus.
Kutemukan rambutan,
buah-buahan
yang rasanya
seperti penghiburan darurat
dari alam
yang tersisa
setengah hidup.
Dengan tali,
kami meluncurkan harapan
sedikit demi sedikit
ke bukit
yang terperangkap.
Lima jam kami berjalan
di atas kayu patah
yang dijadikan jembatan.
Setiap langkah
adalah tawar-menawar
antara hidup
dan kesalahan kolektif.
Ketika akhirnya keluar,
tak ada rumah menunggu.
Tak ada tanah menyambut.
Hanya sisa-sisa
yang dulu disebut
kehidupan.
Ratusan rumah hilang,
bukan pindah,
melainkan digeser
oleh serakah
yang lebih tua
daripada hujan itu sendiri.
Tanah kami kini kerikil.
Kebun kami
menjadi mata sungai baru.
Kuburan
kehilangan alamat.
Dan negara datang terlambat
dengan karung bantuan
untuk luka
yang dibuka
bertahun-tahun.
Kini aku mengerti:
bencana bukan hanya
air dan longsor.
Ia adalah akumulasi
dari gergaji,
izin,
dan pembiaran
yang terlalu lama
dianggap biasa.
Dan di tengah semua itu,
manusia dipaksa memilih
dengan kalimat
paling kejam
yang pernah lahir
dari kepanikan:
“tinggalkan ibu,
selamatkan saja adikmu.”
Perintah yang tak pernah benar, tak pernah salah,
hanya meninggalkan bekas
yang tak bisa disembuhkan
oleh waktu,
bantuan,
atau janji
tentang pembangunan
yang lupa
pada akar. *
Jakarta, 16 Desember 2025
(1) Kisah ini adalah fiksi dan dramatisasi dari pengalaman Arman dan Keluarga
https://youtu.be/dbzPVnwI52M?si=cV502dQ9ZM0IWX6b
-000-
Berbagai puisi esai dan ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/17pBhyNmtw/?mibextid=wwXIf