Resensi Buku Cold War in the Islamic World: Ketika Dunia Islam Menjadi Medan Dingin Perebutan Panas Karya Dilip Hiro
ORBITINDONESIA.COM- Buku Cold War in the Islamic World: Saudi Arabia, Iran and the Struggle for Supremacy (2018) karya Dilip Hiro, jurnalis dan sejarawan kelahiran India yang dikenal luas karena analisis politik Timur Tengahnya, merupakan salah satu karya paling tajam tentang rivalitas ideologis dan geopolitik antara dua kekuatan besar dunia Islam modern — Arab Saudi dan Iran.
Diterbitkan oleh Hurst Publishers pada tahun 2018, buku ini menawarkan pembacaan historis yang komprehensif mengenai bagaimana persaingan sektarian antara Sunni dan Syiah berkembang menjadi perang dingin intra-Islam yang membentuk wajah politik dunia Muslim hingga hari ini.
Dilip Hiro menulis bukan sebagai pengamat dari luar, tetapi sebagai penyaksi panjang sejarah Timur Tengah modern. Ia telah menulis lebih dari tiga puluh buku, dan dalam karya ini, ia memadukan gaya naratif jurnalistik dengan kedalaman analisis akademik.
Seperti halnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, konflik Saudi–Iran bukanlah pertarungan langsung, melainkan rangkaian perang proxy, adu pengaruh, dan pertempuran wacana ideologi yang membelah dunia Islam dari Asia Barat hingga Afrika Utara.
Isi dan Struktur Buku: Dari Revolusi Iran ke Arab Spring
Buku ini tersusun secara kronologis, membentang dari Revolusi Iran 1979 hingga krisis-krisis mutakhir seperti perang Suriah dan perang Yaman. Dilip Hiro memulai dengan momen penting: kemenangan Revolusi Islam di Iran yang menggulingkan Shah dan melahirkan Republik Islam di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Kemenangan ini, tulis Hiro, mengguncang fondasi teologis dan politik dunia Arab yang selama ini dipimpin oleh monarki konservatif Saudi.
Arab Saudi, sebagai penjaga dua kota suci dan sekutu utama Barat, melihat revolusi itu sebagai ancaman eksistensial terhadap legitimasi kekuasaannya. Sejak saat itu, rivalitas ideologis antara “republik revolusioner” Iran dan “monarki wahabi” Saudi Arabia menjadi pusat gravitasi baru politik Islam internasional.
Dilip Hiro melacak bagaimana kedua negara ini mengekspor pengaruhnya: Iran melalui jaringan milisi dan kelompok Syiah di Lebanon, Irak, dan Suriah; sementara Saudi melalui dana petrodolar dan lembaga dakwah global yang menyebarkan ideologi salafi-wahabi. Bab-bab berikutnya membedah konflik-konflik kunci — perang Iran–Irak, invasi Kuwait, intervensi Amerika Serikat, hingga kebangkitan ISIS — sebagai efek domino dari rivalitas Riyadh–Teheran.
Ketika Arab Spring meletus pada 2011, harapan akan demokratisasi justru berubah menjadi babak baru perang dingin Islam. Di Suriah, Iran mendukung rezim Bashar al-Assad, sementara Saudi mendukung kelompok oposisi Sunni.
Di Yaman, konflik lokal berubah menjadi perang proksi besar antara Houthi (didukung Iran) dan koalisi Saudi. Semua ini menunjukkan, menurut Hiro, bahwa perang dingin Islam bukan sekadar soal teologi, tapi pertarungan perebutan pengaruh geopolitik dan legitimasi moral.
Analisis dan Gagasan Utama: Ideologi, Kekuasaan, dan Ironi Modernitas
Melalui riset mendalam dan sumber yang luas, Dilip Hiro menyoroti paradoks besar dunia Islam modern: dua negara yang mengaku berjuang demi Islam justru menjerumuskan umat Islam ke dalam konflik yang tak berkesudahan. Bagi Hiro, Saudi dan Iran adalah dua cermin yang saling menolak tapi memantulkan wajah yang sama — keduanya menggunakan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan politik.
Arab Saudi membangun hegemoni melalui jaringan dakwah dan kekayaan minyaknya, menegaskan diri sebagai penjaga “kemurnian Islam” versi Wahabi. Sementara Iran menampilkan diri sebagai kekuatan revolusioner yang menentang imperialisme Barat dan membela kaum tertindas.
Namun, di balik retorika suci, keduanya terlibat dalam politik realisme keras: mendukung milisi, memanipulasi ideologi, dan menjadikan konflik sektarian sebagai strategi mempertahankan pengaruh regional.
Hiro tidak menulis dengan nada polemis, melainkan analitis. Ia menunjukkan bagaimana agama, minyak, dan militer membentuk segitiga kekuasaan yang menentukan arah politik Timur Tengah.
Dilip Hiro juga menyoroti peran negara-negara kecil seperti Qatar dan UEA, serta keterlibatan kekuatan global seperti AS, Rusia, dan Tiongkok dalam memperkuat atau menyeimbangkan konflik ini.
Di bagian akhir, Hiro menegaskan bahwa perang dingin Islam ini tidak akan berakhir selama kedua negara mempertahankan legitimasi ideologis yang saling bertentangan, tanpa ada mekanisme dialog intra-Islam yang sejati. Seperti halnya Perang Dingin global, penyelesaiannya tidak datang dari kemenangan, tetapi dari keletihan moral dan kebangkrutan ideologis kedua pihak.
Relevansi bagi Dunia Islam dan Indonesia
Buku ini sangat relevan bagi pembaca di dunia Muslim, termasuk Indonesia, yang seringkali menjadi penonton — bahkan sasaran pengaruh — dari pertarungan ideologi dua kekuatan tersebut.
Hiro mengingatkan bahwa konflik Sunni–Syiah bukanlah takdir teologis, melainkan hasil konstruksi politik modern yang diperkuat oleh kepentingan negara.
Dalam konteks Indonesia, Cold War in the Islamic World membuka mata tentang bahaya polarisasi identitas keagamaan dan bagaimana kapitalisme religius dapat memecah belah umat.
Buku ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan Islam moderat yang mampu berdiri di antara dua ekstrem: puritanisme yang kaku dan revolusionisme yang ideologis.
Penutup: Sebuah Cermin dari Perang yang Tak Pernah Dingin
Cold War in the Islamic World bukan sekadar laporan geopolitik, tetapi otopsi intelektual atas tubuh dunia Islam modern.
Dilip Hiro menulis dengan keseimbangan antara empati dan ketegasan, menyajikan sejarah yang pahit namun jujur. Ia tidak berpihak pada Teheran atau Riyadh, melainkan pada rasionalitas, keadilan, dan masa depan dunia Islam yang lebih damai.
Buku ini layak dibaca oleh siapa pun yang ingin memahami akar konflik Timur Tengah, logika politik sektarian, dan bagaimana agama dijadikan alat dalam perang pengaruh global.
Ia menyingkap dengan jernih bahwa “perang dingin” ini sesungguhnya tak pernah benar-benar dingin — karena di balik setiap diplomasi, ada darah, ideologi, dan sejarah panjang luka yang belum sembuh.***

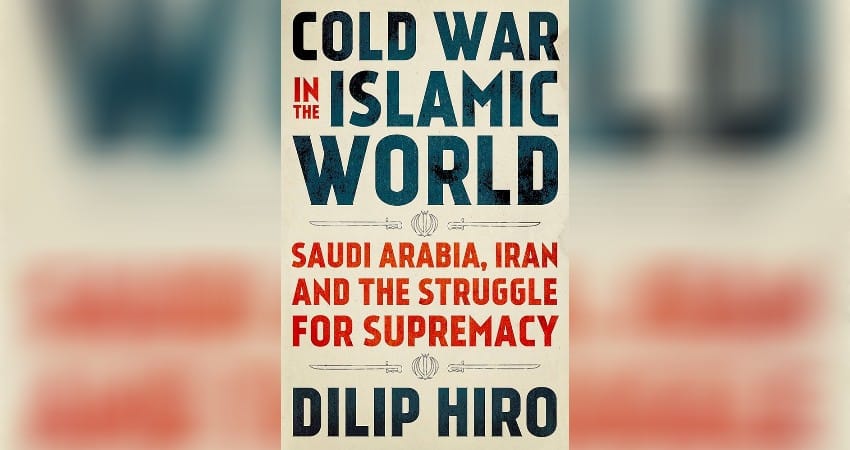





.jpeg)




