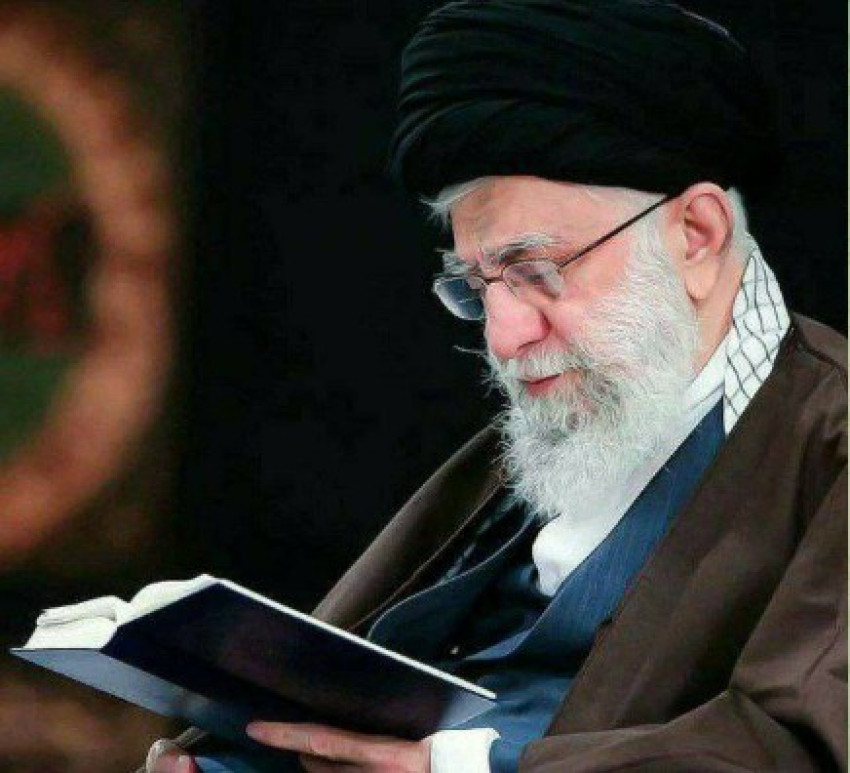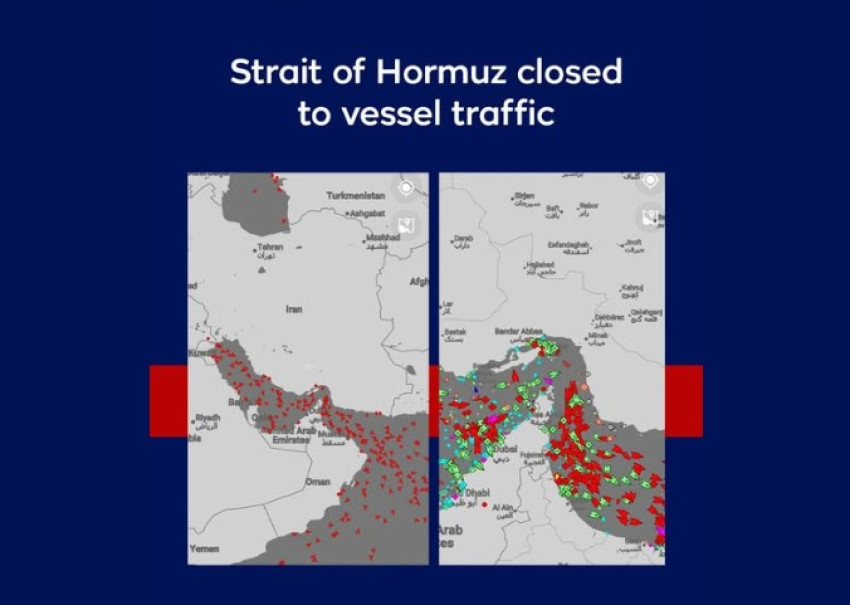Denny JA: Pak Harto, Pahlawan Nasional dan Kisah Kacamata Merah Muda
Oleh Denny JA
ORBITINDONESIA.COM - Pada akhir 1990-an, sekelompok peneliti psikologi di University of Washington melakukan eksperimen sederhana namun memikat.
Mereka membagikan kacamata berwarna lembut kepada para peserta yang baru saja kembali dari perjalanan lapangan.
Para peserta diminta menilai pengalaman mereka saat itu, lalu beberapa minggu kemudian diminta menilainya kembali.
Hasilnya mencengangkan: penilaian kedua selalu lebih tinggi, lebih indah, lebih hangat.
Kacamata, baik yang benar-benar dipakai maupun yang secara metaforis tertanam dalam ingatan, telah mengubah cara manusia menatap masa lalu.
Warna merah muda pada lensa itu bukan sekadar pigmen, tetapi simbol dari kecenderungan batin kita: melunakkan masa lalu agar terasa lebih bisa diterima.
Dari situlah lahir istilah rosy retrospection bias, atau dalam bahasa sehari-hari: melihat dunia dengan kacamata merah muda.
Ini sebuah bias yang membuat kita percaya bahwa dulu segalanya lebih baik, bahkan ketika dulu pun penuh cela.
-000-
Kisah ini yang saya ingat ketika ponsel bergetar: laporan akhir tim LSI Denny JA masuk ke meja saya.
Data itu menampilkan siapa presiden Indonesia yang paling disukai publik: dari Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi.
Kaget saya melihat hasilnya. “Benarkah?” saya bertanya dalam hati.
Saya meminta mereka memeriksa ulang: barangkali ada salah ketik, salah hitung, atau salah tabulasi.
Jawabnya: tidak ada yang salah. Prosedur baku dijalankan: multi-stage random sampling, 1.200 responden, wawancara tatap muka, margin of error ±2,9 persen, bulan Oktober 2025.
Ketelitian yang sama yang membuat LSI Denny JA mampu memprediksi pemenang lima pilpres berturut-turut.
Siapa presiden Indonesia yang paling disukai pemilih dari Aceh hingga Papua?
Angka-angka itu dingin, tetapi nadinya panas:
Soeharto — 29,0 persen.
Joko Widodo — 26,6 persen.
Soekarno — 15,1 persen.
Susilo Bambang Yudhoyono — 14,2 persen.
Gus Dur — 5,0 persen.
B.J. Habibie — 5,0 persen.
Megawati Soekarnoputri — 1,2 persen.
Tidak tahu/tidak jawab — 3,9 persen.
-000-
Saya teringat kembali kisah kacamata merah muda di atas.
Apakah kita sedang mengenakan kacamata yang sama ketika menilai masa lalu?
Apakah itu sebabnya Pak Harto, sosok yang diturunkan pdi 1998, tiga puluh tujuh tahun silam, kini justru paling disukai?
Psikologi kognitif menyebutnya rosy retrospection, bias kacamata merah muda.
Seiring waktu, detail pahit era Pak Harto memudar lebih cepat, yang manis menetap lebih lama.
Yang tegang di era Pak Harto diringankan, yang keras dilapisi kelembutan. Kita menatap ke belakang dan merasa hidup dulu lebih sederhana, lebih murah, lebih tertib.
-000-
Mungkin begitulah bangsa ini mengingat Pak Harto.
Represi, sensor, rasa takut—semuanya pelan menyingkir ke tepian bingkai.
Yang tinggal di tengah: jalan desa yang mulus, listrik yang akhirnya menyala, posyandu yang sibuk tiap pekan, beras yang harganya terasa terjaga.
Mungkinkah Pak Harto menjadi presiden yang kini paling disukai karena bias kacamata merah muda?
Dengan merujuk teori psikologi kognitif Daniel Kahneman, riset ini menjelaskan bahwa bias tersebut mekanisme alamiah otak yang menyaring memori negatif.
Kenangan kolektif bangsa terhadap era tertentu bisa berubah seiring waktu, terlepas dari fakta sejarah yang kompleks.
Namun kacamata merah muda bukan satu-satunya penjelasan.
Sebab jika semua presiden masa lalu kita lihat dengan lensa yang sama, mengapa Soeharto yang berada di puncak?
Mengapa bukan presiden lain yang sama-sama kita kenang dengan nostalgia?
-000-
Jawaban pertama: karena ingatan banyak orang bukan teori, melainkan tanah yang pernah diinjak, perubahan yang memang terjadi di era Pak Harto.
Sekolah yang berdiri, irigasi yang mengalir, pasar yang tertata. Itu semua benda nyata, bukan wacana, bukan omon-omon. Itu warisan konkret dari era Soeharto.
Jawaban kedua: citra paternal yang melekat. Soeharto tampil sebagai ayah rumah besar bernama Indonesia: Bapak Pembangunan.
Ia tegas, protektif, tidak banyak bicara.
Dalam zaman yang gaduh, citra seperti itu memberi rasa aman: seseorang yang “menjaga malam,” agar rakyat dapat tidur dengan tenang.
Di era Pak Harto, pembangunan ekonomi dimulai berderap kencang. Angka kemiskinan merosot tajam. Gedung, jalan, pabrik dibangun cepat.
Jawaban ketiga: keteraturan sebagai hiburan batin.
Ketika ekonomi modern bergerak cepat dan rawan gejolak, banyak keluarga merindukan “harga yang bisa ditebak, hidup yang tidak berayun terlalu liar.”
Ingatan tentang keteraturan menjadi selimut, menenangkan kegelisahan hari ini.
-000-
Lalu, layakkah gelar Pahlawan Nasional disematkan kepada Pak Harto?
Pertanyaan itu kembali membelah bangsa.
Di sinilah kita memasuki wilayah yang tak hitam-putih.
Jasa besar Pak Harto itu nyata: stabilisasi ekonomi pasca-hiperinflasi, pelembagaan pembangunan, jutaan orang terangkat dari kemiskinan.
Namun kesalahannya juga tercatat: pembatasan kebebasan, pelanggaran HAM, KKN yang mengakar di penghujung kuasa.
Bangsa yang dewasa tidak menutup satu mata untuk hanya melihat yang ingin dilihat.
Penghargaan pahlawan nasional, jika kelak diberikan — bukan penghapus dosa, melainkan pengakuan atas paradoks manusia.
Kita bisa berterima kasih atas jembatan yang menolong banyak orang menyeberang, sambil tetap mencatat retakannya di hilir sejarah.
-000-
Saya kembali teringat kisah kacamata merah muda itu. Apa jadinya jika melihat realitas tanpa pakai kacamata yang bias.
Dunia kembali kontras: terang dan gelap berdampingan, sebagaimana adanya.
Begitu pula cara kita membaca Soeharto hari ini. Ia bukan sebagai malaikat yang tak pernah salah. Tetapi pak Harto juga bukan bayang yang tak punya jasa.
Kita menimbangnya sebagai manusia besar yang meninggalkan jejak besar: sebagian jejak membuka jalan, sebagian lain mengingatkan kita untuk berhati-hati melangkah.
-000-
Jika esok ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, biarlah bangsa ini menulis catatan kaki yang jujur: bahwa gelar itu bukan pemutihannya dari kesalahan, melainkan pelajaran.
Bahwa kita memilih menghormati jasa tanpa menutup mata atas luka.
Bahwa kedewasaan bukan melupakan, melainkan mengingat secara utuh.
-000-
Sejarah bukan album potret berisi gambar terbaik.
Ia adalah film panjang: cahaya dan bayangan, tawa dan tangis, salah dan betul, berkejaran di layar yang sama.
Tugas kita bukan memilih adegan favorit, melainkan memahami seluruh alur, agar besok kita tak lagi mengulang babak yang mestinya sudah kita lewati.*
Jakarta, 7 November 2025
REFERENSI
1. R. E. Elson, Suharto: A Political Biography (Cambridge University Press), 2001
2. Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow (Farrar, Straus and Giroux),” 2011
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/1FkzYGpuHD/?mibextid=wwXIfr