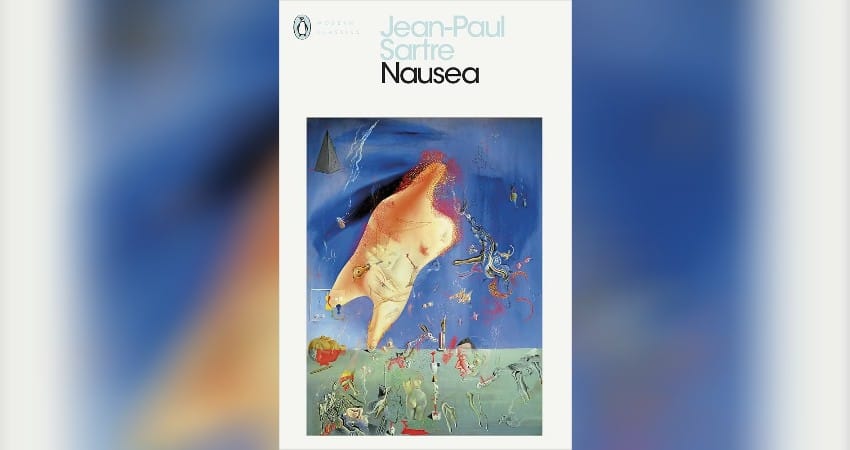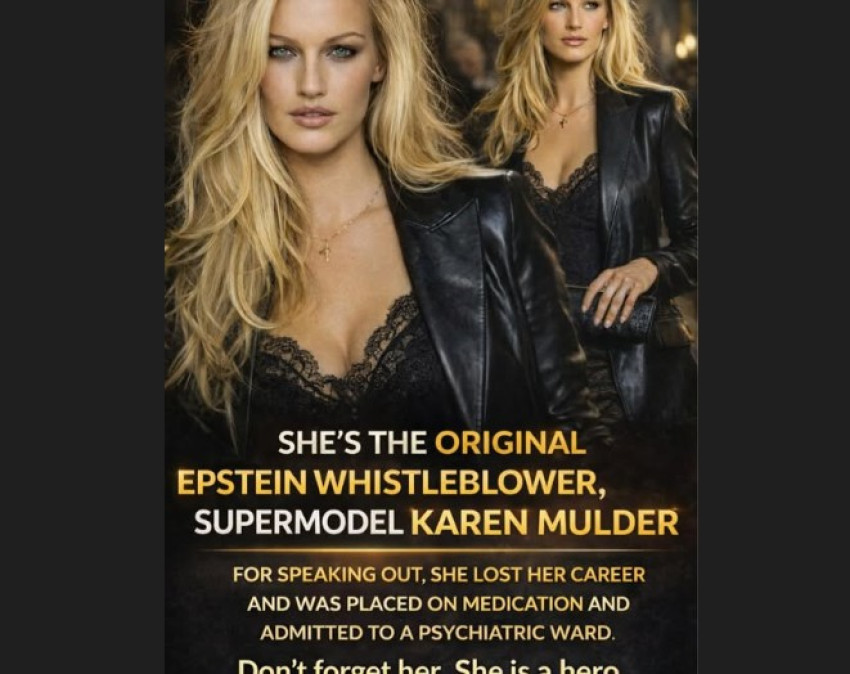Resensi Buku Nausea Karya Jean-Paul Sartre: Eksistensi yang Mual Telaah Eksistensialis Atas Nausea
Nausea adalah novel pertama filsuf Prancis Jean-Paul Sartre, diterbitkan pada tahun 1938 dengan judul asli La Nausée. Buku ini menjadi tonggak penting dalam sastra eksistensialis abad ke-20 dan membuka jalan bagi karya-karya Sartre berikutnya seperti Being and Nothingness (1943).
Dalam novel ini melalui tokoh utamanya, Antoine Roquentin, Sartre menyampaikan krisis makna, absurditas hidup, dan kesadaran eksistensial yang mengguncang.
Kisahnya mengambil tempat di kota fiktif Bouville, Prancis, di mana Roquentin—seorang sejarawan yang sedang meneliti biografi Marquis de Rollebon—mulai mengalami sensasi mual yang aneh terhadap dunia di sekelilingnya.
“Mual” di sini bukan sekadar reaksi fisik, melainkan gejala filosofis: rasa jijik eksistensial ketika manusia menyadari keberadaan dirinya dan benda-benda di dunia tanpa makna yang inheren.
Kisah tentang Kesadaran yang Menyakitkan
Melalui bentuk catatan harian Roquentin, Sartre membawa pembaca ke dalam aliran kesadaran yang jujur, kacau, dan sangat personal. Roquentin merasa dunia kehilangan logika dan tujuan; kursi, pohon, bahkan tangannya sendiri tampak asing dan menjijikkan.
Pengalaman ini menyingkap inti dari filsafat eksistensialisme Sartre: bahwa eksistensi mendahului esensi. Artinya, manusia ada terlebih dahulu, baru kemudian menciptakan makna hidupnya sendiri.
Rasa mual yang dialami Roquentin muncul dari kesadarannya akan fakta telanjang dari keberadaan—bahwa segala sesuatu “ada begitu saja”. Ia menyadari tidak ada alasan mengapa sesuatu harus ada, dan bahwa keberadaan itu sendiri adalah absurditas yang mengganggu.
Dalam momen-momen mual itu, realitas kehilangan lapisan-lapisan ilusi yang biasa menenangkan manusia: moralitas, agama, tujuan hidup, dan rasionalitas. Semua tersingkap sebagai konstruksi rapuh.
Manusia dan Kebebasan yang Menakutkan
Sartre memotret manusia modern yang kehilangan arah di dunia tanpa Tuhan. Setelah menyadari bahwa tidak ada makna objektif, Roquentin menyadari pula bahwa dirinya bebas secara mutlak—dan justru di situlah penderitaannya bermula.
Kebebasan, dalam pandangan Sartre, bukanlah anugerah yang nyaman, melainkan beban. Tidak ada Tuhan atau sistem nilai yang bisa dijadikan sandaran; manusia harus menciptakan maknanya sendiri dari kehampaan.
Sartre menulis Nausea dengan gaya naratif yang sangat filosofis, tetapi juga puitis dan gelap. Ia berhasil mengubah ide-ide rumit tentang kesadaran dan absurditas menjadi pengalaman estetis yang konkret.
Setiap adegan, dari Roquentin duduk di kafe sampai ia menatap akar pohon di taman, menjadi meditasi tentang keberadaan. Dalam absurditas itulah, muncul semacam keindahan tragis—bahwa manusia, meski sendirian di dunia yang kosong, masih bisa memilih untuk memberi makna pada hidupnya.
Refleksi dan Relevansi Modern
Lebih dari delapan dekade setelah diterbitkan, Nausea tetap terasa relevan. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan materialistis, banyak orang mengalami “mual” serupa—rasa hampa di balik rutinitas, kehilangan makna di tengah kemajuan.
Sartre mengingatkan bahwa krisis itu bukan penyakit, melainkan peluang untuk sadar. Mual adalah tanda bahwa seseorang mulai melihat kenyataan tanpa topeng.
Bagi Sartre, satu-satunya jalan keluar dari absurditas bukanlah pelarian, melainkan penciptaan.
Di akhir novel, Roquentin menemukan secercah harapan ketika mendengarkan musik jazz, menyadari bahwa seni bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap kehampaan. Dalam penciptaan seni, manusia menegaskan kebebasannya, memberi makna meski dunia tak memberikannya.
Kesimpulan
Nausea bukan sekadar novel filsafat, melainkan pengalaman eksistensial yang mengguncang pembacanya. Sartre menulis dengan ketajaman intelektual dan kejujuran brutal tentang absurditas hidup.
Melalui Roquentin, kita diajak menatap dunia yang tanpa alasan, namun justru di situ tersimpan kebebasan sejati—kebebasan untuk menciptakan arti bagi diri sendiri.
Novel ini adalah bacaan wajib bagi siapa pun yang mencari pemahaman tentang eksistensi, kehampaan, dan makna menjadi manusia. Nausea menggugat kenyamanan kita, namun pada akhirnya mengajarkan keberanian untuk hidup dengan sadar di tengah absurditas dunia.