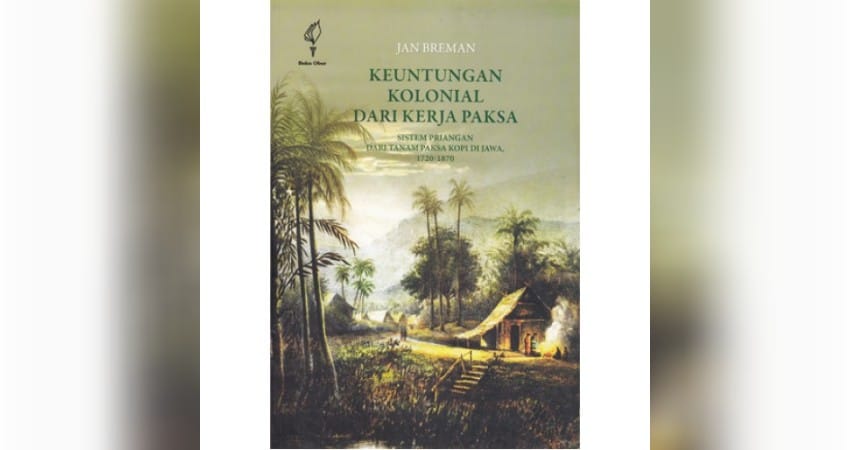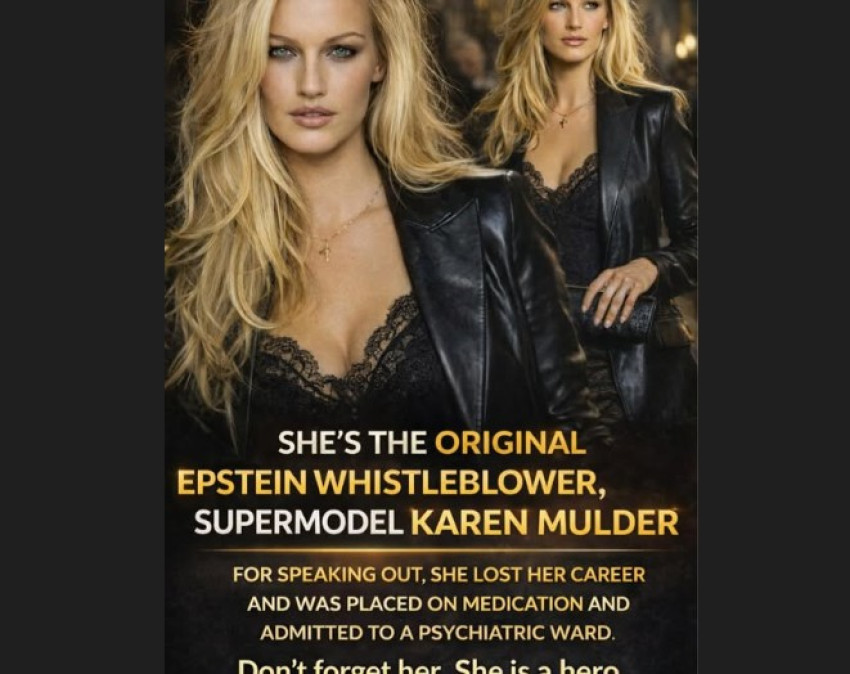Resensi Buku Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720–1870 - Jan Breman
ORBITINDONESIA.COM- Di balik aroma harum kopi yang menguap dari cangkir-cangkir pagi bangsa Eropa pada abad ke-18 hingga ke-19, tersembunyi kisah getir dan luka lama tentang peluh dan darah rakyat Jawa.
Buku Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720–1870 karya Jan Breman, seorang sosiolog dan sejarawan asal Belanda.
Buku ini membuka sangat detail tabir kelam itu dengan ketelitian akademik dan keberanian moral yang jarang ditemui dalam karya ilmiah sezamannya.
Buku ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Belanda, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerbit buku Pustaka Obor dan terbit pada tahun 2010.
Buku ini menjadi bacaan wajib bagi siapa pun yang ingin memahami anatomi eksploitasi kolonial di Hindia Belanda. Breman menulisnya bukan semata sebagai sejarawan, tetapi sebagai penyelidik hati nurani: bagaimana sebuah sistem kekuasaan bisa begitu rapi, efisien, dan legal — namun dibangun di atas penderitaan manusia yang tak bersuara.
Sistem Priangan yang dikupasnya bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi laboratorium sosial bagi kelahiran kapitalisme kolonial. Ia memperlihatkan bagaimana kekuasaan, hukum, dan tradisi berpadu menjadi mesin kerja paksa yang menguntungkan negeri jauh di utara, sementara rakyat Priangan menanggung beban di tanah sendiri.
Isi dan Struktur Buku: Ekonomi Politik dari Keringat dan Derita
Breman menelusuri akar sistem kerja paksa kopi yang dimulai sejak awal abad ke-18, jauh sebelum sistem tanam paksa (cultuurstelsel) resmi diberlakukan pada 1830.
Di wilayah Priangan — terutama di daerah pegunungan yang subur — pemerintah kolonial melalui memerintahkan penduduk untuk menanam kopi sebagai kewajiban pajak. Melalui bupati dan kepala desa, sistem ini bekerja seperti jaring laba-laba kekuasaan yang menjerat seluruh lapisan masyarakat.
Breman menggambarkan dengan detail bagaimana rakyat dipaksa menanam, memanen, dan menyerahkan kopi kepada pemerintah tanpa imbalan layak.
Di antara para petani yang bekerja tanpa suara, para pejabat lokal menikmati posisi istimewa sebagai penghubung antara pemerintah kolonial dan rakyat. Mereka memperoleh sebagian kecil keuntungan, namun pada dasarnya menjadi alat perpanjangan tangan penjajahan.
Struktur buku ini memadukan pendekatan sejarah ekonomi dan sosiologi politik. Breman menelusuri arsip-arsip lama, laporan pejabat Belanda, serta data produksi untuk menunjukkan bahwa Priangan adalah model awal dari sistem kapitalisme kolonial yang bertumpu pada tenaga kerja paksa dan birokrasi lokal.
Jan Breman menolak melihat kolonialisme hanya sebagai dominasi politik: baginya, kolonialisme adalah proses ekonomi sistematis yang menyerap tenaga dan waktu manusia demi akumulasi modal di negeri penjajah.
Makna Sosial dan Politik: Feodalisme yang Dipakai Ulang
Salah satu kekuatan analitis Breman adalah kemampuannya menyingkap lapisan sosial di balik kebijakan ekonomi. Ia memperlihatkan bahwa keberhasilan sistem tanam paksa kopi justru terletak pada kemampuannya menggunakan kembali struktur feodalisme Jawa untuk kepentingan kapitalisme modern.
Para bupati dan priyayi yang dulunya pemilik otoritas tradisional dijadikan “administrator kolonial” yang bertanggung jawab memastikan rakyat memenuhi kuota kopi. Dengan imbalan status dan perlindungan politik, mereka menjadi kaki tangan kekuasaan Eropa.
Di sinilah terjadi ironi sejarah: kapitalisme kolonial bertumbuh di atas fondasi budaya feodal — dua sistem yang tampak berlawanan, namun bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu eksploitasi.
Breman menyebutnya sebagai “paternalistik koersif”: sistem yang tampak seperti hubungan perlindungan antara penguasa dan rakyat, namun sesungguhnya menyembunyikan pemaksaan struktural.
Dalam tatanan seperti ini, kekerasan tak selalu hadir sebagai cambuk atau senjata, tetapi sebagai kepatuhan sosial yang dilembagakan — sebuah kekuasaan yang tak perlu berteriak, karena sudah tertanam di dalam pikiran.
Analisis dan Gaya Penulisan: Antara Arsip dan Nurani
Jan Breman menulis dengan ketelitian seorang ilmuwan, tetapi juga dengan empati seorang humanis. Ia tidak terjebak dalam angka dan statistik semata.
Setiap data yang ia tampilkan seolah berdarah: di balik tonase kopi dan laporan pajak, ada penderitaan nyata. Gaya penulisannya jernih, padat, dan berimbang antara analisis empiris dan refleksi moral.
Pendekatannya yang interdisipliner — menggabungkan Marxisme, sosiologi Weberian, dan antropologi kolonial — menjadikan buku ini lebih dari sekadar sejarah ekonomi.
Ia mengajak pembaca merenungi bagaimana kekuasaan bisa bekerja tanpa perlu kekerasan langsung, hanya dengan mengatur struktur sosial dan makna budaya.
Breman tidak menulis dengan amarah, tetapi dengan kesadaran bahwa memahami penderitaan masa lalu adalah langkah pertama untuk membongkar ketidakadilan masa kini.
Di sinilah kekuatan etis karyanya: ia tidak sekadar mencatat sejarah, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral dari bangsa yang pernah menjajah dan bangsa yang pernah dijajah.
Relevansi Kontemporer: Bayangan Panjang Kolonialisme
Membaca Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa di masa kini berarti membaca arsitektur ketimpangan sosial Indonesia modern. Jan Breman tidak hanya bicara tentang abad ke-18, tetapi tentang warisan mentalitas yang masih kita temui: birokrasi yang memihak kekuasaan, elite lokal yang menindas rakyatnya, dan struktur ekonomi yang terus menempatkan kerja manusia sebagai sumber keuntungan tanpa kesejahteraan.
Sistem Priangan mungkin telah berakhir lebih dari satu abad lalu, tetapi jiwanya masih berkeliaran — dalam bentuk upah murah, eksploitasi buruh perkebunan, atau ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan besar.
Breman seolah ingin berkata bahwa kolonialisme tidak benar-benar mati; ia hanya mengganti wajah, dari VOC menjadi korporasi global, dari bupati menjadi pejabat modern.
Buku ini pun menjadi pengingat bahwa keadilan sosial bukan sekadar cita-cita politik, melainkan pekerjaan sejarah yang belum selesai. Ia mengajarkan bahwa memahami masa lalu bukan untuk menyesali, tetapi untuk membongkar sistem yang masih melanjutkan penindasan dengan bahasa baru.
Penutup: Dari Priangan ke Dunia
Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa bukan sekadar karya sejarah; ia adalah cermin moral dan intelektual yang memantulkan wajah kolonialisme dari masa lalu hingga masa kini.
Melalui penelusuran tentang kopi dan kerja, Breman menunjukkan bahwa di balik kemajuan ekonomi kolonial tersimpan tragedi manusia yang tak boleh dilupakan.
Dengan gaya penulisan yang jernih dan argumentasi yang tajam, Jan Breman menghadirkan karya yang setara dengan The Wretched of the Earth karya Frantz Fanon, atau Orientalism karya Edward Said — sama-sama membuka mata tentang bagaimana kekuasaan membentuk, memeras, dan mendefinisikan dunia.
Membaca buku ini adalah sebuah ziarah intelektual: menelusuri ladang-ladang kopi yang pernah menjadi ladang penderitaan, dan menyadari bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu — melainkan gema yang terus bergema dalam setiap ketimpangan sosial hari ini.
Dari tanah Priangan yang hijau, Breman menulis tentang seluruh dunia: bahwa di mana pun kekuasaan bersekutu dengan keuntungan, di situlah kerja manusia masih menjadi korban.***