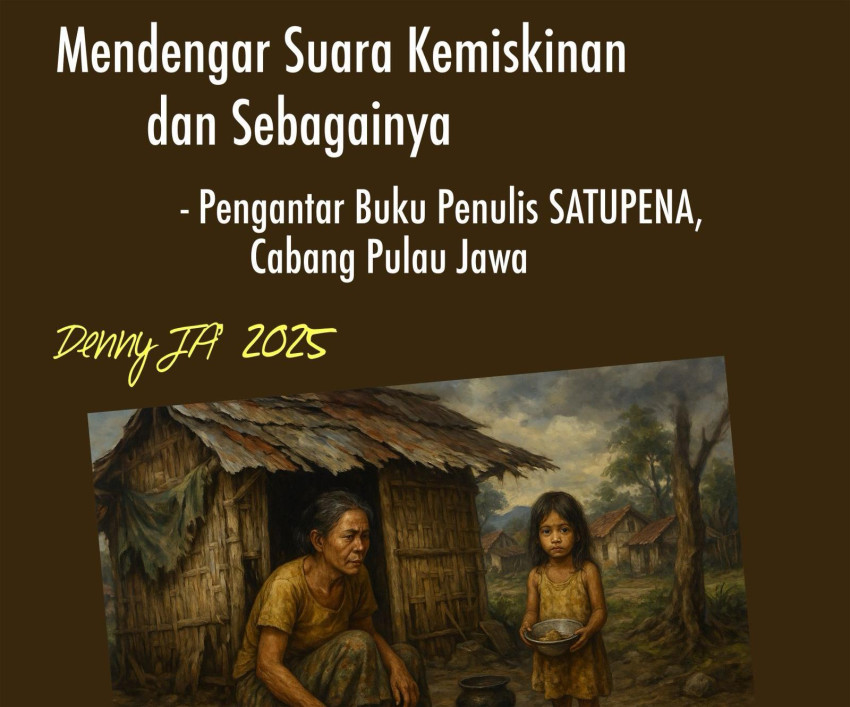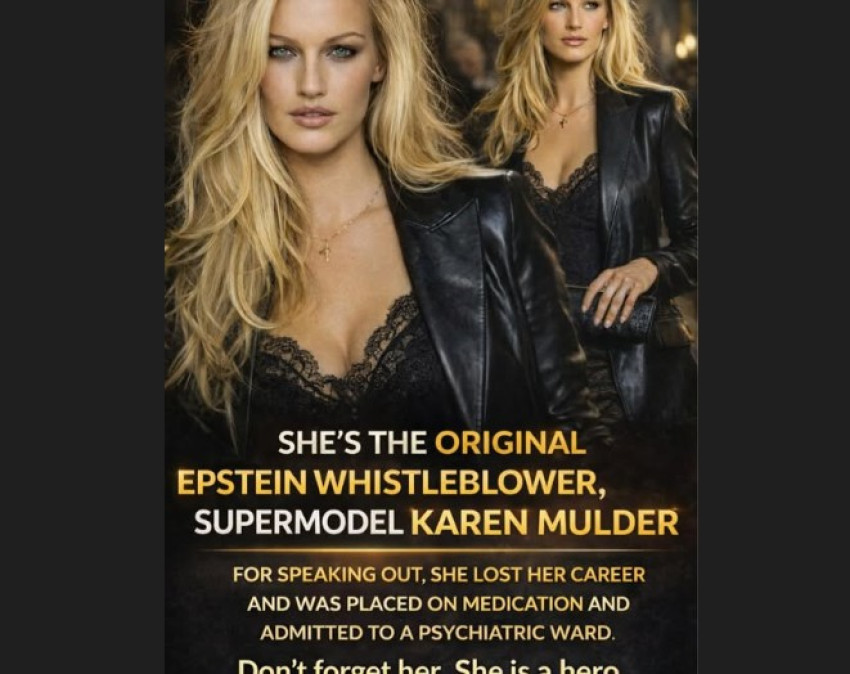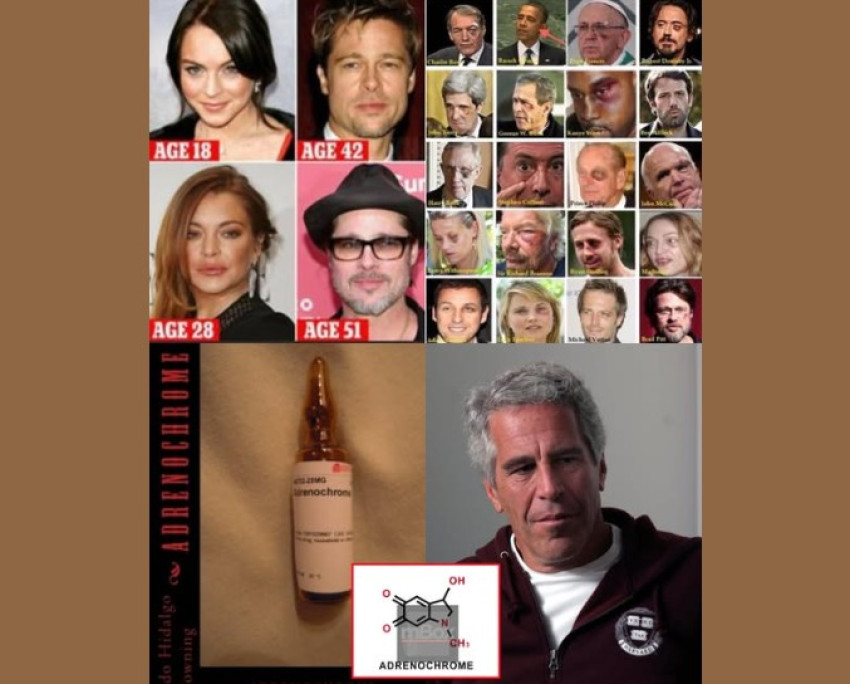Catatan Denny JA: Mendengar Suara Kemiskinan dan Sebagainya
- Pengantar Buku Penulis SATUPENA dari Pulau Jawa, “Api Merdeka, Merdeka Apa?” (2025)
Oleh Denny JA
Ia bangun setiap subuh, menyapu lantai kontrakan sempit yang mulai retak di sudut-sudutnya.
Uang di dompetnya tinggal seribu lima ratus rupiah, cukup untuk membeli sebungkus nasi kucing yang akan dibagi tiga—untuk dirinya, istri, dan anak kecil yang belum mengerti arti lapar.
Ia tak pernah mengeluh. Hanya kadang bertanya dalam hati, mengapa negara menyebutnya “tidak miskin.”
Ia bekerja dua belas jam sehari, mengantar paket dan harapan orang lain, sementara mimpinya sendiri tertinggal di lampu merah.
Ketika membaca berita bahwa angka kemiskinan menurun, ia menatap layar ponselnya lama-lama, seperti menatap dirinya yang tak pernah tercatat.
Di lembar statistik, ia hanyalah angka yang disesuaikan agar grafik tampak indah. Tapi di dunia nyata, ia adalah manusia yang menggigil di bawah jembatan, menunggu fajar yang tak kunjung memberi terang.
Sebab kemiskinannya telah dihapus—bukan dari hidup, tapi dari laporan negara.
Situasi inilah yang terbayang ketika saya membaca esai “Garis Kemiskinan yang Tak Manusiawi” karya Swary Utami Dewi (Tami).
Esai ini adalah kritik sosial yang tajam terhadap cara negara mendefinisikan dan mengukur kemiskinan.
Tami berangkat dari percakapan nyata dengan seorang pengemudi ojek daring di Jakarta. Ia bingung mengapa dirinya—dengan penghasilan sekitar Rp25.000 per hari—tidak dikategorikan sebagai “miskin” oleh pemerintah.
Dari percakapan sederhana itu, Tami menggali ironi mendalam: betapa angka statistik negara kerap tak menggambarkan kenyataan hidup rakyat kecil.
Tami menunjukkan bahwa batas kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS) terlalu rendah dan tidak manusiawi.
Tami menuliskan bahwa per Maret 2025, BPS mencatat angka kemiskinan 8,47% dari total populasi (sekitar 23,85 juta jiwa). Ini disebut sebagai yang terendah dalam dua dekade terakhir.
Ia menggarisbawahi bahwa secara statistik, seseorang dikategorikan miskin bila pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Rp609.160, atau sekitar Rp20.000 per hari.
Tami menilai bahwa “Garis Kemiskinan versi BPS sangat tidak masuk akal dan tak manusiawi.” Jumlah Rp20.000 per hari tidak cukup untuk makan tiga kali, apalagi memenuhi kebutuhan dasar lain seperti papan, pendidikan, dan kesehatan.
Ia juga menyoroti dampaknya: banyak warga yang sebenarnya miskin kehilangan hak sosialnya, seperti bantuan atau pembebasan iuran kesehatan, hanya karena secara statistik pendapatannya sedikit di atas garis kemiskinan.
Ia membandingkannya dengan standar Bank Dunia tahun 2024. Lembaga ini menetapkan batas kemiskinan global untuk negara berpendapatan menengah ke bawah sebesar US$8,30 per hari (sekitar Rp130.000).
Bagi Tami, perbedaan angka ini bukan sekadar hitungan ekonomi, tetapi menyangkut hak dasar manusia—tentang akses terhadap pangan yang layak, pendidikan, dan kesehatan.
Ketika pemerintah menggunakan garis kemiskinan yang terlalu rendah, jutaan warga miskin terhapus dari sistem bantuan sosial dan kehilangan hak perlindungan negara.
Gagasan utama Tami: kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan moral dan struktural. Ia mengajak pembaca melihat kembali cara negara “menghitung” manusia.
Tami menuntut agar kebijakan publik berangkat dari rasa kemanusiaan, bukan sekadar efisiensi fiskal.
Tulisan ini memadukan empati, data, dan kesadaran etis—memperlihatkan wajah kemiskinan yang hidup, bukan melalui tabel statistik, melainkan dari peluh pengemudi ojek yang berjuang menafkahi keluarga.
Tami menutup esainya dengan nada reflektif: jika kemerdekaan sejati adalah kebebasan dari penderitaan, maka bangsa yang masih menutup mata terhadap kelaparan warganya belum benar-benar merdeka.
Kemiskinan yang tak manusiawi bukan sekadar angka—ia adalah cermin nurani bangsa yang retak.
-000-
Membaca esai Swary Utami Dewi, saya teringat Charles Booth—pelopor yang pertama kali mengukur kemiskinan secara sistematis.
Gagasan tentang mengukur kemiskinan baru muncul pada akhir abad ke-19. Saat itu dunia industri menuntut definisi ilmiah tentang siapa yang “miskin,” agar negara bisa menyalurkan bantuan sosial secara efisien.
Charles Booth (Inggris, 1886–1903) adalah industrialis yang resah melihat kondisi buruh London. Ia melakukan survei rumah tangga pertama yang sistematis, memetakan kemiskinan berdasarkan pendapatan dan kebutuhan dasar.
Hasilnya adalah Life and Labour of the People in London (1903).
Ia menemukan bahwa sekitar 30% penduduk London hidup di bawah “garis kemiskinan”—istilah yang untuk pertama kalinya digunakan secara kuantitatif.
Lalu datang Seebohm Rowntree (Inggris, 1901), yang menyempurnakan metode Booth dengan membuat poverty line berdasarkan biaya minimum untuk pangan, pakaian, dan perumahan yang menjaga “efisiensi fisik.”
Dalam bukunya Poverty: A Study of Town Life (1901), ia memperkenalkan konsep absolute poverty—kemiskinan yang diukur dari kemampuan bertahan hidup secara fisik, bukan gaya hidup sosial.
Konteks sosialnya: Revolusi Industri mengubah tatanan feodal menjadi kapitalistik. Urbanisasi dan eksploitasi buruh menimbulkan ketimpangan ekstrem.
Lahirlah dorongan moral dan politik untuk mengukur penderitaan rakyat secara ilmiah—agar kebijakan upah dan bantuan sosial bisa dipertanggungjawabkan.
-000-
Setelah Perang Dunia II, pengukuran kemiskinan menjadi instrumen pembangunan internasional.
Pada dekade 1940–1960-an, negara Barat mulai memakai household surveys untuk menghitung pendapatan dan konsumsi minimum.
Amerika Serikat, misalnya, menetapkan official poverty line tahun 1963 oleh Mollie Orshansky, ekonom Biro Statistik Tenaga Kerja.
Ia menggunakan biaya pangan minimum dikalikan tiga, karena saat itu keluarga miskin menghabiskan sepertiga penghasilan untuk makan.
Pada 1970–1980-an, Bank Dunia mulai menyatukan standar internasional.
Tahun 1990, ekonom Bank Dunia seperti Martin Ravallion memperkenalkan garis kemiskinan global sebesar US$1 per hari (berdasarkan purchasing power parity atau PPP).
Inilah tonggak awal kemiskinan dihitung dengan angka dolar yang berlaku lintas negara.
-000-
Seiring kritik terhadap pendekatan ekonomi semata, muncul pandangan baru bahwa kemiskinan bukan hanya soal uang, tapi juga kebebasan dan kemampuan hidup bermartabat.
Tokoh yang terkenal membawa konsep baru ini adalah Amartya Sen. Ia memperkenalkan Capability Approach (1990).
Peraih Nobel Ekonomi asal India ini menggugat cara lama yang hanya menghitung uang.
Menurut Sen, kemiskinan adalah deprivation of capabilities—kekurangan kebebasan untuk memilih kehidupan yang bernilai: pendidikan, kesehatan, partisipasi sosial, keamanan, dan harga diri.
Pendekatan ini melahirkan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index / HDI) yang diluncurkan oleh UNDP pada 1990 bersama Mahbub ul Haq.
Dari Booth dan Rowntree di London kumuh hingga Amartya Sen di forum PBB, pengukuran kemiskinan berevolusi: dari hitungan nasi menjadi ukuran martabat.
Awalnya, garis kemiskinan berfungsi administratif—menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Kini, ia menjadi cermin keadilan sosial.
Membaca sejarah panjang pengukuran kemiskinan ini, kritik Swary Utami Dewi atas cara Indonesia mengukur kemiskinan menjadi sangat relevan—dan layak diapresiasi.
-000-
Esai Tami ini hanyalah satu dari banyak karya dalam antologi Api Merdeka, Merdeka Apa?
Buku megah ini menghimpun karya para penulis Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA Wilayah Jawa, diterbitkan Oktober 2025, setebal lebih dari 500 halaman.
Dalam satu jilid yang berdenyut seperti nadi Nusantara, terkumpul puluhan karya dalam berbagai bentuk—esai, puisi, puisi-esai, dan cerpen.
Para penulis berasal dari enam provinsi di Pulau Jawa: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Antologi ini adalah peta batin Pulau Jawa yang menyuarakan kegelisahan kolektif: tentang kemerdekaan yang belum selesai, tentang kesenjangan yang melebar, dan tentang manusia Indonesia yang terus mencari makna di antara debu modernitas.
Dalam pengantar berjudul “Menyalakan Kembali Agni Brata,” Dhenok Kristianti menulis dengan daya simbolik yang mendalam.
Ia mengutip ajaran Astabrata Kepemimpinan, khususnya Agni Brata—jalan kepemimpinan yang menuntut seseorang untuk menjadi seperti api: berani, menerangi, dan memurnikan.
Namun dalam kenyataan, Dhenok menatap getir. Terlalu banyak pemimpin yang justru menjadi api yang membakar, bukan menghangatkan.
Api kemerdekaan yang dulu menyala di dada para pejuang kini redup, tertutup asap kepentingan dan kerakusan. Dari sanalah lahir pertanyaan tajam yang menjadi jiwa buku ini:
“Inikah yang disebut negara merdeka? Masih adakah api kemerdekaan itu di dada para pemimpin dan rakyatnya?”
Bagi Dhenok, kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan untuk berkuasa, melainkan keberanian untuk membakar ego dan menyalakan nurani.
Ia menutup pengantarnya dengan ajakan yang menggugah: agar SATUPENA menjadi nyala kecil yang tak padam di tengah gelap zaman.
-000-
Buku ini berdenyut dari berbagai arah: dari suara petani hingga urban middle class, dari desa yang dilupakan hingga kota yang kehilangan empati.
Tema-tema besar yang mengalir di dalamnya meliputi:
• Ketimpangan antara kota dan desa — bagaimana modernitas mengikis akar kebersamaan.
• Krisis kepemimpinan moral dan nasionalisme — api idealisme yang kini tersisa abu.
• Perempuan dan rakyat kecil — suara yang selama ini terpinggirkan, kini menulis kembali sejarahnya sendiri.
• Kegelisahan spiritual Jawa — benturan antara nilai-nilai tradisi dan dunia digital yang dingin.
Antologi ini menjadi ruang penyembuhan kolektif—tempat kata-kata bekerja sebagai doa sekaligus protes.
-000-
Keragaman dalam buku ini dapat kita renungkan dari beberapa karya berikut.
1. Tulisan karya Nia Samsihono, “Raya, Anak Cacingan dari Sukabumi.”
Bentuknya adalah puisi esai, yaitu gabungan narasi puitik dan refleksi sosial dengan catatan kaki sumber berita nyata .
Puisi esai ini mengisahkan Raya, balita yang meninggal karena cacingan dan kemiskinan ekstrem di Sukabumi.
Nia menggugat kelalaian sosial: orang tua, tetangga, dan negara yang tak hadir.
Kematian Raya menjadi simbol luka bangsa—betapa pembangunan yang megah sering menutupi tragedi kemanusiaan di desa-desa terlupakan.
2. “Dari Pedalaman Kami Menuju Indonesia” – Bambang Hendarto
Seruan dari desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia menulis dengan nada getir dan tulus:
“Kami masih menunggu jalan yang tak hanya membawa mobil, tapi juga harapan.” Sebuah potret pedalaman yang menolak dilupakan.
3. “Pati, Topi Jerami, dan Wajah Negeri” – Dwi Sutarjantono
Cerpen tentang petani tua yang menatap sawahnya berubah jadi perumahan. Di balik topi jeraminya, ada nostalgia dan doa panjang agar tanah tak kehilangan makna.
4. “Indonesia dari Serambi Desa” – Asmariah
Puisi-esai reflektif yang menggambarkan desa sebagai serambi terakhir kemanusiaan—tempat nilai sederhana masih bertahan melawan arus industri dan individualisme.
-000-
Mengapa Buku Ini Penting
1. Menyalakan Literasi Moral dan Nurani.
Di tengah zaman ketika kata-kata sering kehilangan makna, antologi ini menegaskan kembali fungsi sastra sebagai penyulut kesadaran.
Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan tanpa etika hanyalah kebebasan yang liar.
2. Menyatukan Suara Jawa sebagai Cermin Bangsa.
Dari Banten hingga Surabaya, para penulis ini menulis dengan logat berbeda, tapi hati yang sama: cinta tanah air yang belum selesai.
Jawa di sini bukan sekadar ruang geografis, tetapi simbol pergulatan moral bangsa Indonesia.
3. Mengabadikan Luka dan Harapan Zaman.
Buku ini adalah arsip batin Indonesia kontemporer: dokumentasi rasa sakit, ketimpangan, dan keyakinan bahwa kata-kata masih bisa menyembuhkan.
Di dalamnya, api kemerdekaan mungkin kecil, tapi ia nyata—dan masih menyala.
Api Merdeka, Merdeka Apa? bukan hanya buku. Ia adalah nyala batin kolektif para penulis Jawa yang menolak menjadi abu.
Dalam setiap halaman, ada keberanian untuk berkata jujur, menulis meski getir, dan percaya bahwa literasi adalah bentuk tertinggi dari kemerdekaan manusia.
-000-
Pada akhirnya, Api Merdeka, Merdeka Apa? bukan sekadar antologi sastra, melainkan napas panjang nurani bangsa.
Dari Swary Utami Dewi yang menggugat “garis kemiskinan yang tak manusiawi,” hingga Dhenok Kristianti yang menyalakan kembali Agni Brata kepemimpinan, buku ini menjadi cermin bagi negeri yang tengah mencari makna kemerdekaannya sendiri.
Di sini, kata-kata bukan hanya alat ekspresi, melainkan bentuk perlawanan terhadap sistem yang kerap membungkam kemanusiaan di balik data, kebijakan, dan retorika pembangunan.
Membaca buku ini, kita seakan berjalan di antara dua dunia: dunia statistik yang dingin dan dunia manusia yang berdarah-daging.
Kita diajak mendengar suara ojek daring, petani, dan perempuan renta—suara yang selama ini tenggelam di balik laporan ekonomi dan janji politik.
Dari sinilah sastra kembali menemukan fungsinya: menyembuhkan yang luka, membangunkan yang diam, dan menyalakan yang padam.
Jika kemerdekaan sejati adalah kebebasan untuk hidup bermartabat, maka buku ini pengingat perjuangan itu belum selesai.
Api Merdeka menyala bukan di istana, tetapi di hati mereka yang berani menulis kebenaran.
Di tengah abu zaman, kata-kata masih bisa menjadi bara. Ia kecil, tapi cukup untuk menyalakan cahaya bangsa. *
Jakarta, 18 Oktober 2025
Referensi:
1. Charles Booth, Life and Labour of the People in London. London: Macmillan, 1903.
2. Amartya Sen, Development as Freedom. New York: Oxford University Press, 1999.
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/19cGChDWV6/?mibextid=wwXIfr ***