Antara Harapan dan Syarat: Kesiapan Otoritas Palestina Mengelola Perbatasan Rafah dan Rekonstruksi Gaza
ORBITINDONESIA.COM - Di tengah gencatan senjata yang masih rapuh dan debu reruntuhan yang belum sempat mereda, Otoritas Palestina (PA) menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih kembali pengelolaan perbatasan Rafah. Pernyataan itu datang sebagai angin segar di tengah ketidakpastian politik yang melingkupi Gaza pasca-KTT Perdamaian di Mesir, di mana dunia menaruh harapan baru pada upaya rekonstruksi dan stabilisasi wilayah yang telah hancur oleh perang.
Namun seperti banyak hal di Timur Tengah, di balik pernyataan optimistis itu, realitasnya jauh lebih rumit. Dalam kesepakatan awal yang difasilitasi oleh Mesir dan didukung Amerika Serikat serta Uni Eropa, PA memang disebut sebagai pihak yang “paling layak secara administratif” untuk mengelola kembali lintasan Rafah — gerbang vital bagi masuknya bantuan kemanusiaan dan keluarnya warga sipil yang membutuhkan perawatan di luar Gaza.
Tapi peran itu belum penuh. Israel dan sejumlah mitra internasional menuntut terlebih dahulu reformasi struktural di tubuh PA sebelum tanggung jawab operasional benar-benar diserahkan.
Pihak Israel, melalui pernyataan resminya, menekankan bahwa PA “harus membuktikan kapasitas birokratis dan keamanannya” untuk memastikan Rafah tidak kembali menjadi jalur penyelundupan senjata atau perlintasan kelompok bersenjata. Sementara di Ramallah, pemerintahan Mahmoud Abbas menyebut reformasi itu “bukan penundaan, melainkan proses penyesuaian demi membangun kredibilitas di mata dunia.”
Rafah sendiri memegang arti strategis yang tak tergantikan. Selama bertahun-tahun, pintu ini menjadi jalur kehidupan bagi lebih dari dua juta penduduk Gaza. Ketika konflik meledak, gerbang ini menutup; ketika gencatan dicapai, ia menjadi simbol awal dari pemulihan. Kesiapan PA untuk mengelolanya kembali dipandang sebagai langkah penting menuju keterlibatan lebih besar Palestina dalam urusan internal Gaza — sesuatu yang selama ini didominasi Hamas sejak 2007.
Namun di lapangan, banyak pihak meragukan apakah PA benar-benar siap secara teknis dan politis. Infrastruktur administrasi di Gaza nyaris lumpuh; sebagian besar staf pemerintahan PA tidak lagi aktif di wilayah itu selama lebih dari satu dekade. Untuk bisa beroperasi efektif, PA membutuhkan dukungan finansial, pelatihan keamanan, dan koordinasi yang intensif dengan Mesir — yang selama ini menjadi penjaga utama lintasan Rafah.
Diplomat Eropa yang terlibat dalam pembahasan mekanisme pengalihan wewenang menyebut bahwa “pemerintah Palestina harus membangun kembali bukan hanya kantor, tapi juga kepercayaan.” Bukan rahasia bahwa sebagian warga Gaza skeptis terhadap kembalinya PA, khawatir kehadiran mereka justru membawa lapisan baru birokrasi tanpa perubahan nyata di lapangan.
Meski begitu, peluang tetap terbuka. Di Kairo, perwakilan dari Mesir, Qatar, dan Norwegia telah mengajukan rencana tahap awal rekonstruksi Gaza, dengan PA sebagai mitra administratif. Program ini mencakup pengadaan energi darurat, perbaikan rumah sakit dan sekolah, serta pembangunan sistem logistik bantuan yang terpusat di Rafah. PA sendiri berjanji akan membentuk “Badan Koordinasi Rekonstruksi Nasional” yang bertugas menyalurkan dana dan mengawasi proyek-proyek pembangunan agar lebih transparan.
Bagi masyarakat internasional, keterlibatan PA dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju normalisasi politik Palestina. “Jika PA berhasil menunjukkan kepemimpinan yang stabil di Rafah, ini bisa jadi langkah pertama menuju reunifikasi Gaza dan Tepi Barat,” ujar seorang pejabat PBB di Jenewa. Namun waktu tak berpihak: setiap hari keterlambatan berarti lebih banyak warga Gaza yang kekurangan air bersih, makanan, dan perawatan medis.
Malam di Rafah kini diisi suara generator dan percakapan samar tentang masa depan. Di sisi Mesir, konvoi bantuan masih menunggu izin; di sisi Gaza, ribuan keluarga menanti kabar kapan gerbang akan dibuka kembali. Di antara dua dunia itu, Otoritas Palestina berusaha meyakinkan semua pihak — bahwa mereka mampu, bahwa mereka siap, meski harus menempuh jalan yang panjang untuk membuktikannya.
Jika perbatasan adalah cermin keadaan sebuah bangsa, maka Rafah hari ini memantulkan dua wajah Palestina: satu yang masih disandera oleh politik, dan satu lagi yang perlahan, tapi pasti, berusaha mengambil kembali kendali atas nasibnya sendiri.***





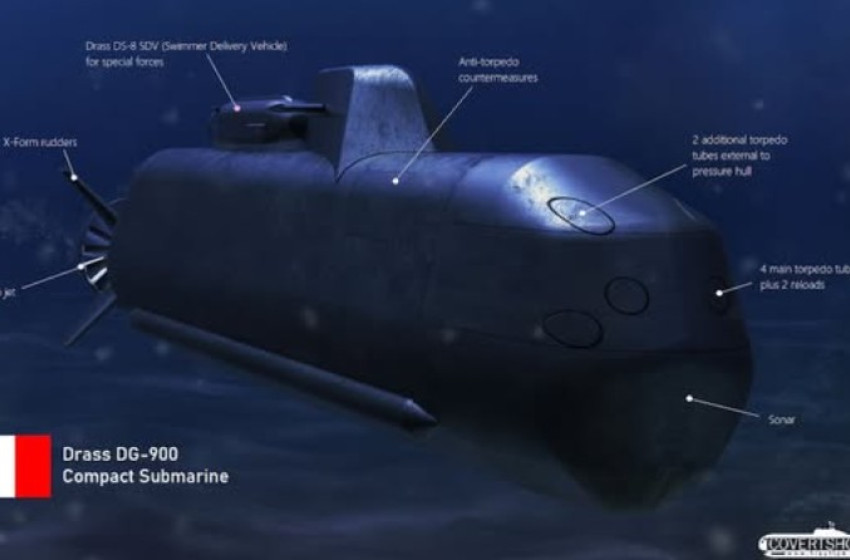



.jpeg)


