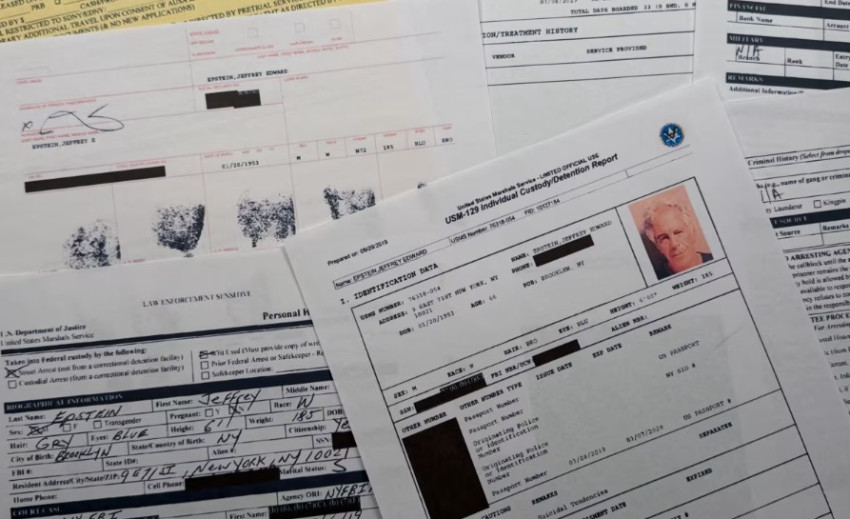Siapa yang Melukai Anak-anak Kita?
Pengantar dari Denny JA untuk Buku Puisi Esai Narudin Pituin, Menjahit Luka Anak Bangsa
ORBITINDONESIA.COM - Seorang bocah 14 tahun dari Medan dijanjikan pekerjaan di kota. Ia bermimpi bisa mengirim uang untuk orang tuanya, mungkin untuk membeli beras atau membayar utang.
Namun alih-alih pekerjaan yang bermartabat, ia justru dipaksa melayani lelaki hidung belang di Yogyakarta. Rambutnya digunduli, tubuhnya disundut rokok, dan masa kecilnya dirampas.
Kisah nyata ini kemudian lahir kembali dalam puisi esai Narudin Pituin berjudul Anak Itu Disundut Rokok.
Hanya beberapa bait awal saja sudah cukup untuk membuat pembaca tertegun. Betapa cepat sebuah mimpi berubah menjadi neraka. Betapa mudah anak-anak kita dijebak oleh orang dewasa yang kehilangan nurani.
Saya kutipkan beberapa kalimat puisi esai Narudin Pituin itu:
Bocah itu diterbangkan bukan oleh burak,
Tetapi oleh sayap air mata
Dari Medan menuju Jakarta.
“Di kota besar, penduduk besar, uang besar.”
(…)
Ah, telah empat bulan aku di Jakarta, tetapi mengapa
tubuhku difoto dan dibuat video tanpa busana?
Bukankah anak perempuan berumur 14 tahun
sepertiku belum tampak laksana model iklan
televisi?”
Ketiga setan itu tertawa. Ha ha ha….
(…)
Bocah itu diajak keliling dengan motor dan dipaksa
melayani para lelaki hidung belang di sana.
Lalu uang demi uang luruh laksana daun kering ke
atas tubuhnya yang ramping.
“Mengapa uang tak kalian beri kepadaku? Dan
mengapa kalian menjual diriku?”
Bocah itu diringkus, digunduli kepalanya, dan
disundut rokok seluruh kulit badannya.
-000-
Membaca puisi esai Narudin ini, pikiran saya melayang ke ujung sejarah.
Dari Mesir kuno, Kekaisaran Romawi, hingga kolonialisme, manusia dijadikan komoditas: diperjualbelikan, dipaksa bekerja, bahkan dijadikan hiburan.
Kita mengira peradaban modern telah menutup lembaran itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) menegaskan: “Tak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba.”
Namun kenyataannya, roh perbudakan itu belum mati. Hari ini ia berganti nama menjadi human trafficking.
Menurut ILO dan IOM (2022), sekitar 50 juta orang masih hidup dalam kondisi perbudakan modern.
Dari jumlah itu, lebih dari 27 juta orang korban kerja paksa, dan 1 dari 3 korban adalah anak-anak, sebagian besar perempuan di bawah 18 tahun.
Di Indonesia, antara 2017–2022, Kementerian PPPA mencatat lebih dari 1.700 kasus perdagangan orang. Angka sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi, karena banyak kasus tak pernah dilaporkan.
Mengapa masih terjadi perbudakan modern itu? Trafficking bertahan karena tiga hal.
Pertama, kemiskinan, yang membuat keluarga rela melepas anak demi janji pekerjaan.
Kedua, kerentanan sosial, terutama minimnya pendidikan dan literasi digital. Ini yang membuat banyak orang mudah tertipu daya.
Ketiga, permintaan pasar: selama ada permintaan tenaga kerja murah dan seks komersial, selama itu pula sindikat perdagangan manusia mencari korban baru.
Korban anak-anak adalah wajah paling tragis. Saat mereka diperjualbelikan, yang sejatinya diperdagangkan bukan hanya tubuh, melainkan juga derita banyak orang.
-000-
Narudin Pituin tidak sendirian. Dunia sastra global juga menjeritkan hal serupa.
Patricia McCormick, dalam novel Sold (2006), menulis kisah Lakshmi. Ia gadis 13 tahun dari Nepal yang dijual ke India dan dipaksa bekerja di sebuah rumah bordil bernama Happiness House.
Ditulis dalam prosa liris, novel itu berbasis riset lapangan dan wawancara dengan korban. Lakshmi adalah fiksi, tetapi lahir dari realitas pahit ribuan anak perempuan Asia Selatan.
Lakshmi, gadis 13 tahun dari desa miskin di Nepal, hidup dengan ibunya di gubuk jerami, bermimpi sederhana: bisa bersekolah dan membeli sepatu plastik baru.
Ayah tirinya, terjerat hutang, menjualnya dengan janji pekerjaan di kota. Dengan penuh harap ia berangkat, namun langkahnya berakhir di India, di sebuah rumah bordil bernama Happiness House.
Di sana Lakshmi menyadari kebenaran pahit: ia dipaksa melayani lelaki asing, tubuhnya dijadikan komoditas.
Setiap penolakan berbuah ancaman dan kekerasan. Hari-harinya terperangkap dalam jeruji yang tak terlihat—kemiskinan, kebohongan, dan kekuasaan orang dewasa.
Namun Lakshmi tetap menggenggam secercah cahaya: kenangan akan ibunya, mimpi belajar menulis angka, dan harapan akan kebebasan.
Hingga suatu hari, datanglah seorang pekerja bantuan yang menawarinya jalan keluar. Novel berakhir dengan Lakshmi melangkah ke arah kebebasan, membawa pesan kuat: meski dunia menghancurkan, keberanian dan harapan tetap bisa menyelamatkan jiwa.
Jika Sold menjerit dengan prosa pendek dan ingatan patah-patah seorang anak, maka Narudin menjerit dengan puisi esai: narasi faktual yang dipadu dengan kekuatan metafora.
Keduanya berbeda gaya, namun satu pesan: jangan biarkan anak-anak ditukar dengan uang, jangan biarkan mereka kehilangan masa kanak-kanaknya.
-000-
Puisi soal perdagangan anak-anak itu hanya salah satu dari 15 puisi esai karya Narudin Pituin yang terangkum dalam buku Menjahit Luka Anak Bangsa.
Judul-judulnya mengguncang: Ayah Tiri yang Tega, Mangsaku 31 Anak, Bunuh Diri Saja Aku, Guruku Guru Cabul, Di Panti Asuhan, Kamu Pemerkosa Aku Pemutilasi, dan lain-lain.
Semua diangkat dari kasus nyata. Anak-anak dijual lintas kota, dikhianati ayah tiri, diperalat media sosial, bahkan disakiti oleh guru yang seharusnya mendidik.
Benang merahnya jelas: anak-anak adalah korban paling rentan, dan lembaga yang seharusnya melindungi—keluarga, sekolah, masyarakat—sering justru menjadi sumber luka.
Kekuatan buku ini ada pada tiga hal:
1. Bentuk puisi esai yang unik, menggabungkan fakta dan estetika.
2. Keberanian tematik, menyentuh isu-isu yang kerap dianggap tabu.
3. Saksi sosial, karena puisi esai ini bukan sekadar seni, tapi juga dokumen nurani dalam satu momen sejarah.
-000-
Untuk mencapai solusi konkret melawan perdagangan anak- anak, gerakan multisektoral harus digalakkan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan di daerah rentan.
Sekolah wajib mengintegrasikan pendidikan literasi digital sejak SD. Dan masyarakat sipil membentuk jaringan pengawasan berbasis komunitas.
Bagus pula jika dikembangkan Inisiatif seperti Aplikasi LindungiAnak. Ia menghubungkan korban dengan psikolog dan pengacara.
Ketika seorang anak dilukai, sesungguhnya bangsa itu sedang melukai dirinya sendiri.
Luka pada anak bukan hanya luka pribadi, melainkan luka sosial, luka budaya, luka peradaban.
Menjahit Luka Anak Bangsa mengingatkan kita: melawan trafficking bukan sekadar agenda hukum, tetapi agenda kemanusiaan.
Setiap anak yang terselamatkan adalah benang yang menjahit kembali kain peradaban yang terkoyak.
Maka, pertanyaan besar buku ini menggema seperti doa yang tak selesai:
Siapa yang melukai anak-anak kita?
Dan lebih jauh lagi: apa yang kita abai sehingga perdagangan anak- anak itu masih terjadi di samping rumah kita sendiri?
Sebab pada akhirnya, ukuran sejati sebuah peradaban bukanlah gedung pencakar langit atau angka pertumbuhan ekonomi, melainkan sejauh mana ia menjaga anak-anaknya.
Jika anak-anak tetap menjadi korban, maka segala kemajuan hanyalah ilusi.***
Bali, 25 Agustus 2025
Referensi
1. Patricia McCormick, Sold. New York: Hyperion, 2006.
2. Siddharth Kara, Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery. New York: Columbia University Press, 2009.
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/16rzpKcw1B/?mibextid=wwXIfr


.jpeg)