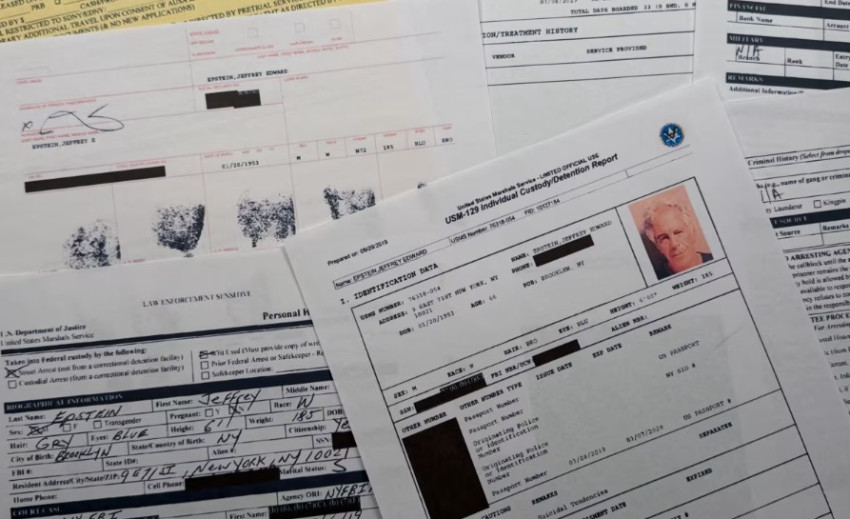Politik Pembangunan di Papua yang Tak Pernah Belajar dari Masa Lalu
ORBITINDONESIA.COM – Saat Wapres Gibran Rakabuming Raka diumumkan menerima mandat percepatan pembangunan Papua, publik bereaksi dengan dua nada: sebagian menyambut dengan harapan, sebagian bertanya dalam hati—apa yang bisa dibangun, jika cara pandang pusat terhadap Papua belum pernah benar-benar berubah?
Masalahnya bukan sekadar siapa yang ditunjuk. Masalahnya terletak pada cara negara memosisikan Papua selama ini—sebagai objek pembangunan, bukan subjek politik. Sebagai ruang untuk didorong percepatan, bukan wilayah yang boleh memilih ritmenya sendiri.
Dalam pendekatan kebijakan publik klasik, William Dunn menegaskan pentingnya stakeholder knowledge—kebijakan hanya efektif jika lahir dari pemahaman lokal, dan bukan sekadar diimpor dari meja pusat. Tapi dalam sejarah panjang relasi Jakarta dan Papua, pengetahuan lokal sering dianggap penghambat, bukan penuntun.
Dalam konteks itu, penunjukan Gibran—yang belum memiliki rekam jejak langsung dalam pembangunan wilayah sensitif konflik atau pengelolaan kebijakan berbasis adat—memunculkan pertanyaan wajar: apakah ini penugasan strategis, atau simbolik? Dan jika simbolik, untuk siapa simbol itu diarahkan?
Papua bukan sekadar soal pembangunan fisik. Ia menyimpan sejarah panjang relasi tak setara: dari transmigrasi, perubahan struktur pemerintahan adat, hingga sentralisasi keputusan fiskal. Banyak kebijakan, meski bermaksud baik, justru gagal karena menempatkan pembangunan sebagai proyek birokrasi, bukan proses bersama warga.
Michael Lipsky, dalam teori street-level bureaucracy, mengingatkan bahwa kebijakan publik yang tidak melibatkan pelaku lapangan—guru, tenaga kesehatan, tokoh adat, dan masyarakat desa—cenderung menjadi perintah yang tidak relevan secara realitas.
Sementara negara terus menata skema besar di atas, masyarakat Papua menata hidupnya dari bawah: membangun sekolah lokal, menjaga lahan ulayat, menyembuhkan trauma lewat komunitas. Tetapi upaya-upaya ini sering tak tercermin dalam dokumen negara. Pembangunan berjalan dengan logika proyek, bukan proses. Hasilnya: jalan jadi, tapi legitimasi rusak.
Maka, kekhawatiran atas penunjukan Wapres Gibran bukan terletak pada niatnya, tapi pada struktur kekuasaan yang belum membuka ruang partisipasi nyata. Masyarakat Papua telah lama meminta agar pembangunan dimulai dari mendengar, bukan dari memutuskan.
Pertanyaan mendesak kini adalah: apakah model percepatan ini akan menampung suara masyarakat adat, gereja lokal, aktivis lingkungan, dan pemuda Papua? Ataukah ini akan menjadi babak baru dari pendekatan top-down yang hanya mempertebal kecurigaan?
Banyak laporan publik dan akademik, seperti yang dirilis LIPI pada 2022, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Papua bergantung pada dua hal: (1) tingkat partisipasi komunitas lokal, dan (2) kemampuan negara memahami kompleksitas sosial-budaya Papua sebagai wilayah yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain.
Tanpa dua hal itu, kebijakan percepatan hanya akan menjadi proyek politik tahunan. Yang dibangun adalah laporan, bukan relasi. Yang diperkuat adalah angka, bukan rasa memiliki.
Maka, jika Wapres Gibran ingin penugasan ini lebih dari sekadar tugas politik, maka ia perlu hadir bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai pendengar. Ia perlu mengunjungi kampung, bukan hanya kantor. Ia harus bicara dengan komunitas yang belum pernah diajak duduk oleh pejabat pusat.
Percepatan pembangunan tak boleh dimaknai sebagai kecepatan mengeksekusi anggaran, tetapi kemampuan memperlambat ego dan membuka dialog. Papua tidak butuh pemburu target—ia butuh sekutu yang memahami bahwa pembangunan sejati tidak mencetak grafik, tapi memulihkan kepercayaan.
Penugasan Wapres kali ini menjadi ujian: apakah negara bisa keluar dari siklus lama pembangunan dari atas? Atau justru mengulang pola yang gagal—dengan wajah baru yang berbeda, tapi sistem yang sama? Jawaban atas itu hanya bisa dibuktikan jika Jakarta berhenti membayangkan Papua sebagai ruang kosong, dan mulai melihatnya sebagai ruang yang punya kehendak, suara, dan jalan sendiri menuju sejahtera.***

.jpeg)