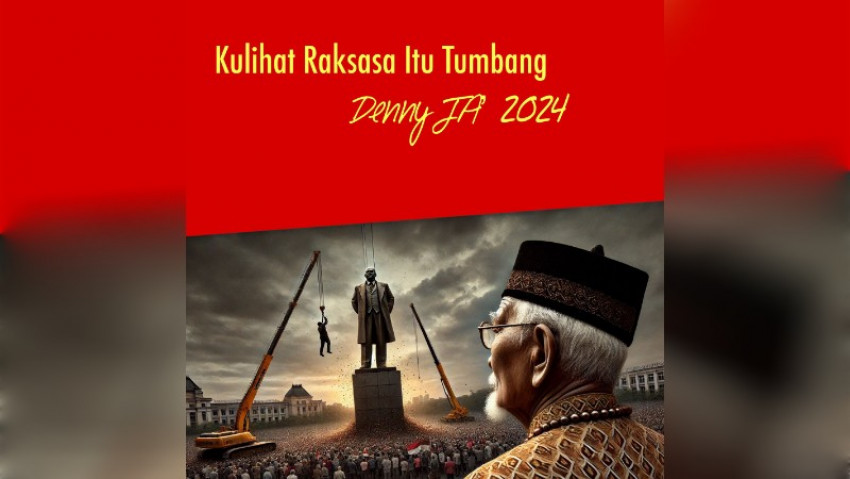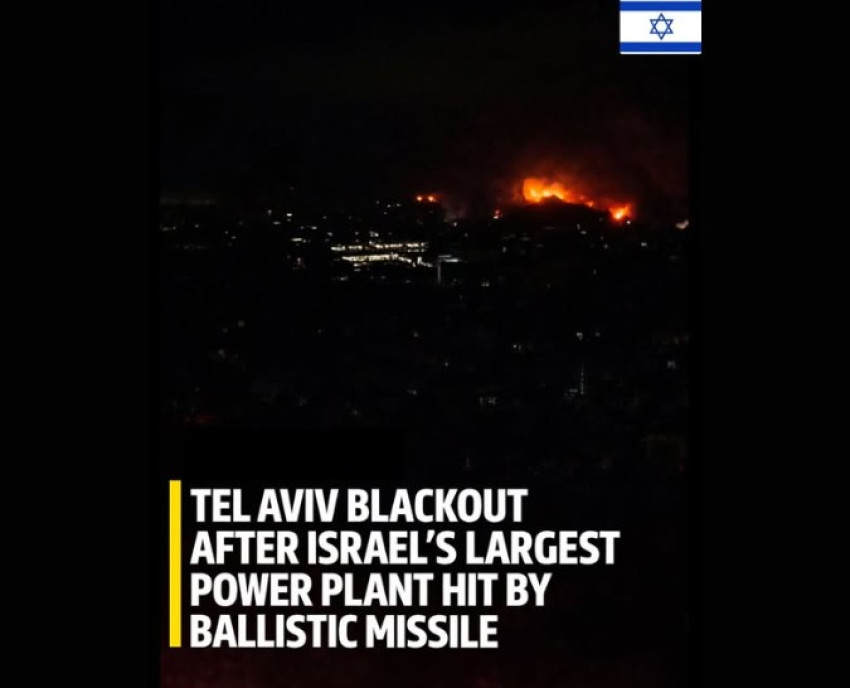Puisi Denny JA: Kulihat Raksasa Itu Tumbang
ORBITINDONESIA.COM - Di tahun 1960-an, Mualim dikirim ke Moskow untuk belajar. Prahara politik dekade itu membuatnya tak bisa pulang, dan mengubah hidupnya.
-000-
Apa yang bisa diharap oleh daun,
yang lepas dari pohon,
melayang tanpa arah,
diombang-ambingkan angin?
"Akulah daun itu," kata Mualim,
dihempaskan oleh ilusi revolusi,
hilang, tanpa tahu di mana berakhir.
Di Moskow, di masa tua,
Mualim kedinginan.
Namun, hatinya lebih beku.
Kebun di dadanya, dulu penuh bunga
dan yel-yel revolusi,
kini layu, tersisa luka yang menganga.
Ia menatap patung Lenin.
Angin membawa ingatannya jauh,
ke masa Indonesia menyala,
ketika revolusi adalah mantra.
Mualim, pemuda penuh api,
dikirim Bung Karno sekolah ke Moskow
Belajar untuk bangun negeri,
lalu kelak memetik bintang. 1
Tapi api itu padam.
Bung Karno jatuh.
Zaman berbelok arah.
Mualim menjadi bagian dari cerita lama.
Pulang berarti penjara,
paspor dicabut,
ia melayang,
warga tanpa negara.
-000-
Waktu menghantamnya keras.
Moskow, negeri merah,
dengan Kremlin yang megah,
Kuba emas yang berkilau,
tak lebih dari bayangan yang sunyi.
Di balik kemegahan,
jiwa terkubur,
seperti daun yang tertiup,
di atas tanah tandus.
Mualim, di jantung revolusi,
melihat ombak besar,
tak tahu kapan reda,
tak tahu di mana mereda.
-000-
Di antara menara raksasa, di kota Moskow,
Mualim melihat kebesaran yang kosong
patung Lenin berdiri,
tapi mata batunya hampa.
Kereta bawah tanah melesat,
stasiun-stasiun penuh mosaik.
Namun, siapa peduli pada keindahan
ketika jiwa beku di dalam?
Ia tersesat,
di labirin kota yang dingin,
di janji revolusi yang meredup,
di salju yang turun tanpa akhir,
menelan tubuhnya perlahan.
-000-
Mualim berdiri di pinggir sungai Moskva,
menatap air yang tak mengalir,
seperti hidupnya,
terhenti, tak tahu ke mana pergi.
"Kembalilah!" seru suara dari jauh.
Namun apa arti pulang,
jika rumah tak lagi ada?
Apa arti tanah air,
jika hanya penjara yang menunggu?
Uni Soviet,
raksasa yang dulu ia puja,
perlahan runtuh,
seperti istana pasir tersapu ombak.
Batu-batu besar jatuh satu per satu,
tubuh besar kehilangan nyawa.
Dan Mualim,
dulu pemuda penuh semangat,
kini hanya saksi.
Revolusi yang dulu membakar dada,
kini abu yang dihembus angin,
lenyap dalam dingin Moskow
yang tak peduli.
Revolusi hanya ilusi,
cermin retak yang memantulkan kosong.
Mualim,
sungai yang kehilangan hulu,
mengalir tanpa tujuan,
tak pernah tiba di laut.
Raksasa yang ia puja tumbang,
bukan dengan gemuruh,
tapi dengan sunyi yang menusuk,
seperti pohon besar kehilangan akar,
runtuh tanpa sisa,
meninggalkan debu yang beterbangan.
---
Kini, Mualim tua,
tersesat dalam bayang-bayang,
berdiri di reruntuhan mimpi.
Revolusi yang ia puja,
hanya angin yang berhembus,
tanpa arah.
Tak ada yang tersisa untuk dirayakan,
hanya rindu yang tak padam.
Rindu pada tanah air,
pada masakan ibu di dapur,
pada wayang kulit hingga subuh,
pada keriangan masa kecil,
mandi di bawah pancuran hujan.
Walau tubuh tinggal di Moskow,
batinnya melayang,
menapak tilas perjalanan pulang,
hanya di angan-angan.
Dan tiba-tiba ia sadar,
bahwa rindu yang selalu ia peluk
adalah satu-satunya yang tersisa:
tak ada revolusi, tak ada negara,
hanya rindu yang bertahan.
Tapi rindu itu, seperti revolusi,
tak pernah sampai,
tak pernah menjejak tanah.
Ia selalu melayang,
seperti dirinya,
terhempas angin,
terlepas, tanpa akar.
Jakarta, 30 September 2024 ***
CATATAN:
(1) Puisi ini diinspirasi oleh kisah nyata banyak pelajar Indonesia yang disekolahkan ke luar negeri pada tahun 1960-an. Namun, prahara politik membuat mereka menjadi eksil, terbuang dari Indonesia.