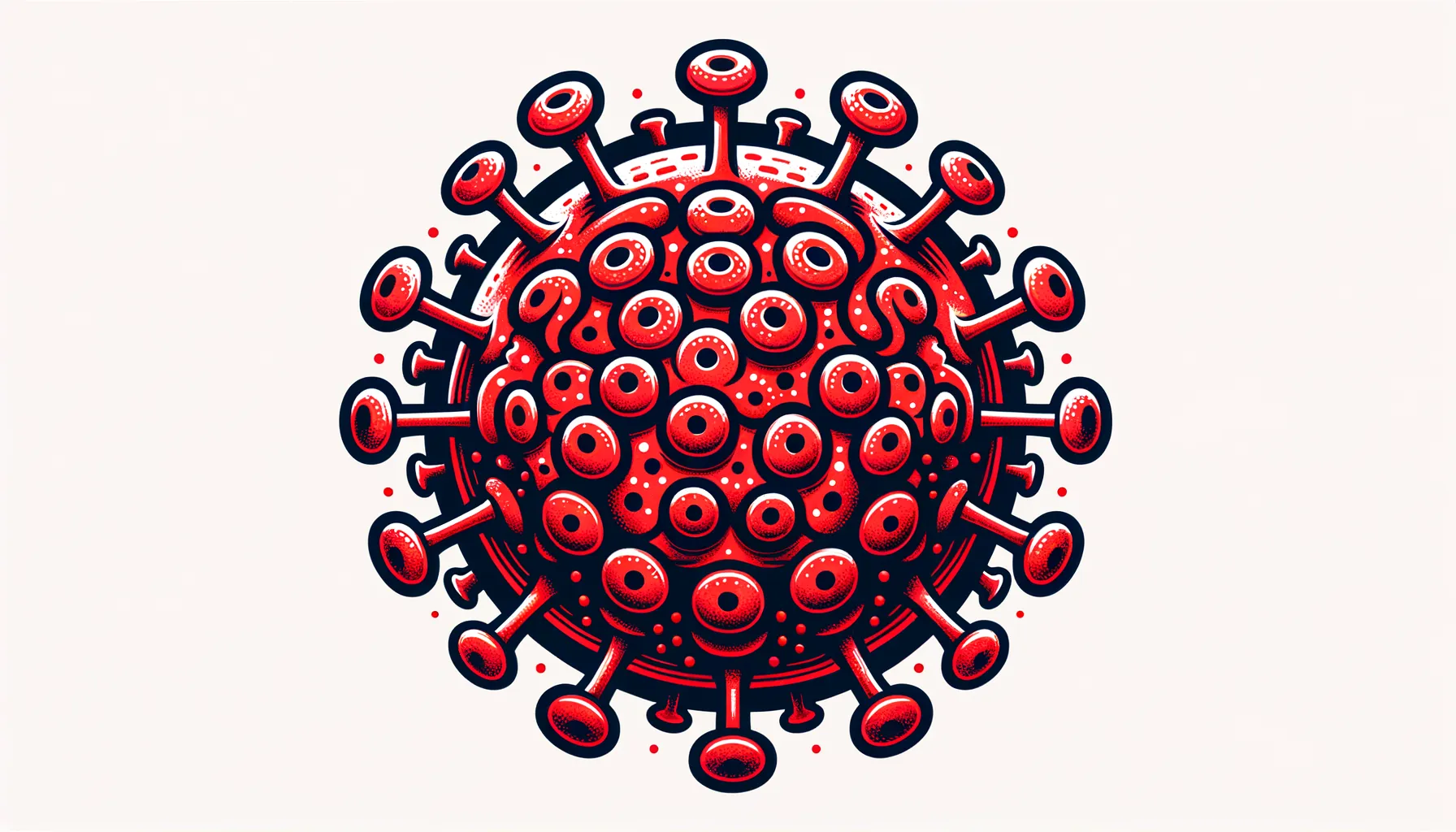Laporan Isti Nugroho: BRICS Award Bertemu Narasi Kontemplasi Kemanusiaan
ORBITINDONESIA.COM - Dinilai membuka kemungkinan baru dalam jagat sastra-- melalui puisi esai-- penyair Denny JA mendapatkan Penghargaan Khusus untuk Inovasi Sastra tingkat internasional dari BRICS (blok ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia). Selain Denny, sastrawan Mesir Salva Bakr juga menerima BRICS Award 2025. Atas keberhasilan itu, Denny JA menggelar doa syukur dalam reriuangan (pertemuan penuh keakraban) bersama para sahabatnya Minggu, 14 Desember 2025 di Hotel Harris Jakarta.
BRICS Award merujuk pada penghargaan sastra internasional baru, BRICS Literature Award, untuk mengangkat sastra Global South dan memperkuat diplomasi budaya. Penghargaan ini bertujuan memberikan platform bagi kisah-kisah dari negara berkembang dan mendorong dialog lintas budaya, menentang dominasi narasi Barat dalam dunia sastra.
“Saya bangga Indonesia ikut diakui. Dan saya bangga Denny menerima Special Prize for Innovation in Literature. Tanpa ia sadari, ia telah mengangkat profil Indonesia di mata dunia," ujar Sastri Bakry, Koordinator BRICS Literature Network Indonesia.
*Selain syukuran atas BRICS Award Denny JA, acara itu dimaksudkan umbul donga (mengangkat doa ke langit) bagi korban bencana banjir di Sumatera. Juga rasa syukur atas keberhasilan bung Asrun sebagai anggota Komisi Yudisial dan perayaan ulang tahun mbak Fatin Hamama, Elza, Asrun dan Ali. Acara semakin lengkap karena ada diskusi buku karya Berthold Damshauser bertajuk Eksegesis Pancasila, di mana bung Denny dan bung Agus Sarjono jadi pembahas; ada pembacaan puisi esai karya bung Denny dan musik serta lagu. Tak ketinggalan makan enak.
Ada empat pembaca puisi yang tampil yaitu Monica Anggi Puspita, Fatin Hamama, Sasti Bakry dan Isti Nugroho.
Dalam puisi esai yang bertajuk “Bukit Itu Menangis Menimbun Satu Keluarga” dibacakan Fatin Hamama, Denny berhasil menghadirkan duka derita akibat bencana banjir di Sumatera mengalir dalam rongga jiwa para hadirin. Keprihatinan atas alam dan lingkungan luluh menyatu dengan energi puitik, lalu menjelma jadi kontemplasi kolektif. Puisi esai Denny JA terbukti mampu menjadi wahana kontemplasi kemanusiaan terkait luka alam dan lingkungan akibat dominasi kuasa modal dan predator industrial.
Puisi Denny bicara penuh kepedihan: “… perusahaan-perusahaan itu naik ke punggungku/menjadi pasukan yang lapar/menggunduli rabut hijauku/menelanjangiku sampai ke tulang/”.
Akhirnya karena hujan sangat deras, bukit yang gundul itu tak mampu menahan hantaman arus air. Bukit itu runtuh. Longsor dan menimbun sebuah keluarga tak berdosa. Puisi esai ini sangat menggugah dan menyentuh jiwa.
***
Monica Anggi Puspita, tampil membacakan puisi esai Denny JA “Aku dan Ibuku Terisolasi”. Ia tak hanya membaca tapi juga menyanyikan larik-larik puisi esai. Vokalnya utuh dan kuat serta artikulatif. Ia membaca penuh penghayatan. Aura kecerdasan puitiknya pun memancar.
Puisi esai itu mengisahkan perempuan yang disebut ibu yang menjadi salah satu korban banjir. Kisah dan ketokohan sang ibu berkelindan dengan derita alam/lingkungan yang terluka. Dihadirkan melalui gaya monolog, di mana “aku lirik” menjadi pusat penceritaan.
Dalam puisi itu Denny menghadirkan ironi getir seputar eksploitasi alam, kuasa modal yang merajalela, dan luputnya perhatian mata dunia atas penderitaan para korban yang terselip di tumpukan reruntuhan persoalan. Simak ucapan Denny: “Di layar kecil ponselku/ aneka bantuan/ hanya muncul sebagai notifikasi tertunda;/ truk bantuan berbaris rapi di berita,/ sementara di koordinat kami/, hanya suara katak dan detak jam dinding yang menua”
***
Masih soal nasib korban banjir, puisi esai “Dua Hari Ia Berjalan Mencari Istri dan Anak” karya Denny JA yang saya baca, bicara tentang rasa kehilangan. Pandu, tokoh utama tak hanya mengalami keterputusan secara fisik dan sosial tapi juga secara eksistensial. Istri dan dua anaknya tidak jelas rimbanya. Ia pun mencari mereka, menempuh berkilo-kilo meter waktu. Ia pun memasuki desa demi desa, kota demi kota hingga ke ceruk-ceruk kecil, namun hasilnya nihil. Termasuk ketika ia menanyakan keberadaan anak dan istrinya kepada otoritas wilayah. Negara ternyata juga tak hadir dalam kepungan persoalan Pandu.
Denny berucap pedih, “Di satu tanjakan/, Pandu melihat siluet tiga tubuh/, seorang perempuan dan dua anak kecil berdiri di seberang sungai kecil/ Hatinya pecah/menjadi kaca yang dilempar ke jurang gelap/ seluruh dirinya runtuh/ia rumah yang diseret arus/ Ia melompat/menuruni tebing kecil itu/menyeberangi sungai dangkal/yang arusnya menarik-narik celananya/ ke dalam cerita lain/Namun ketika ia tiba di seberang/tak ada siapa/siapa/”
Ironi itu secara tajam dihadirkan Denny: “Beberapa kilometer kemudian/ia bertemu Bupati Tapanuli tengah/Orang-orang berkumpul/Kamera menyala/Langit menjadi saksi bisu/ Dengan suara yang dimakan takut dan cinta yang tinggal seutas benang/ia memohon: Tolong saya Pak/Di mana istri saya/Di mana anak saya// Itu bukan permintaan, itu jiwa seorang ayah yang runtuh/lalu jatuh menjadi suara// Video itu menyebar/Warganet berdoa/Namun tak ada berita/yang bisa mengeringkan air mata seorang ayah/ yang sedang mencari dunianya sendiri yang hilang//.
Puisi ini sarat dengan renungan kemanudiaan. Menggedor nurani, Mengguncang jiwa. Emosi saya pun larut dalam jiwa puisi hingga tanpa sadar saya menangis ketika membaca puisi Denny.
.Melalui ratusan puisi yang ditulisnya, Bung Denny percaya hidup tak hanya membutuhkan kecakapan intelektual tapi juga ketajaman intuisi, sehingga manusia tidak larut ke dalam arus realitas yang keras dan banal. Manusia butuh melakukan transendensi demi mencapai pencerahan. Sehingga ia lahir kembali sebagai “manusia baru” atau manusia otentik (sejati). Yaitu manusia yang memiliki kedaulatan diri yang mewujud dalam integritas dan komitmen sosial. Dan, puisi esai, dalam konteks itu,, mampu menjadi wahana penyadaran atas pentingnya orientasi nilai yang ideal.
***
Acara yang tidak kalah menarik adalah diskusi buku karya Berthold Damshauser bertajuk Eksegesis Pancasila. Denny antara lain mengatakan, Berthold Damshäuser, Indonesianis dari Universitas Bonn, menjawab kegelisahan itu melalui esainya yang monumental, Teks Pancasila – Sebuah Eksegesis. Ia mengajak kita menafsir ulang Pancasila dengan ketelitian seorang filolog, bukan dengan dogma seorang teolog.
Dikatakan Denny, Damshäuser menunjukkan bahwa kata “Ketuhanan” bukan berarti kepercayaan kepada Tuhan personal, melainkan menunjuk pada konsep abstrak keilahian—suatu realitas metafisik yang tidak terikat pada bentuk agama atau sosok pribadi. Ia menulis: “Ketuhanan adalah konsep yang setara dengan Keilahian, bukan personalitas Ilahi.”
“Dengan metodologi eksegesis tekstual—yakni menafsir teks Pancasila melalui dirinya sendiri dan bukan melalui tafsir ideologis atau religius— Damshäuser menyimpulkan bahwa sila pertama tidak bersifat teistik maupun monoteistik, melainkan bersifat transenden dan non-personal.” Ujar Denny.
Adapun sastrawan Agus Sarjono mengatakan, “Sebagai penyair, saya memandang bahwa bagaimanapun, Pancasila adalah jawaban Soekarno (dan para pendiri bangsa se generasinya) atas persoalan, situasi, dan kondisi revolusi Indonesia. Di sini Pancasila menjadi wahana politik dan budaya untuk memperkuat persatuan bangsa.”
Dikatakan Agus, di mata Soekarno, masalah terbesar bangsa Indonesia adalah tiadanya kesatuan. Belanda sendiri, sebagaimana lazimnya semua praktik kolonialisme di dunia, dengan sungguh-sungguh menjalankan politik standard et impera, memecah belah suatu negeri hingga saling bertikai agar mudah dikuasai.
Pemecahbelahan itu berjalan lancar di Indonesia mengingat demikian banyak unsur pemecah belah yang tersedia, mulai dari ras, suku, agama, ideologi, partai, organisasi masyarakat, komunitas, dan tentu juga berbagai kepentingan politik, baik politik kelompok maupun politik individu. Dalam konteks ini, Pancasila mampu hadir menjadi jawaban persoalan kebangsaan.
(Laporan Isti Nugroho) ***