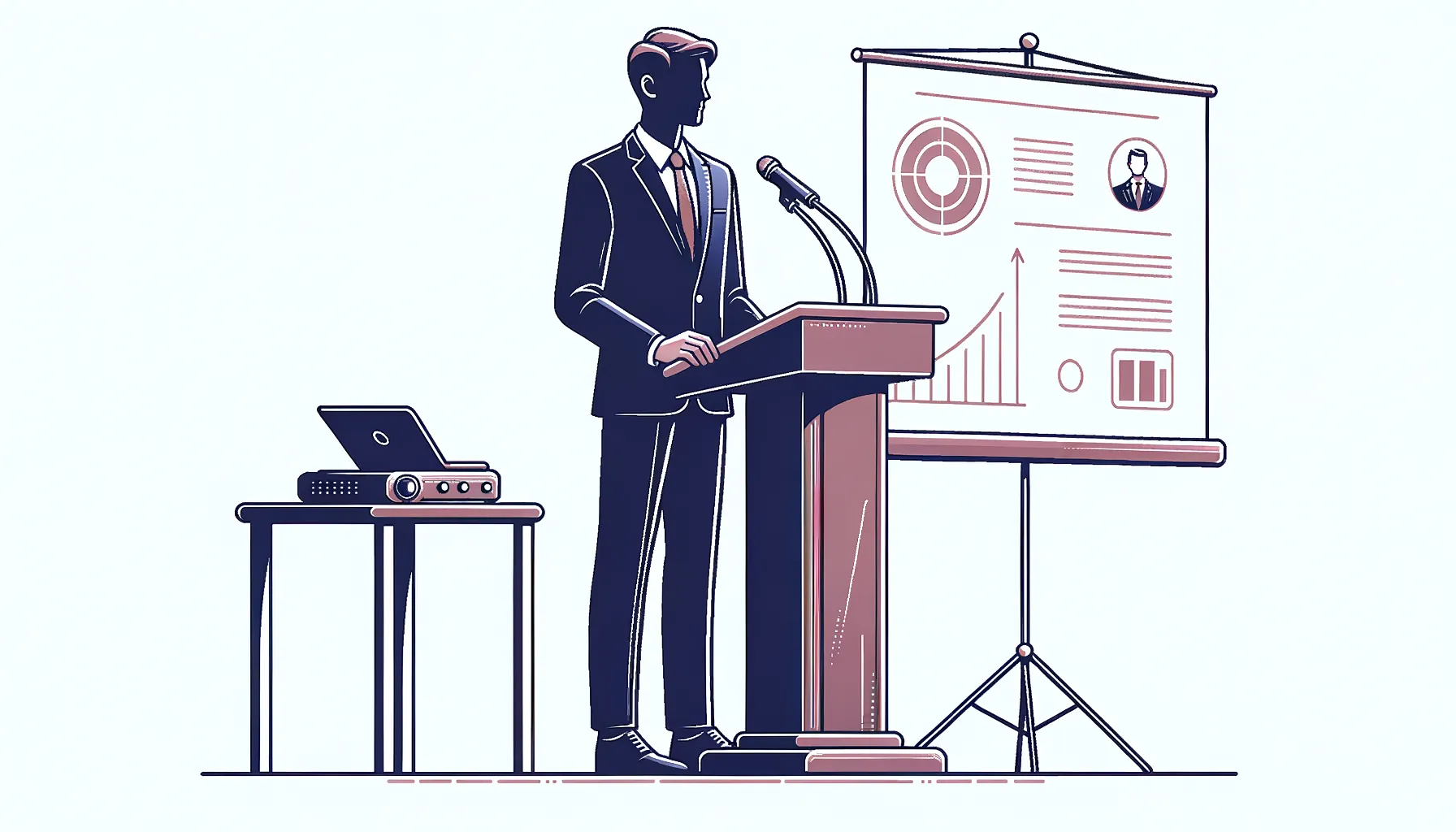Satrio Arismunandar: Menyikapi Bencana Alam dengan Merleau-Ponty dan Ekofenomenologi
Oleh Satrio Arismunandar
ORBITINDONESIA.COM - Bencana alam besar berupa banjir bandang dan tanah longsor pada November 2025 melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hantaman ini mengguncang kita bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Ratusan korban hilang atau meninggal, ribuan orang kehilangan rumah, dan infrastruktur rusak di mana-mana.
Di tengah kepedihan itu, muncul pertanyaan yang lebih dalam dari sekadar teknis. Apa yang sebenarnya terjadi antara kita dan alam?
Kita terbiasa membaca bencana sebagai curah hujan ekstrem, longsor di lereng rapuh, sedimentasi sungai, atau kelalaian tata ruang. Semua itu benar. Tetapi ada sesuatu yang luput: kita jarang melihat bencana sebagai retaknya hubungan antara manusia dan dunia yang ia tinggali.
Di sinilah ekofenomenologi—pemikiran yang dipengaruhi Maurice Merleau-Ponty dan dikembangkan lebih jauh oleh David Abram—memberi sudut pandang yang lebih manusiawi, lebih utuh, dan mungkin lebih menyentuh nurani.
Pemikiran Ekofenomenologi adalah salah satu cara paling subtil dan filosofis untuk memahami hubungan manusia dengan alam. Cabang ini melampaui sains, melampaui aktivisme lingkungan, dan bahkan melampaui etika tradisional; ia masuk ke akar cara manusia mengalami dunia.
Pemikiran Merleau-Ponty
Bagi Merleau-Ponty, manusia memahami dunia bukan lewat akal yang mengapung “di luar tubuh”, tetapi lewat pengalaman tubuh-hidup (lived body/le corps propre). Persepsi bukan sekadar data indra, melainkan cara tubuh menjalin hubungan dengan dunia. Tubuh bukan objek, melainkan subjek pertama yang berjumpa dengan dunia. Dunia tidak ditangkap seperti kamera, tetapi dialami secara langsung melalui gerak, ambang rasa, orientasi, dan ritme tubuh.
Di sinilah ia berbeda dengan Cartesian dualism (tubuh vs pikiran). Merleau-Ponty menggugurkan pemisahan itu. Sebelum kita berpikir, menganalisis, atau memberi nama, kita sudah lebih dulu mengalami. Persepsi terjadi sebelum bahasa, sebelum konsep, sebelum analisis rasional.
Kita tahu kursi bisa diduduki bukan karena teori, tapi karena tubuh “mengerti” bentuk dan jaraknya. Kita tahu tebing itu berbahaya karena tubuh merasakannya dan otomatis bereaksi. Merleau-Ponty menyebut ini sebagai pengertian implisit tubuh — sebuah kecerdasan yang mendahului logika.
Bagi Merleau-Ponty, manusia dan dunia itu saling-mengada (intertwining/chiasm). Chiasm (dalam bahasa Prancis chiasme) adalah salah satu konsep paling penting dalam filsafat Maurice Merleau-Ponty, terutama pada karya akhirnya The Visible and the Invisible.
Agar gampang dipahami: chiasm = persilangan, pertautan, atau “saling-menembus” antara tubuh manusia dan dunia. Seolah-olah manusia dan dunia tidak berdiri berhadap-hadapan, tetapi saling menjalin seperti dua benang yang bersilangan dan membentuk satu anyaman.
Dalam karya terakhirnya, ia memperkenalkan konsep the flesh of the world — “daging dunia”. Ini bukan daging biologis, tetapi metafora untuk menggambarkan bahwa: manusia dan dunia terjalin, bukan terpisah; subjek dan objek bersilang, bukan bertentangan; melihat dan dilihat adalah proses saling memasuki.
Saat saya melihat pepohonan, pepohonan itu juga membentuk cara saya melihat: bayangannya, aromanya, teksturnya, suhu udara — semuanya mengajak tubuh saya merespons. Hubungan manusia–alam menurut Merleau-Ponty bersifat timbal balik, bukan dominatif.
Makna Lahir dari Hubungan, Bukan Pikiran Abstrak
Fenomena dunia bukan benda mati yang “ada begitu saja”. Ia penuh makna yang muncul dari cara kita hadir di dalamnya. Makna bukan ditempelkan oleh pikiran, melainkan tumbuh dari perjumpaan. Rumah masa kecil kita bermakna bukan karena definisi arsitektur, tapi karena tubuh mengalami kehangatan, bau dapur, suara hujan di atap. Hutan tidak hanya “kumpulan pohon”, tetapi ruang yang menata pernapasan, cahaya, arah langkah kita.
Inilah yang membuat Merleau-Ponty sangat relevan untuk etika lingkungan dan ekofenomenologi. Merleau-Ponty penting dalam Ekofenomenologi karena ia membongkar cara berpikir modern yang memisahkan manusia dari alam: manusia bukan penguasa alam; bukan penonton alam; bukan pengamat yang berdiri di luar.
Kita adalah bagian dari tekstur dunia, menghirup udara yang sama, bergerak dalam ruang yang sama, diikat oleh “daging dunia” yang sama. Dalam konteks bencana ekologis, gagasan Merleau-Ponty membantu kita melihat: kerusakan lingkungan bukan sekadar statistik, tetapi keretakan relasi antara tubuh-hidup manusia dan tubuh-hidup bumi.
Banjir, tanah longsor, krisis iklim bukan hanya peristiwa alam, tetapi ketidakseimbangan hubungan antara cara kita hidup dan cara alam merespons.
Merleau-Ponty tidak memulai dari “pikiran”, tetapi dari tubuh yang merasakan. Tubuh adalah cara kita berada-di-dunia. Kita tidak mengamati alam dari luar; kita menubuh di dalamnya. Persepsi tidak netral—ia selalu embodied, melekat pada tubuh kita yang juga bagian dari materi alam.
David Abram dan Gagasan Merleau-Ponty
Konsep kunci Merleau-Ponty adalah le sensible — dunia yang kita sentuh juga “menyentuh” kita. Saat kita memandang gunung, gunung itu “menagih” respons tertentu dari kita. Hubungan selalu dua arah—manusia dan alam saling memanggil, saling mempengaruhi. Di sinilah benih Ekofenomenologi: alam bukan objek pasif, tetapi mitra dalam jaringan relasional pengalaman.
Merleau-Ponty menolak gagasan bahwa manusia adalah subjek yang mengamati objek bernama alam. Baginya, kita selalu berada di dalam dunia, bukan di luar. Kita tidak hanya melihat alam; kita disentuh olehnya. Ada relasi timbal balik—reversibility—yang membuat manusia dan bumi saling memanggil dan saling mempengaruhi.
David Abram, seorang filsuf dan antropolog ekologis, kemudian memperluas gagasan ini menjadi pemahaman bahwa dunia tidak pernah mati, tidak pernah diam.
Hutan berbicara lewat desiran angin, sungai menyampaikan arah melalui alirannya, tanah punya ingatan tentang air, dan setiap lanskap menyimpan semacam kecerdasan ekologis yang tidak kalah tua dari sejarah manusia. Inilah yang ia sebut sebagai “more-than-human world”—dunia yang lebih luas dari sekadar manusia.
Namun modernitas telah mencabut kita dari keintiman itu. Bahasa kita semakin abstrak, kota-kota kedap suara alam, dan kehidupan sehari-hari kita menutup akses pada pengalaman langsung atas dunia. Kita tidak lagi mendengar suara daun jatuh, langkah air di bebatuan, atau ritme musim yang dulu menentukan cara hidup nenek moyang kita. Ketika persepsi kita tumpul, hubungan pun rapuh.
Bencana sebagai Disrupsi Relasi
Dalam kacamata ekofenomenologi, bencana bukan hanya fenomena fisik—ia adalah pembalikan hubungan. Kita menekan terlalu dalam, dan dunia merespons sesuai mekanismenya. Ketika hutan yang selama ratusan tahun menahan air digunduli, hilanglah dialog ekologis yang menjaga keseimbangan lereng. Ketika sungai dipersempit atau diarahkan ulang, hilang pula ruang hidup bagi air untuk menyalurkan dirinya tanpa menghancurkan.
Abram menyebut hal seperti ini sebagai krisis persepsi: kita berhenti melihat alam sebagai mitra hidup, sehingga mudah melanggarnya. Kita merusak tanah karena kita tidak lagi merasakannya sebagai tubuh yang memikul jejak kita. Kita membangun di kaki bukit seakan bukit tidak pernah bicara, tidak pernah memberi tanda bahaya, padahal dalam cara-cara halusnya ia selalu memberi petunjuk bagi mereka yang mau mendengar.
Banjir bandang dan tanah longsor, dalam cara ini, bukan “hukuman alam”, tetapi konsekuensi dari relasi yang timpang. Dunia menyeimbangkan dirinya, dan manusia yang berada di jalurnya.
Krisis Lingkungan adalah Krisis Pengalaman
Kajian ekologis modern sudah sangat kaya data: peta curah hujan, analisis DAS (daerah aliran sungai), peta rawan longsor, indeks vegetasi, model prediktif berbasis satelit. Semua itu penting. Tapi ekofenomenologi mengingatkan bahwa: kerusakan lingkungan terjadi karena kita berhenti mengalami dunia secara langsung.
Kita bisa hafal angka-angka curah hujan, tetapi lupa bagaimana rasa udara sebelum badai. Kita membaca laporan deforestasi, tetapi kehilangan kepekaan terhadap aroma tanah yang kehilangan humusnya. Kita tahu rumus debit sungai, tetapi lupa suara gelombang kecil ketika sungai mulai penuh.
Krisis ekologis pertama-tama adalah krisis persepsi. Krisis kedekatan. Krisis makna eksistensial. Karena itu solusi bukan hanya teknis. Solusi juga harus mengembalikan manusia untuk melihat alam sebagai mitra, bukan objek.
Menurut Abram, krisis lingkungan bukan pertama-tama karena teknologi atau ekonomi, tetapi kita kehilangan kemampuan untuk mengalami dunia sebagai sesuatu yang hidup. Alam menjadi “latar belakang tak bernyawa” dalam imajinasi modern. Dan kalau sesuatu dianggap tak bernyawa, ia mudah dieksploitasi.
Belajar Mendengar Kembali
Jika bencana adalah tanda relasi yang rusak, maka solusi tidak boleh semata teknis. Adaptasi iklim, rehabilitasi DAS, dan tata ruang berbasis risiko—semuanya mutlak. Tapi itu belum cukup. Kita perlu mengembalikan posisi manusia sebagai bagian dari jaringan kehidupan, bukan pemilik tunggal ruang.
Ekofenomenologi memberi tiga jalan:
Pertama, mengembalikan pengalaman inderawi dengan alam. Bukan sekadar wisata, tetapi membiarkan diri kita hadir, berjalan pelan, merasakan angin, mendengar air, mencium aroma tanah basah. Dari sini muncul rasa hormat yang tidak bisa digantikan regulasi.
Kedua, mengkaji kembali cara kita tinggal, membangun, dan bergerak. Arsitektur yang menyatu dengan kontur, pembangunan yang menjaga napas sungai, dan tata ruang yang mendengar petunjuk lanskap.
Ketiga, mengakui bahwa alam adalah mitra dialog. Pengakuan ini tidak romantis; justru realistis. Lereng yang miring, tanah yang rapuh, sungai yang berbelok—semuanya mengajari kita batas. Mengabaikan batas itu bukan hanya kelalaian teknis, tapi kelalaian eksistensial.
Kritik Terhadap Ekofenomenologi
Ekofenomenologi bukan satu-satunya alternatif pemikiran untuk menghadapi krisis lingkungan, yang terkait erat pada hubungan manusia dan alam. Alternatif lain adalah pemikiran deep ecology.
Ekofenomenologi dan deep ecology memberikan tawaran berbeda, bahkan saling melengkapi, untuk membongkar akar terdalam krisis ekologis yang kita hadapi. Keduanya mengusung visi yang tampak serupa: mengkritik antroposentrisme dan mendorong rekonsiliasi antara manusia dan bumi.
Namun, keduanya berangkat dari arah yang tidak sama, bahkan kadang bertolak belakang. Memahami perbedaan ini penting agar wacana lingkungan di media tidak anti-politik atau anti-realitas, tetapi tetap berakar pada pengalaman manusia sekaligus berorientasi pada perubahan struktural.
Ekofenomenologi berangkat dari satu gagasan sederhana namun revolusioner: krisis ekologis bukan hanya soal kerusakan fisik alam, tetapi juga soal kerusakan cara kita mengalami alam.
Fenomenologi—melalui Merleau-Ponty, Heidegger, dan para penerusnya—sejak awal mengajarkan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai “pengamat” yang terpisah dari dunia. Kita selalu hadir ke dunia melalui tubuh, melalui pengalaman langsung, melalui perjumpaan yang tak bisa direduksi menjadi data.
Dalam perspektif ini, alam bukan objek. Ia adalah “dunia yang ditampakkan” (the phenomenal world), tempat kita merasakan angin sebagai hembusan yang menyentuh kulit, bukan sebagai angka kecepatan. Pohon bukan sekadar biomassa; ia adalah kehadiran yang membingkai horizon pandang dan memberi rasa teduh. Sungai bukan sekadar volume debit air; ia adalah gerak yang menyampaikan ritme kehidupan.
Krisis ekologi—dalam tafsir ekofenomenologi—terjadi ketika relasi manusia dengan dunia menjadi dangkal, tereduksi oleh representasi: citra di layar, laporan teknis, atau narasi ekonomi. Kita tak lagi menyentuh dunia; kita hanya menatapnya. Akibatnya, kepekaan ekologis memudar. Kerusakan alam terjadi bukan hanya karena rakus, tapi karena kita tak lagi “mendengarkan” dunia.
Ekofenomenologi ingin menghidupkan kembali kepekaan itu. Ia mengajak kita menata ulang kesadaran: kembali melihat alam sebagai ruang kehadiran, bukan komoditas. Di sini politik lingkungan dimulai dari perubahan cara memaknai hidup.
Namun pendekatan ini punya kelemahan: terlalu reflektif, terlalu halus. Sulit mengubah struktur kebijakan hanya dengan kesadaran. Itu sebabnya kita perlu membandingkannya dengan deep ecology.
Deep Ecology Menggugat Struktur Nilai Modernitas
Jika ekofenomenologi masuk melalui pintu pengalaman, deep ecology masuk melalui pintu nilai moral yang paling fundamental. Dipelopori Arne Naess, tradisi ini menolak pandangan bahwa manusia lebih bernilai daripada makhluk hidup lain. Deep ecology mengusung biospheric egalitarianism—gagasan bahwa seluruh entitas hidup memiliki nilai intrinsik yang sama, bukan karena berguna bagi manusia, tetapi karena keberadaannya di jaring kehidupan.
Deep ecology hadir sebagai kritik keras terhadap etika antroposentris: etika yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya, penguasa tertinggi yang berhak menentukan baik-buruknya sesuatu berdasarkan keuntungan manusia.
Gagasan ini kemudian menjelma menjadi platform aksi: perlindungan ekosistem total, pengurangan drastis konsumsi, gaya hidup sederhana, hingga kritik terhadap industrialisme. Tak heran jika deep ecology sering diasosiasikan dengan aktivisme yang radikal.
Kekuatan pendekatan ini terletak pada kejelasannya: ia memberi kerangka moral yang tegas untuk menilai tindakan manusia terhadap bumi. Namun sekaligus mengundang kritik.
Sebagian menilai deep ecology terlalu romantik; sebagian lain bahkan menuduhnya membuka jalan bagi “eko-otoritarianisme” jika nilai-nilai itu diterapkan secara ekstrem: siapa yang menentukan prioritas antara manusia dan spesies lain? Bagaimana mengatur populasi? Bagaimana dengan kesenjangan ekonomi global?
Meski begitu, deep ecology memaksa kita untuk tidak hanya bertanya “bagaimana kita merawat alam?”, tetapi lebih radikal: “apa hak kita sebagai manusia di bumi ini?”
Perbedaan Ekofenomenologi dan deep ecology keduanya bisa diringkas begini: Ekofenomenologi membongkar cara kita mengalami dunia, sedangkan deep ecology membongkar cara kita memberi nilai terhadap dunia. Yang satu menggali kesadaran, yang lainnya menggugat sistem nilai.
Ekofenomenologi mendekat dari dalam diri manusia—melalui kesadaran, persepsi, dan relasi dasar dengan dunia. Deep ecology mendekat dari luar—melalui etik, norma, dan politik ekologis. Yang satu bersifat deskriptif dan reflektif; yang lain normatif dan programatik. Dan justru karena perbedaan ini, keduanya bisa membaca krisis ekologis dari dua sisi: pengalaman dan nilai, subjektivitas dan politik.
Jalan Pulang ke Dunia Hidup
Bencana yang melanda Sumatra bukan sekadar duka—ia juga undangan. Undangan untuk kembali mengalami dunia, bukan hanya memetakannya. Undangan untuk membaca lanskap sebagai teks yang hidup. Undangan untuk merasakan bumi sebagai tempat tinggal yang berbicara.
Ekofenomenologi mengajak kita melihat bahwa alam tidak meminta banyak; ia hanya menuntut agar kita hidup bersama dengannya, bukan di atasnya.
Dan mungkin, ketika kita belajar mendengar kembali suara bumi, kita bisa mulai menata hidup yang tidak hanya lebih aman, tetapi juga lebih manusiawi.
Namun, di dunia yang semakin dipenuhi media digital, narasi lingkungan sering bergerak di antara dua ekstrem: terlalu politis atau terlalu teknokratis. Kita kehilangan kedalaman, kehilangan cerita tentang pengalaman manusia, namun juga kehilangan arah perubahan struktural. Maka selain Ekofenomenologi kita juga butuh deep ecology.
Ekofenomenologi mengingatkan bahwa isu lingkungan harus mengembalikan manusia pada dunia yang dialami—bukan sekadar dipresentasikan. Sementara deep ecology menegaskan bahwa pengalaman saja tidak cukup; perlu ada kompas nilai yang kuat untuk mengubah sistem sosial, ekonomi, dan politik yang merusak bumi.
Keduanya memberi pelajaran penting untuk masa depan. Perubahan ekologis dimulai dari kesadaran, tetapi harus berujung pada struktur. Kita perlu merasakan dunia kembali, tetapi juga menetapkan batas moral yang baru.
Pada akhirnya, krisis ekologis hari ini adalah krisis imajinasi tentang apa itu kehidupan, apa itu dunia, dan apa itu manusia. Ekofenomenologi menawarkan jalan untuk menemukan kembali kedalaman pengalaman hidup, sementara deep ecology menawarkan jalan untuk merumuskan kembali etika hidup bersama bumi.
Dua jalan ini—meski berbeda—mengarah pada tujuan yang sama: membangun masa depan yang tidak hanya layak secara ekologis, tetapi juga bermakna secara eksistensial. Dan mungkin, itu satu-satunya masa depan yang masih mungkin kita perjuangkan. ***
Depok, 5 Desember 2025
*Satrio Arismunandar adalah penulis buku dan wartawan senior. Saat ini menjabat Pemimpin Redaksi media online OrbitIndonesia.com dan majalah pertahanan ARMORY REBORN. Ia saat ini menjadi Staf Ahli di Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Juga, Sekjen Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA (sejak Agustus 2021).
Ia pernah menjadi jurnalis di Harian Pelita (1986-1988), Harian Kompas (1988-1995), Majalah D&R (1997-2000), Harian Media Indonesia (2000-2001), Executive Producer di Trans TV (2002-2012), dan beberapa media lain.
Ia lulus S1 dari Jurusan Elektro Fakultas Teknik UI (1989), S2 Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional UI (2000), S2 Executive MBA dari Asian Institute of Management (AIM), Filipina (2009), dan S3 Filsafat dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI (2014).
Kontak/WA: 0812 8629 9061. E-mail: sawitriarismunandar@gmail.com