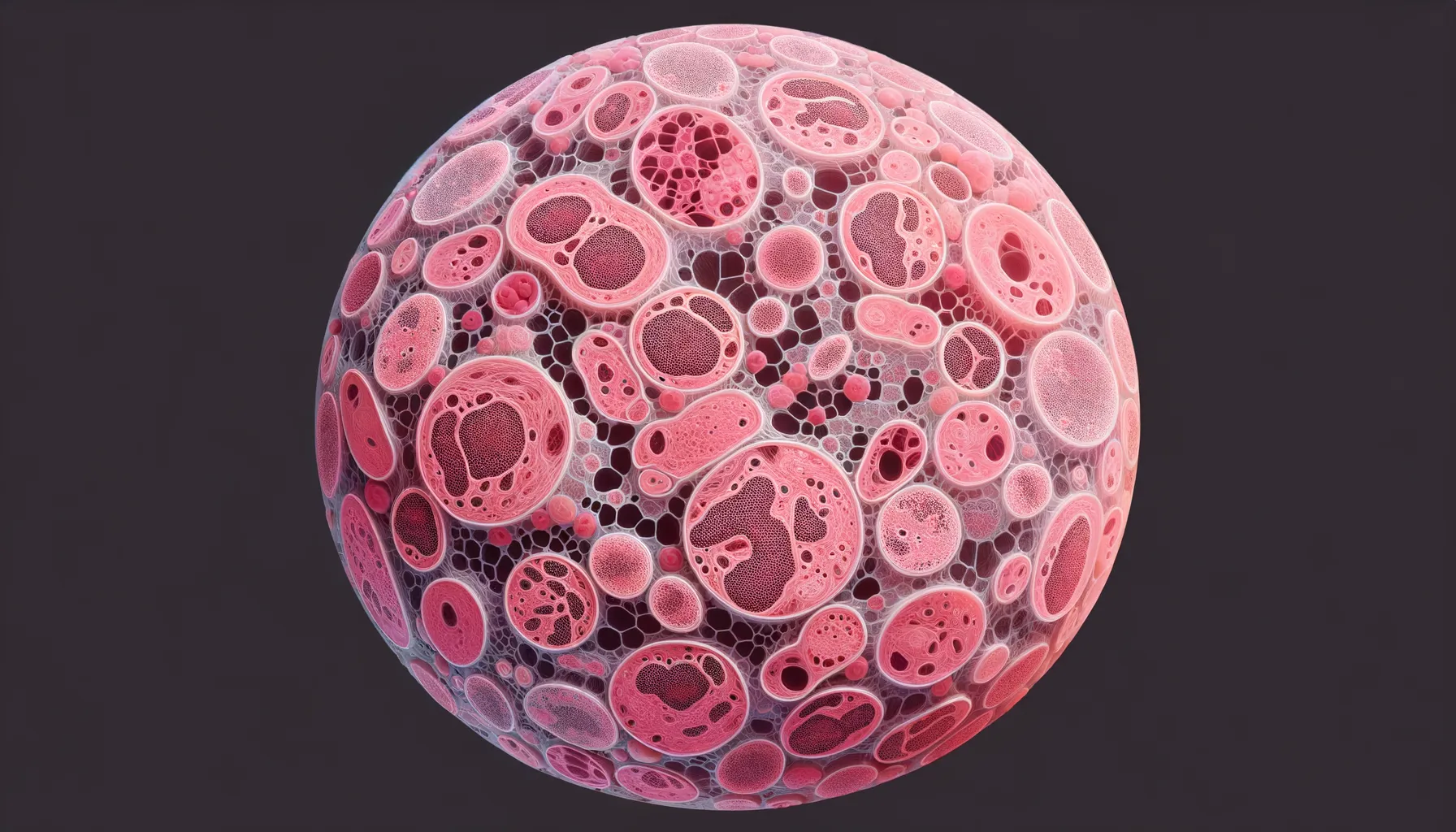Mengatasi Budaya Korupsi yang Sudah Terlanjur Merajalela di Indonesia
Agus Bandono dan Moroe Supranoto. Budaya Korupsi: Sebab, Dampak, dan Solusi. Penerbit: Alfabeta Indonesia, 2025. Tebal: xii + 122 halaman.
ORBITINDONESIA.COM - Di Indonesia sudah cukup banyak buku bertema korupsi yang diterbitkan. Masalah korupsi memang sangat serius sehingga wajar jika banyak buku yang mengulasnya dari berbagai aspek. Maka terbitnya buku “Budaya Korupsi: Sebab, Dampak, dan Solusi” ini diharapkan bisa melengkapi atau mengisi hal-hal yang masih kurang tergali.
Terbagi dalam tujuh bab, buku ini memulai dengan paparan bahwa korupsi adalah isu abadi. Dikatakan, praktik korupsi yang marak di Indonesia merupakan kesinambungan historis, warisan dari sistem pemerintahan feodal Jawa ala Mataram dan pemerintahan kolonial ala VOC, kemudian dipertahankan pada masa kolonial Hindia Belanda.
Saat ini perilaku korupsi yang dilakukan para pejabat publik di Indonesia sudah merajalela, membabi buta, dan masif. Korupsi dengan berbagai variasi sudah menjadi budaya baru, tata nilai baru, yang menggantikan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan ketulusan. Korupsi dilakukan secara berjamaah. Korupsi sudah menjadi banal, dianggap sudah biasa, seolah-olah normal.
Menurut penulisnya, ada beberapa hal yang membedakan buku ini dari buku-buku bertema korupsi yang telah terbit sebelumnya. Selain menyajikan data korupsi terbaru tahun 2025, buku ini menyinggung tentang filsafat manusia, moralitas, dan agama. Penulis meyakini, perilaku manusia dapat diperbaiki, sehingga menumbuhkan optimisme bahwa korupsi dapat diberantas.
Buku ini juga menunjukkan fakta empirik ada negara yang “nol korupsi,” seperti Finlandia, Denmark, Singapura, dan beberapa negara Skandinavia, serta Selandia Baru. Ini artinya, sangat mungkin korupsi di Indonesia itu dibuat jadi tidak ada.
Solusi Pencegahan Korupsi
Penulis mengulas juga tentang etika materialisme dan hedonisme serta nilai-nilai kearifan lokal, yang turut mempengaruhi gaya hidup manusia Indonesia.
Terakhir, penulis menggarisbawahi, buku-buku yang lain kurang membahas strategi solusi pencegahan dan penindakan yang menghasilkan efek jera. Buku ini di samping membahas sebab dan dampak, juga merekomendasikan solusi pencegahan korupsi sejak dini, dan pemberantasan korupsi yang diharapkan menghasilkan efek jera.
Penerbitan buku ini patut diapreasi karena kedua penulis tampaknya memiliki keprihatinan yang besar terhadap maraknya perilaku korupsi, yang sudah masuk kategori kejahatan luar biasa. Korupsi adalah salah satu problem akut negeri ini. Sukses-gagalnya program pembangunan yang dijalankan pemerintah, serta jatuh-bangunnya negeri ini, tampaknya akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh bangsa ini mampu mengatasi masalah korupsi.
Penulis juga tampaknya mencoba merangkum semua aspek dari masalah korupsi, mulai dari sejarah praktiknya, definisi dari berbagai ahli, hingga cara pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mungkin karena terlalu banyak yang ingin dicakup, justru buku ini terkesan kurang fokus.
Karena judulnya menggunakan istilah “budaya korupsi,” dan adanya anggapan atau keyakinan meluas bahwa korupsi memang betul-betul sudah membudaya, semula pembaca mungkin mengantisipasi akan ada ulasan yang mendalam dalam aspek budaya ini. Tetapi sayangnya hal ini kurang terlihat.
Shame Culture & Guilt Culture
Karena penulis menggunakan buku K. Bertens tentang etika sebagai salah satu rujukan, sebetulnya ada ulasan tentang budaya malu (shame culture) dan budaya kebersalahan (guilt culture) dalam buku Bertens tersebut, yang bisa dimanfaatkan sebagai “strategi budaya” untuk mengatasi masalah korupsi. Sayangnya, hal ini kurang dipaparkan oleh penulis.
Di Indonesia, korupsi sering terasa seperti penyakit kronis: tak pernah benar-benar sembuh, hanya mereda sesaat sebelum kembali mencuat dalam berbagai skandal. Berpuluh tahun kita mengandalkan pendekatan hukum—UU Tipikor, KPK, audit, transparansi anggaran—namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Di tengah kebuntuan itu, semakin kuat kesadaran bahwa masalah korupsi bukan sekadar soal aturan, tetapi soal budaya yang menyerap sampai ke cara kita melihat diri sendiri dan masyarakat.
Dua konsep antropologis klasik—budaya malu dan budaya kebersalahan—layak kembali dibicarakan. Keduanya pernah dibahas oleh Ruth Benedict, dan kini terasa relevan ketika bangsa ini mencari strategi baru untuk menegakkan integritas publik.
Budaya malu bekerja melalui sorotan sosial. Di dalamnya, seseorang menjaga perilaku terutama karena takut dipermalukan. Kehormatan bukan hanya milik pribadi, tapi nama baik keluarga, komunitas, bahkan kampung halaman. Dalam konteks ini, pengawasan masyarakat menjadi mekanisme moral yang sangat efektif. Seseorang menghindari tindakan buruk bukan semata karena salah, tetapi karena khawatir wajahnya terpampang di media, dicibir tetangga, atau dikecewakan orang tua.
Sebaliknya, budaya kebersalahan bekerja melalui suara batin. Individu menolak melakukan pelanggaran karena merasa integritas dirinya sendiri terancam. Di sini, moral bukan hasil pengawasan orang lain, tapi dialog batin—apa yang dianggap benar, apa yang dirasakan salah. Budaya kebersalahan lebih dekat dengan etika universal, pendidikan modern, dan pemahaman hukum yang kuat: kejujuran dilakukan meski tidak ada yang melihat.
Tekanan Eksternal dan Kompas Internal
Indonesia pada dasarnya memiliki dua-duanya, meski keduanya kini seperti kekuatan yang meredup. Budaya malu melemah ketika masyarakat menjadi lebih permisif: pelaku korupsi tetap dihormati, dielu-elukan di acara keluarga, bahkan dipilih dalam pemilu. Sementara budaya kebersalahan kehilangan taring ketika pragmatisme dan patronase menekan suara nurani. Di titik itulah korupsi menjadi bukan lagi hal yang memalukan, bukan pula hal yang salah—melainkan sekadar “risiko pekerjaan”.
Padahal, dua budaya ini justru bisa menjadi “strategi kultural” yang melengkapi lembaga penegak hukum. Budaya malu dapat diaktifkan kembali melalui transparansi publik yang membuat pejabat merasa kehilangan muka bila menyimpang. Publikasi LHKPN, keterbukaan gaya hidup, hingga peran media dan komunitas sosial dapat menjadi tekanan moral yang lebih kuat daripada sekadar ancaman hukuman.
Sementara itu, budaya kebersalahan dapat diperkuat melalui pendidikan karakter, pelatihan etika bagi ASN, dan pembiasaan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Cara kita mendidik anak, mengelola organisasi, dan memberikan teladan di ruang publik akan menentukan apakah generasi mendatang tumbuh dengan kesadaran moral atau sekadar kemampuan menyembunyikan kesalahan.
Upaya melawan korupsi hanya akan efektif jika dua pilar ini bekerja bersama: tekanan eksternal yang membuat perilaku buruk memalukan, dan kompas internal yang membuatnya terasa salah. Ketika masyarakat menolak memberi panggung bagi koruptor, dan para pejabat tumbuh dengan nurani yang terlatih, maka hukum tidak hanya bekerja melalui ancaman, tetapi melalui budaya.
Di tengah kegaduhan politik dan skandal yang terus menghias halaman media, mungkin kita perlu kembali kepada sesuatu yang justru sangat sederhana: memulihkan rasa malu, dan merawat rasa bersalah. Dua hal yang dahulu begitu kuat menuntun perilaku masyarakat Nusantara—dan kini harus kembali menjadi fondasi moral perjalanan bangsa.
Selain mengenai konten, ada sedikit masukan tentang aspek fisik atau tampilan. Yang mudah terlihat dari buku ini adalah desain sampul depannya yang terkesan sederhana, terlalu biasa dan seadanya. Untuk topik korupsi, sebetulnya bisa didesain sampul muka yang lebih menarik.
Kemudian, dari segi penyuntingan, pihak editor tampaknya kurang cermat. Masih dijumpai salah ketik, salah eja, penggunaan huruf kapital yang kurang pas, dan lain-lain (contoh, lihat hlm. 17). Ada kesan penyuntingan buku ini dilakukan terburu-buru sehingga kurang rapi.
Tetapi saya yakin bahwa hal-hal teknis ini akan mudah diperbaiki atau lebih disempurnakan untuk edisi mendatang. Bagaimanapun, buku ini tetap patut diapresiasi sebagai salah satu sumbangsih untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia.
(Satrio Arismunandar, jurnalis dan penulis buku) ***