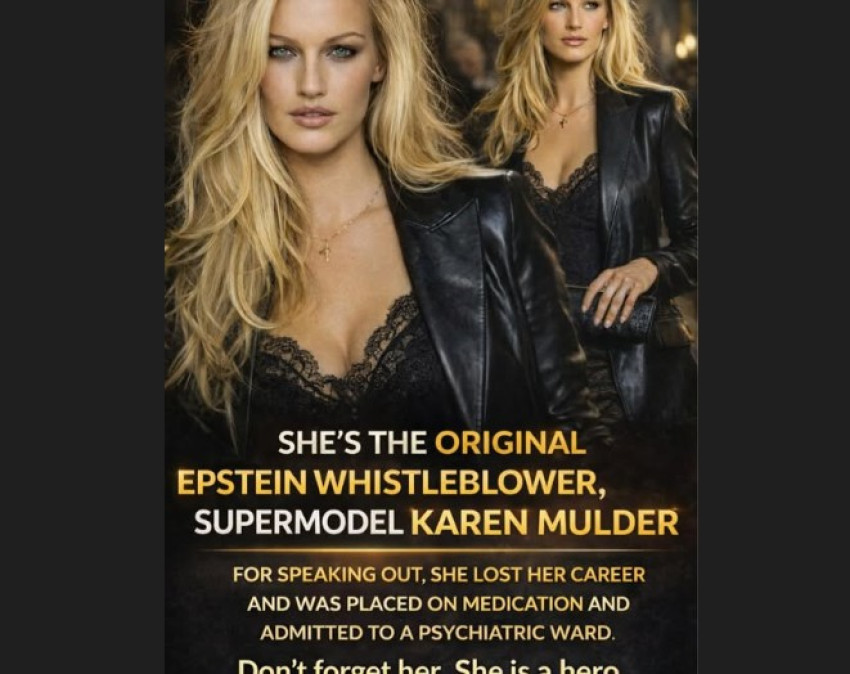Anas Al-Sharif, Jurnalis yang Lebih Ditakuti dari Seribu Tentara
ORBITINDONESIA.COM - Jika ada satu orang yang bisa membuat tentara paling brutal di dunia gelisah bukan karena senjata, tapi karena kamera, maka itu adalah Anas Al-Sharif.
Ia tak membawa drone. Tak memegang rudal. Ia hanya menyalakan mikrofon dan membiarkan dunia melihat sendiri: bahwa neraka di Gaza tak membutuhkan imajinasi, cukup cuplikan video dari lelaki ini.
Anas bukan sekadar jurnalis. Ia adalah saksi hidup yang mustahil dibungkam. Dan karena itulah, Israel memutuskan untuk mencoba membunuhnya—bukan sekali, tapi berkali-kali.
Bayangkan, ada satu rumah yang diledakkan lebih sering dari mercusuar militer: rumah Anas. Ayahnya dibunuh. Keluarganya diburu. Satu per satu, potongan hidupnya dihapuskan oleh rudal. Tapi Anas tetap berdiri, dengan jaket pers yang mungkin lebih tahan peluru daripada janji-janji PBB.
Apa yang membuat seorang wartawan menjadi ancaman? Sederhana: ia tidak bisa dibeli, tidak bisa ditakut-takuti, dan tidak bisa dipaksa untuk diam. Dalam dunia yang penuh jurnalis peliharaan, Anas adalah spesies langka—dan seperti semua spesies langka, ia kini dalam daftar target perburuan.
Juru bicara militer Israel bahkan menyebut namanya di depan kamera. Seolah-olah sedang membuka rapor murid nakal, padahal ini bukan sekolah, ini medan pembantaian. Dan Anas dianggap terlalu jujur untuk dibiarkan hidup.
Karena di dunia terbalik ini, jurnalis yang melaporkan pembunuhan dianggap lebih berbahaya daripada pelakunya.
Tapi mari kita jujur: ini bukan hanya tentang Anas. Ini tentang semua pena yang masih menolak tunduk, semua kamera yang masih berani menyala di tengah genangan darah.
Ini tentang bagaimana satu orang dari kamp pengungsian bisa mengguncang panggung global lebih dari seribu diplomat yang sibuk rapat tanpa hasil.
Anas adalah anak dari tanah yang terluka. Ia bukan produk institusi besar. Ia tidak lahir dari redaksi mewah dengan pendingin udara. Ia lahir dari derita, dari tenda, dari bunyi dentuman yang jadi alarm subuh.
Dia bukan koresponden biasa. Dia adalah peluit yang dibunyikan saat dunia tertidur. Dan karena dia terus membunyikannya, para perampas tanah itu menjadi panik.
Apa yang dilakukan Anas tidak bisa dibayar dengan gaji. Tidak bisa dimasukkan dalam grafik KPI. Apa yang dia lakukan adalah bentuk keberanian paling murni: bertahan di tempat di mana semua orang diperintahkan untuk mati dalam diam.
Dan sekarang, ketika namanya kembali disebut dalam ancaman terbuka, kita harus memilih: apakah kita akan tetap jadi penonton, atau berdiri di sampingnya sebagai barisan pena.
Untuk jurnalis Indonesia, ini adalah panggilan. Tidak semua bisa ke Gaza. Tidak semua bisa pegang kamera di reruntuhan. Tapi semua bisa menulis. Semua bisa bersuara. Semua bisa menggenggam pena dengan keberpihakan yang jelas.
Menolong Palestina tidak harus dengan bom. Cukup dengan menyibak kabut propaganda. Dengan menulis yang jujur. Dengan menyebut nama-nama yang ingin mereka hapus. Dengan menyimpan ingatan yang ingin mereka musnahkan.
Anas bukan ikon. Dia adalah peringatan. Bahwa bila kebenaran bisa dibunuh, maka kita semua tinggal menunggu giliran. Dan bila kita diam ketika satu suara dibungkam, maka saat suara kita dibungkam nanti—tak akan ada yang peduli.
Jadi, seharusnya kita semua mendoakan keselamatannya, melindungi Anas seperti kita melindungi cermin: karena ketika ia hancur, yang pertama lenyap adalah bayangan kita sendiri.
(Dikutip dari FB Massayik IR) ***