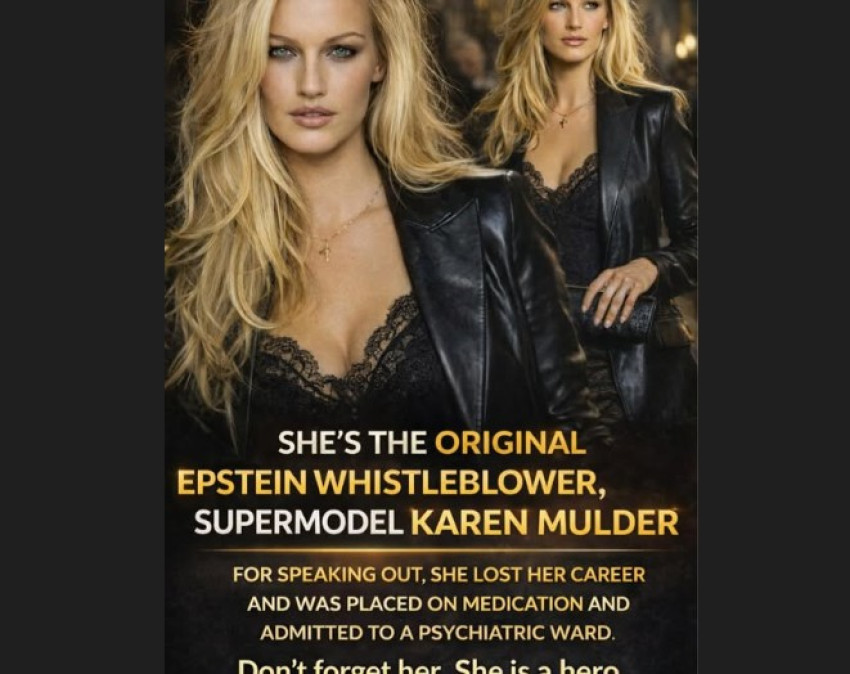Gedhe Kauman: Masjid yang mengajarkan Cara Pulang
Oleh Elza Peldi Taher
ORBITINDONESIA.COM - Kamis jelang subuh, begitu mobil kami memasuki halaman parkir Masjid Gedhe Kauman, saya membuka pintu dan melangkah turun sambil menatap masjid tua ini. Entah mengapa, sesuatu menyeruak dari dalam diri. Mungkin karena udara subuh Jogja yang lembap, atau mungkin karena siluet bangunan masjid itu nampak tenang, anggun, dan seolah berusia lebih tua dari waktu.
Sungguh, inilah masjid yang menyatu dengan alam. Sebagian bangunannya masih terbuat dari kayu berkualitas, kayu yang telah melewati banyak musim dan tetap tegak. Di luar ruang utama, halaman tempat salatnya terbuka tanpa dinding.
Langit menjadi atap tambahan, angin menjadi penjaga sunyi, pepohonan menjadi jemaah yang ikut mengucap tasbih lewat daunnya yang bergetar pelan. Inilah masjid yang tidak memisahkan manusia dari alam; justru alam menjadi bagian dari arsitekturnya.
Saya berdiri cukup lama di halaman itu sebelum melangkah masuk. Ada getaran tertentu yang saya rasakan—semacam sentuhan yang tidak tampak. Bagi saya, pengalaman spiritual sering kali bermula dari perjumpaan pertama dengan ruang: mata yang melihat, hati yang mendengar, dan jiwa yang tiba-tiba merasa pulang tanpa alasan yang logis. Di Masjid Gedhe Kauman, perasaan itu datang begitu cepat, begitu kuat. Seolah masjid ini tidak meminta apa-apa, tetapi memberi banyak hal sejak tatapan pertama.
Subuh di Jogja selalu membawa suasananya sendiri. Udara lembap namun tidak menusuk, suara azan dari deretan masjid di sekitar keraton yang saling bersahutan namun tidak saling menenggelamkan, cahaya lampu jalan yang masih redup, dan langkah-langkah kecil manusia yang mencari-Nya dengan caranya masing-masing. Saat saya dan kawan-kawan berjalan menuju masjid, suasana itu menyelimuti kami seperti kain tipis yang menenangkan.
Lorong menuju masjid itu terasa seperti pintu waktu. Rumah-rumah kecil yang berjajar, pedagang bubur yang sudah mulai menatap panci, suara ayam kampung yang baru belajar kokok, serta angin yang bergerak pelan seakan berkata: “Selamat datang. Hari ini dimulai dari sini.”
***
Masjid Gedhe Kauman berdiri persis di sisi barat Alun-Alun Keraton Yogyakarta. Lokasinya tidak hanya strategis, tetapi simbolis. Ia seolah sengaja ditempatkan di pangkal denyut budaya Jawa: keraton dan masjid berdampingan, seperti dua saudara tua yang saling memahami tanpa banyak kata.
Arsitekturnya sederhana, tetapi penuh makna. Dari luar, yang tampak bukan kemewahan, melainkan kearifan lokal yang dijaga dengan sepenuh hati. Atap limas bertumpang tiga—ciri khas masjid Nusantara—berdiri kokoh tanpa harus berlomba dengan kubah raksasa seperti masjid masa kini.
Langkah saya pelan ketika memasuki pelataran masjid. Di sinilah pertama kali saya benar-benar merasakan keanggunan dari kesederhanaan itu. Pagar sederhana, pohon yang menaungi halaman, dan pilar-pilar kayu yang terawat dengan baik. Tidak ada yang ingin dipamerkan. Masjid ini seperti orang tua bijak yang tidak memerlukan perhiasan untuk dipercaya. Hanya dengan kehadirannya, pengalaman batin itu sudah terasa.
Ruang terbuka di samping masjid menjadi hal yang paling mengundang perhatian saya. Ruang itu luas, lapang, tanpa dinding. Angin subuh masuk tanpa izin, membawa aroma tanah basah, rumput yang baru terkena embun, dan suara kehidupan dari kampung sekitar. Ruang itu mengingatkan saya bahwa masjid bukan hanya bangunan untuk ritual, tetapi ruang kehidupan.
Saya melihat beberapa jamaah yang memilih salat di bagian terbuka itu, meski ruang utama tersedia. Mereka seperti ingin menjawab panggilan alam. Dan masjid ini memberi ruang bagi pilihan itu.
***
Saat melangkah masuk ke ruang utama, aroma kayu tua langsung menyapa. Aroma itu membawa saya kepada ingatan-ingingan lama: surau kampung di Solok Selatan yang juga terbuat dari kayu, tempat anak-anak belajar mengaji sambil duduk di lantai dingin, dan tempat saya pertama kali belajar bahwa kesucian tidak selalu tampak dari marmer, tetapi dari kehangatan ruang yang menerima siapa saja. Saya merasa sedang melihat bayangan masa kecil saya sendiri di antara tiang-tiang kayu itu.
Ruang utama masjid memang menggunakan pendingin udara. Namun kehadiran AC tidak menghilangkan suasana tradisionalnya. Tiang-tiang saka guru berdiri tegak seperti penjaga waktu. Saya membayangkan tiang-tiang itu pernah menyaksikan ratusan kali pergantian imam, ratusan kali subuh yang sunyi, ribuan doa yang mengalir, dan jutaan langkah manusia yang datang dan pergi. Arsitektur masjid ini memelihara kesederhanaan dalam wujud yang paling elegan.
Tetapi bagi saya, ruang kedua—ruang semi terbuka tanpa AC, tanpa dinding—adalah pusat pengalaman rohani di tempat ini. Ruang itu adalah jantung masjid. Di sanalah hubungan manusia dengan alam tidak dipisahkan oleh tembok. Udaranya natural. Suaranya natural. Cahaya paginya natural. Ruang seperti ini mengingatkan saya pada ruang-ruang ibadah awal umat Islam: teduh, terbuka, dan dekat dengan bumi.
Dalam ruang itu saya memilih mengambil saf. Dan ketika imam mengumandangkan takbir, saya seperti meresapi suasana yang tidak saya temukan di banyak masjid kota besar. Suara imam tidak bergema keras seperti di masjid modern; ia mengalun lembut, memantul pada kayu, diserap dinding, dan menyatu dengan udara luar. Suara itu terdengar seperti bagian dari alam. Suara yang bersumber dari manusia tetapi diredam kehangatan ruang.
Ketika sujud pertama, saya merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dalam dinginnya udara subuh, dalam ruang yang terbuka, dalam keheningan yang pelan, saya merasa seperti sedang merapat kembali kepada sesuatu yang sudah lama saya tinggalkan: rasa pulang kepada diri sendiri.
***
Selepas salat, saya duduk agak lama sembari memandangi ruang sekitar. Jamaah belum sepenuhnya bubar. Beberapa orang masih duduk bersandar pada tiang. Ada seorang bapak tua yang tertidur dengan sarung menutupi sebagian wajahnya. Ada dua anak muda yang membaca Quran dengan suara pelan. Ada ibu-ibu yang menyusun barang sambil sesekali tersenyum satu sama lain. Masjid ini terasa hidup. Tidak sekadar tempat ibadah, tetapi tempat jeda—tempat manusia memulihkan dirinya dari segala beban.
Masjid-masjid modern hari ini sering kali dibangun dengan tujuan memukau mata. Kubah besar, marmer mahal, chandelier megah, pendingin ruangan dari berbagai sudut. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ada masjid-masjid yang terlalu indah sehingga menjadi asing. Masjid yang membuat jamaah merasa kecil bukan karena kerendahan hati, tapi karena jarak yang diciptakan kemegahannya.
Masjid Gedhe Kauman mengambil jalan yang berbeda. Ia tidak mengecilkan manusia. Ia memeluk manusia. Di ruang terbuka itu, saya menyadari sesuatu: ada hubungan langsung antara kesederhanaan dan kedalaman spiritual. Ruang yang tidak banyak bicara justru memberi ruang bagi jiwa untuk berbicara. Ruang yang tidak memaksa hanya dengan kehadirannya justru menguatkan kehadiran manusia itu sendiri.
Saya teringat sebuah kalimat dari seorang arsitek Jepang yang pernah saya baca: “Bangunan yang paling baik adalah bangunan yang membuat manusia merasa lebih manusia.” Saya merasa itulah yang saya rasakan pagi itu.
***
Di samping pengalaman spiritual, tak bisa saya abaikan sejarah panjang masjid ini. Masjid Gedhe Kauman dibangun pada tahun 1773 pada masa Sultan Hamengku Buwono I. Ia bukan hanya tempat salat, tetapi pusat kehidupan keagamaan Kauman—kampung para penghulu keraton.
Di sinilah fatwa-fatwa, diskusi agama, tradisi, dan adat bersilangan. Di serambi masjid inilah pemikiran pembaruan Islam mulai tumbuh, terutama ketika K.H. Ahmad Dahlan, tokoh muda yang gelisah dengan stagnasi pendidikan Islam kala itu, mulai melakukan kajian ulang terhadap cara beragama.
Kauman adalah kampung ilmu. Kampung tempat agama bukan hanya diajarkan, tetapi ditafsirkan kembali. Dari sinilah Muhammadiyah lahir. Dari serambi-serambi inilah pandangan Islam modern yang berorientasi pada pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial mulai menembus batas zaman. Tentu saja, saya tidak menulis sejarah panjang itu di kepala saya pagi itu. Tapi saya merasakan jejaknya. Masjid ini mengandung napas perjalanan panjang umat Islam di Indonesia.
Ada satu momen ketika saya memandangi kayu-kayu tua di tiang masjid, lalu saya bertanya dalam hati: Berapa banyak doa yang diserap oleh kayu-kayu ini selama hampir dua setengah abad? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban. Tetapi justru di situlah keindahannya.
***
Ketika keluar dari masjid menjelang matahari terbit, halaman mulai hidup. Sinar matahari menyentuh atap masjid yang berlapis tiga itu. Warna kuning keemasan memantul di genteng dan pohon-pohon sekitar. Beberapa orang duduk di bangku dekat pagar sementara anak-anak kecil mulai berlari-lari kecil. Jogja, seperti biasa, menunjukkan kecantikannya yang paling murni pada pagi hari.
Saya berhenti sebentar di gerbang masjid. Ada rasa yang aneh—seperti rasa yang muncul setiap kali kita selesai mengunjungi rumah seseorang yang sangat dekat dengan jiwa kita. Ada kelegaan karena datang, tetapi ada juga kesedihan halus karena harus pergi. Masjid Gedhe Kauman memberi saya sesuatu yang tidak saya sadari saya cari: ruang untuk mendengar kembali suara diri saya sendiri.
Di kota-kota besar, kita sering kehilangan kemampuan untuk mendengar diri. Suara mesin, pekerjaan, ambisi, dan kesibukan perlahan mengisi seluruh ruang batin kita. Masjid Gedhe Kauman, dengan kesederhanaannya, memberikan kembali ruang itu. Ruang kosong yang berharga. Ruang di mana jiwa bisa bernafas tanpa tuntutan apa pun.
Saya melangkah perlahan meninggalkan halaman, tetapi perasaan damai itu tidak hilang. Bahkan semakin kuat. Saya merasa seperti membawa pulang sepotong pagi Jogja, sepotong kayu tua, sepotong angin subuh itu ke dalam dada saya.
Dan tepat ketika saya melewati gerbang masjid itu, sebuah harapan muncul dalam diri saya. Harapan agar masjid-masjid yang sedang dan akan dibangun di berbagai daerah Indonesia belajar dari Masjid Gedhe Kauman: bahwa arsitektur lokal bukan sekadar estetika, tetapi cermin jiwa masyarakatnya. Bahwa kayu, angin, halaman terbuka, dan kesejajaran dengan alam bukanlah sesuatu yang ketinggalan zaman, melainkan cara ruang suci menjaga manusia tetap rendah hati dan dekat dengan bumi tempatnya berpijak. Bahwa masjid tidak harus bersaing menunjukkan kemegahan; cukup menjadi diri sendiri, cukup setia pada budaya tempat ia berdiri.
Saya berharap masjid-masjid di Nusantara mempertahankan kekhasannya—yang mencerminkan ruh daerah, sejarahnya, dan hikmah para leluhurnya. Masjid Gedhe Kauman memberi saya pelajaran penting: kesakralan lahir bukan dari marmer dan kubah megah, tetapi dari ruang yang membiarkan angin lewat, cahaya masuk, dan jiwa manusia menemukan keteduhan tanpa syarat.
Jogja selalu punya cara untuk memulangkan manusia kepada dirinya.
Dan pagi itu, saya tahu: masjid yang paling indah bukan yang paling besar, tetapi yang paling membuat kita merasa pulang.
Gedhe Kauman 4 Desember 2025
*Elza Peldi Taher, penulis SATUPENA.