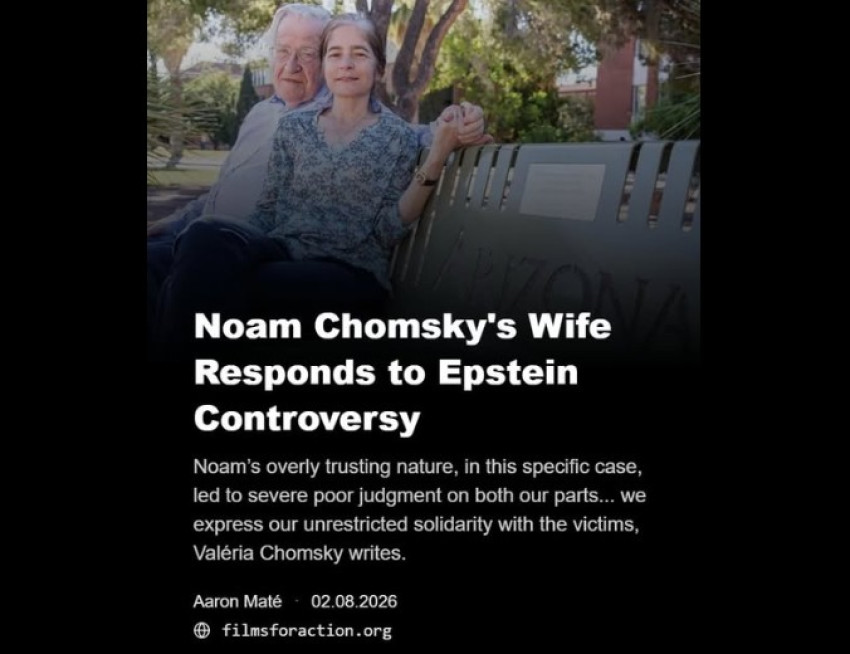Apakah Kita Hidup dalam Simulasi? Perdebatan yang Tak Kunjung Usai
ORBITINDONESIA.COM - Selama bertahun-tahun, manusia sering bertanya: apakah dunia yang kita lihat benar-benar nyata, atau hanya tiruan yang sangat meyakinkan?
Pertanyaan itu menemukan bentuk modernnya ketika filsuf Swedia Nick Bostrom pada awal 2000-an mengajukan gagasan provokatif: ada kemungkinan besar bahwa alam semesta ini hanyalah simulasi komputer ultra-canggih. Kita, katanya, mungkin seperti Neo dalam The Matrix—makhluk digital yang merasa hidup di dunia fisik.
Gagasan itu segera memancing rasa ingin tahu banyak orang: para ilmuwan, penggemar sains, hingga mereka yang diam-diam penasaran apakah realitas ini cuma program yang dijalankan oleh “peradaban supermaju” entah di mana.
Namun baru-baru ini, sebuah tim fisikawan internasional yang dipimpin Mir Faizal dari University of British Columbia menerbitkan makalah ilmiah yang mengklaim hal sebaliknya. Menurut mereka, alam semesta tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai simulasi.
Tak ada “grid”, tak ada batas energi khas komputer, dan tak ada pola fisika yang menyingkapkan bahwa realitas kita dibangun oleh sistem komputasi raksasa. Jika benar demikian, maka tidak ada “programmer agung” yang merancang semesta. Alam ini berdiri sendiri, bukan hasil coding kosmik.
Klaim tersebut segera menjadi tajuk media populer. Situs-situs sains menulis judul bombastis seperti, “Fisika Membuktikan Alam Semesta Bukan Simulasi.” Publik pun seolah diberi alasan untuk bernapas lega: kita hidup di dunia nyata, bukan di dalam perangkat lunak.
Tetapi dunia ilmiah jarang sesederhana itu. Sabine Hossenfelder, fisikawan Jerman sekaligus YouTuber sains yang dikenal blak-blakan, langsung mengkritik makalah tersebut. Menurutnya, argumen tim Faizal salah secara logika.
Mereka mungkin meneliti tanda-tanda tertentu, tetapi tidak mungkin memeriksa semua bentuk simulasi yang bisa dibayangkan. Bagaimana jika programnya jauh lebih canggih daripada asumsi kita? Bagaimana jika simulasi menggunakan prinsip fisika yang berbeda, atau bahkan tidak meniru komputer sama sekali?
Hossenfelder menegaskan: hipotesis simulasi pada dasarnya berada di luar ranah sains karena tidak dapat dibuktikan atau dibantah secara pasti. Untuk itu, ia memberi makalah UBC nilai sembilan dari sepuluh dalam “indikator omong kosong”—bukan karena risetnya jelek, tetapi karena kesimpulannya melampaui apa yang fisika bisa buktikan.
Pada titik ini, perdebatan menjadi semakin menarik. Di satu sisi, ada usaha ilmuwan untuk mencari jejak-jejak teknis yang mungkin membocorkan bahwa realitas ini buatan. Di sisi lain, ada pemikiran filosofis bahwa simulasi adalah hipotesis yang terlalu luas untuk diuji. Sains membutuhkan sesuatu yang bisa diverifikasi, dan simulasi tidak menawarkan hal itu.
Lalu, apakah makalah itu benar-benar membuktikan bahwa kita tidak hidup dalam simulasi? Tidak juga. Tetapi apakah Bostrom telah membuktikan bahwa kita berada di dalamnya? Juga tidak. Kita berada di wilayah abu-abu, di mana batas antara sains, filsafat, dan imajinasi semakin kabur.
Pada akhirnya, perdebatan ini lebih banyak mengungkap rasa ingin tahu manusia daripada jawaban final. Ia menunjukkan betapa kita selalu tergoda bertanya tentang asal-usul realitas, tentang apakah ada sesuatu “di balik tirai”, tentang apa arti keberadaan itu sendiri. Dan selama rasa ingin tahu itu masih menyala, perdebatan simulasi—entah logis, metafisik, atau hanya permainan pikiran—tidak akan pernah benar-benar mati.***