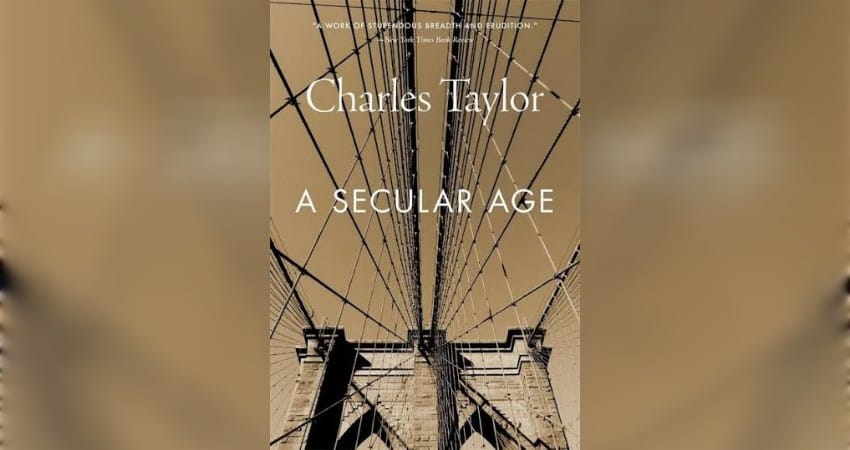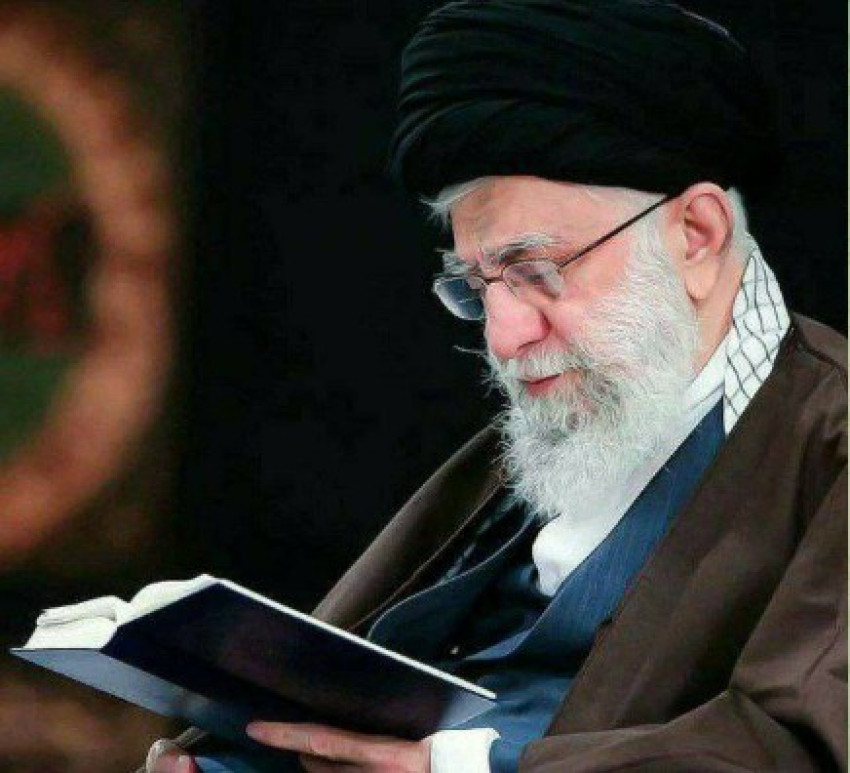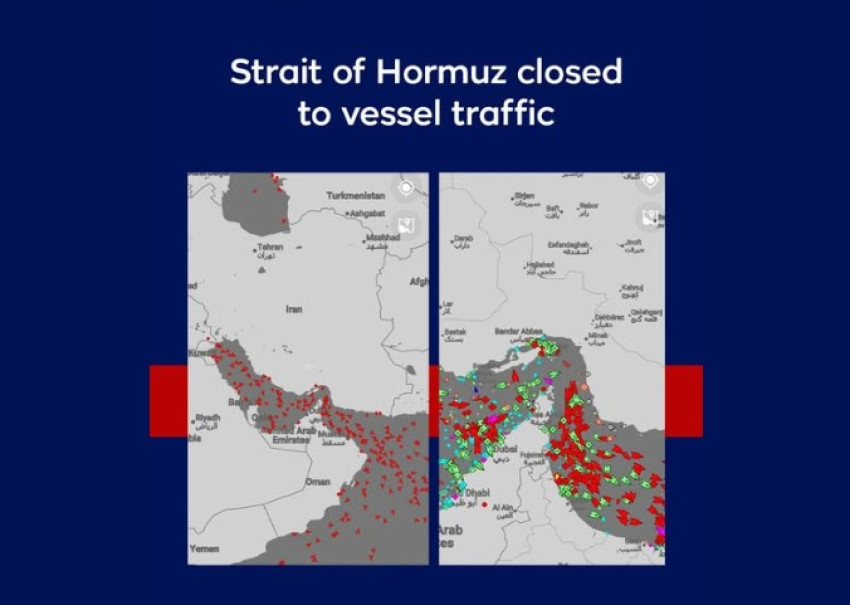Resensi Buku A Secular Age Karya Charles Taylor: Zaman Sekuler sebagai Latar Keberimanan Baru
ORBITINDONESIA.COM- Buku A Secular Age (2007) karya filsuf Kanada Charles Taylor, yang diterbitkan oleh Harvard University Press, adalah salah satu karya paling monumental dalam filsafat kontemporer tentang agama dan modernitas.
Karya ini tidak sekadar merenungkan kemunduran agama di dunia Barat, melainkan menggali secara filosofis bagaimana kondisi batin manusia berubah: dari dunia yang dulu dipenuhi Tuhan, menuju dunia yang merasa bisa berjalan sendiri tanpa kehadiran-Nya.
Taylor memulai dengan satu pertanyaan sederhana namun mengguncang: “Mengapa pada tahun 1500, hampir semua orang di Barat percaya kepada Tuhan, sementara pada tahun 2000, iman hanyalah satu pilihan di antara banyak kemungkinan lain?”
Pertanyaan itu bukan sekadar statistik religius, melainkan cermin bagi transformasi kesadaran: bagaimana manusia modern menggeser tumpuan maknanya dari langit ke bumi, dari sakral ke sekuler, dari kosmos penuh roh ke dunia yang “immanent”—tertutup dalam batas duniawi.
Karya ini tidak menawarkan dogma baru atau pembelaan iman tradisional. Ia justru seperti peta besar kesadaran modern, yang menunjukkan bagaimana manusia sampai pada titik di mana Tuhan tidak lagi menjadi asumsi dasar kehidupan, melainkan salah satu pilihan sadar yang bisa diterima atau ditolak.
Isi dan Struktur Buku: Menelusuri Jejak Panjang Sekularisasi
A Secular Age terdiri dari lima bagian besar, tetapi struktur buku ini lebih menyerupai perjalanan ziarah intelektual daripada sistematika akademis biasa. Taylor menulis seperti seorang penjelajah sejarah batin Barat — berjalan melintasi abad-abad, memungut jejak kepercayaan, dan menafsirkan perubahan spiritual yang terjadi perlahan namun pasti.
Buku ini dimulai dengan dunia pra-modern, di mana kehidupan manusia dipenuhi makna ilahi. Dunia pada masa itu, menurut Taylor, adalah “dunia berpori” (porous world): dunia di mana batas antara diri manusia dan kekuatan spiritual amat tipis.
Roh, malaikat, berkah, dan kutukan dirasakan sebagai bagian dari realitas sehari-hari. Namun, modernitas membawa pergeseran mendasar: manusia menjadi “diri berlapis” (buffered self), individu yang tertutup dari yang transenden, hidup dalam dunia yang terukur, rasional, dan terobjektifikasi.
Taylor kemudian menjelaskan bahwa sekularisasi tidak hanya berarti menurunnya kehadiran agama, tetapi perubahan dalam “kondisi keberimanan” itu sendiri. Dahulu, orang percaya karena dunia memang terasa penuh Tuhan; kini, orang beriman meski dunia tampak sunyi dari suara-Nya.
Sekularitas, dalam pandangan Taylor, bukanlah hilangnya iman, tetapi munculnya kemungkinan untuk tidak beriman. Dunia menjadi plural, di mana kepercayaan dan ketidakpercayaan hidup berdampingan dalam satu ruang kesadaran yang sama.
Ia menyebut situasi ini sebagai “immanent frame” — kerangka berpikir modern yang membatasi makna hidup hanya dalam batas dunia ini. Namun kerangka itu tidak serta-merta meniadakan kerinduan pada yang transenden; ia justru melahirkan “cross pressures”, ketegangan batin antara iman dan keraguan, antara sekularitas dan spiritualitas.
Sejarah Kesadaran: Dari Reformasi hingga Zaman Autentisitas
Taylor melihat akar sekularitas modern berawal dari Reformasi Protestan abad ke-16. Reformasi, dengan semangatnya untuk memurnikan iman dan menolak ritual yang dianggap dangkal, justru tanpa disadari menyempitkan ruang sakral dalam kehidupan manusia.
Iman dipindahkan dari ruang publik ke ruang batin; dari komunitas ke hati individu. Dengan demikian, iman menjadi interior, privat, dan rasional.
Selanjutnya, muncul zaman yang ia sebut Age of Authenticity — abad ke-20 dan seterusnya — di mana kebenaran moral tidak lagi dicari dari wahyu, melainkan dari keaslian diri. Manusia modern tidak ingin tunduk kepada dogma, tetapi ingin hidup "setia pada dirinya sendiri."
Spiritualitas pun menjadi cair: seseorang bisa merasa “spiritual tapi tidak religius”, mencari makna tanpa lembaga, dan berdoa tanpa Tuhan formal. Inilah wajah khas sekularitas modern: bukan dunia tanpa iman, tetapi dunia dengan jutaan bentuk iman pribadi.
Bagi Taylor, perubahan ini tidak sepenuhnya buruk. Ia menandai kedewasaan reflektif dalam beriman. Orang tidak lagi percaya hanya karena diwariskan, tetapi karena dipilih secara sadar di tengah kemungkinan tak beriman.
Sekularitas, dalam arti ini, membuka ruang kebebasan eksistensial yang belum pernah ada sebelumnya. Namun di sisi lain, kebebasan itu sering membawa kehampaan makna: manusia merasa bebas, tapi juga sendirian di alam semesta yang bisu.
Makna Filsafatnya: Sekularisasi sebagai Ziarah Batin Manusia
Di tangan Taylor, sekularisasi bukan ideologi anti-Tuhan, melainkan perjalanan batin manusia menuju refleksi diri yang lebih dalam. Ia menolak pandangan sempit yang menganggap sekularitas sebagai dekadensi moral atau kemenangan ateisme. Baginya, dunia modern justru menunjukkan bahwa kerinduan akan makna tidak pernah padam — hanya berganti bentuk, dari altar gereja ke ruang kesadaran manusia.
Manusia modern, menurut Taylor, bukan kehilangan iman, melainkan kehilangan kepastian. Ia hidup dalam “cross pressures”: ditarik oleh pesona iman dan daya tarik skeptisisme sekaligus.
Dalam situasi ini, iman menjadi tindakan keberanian, bukan kebiasaan sosial. Untuk percaya pada Tuhan di zaman sekular berarti melawan arus, bukan mengikuti tradisi.
Taylor juga menegaskan bahwa sekularitas membuka peluang baru bagi dialog spiritual lintas budaya. Dalam dunia plural, iman tidak bisa lagi dipaksakan; ia harus tumbuh dari kebebasan, dari pencarian makna yang tulus. Dengan demikian, A Secular Age adalah refleksi tentang bagaimana iman dapat bertahan secara bermartabat di zaman tanpa jaminan metafisik.
Relevansi dan Signifikansi: Cermin bagi Zaman Kita
Membaca A Secular Age hari ini seperti bercermin pada wajah spiritual manusia modern: tercerai dari tatanan sakral lama, namun tetap haus akan makna.
Buku ini relevan bagi siapa pun yang bergulat antara iman dan akal, antara tradisi dan kebebasan. Ia tidak menawarkan jawaban siap pakai, tetapi membantu pembaca memahami mengapa kita berpikir, merasa, dan beriman seperti sekarang.
Dalam konteks masyarakat non-Barat — termasuk dunia Islam — karya ini penting untuk memahami sekularisme bukan sekadar ide politik atau pemisahan agama dari negara, melainkan pergeseran struktur kesadaran.
Taylor memberi peta untuk membaca gejala spiritualitas baru: keimanan yang cair, personal, dan reflektif — fenomena yang juga tampak dalam masyarakat Muslim urban masa kini.
Penutup: Dunia yang Tak Sepenuhnya Tanpa Tuhan
A Secular Age bukan buku yang ringan. Ia menuntut kesabaran dan ketekunan, tapi juga memberi ganjaran intelektual yang besar. Ia mengajak kita merenung, bukan hanya tentang sejarah agama, tapi tentang kondisi eksistensial manusia modern.
Taylor menunjukkan bahwa dunia sekular bukan dunia tanpa Tuhan, melainkan dunia di mana iman menjadi pilihan sadar, bukan warisan.
Zaman sekular, kata Taylor, bukan akhir dari iman, melainkan babak baru dalam pencarian makna.
Dunia mungkin menjadi lebih sunyi, tapi dalam kesunyian itu manusia justru mendengar gema baru dari transendensi — bukan lagi datang dari langit, melainkan bergema dari dalam dirinya sendiri.***